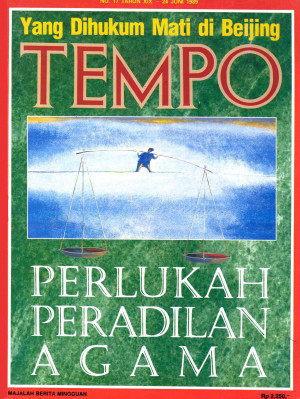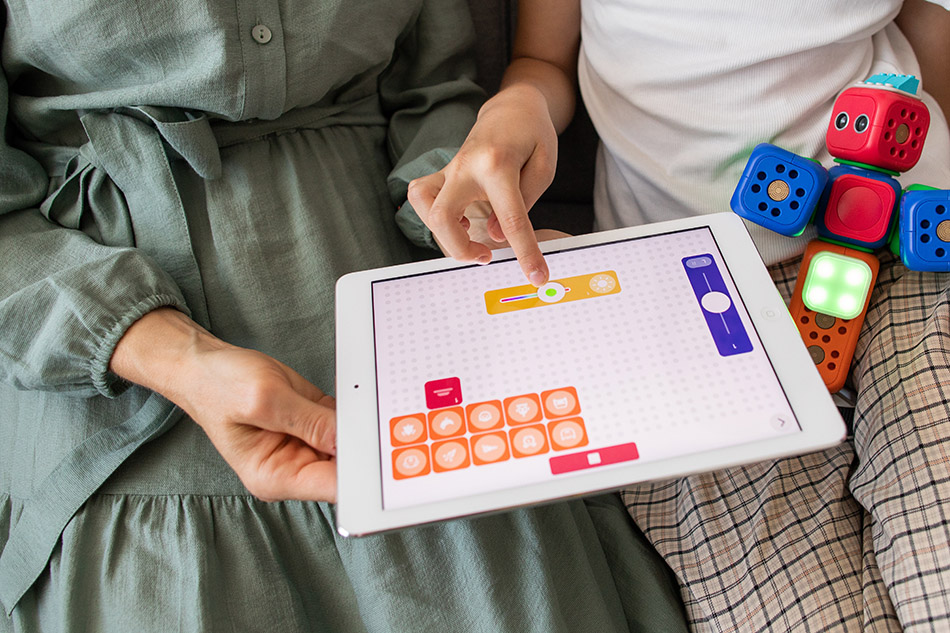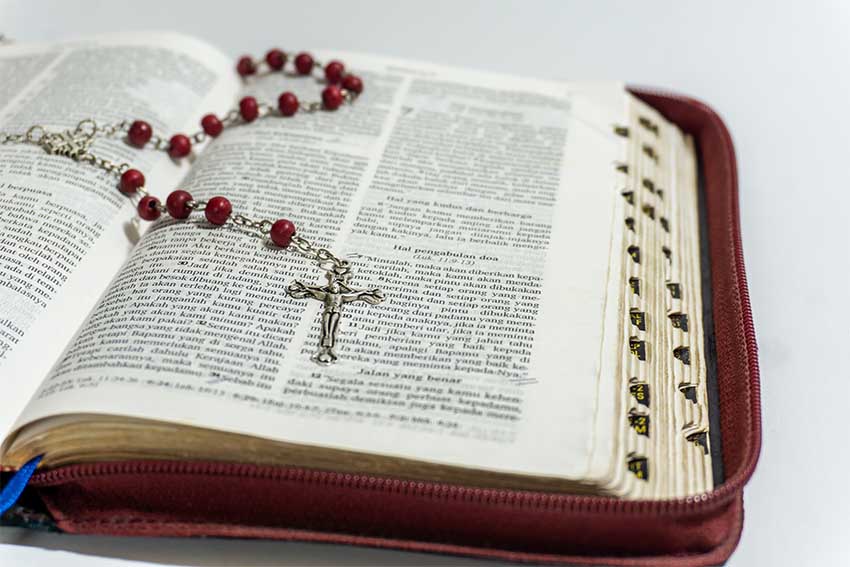TENANG tapi cemas? Atau tenang tulen? Sulit menebak perasaan di masyarakat Indonesia kini. Juga untuk suatu persoalan yang penting, bahkan sebenarnya peka. Lihat di DPR, hari-hari ini. Tak ada ledakan, tak ada yang naik pitam. Tepuk tangan pun tak kedengaran. Beberapa wakil rakyat malah kelihatan terkantukkantuk di kursi, atau keluar dari ruangan untuk menikmati kopi dan kue di kantin sebelah ruang sidang. Padahal, DPR tengah membahas Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama (disingkat RUU-PA), yang oleh sementara kalangan dianggap mengistimewakan golongan Islam -- dan "tak begitu sesuai dengan Pancasila". Juga Senin pekan ini. Di mimbar, di depan ruangan sidang umum itu, berdiri Menteri Agama Munawir Sjadzali. Ia -- menteri agama pertama dalam sejarah RI yang membawakan sebuah rancangan undang-undang ke DPR -- membacakan sebuah bundel setebal 29 halaman. Isinya jawaban Pemerintah atas berbagai pertanyaan yang dilemparkan di DPR dalam acara pemandangan umum terhadap Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama, sepekan sebelumnya. Dari seantero sudut, tak ada kesan bahwa materi yang sedang dibahas hari itu gawat. Maklum, belum satu fraksi pun yang menyatakan menolak RUU itu. Secara sepintas, tampaknya RUU ini akan gol dan jadi undang-undang. F-ABRI, F-KP, dan F-PP secara tegas sudah dapat menerima RUU, dengan berbagai perbaikan di sana-sini. Cuma F-PDI, fraksi terkecil di DPR -- sekalipun secara eksplisit tak menolak -- yang melemparkan berbagai pertanyaan yang mendasar. PDI misalnya menanyakan: tidakkah RUU-PA ini tidak bertentangan dengan prinsip babwa Indonesia harus hanya ada satu hukum nasional? Bukankah RUU itu menggunakan syariat Islam dan berlaku khusus untuk orang Islam? Bagaimana Pemerintah menjamin orang bebas melakukan pilihan hukum, hingga seorang Islam diperkenankan tidak memilih Peradilan Agama sebagai lembaga untuk menyelesaikan perkara kewarisannya? Itu tentu saja pertanyaan yang secara fundamentil menyangkut kearifan bernegara di tanah air yang rumit dan majemuk ini. Tapi PDI tak memakai nada keras. Kalimatnya berbelit -- dan sebab itu terpaksa disederhanakan agar jelas -- tapi nampaknya hal itu disengaja agar tak menyinggung pihak mana pun, termasuk Pemerintah. Jadi, tak terasa ada sesuatu yang kontroversial jika didengar di DPR. Tapi suara lebih keras justru bergaung di luarnya. Tak kurang dari bekas Ketua DPR Amirmachmud, pensiunan ABRI, yang tampil mengecam RUU-PA. Sebelumnya, ada suara lain: dari mantan Gubernur Jakarta Soeprapto. Amirmachmud dulu. Tokoh ini, yang pernah jadi Menteri Dalam Negeri, mengingatkan agar jangan diciptakan undang-undang yang mengandung kontradiksi. "Syariat Islam bagaimanapun tidak bisa masuk ke dalam hukum nasional, sebab hukum kita adalah hukum Pancasila," kata Amirmachmud. Ia punya pengalaman. Semasa menjabat Mendagri, ia mengaku pernah memerintahkan mencabut sejumlah peraturan daerah (Perda) yang sudah disetujui DPRD di Aceh, Riau, Jambi, Nusa Tenggara Barat, dan salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan, karena dianggapnya "mengandung syariat Islam". Maka, katanya, "Kalau dulu perda saya cabut, sekarang kok mau dijadikan hukum nasional. Itu namanya aneh." Tiga hari sebelum statemen Amirmachmud, Wakil Ketua MPR dari Fraksi Utusan Daerah Soeprapto mengirim surat kepada Ketua DPR. Sebagai lampiran surat itu, ia sertakan makalah enam halaman, berisi telaah terhadap RUU-PA. Mantan Gubernur Jakarta ini mengkritik nama RUU itu. Kata "Peradilan Agama" dapat mengesankan umat agama lain pun harus tunduk pada undang-undang itu. Padahal, hakekatnya RUU itu adalah Peradilan Agama Islam yang khusus untuk penganut Islam. Maka, Soeprapto pun kemudian mempertanyakan, akan adakah PA yang lain untuk penganut agama di luar Islam. Bila demikian, itu bertentangan dengan prinsip Wawasan Nusantara -- "yang tercantum di dalam Garis Besar Haluan Negara tahun 1973" -- yang menghendaki "pembentukan dan pengembangan satu sistem hukum nasional yang berasaskan Pancasila". Dengan argumentasi itu, Soeprapto menggugat UU Nomor 14 Tahun 1970, yang mengatur ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Undang-undang yang lahir 19 tahun yang lalu itu memang induk dari RUU-PA yang sedang dibawa Pemerintah ke DPR. Soalnya, UU di tahun 1970 itu dibikin sebelum adanya Wawasan Nusantara, dan sebelum 1983, ketika Pancasila ditetapkan sebagai asas tunggal. Di akhir suratnya, Soeprapto menyarankan agar negara menjamin kemerdekaan tiap warga untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya -- sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 29 Konstitusi. Dan tentang pelaksanaan syariat agama, serahkan saja itu pada para pemeluk agama masing-masing. Peniadaan peradilan agama, seperti yang tersirat dalam surat Soeprapto, memang usul yang radikal. Bahkan Soeprapto, dalam keterangan kemudian kepada TEMPO, menegaskan: kalau ada sengketa dalam menjalankan syariat itu, "tak perlu dibuat peradilan agama, panggil saja Majelis Ulama." Alasan Soeprapto, dengan pandangan seperti itu, agaknya khas datang dari seorang purnawirawan ABRI (ia letnan jenderal TNI-AD) yang pernah bertempur dengan pasukan "Darul Islam" lebih dari tiga puluh tahun yang silam. "Saya merasa perlu mengingatkan generasi mendatang agar waspada: negara kita adalah negara Pancasila, bukan negara agama." Tak urung, surat Soeprapto itu banyak dibicarakan orang. Ada yang mengkritik caranya, ada yang membantah pandangannya. Surat itu ditulis di atas kertas berkop MPR, ada nomor surat, dan stempel Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Maka, datanglah suara yang disiarkan kepada umum, dari seorang purnawirawan TNI-AD yang lain, yang juga bekas pejabat penting: Menko Kesra Alamsjah Ratu Perwiranegara, yang pernah juga jadi Menteri Agama. Menurut Alamsjah, seharusnya Soeprapto tak mengatasnamakan MPR untuk menilai RUU-PA. Sebab, dengan surat seperti itu, seolah-olah ia berbicara "atas nama seluruh rakyat". Ketua Fraksi Karya Pembangunan, tokoh Golkar Soeharto, juga mempersoalkan cara Soeprapto. Katanya: "Kalau memang maksudnya untuk sumbang saran secara pribadi, mengapa surat itu menggunakan nomor dan stempel segala." Sebuah sumber lain menganggap, dengan surat itu, Soeprapto telah menilai kebijaksanaan Presiden. Ini datang dari anggota MPR dari PPP, Abdi Kusumanegara. Menurut Abdi, sebagai Wakil Ketua MPR, Soeprapto dilarang menilai kebijaksanaan Mandataris, kecuali di dalam Sidang Umum atau Sidang Umum Istimewa MPR. Soeprapto sendiri bertahan bahwa suratnya itu berupa usul secara pribadi kepada Ketua MPR Kharis Suhud. Bahwa bentuk surat dengan nomor, stempel, dan kop MPR, menurut dia cuma untuk pendokumentasian. "Pak Kharis Suhud bisa mengerti bahwa surat itu dari pribadi Wakil Ketua MPR kepada Ketua MPR, dan isinya adalah urun rembuk," katanya. Menurut Soeprapto, surat seperti itu juga ia buat, ketika mempersoalkan landasan hukum eksistensi Badan Pertanahan Nasional, Juni tahun lalu. "Saya heran, kenapa surat yang sekarang baru bikin ramai," katanya. Tangkisan kepadanya memang rada seru. Bila ia menggugat UU Nomor 14 Tahun 1970, berarti ia menggugat sejumlah undang-undang lain yang berawal dari sana. Termasuk undang-undang tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan tahun 1986 tentang peradilan umum dan peradilan tata usaha negara. Dengan kata lain, dasar hukum hampir seluruh lembaga peradilan yang ada di Indonesia akan goyah. Usul Soeprapto agar umat Islam di Indonesia "melaksanakan sendiri syariat Islam", tanpa bantuan atau campur tangan negara, juga ditangkis. Bisa kacau, kata pendebatnya. Prof. Dr. Ismail Suny, guru besar teori ilmu hukum pascasarjana UI, misalnya, mengatakan, "Kalau pelaksanaan syariat diserahkan kepada umat Islam, apakah orang Islam di sini boleh saja memotong tangan pencuri?" Menurut Suny, untuk mengelakkan kekacauan seperti itulah undang-undang negara diperlukan buat mengatur apa saja di antara syariat itu yang bisa dilaksanakan di sini. Ada juga yang membantah ide Soeprapto dari segi praktis. Sundoro Syamsuri, juru bicara Fraksi ABRI, misalnya, mengatakan, "Secara bodoh saja, peradilan agama itu sudah ada, kalau tidak dibenahi atau ditiadakan, apa tidak malah membuat kacau?" Peradilan agama memang sudah ada. Sejarahnya juga panjang. Seperti dijelaskan Munawir Sjadzali di depan sidang pleno DPR tadi, peradilan agama sudah ada di nusantara "sejak agama Islam dianut oleh penduduk wilayah ini." Setidaknya (lihat selanjutnya: Masihkah Peradilan Agama Dipercaya?), dari kepustakaan yang ada, diketahui bahwa pada 1808 ada instruksi dari Pemerintah Hindia Belanda kepada para bupati, yang isinya melarang mengganggu urusan "agama orang Jawa" (maksudnya, tentu: bumiputra). Pemuka agama harus dibiarkan saja memutus perkara-perkara perkawinan dan kewarisan, sepanjang hal itu tak disalahgunakan. Di tahun 1882, Pemerintah Belanda meresmikan berdirinya peradilan agama di Jawa dan Madura. Saat itu memang berkembang pendapat di kalangan Belanda, bahwa hukum yang berjalan pada penduduk pribumi adalah undang-undang agama yang mereka yakini, dan itu Islam. Sebab, orang Islam setempat, menurut pendapat ini, sudah meresepsi hukum Islam secara keseluruhan. Sejak itu pula, pengadilan agama berdiri di kota yang sudah memiliki pengadilan umum. Wewenangnya mengadili perkara yang menyangkut agama, termasuk perkawinan dan kewarisan. Belakangan sikap Pemerintah Belanda memang berubah. Di tahun 1937, wewenang pengadilan agama disunat: tinggal menangani perkara perkawinan. Setelah kemerdekaan, di tahun 1957 dengan Peraturan-Pemerintah Nomor 45, Pemerintah mendirikan pengadilan agama di daerah-daerah di luar Jawa-Madura dan Kalimantan Selatan. Pengadilan itu disebut Mahkamah Syariah, dengan wewenang yang lebih besar, berhak mengadili peskara kewarisan serta berbagai perkara perdata Islam lainnya. Sejak itu Pengadilan Agama sudah ada hampir di seluruh Indonesia. Lembaga ini juga menyangkut sejumlah besar manusia. Sampai RUU-PA ini diajukan Pemerintah ke DPR, 3 Desember 1988, sudah terdapat 303 pengadilan agama dan 18 pengadilan tinggi agama, dengan 6.753 pegawai, dan 1.400 hakim. Setiap tahun, pengadilan itu menampung lebih dari 200.000 perkara. Maka, memang sulit dibayangkan repotnya bila lembaga ini ditiadakan. RUU-PA justru diajukan untuk dijadikan undang-undang dengan tujuan melengkapi lembaga yang ada. Jumlah pengadilan tinggi agama, misalnya, akan bertambah karena, dalam rancangan, pengadilan tinggi itu berkedudukan di ibu kota provinsi. Selain itu, RUU-PA menyeragamkan wewenang pengadilan agama di seluruh Indonesia. Wewenang untuk perkara kewarisan yang selama ini cuma dimiliki oleh pengadilan agama di luar Jawa-Madura dan Kalimantan Selatan akan berlaku di seluruh Indonesia. Ditambahkan juga kepadanya wewenang eksekusi atas perkara-perkara yang sudah diputusnya. Selama ini, eksekusi baru bisa dilaksanakan dengan persetujuan pengadilan negeri. Maka, setiap pengadilan agama nanti memiliki juru sita. Penyempurnaan pengadilan agama tak cuma menyangkut organisasi dan personalia. Juga prosedur. Semua Pengadilan agama kelak akan menggunakan hukum acara yang berlaku di pengadilan umum. Kecuali untuk perkara tertentu yang tak diatur oleh peradilan umum, misalnya perkara sengketa perkawinan tentang cerai talak dan cerai gugat. Gengsi pengadilan agama juga akan naik. Menurut UU Nomor 14 tahun 1970, yang mengatur ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, pelaksaan kekuasaan kehakiman harus dibagi atas empat jenis peradilan: peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Keempat jenis peradilan itu berpucuk pada Mahkamah Agung, selaku satu-satunya lembaga kasasi. Bila diamati, memang tak terlalu banyak yang akan berubah dengan RUU ini. Kenapa banyak debat? Jawabnya: karena menyangkut pandangan dasar tentang pembinaan hukum di Indonesia. Sejauh mana hukum harus satu dalam unifikasi, sejauh mana pula kebhinekaan rasa keadilan dan tradisi khusus diberi tempat, itu soal yang selalu timbul di sebuah negara seperti Indonesia. Apalagi para pakar hukum bisa mengajukan pandangan yang silang-menyilang Prof. Ismail Suny, misalnya, menafsirkan unifikasi hukum itu tak sama dengan menciptakan hanya satu hukum yang berlaku untuk seluruh warga negara. Ia menunjuk pasal 29 UUD 45, yang memberi kebebasan memilih agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Konsekuensinya, penganut Islam boleh menganut hukum perdata Islam yang lain dengan penganut Kristen, misalnya. Sudah sejak zaman Belanda, di Indonesia ada hukum perdata burgerlijk wetboek (BW), yang menurut Suny "dijiwai oleh ajaran Kristen". Soalnya, ketika dibuat dulu, hukum itu untuk orang Belanda di Indonesia yang menganut Kristen. Sebab itulah, kata Suny, Garis Besar Haluan Negara tahun 1983 menentukan bahwa unifikasi hukum dilakukan pada bidang-bidang tertentu, "dengan memperhatikan kesadaran hukum di tengah masyarakat." Berbeda dengan Suny, ahli hukum tata negara dari Universitas Padjajaran di Bandung, Prof. Sri Sumantri, berpendapat bahwa harus ada satu kesatuan hukum nasional. "Sesuai dengan apa yang dikehendaki Wawasan Nusantara," katanya. Karena itu, ia menganggap UU Nomor 14 Tahun 1970, yang menghendaki adanya sebuah undang-undang peradilan agama tersendiri, bertentangan dengan Wawasan Nusantara. Tapi Sumantri menyadari, unifikasi dalam hukum yang menyangkut keluarga itu sensitif, karena menyangkut masalah agama. Sebab itu, ia menganggap soal seperti ini harus diselesaikan dengan arif. RUU-PA itu bisa saja diterima, "tapi harus dianggap sebagai undang-undang sementara, menunggu adanya hukum perdata nasional yang akan mencakup seluruh bidang hukum." Ahli hukum tata negara yang lain, Padmo Wahyono, bisa menerima adanya peradilan agama, seperti disebutkan UU Nomor 14 Tahun 1970, yang khusus untuk keperluan orang-orang Islam. Sebab, belum ada lembaga hukum yang menegakkan hukum perdata Islam seperti masalah waris, talak, cerai, dan sebagainya. Padahal, untuk orang Kristen sudah ditampung di dalam BW. Namun, bagi ahli hukum ini, "peradilan" tidak harus sama dengan "pengadilan". Maksudnya, kurang-lebih, yang pertama menyangkut proses, yang kedua menyangkut lembaga. Sekalipun ia setuju adanya peradilan agama, ia menolak adanya "Pengadilan Agama" yang khusus disediakan untuk orang Islam. Menurut Padmo Wahyono, peradilan agama lebih baik jadi salah satu kamar di pengadilan negeri -- satu hal yang sebenarnya agak mirip dengan pendapat sejumlah tokoh partai Islam Masyumi di tahun 1950-an. Padmo Wahyono, seperti banyak orang lain, memperkirakan, dalam bentuk yang sekarang, RUU itu bisa menyebabkan orang-orang non-muslim merasa didiskriminasikan. Sebenarnya bisa saja orang Islam menggunakan hukum perdata Islam tapi perkaranya dilaksanakan di pengadilan negeri -- lembaga yang juga menyelesaikan perkara warga yang beragama lain. Tapi toh Padmo Wahyono menyadari, itu tampaknya sulit dilaksanakan, karena menyangkut sebuah lembaga yang sudah mapan. Lagi pula, mungkin soal yang pokok bukan iri hati dari kalangan agama lain. Mgr. Leo Soekoto, Wakil Ketua Konprensi Wali-Wali Gereja Indonesia (KWI), misalnya, menanggapi RUU itu secara pribadi, karena KWI sendiri belum mengeluarkan sikap resmi terhadap RUU-PA. "Kami, umat Katolik," kata Leo Sukoto "tidak merasa didiskriminasikan dengan RUU-PA." Menurut Uskup Agung Jakarta itu, sudah merupakan sikap umat Katolik, melihat negara dan agama sebagai dua aparat yang memiliki otonomi sendiri-sendiri. Sebab itu, ia tak merasa perlu sebuah PA sendiri untuk umat Katolik. "Andai kata diberi pun, kita akan menolak," ujarnya. Itu tak berarti kalangan yang beragama Katolik, yang merupakan minoritas, tidak merasa prihatin. Dalam kata-kata Leo Sukoto: "Yang kami prihatinkan, apakah negara Pancasila yang sudah kita terima bersama akan tetap berupa negara yang kita terima semua?" Terjemahan kata-kata halus itu ialah sejauh mana kelak Indonesia masih akan tetap menganggap umat Katolik, yang juga warga negara Indonesia yang sederajat dengan umat Islam, tidak pada akhirnya jadi "anak tiri". Ahli filsafat Franz Magnis Suseno, yang menulis di harian Kompas Jumat pekan lalu, lebih tegas lagi dalam menyatakan kecemasannya: ia memberi contoh negara-negara yang menjadikan salah satu agama sebagai agama negara. Yang jelas, di sana, gejolak-gejolak yang ditimbulkan kaum fundamentalis tidak berkurang. "Diberi terlunjuk jari mau memegang seluruh tangan," tulis Franz Magnis Suseno. Di kalangan Kristen, reaksi resmi sudah keluar. Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) mengirimkan surat ke DPR, 10 Mei yang lalu, menyampaikan keputusan Sidang Mejelis Pekerja Lengkap PGI, tentang RUU-PA, akhir April yang lalu di Caringin, Jawa Barat. Isinya juga berupa kekhawatiran kalau RUU itu mengganggu konsensus nasional "yang menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara." Sidang itu juga berpendapat, sebaiknya, sebelum RUU-PA itu dibahas DPR, diadakan pertemuan di antara lembagal-embaga agama yang ada, untuk menciptakan semacam konsensus nasional, untuk menilai RUU itu. Saran itu memang mungkin tak praktis, tapi bisa dipahami. Selama ini, berbagai undang-undang yang berkaitan dengan agama memang selalu diamati dengan khawatir. Lihat saja, ramai-ramai di DPR, saat RUU Perkawinan dibahas beberapa tahun yang lalu. Sedikit repot juga terjadi pada saat RUU Pendidikan -- yang menyinggung soal pendidikan agama -- disahkan belum lama ini. Rupanya, kebhinekaan Indonesia selalu akan mengandung persoalan, sekalipun Pancasila sudah jadi asas tunggal. Harapan bukannya tidak ada: selama ini orang tak kepingin Indonesia berantakan.Amran Nasution, Rustam F. Mandayun, Ahmadie Thaha, Diah Purnomowati
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini