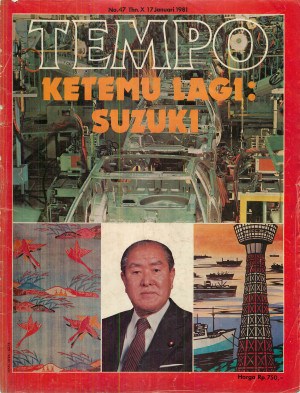SEPERTI orang normal, anak-anak itu dengan gampang menuju
rak-rak buku yang ada. Memilih buku yang dibutuhkan, kemudian
mendatangi meja penjaga perpustakaan untuk mencatatkan judul
yang hendak dipinjam.
Ruangan 10 x 4 meter itu, di Sekolah Luar Biasa (SLB) A
Cilandak, Jakarta, sepintas memang mirip perpustakaan lazim.
Orang baru bisa terkejut ketika melihat mata para penyunjung --
meskipun cara mereka berjalan, misalnya, memang sudah berbeda.
Tentu saja bukunya pun lain. Walaupun sampul buku warna-warni,
dan tercantum pula judul buku dengan huruf Latin (di samping
huruf Braille), semua halaman dalam putih belaka. Tak ada gambar
huruf maupun gambar biasa, kecuali tonjolan kecil-kecil. Kata
Ny. Sumartilah, salah seorang pengasuh SLB, setengah bergurau
"Tentu saja buku komik tak ada di sini."
Dari ruang itulah anak-anak SLB A (khusus buta) Cilandak
mengharap tambahan pengetahuan di luar kelas. Apa boleh buat.
Media film, slide atau buku-buku biasa memang tak berbicara
kepada mereka.
Hanya, jenis buku ternyata terbatas sekali. "Kami kekurangan
buku bacaan. Lebih banyak Al Quran, disumbangkan dari Departemen
Agama," kata Ny. Sumartilah, yang mulai mengajar di SLB SD dan
SMP itu sejak 1967.
Tidak berarti tak ada perhatian mlsyarakat. Masalahnya:
buku-buku yang mereka sumbangkan adalah buku-buku biasa --
berhuruf dan bergambar. Bagaimana anak-anak tunanetra bisa
membaca? Tapi mengharap sumbangan buku berhuruf Braille agaknya
memang susah, meski di Bandung sudah ada percetakan Braille.
Para penyumbang sendiri mungkin ada yang belum pernah melihat
huruf itu.
Untunglah pihak sekolah itu tak tinggal mengeluh. Mereka lantas
menyalin buku-buku yang dipandang bermanfaat dengan huruf
istimewa itu -- menggunakan mesin tulis Braille juga, tentu.
Juga ada beberapa yang lantas direkam ke dalam kaset -- untuk
didengarkan.
Dalam soal menyalin ke dalam huruf Braille inilah ada sumbangan
besar dari Kelompok Sukarela Penyalin Braille. Kelompok ini
terdiri dari ibu-ibu. Hanya saja mereka memang belum sangat
menguasai tulisan Braille. Karena itu setiap sumbangan buku dari
kelompok ini dikoreksi dulu oleh Mulyadi, guru Bahasa Indonesia
di situ -- yang juga tunanetra.
Di Wisma Tan Miyat, bersebelahan dengan SLB itu, lembaga
pendidikan tunanetra bagi yang telah tak pantas masuk SLB
Cilandak, ada pula perpustakaan Braille. Tapi koleksi bukunya
bahkan kalau tak salah lebih sedikit. "Kini anak-anak Tan Miyat
mulai segan ke perpustakaan, karena bukunya itu-itu juga," kata
Ny. S. Yochana, salah seorang pengasuh. Kecilnya jumlah koleksi
-- selain tak tercatatnya jumlah buku dengan baik, seperti juga
di SLB -- bisa dilihat dari mudahnya anak-anak itu mencari dan
mengambil buku sendiri, tanpa diperlukannya kartu katalog.
Sitti Nurbaya
Tapi jangan khawatir. Di Bandung ada perpustakaan Braille yang
agak lebih lengkap. Terletak dalam kompleks Panti Asuhan
Tunanetra Wiyata Guna. Maklum perpustakaan ini tak berdiri
sendiri -- dengan badan penerbitnya merupakan bagian dari Balai
Penerbitan Braille Indonesia (BPBI), yang ketika berdiri --1961
-- bernama Lembaga Penerbit dan Perpustakaan Braille Indonesia.
Balai ini di bawah Departemen Sosial.
Perpustakaan itu terutama dipakai anak-anak Panti Asuhan
Tunanetra Wiyata Guna, selain peminjam luar. Dan sebagaimana di
perpustakaan biasa sering pula peminjam tak mengembalikan buku.
"Memang tak ada sanksi bagi yang tak mengembalikan buku," tutur
Freddy Mangkupatih, Kepala Bagian Perpustakaan.
Koleksi buku di sini sekitar 2.5 buah. Ada sebuah katalog yang
memuat daftar judul. Lewat katalog itulah para peminjam memilih
buku, dan petugasnyalah yang mengambilkan. Kecuali buku
pengetahuan, juga beberapa novel Indonesia telah dibraillekan
Sitti Nurba ya karangan Marah Rusli, Tenggelamnya Kapal van der
Wijck Hamka, Salah Asuhan Abdul Muis.
Yang juga sangat banyak dipinjam adalah majalah Gema Braille,
yang terbit sejak berdirinya percetakan Braille pula -- 1959 --
dan beroplah 2.500 eksemplar.
Ini majalah bulanan. "Tapi sering ngaret," kata H. Aan Suhana,
tunanetra yang menjadi pimpinan redaksinya. Biaya mencetak
majalah Braille memang jauh lebih mahal. Untuk 2.500 eksemplar
itu saja mencapai sekitar Rp 1 juta." Itu tak termasuk
honorarium penulis. Karena penulis dibayar gratis." Dan memang
sumbangan tulisan dari tunanetra sendiri jarang -- kebanyakan
artikelnya kutipan majalah biasa.
Isinya gado-gado. "Karena peminatnya dari anak-anak sampai orang
tua, kami sulit menentukan rubrik yang paling mereka gemari,"
kata Suhana lagi. Ada kritik dari Sugiono, tunanetra siswa SPG:
"Seharusnya ada rubrik musik dan sahabat pena. Tunanetra
rata-rata senang musik, lho."
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini