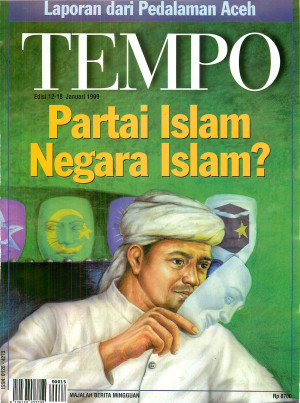Gedung KNPI Kabupaten Aceh Utara di Jalan Iskandar Muda 29, Lhokseumawe, itu persis berdampingan dengan Markas Komando Resor Militer Lilawangsa. Hanya berbatas tiga lajur kawat berduri. Di seberang jalan, hanya berjarak sekitar 50 meter, tinggallah Kolonel Johnny Wahab, orang pertama militer di resor militer Aceh. Di dalam gedung organisasi pemuda tadi, ditahan 39 orang yang diduga pihak militer pengikut Muhammad bin Rasyid alias Ahmad Kandang. Anak muda yang ditaksir berusia 30-33 tahun itu disebut pihak militer sebagai gembong Gerakan Aceh Merdeka.
Waktu buka puasa tiba, jam 18.30, dan petugas Korem membagikan makanan kepada para tahanan. Di rumahnya, Kolonel Johnny Wahab tengah berbuka puasa bersama Tengku Abdul Rahman, kiai muda Aceh yang pernah ditahan selama delapan tahun. Mendadak, sekitar 19.45, masuklah 50 orang tentara dari berbagai kesatuan ke Gedung KNPI. Mereka tak berseragam, tapi bersepatu lars. Petugas provos yang menjaga lokasi itu mencoba menahan, tapi pasukan rupanya sudah gelap mata. Adegan mengerikan itu terjadilah: para tahanan--yang sebagian besar bercelana jins--dipukuli, ditendang, dan diinjak. Sebagian besar luka-luka sangat serius di bagian kepala. Dua orang langsung tewas, dua lagi menyusul esok harinya, dan 21 orang luka parah terbaring di Rumah Sakit Lhokseumawe. "Saya benar-benar kecopetan, padahal gedung itu sudah dijaga," kata Kolonel Johnny Wahab ketika dilapori seorang aparatnya, dua jam setelah kejadian "berdarah" itu. Ia segera bertindak: menahan aparatnya yang diduga terlibat aksi "tinju bebas".
Luka kembali menganga di Aceh. Dalam dua pekan terakhir ini, lebih dari 20 orang tewas. Dan perjuangan Gerakan Aceh Merdeka, yang menuntut pembebasan Aceh dari Republik Indonesia--sebuah gerakan yang timbul-tenggelam selama 100 tahun ini--kembali menjadi berita di panggung internasional. Tokohnya kali ini adalah Ahmad Kandang, anak muda bercelana jins dan berjaket kulit, yang lolos dari kepungan seribu tentara dalam penyerbuan sengit di Desa Blang Kandang, Kecamatan Muara Dua--sekitar enam kilometer dari pusat Kota Lhokseumawe--Sabtu pekan lalu. Tentara menewaskan 11 orang dan menahan 39 orang, juga bendera Aceh Merdeka, dari sebuah musala--bergambar bulan dan bintang.
Penyerbuan itu dipicu oleh kejadian di Lhokseumawe pada Desember 1998. Sebuah kejadian kecil di awal bulan puasa di Desa Bayu: seorang bintara pembina desa menarik kain mukena seorang ibu yang berangkat salat tarawih. Berita yang menyebar laksana angin membuat kemarahan meruap cepat. Markas Komando Rayon Militer di kecamatan setempat dihujani batu, tapi usaha membakarnya bisa dicegah aparat yang segera berdatangan. Dalam aksi sweeping oleh massa, Mayor Harahap, perwira di Korem Aceh, dipaksa turun dari mobilnya dan kemudian digebuki sampai patah tangan.
Sweeping terus berlanjut sampai menjelang akhir tahun. Di dalam Bus "Kurnia", yang dicegat massa di Desa Lhoknibung, ada 18 tentara dan dua orang polisi. Tak semua aparat itu memiliki kartu tanda penduduk. Tujuh orang aparat yang tak membawa KTP akhirnya disandera. Tapi, dua hari kemudian, empat anggota ABRI itu ditemukan mati secara mengenaskan di Sungai Arakundoe. Sebelum tewas, korban diikat dari kaki hingga kepala. "Mereka diperlakukan secara biadab," kata Kolonel Johnny Wahab, keras. Dari tiga "sandera", sampai sekarang tinggal dua orang anggota marinir yang belum ketahuan nasibnya.
Pihak militer segera menggelar Operasi Satgas Wibawa '99. Inilah operasi militer pertama yang digelar setelah status Aceh sebagai daerah operasi militer (DOM) dicabut pada 3 Agustus 1998. Sasaran utama adalah penegakan hukum. Tapi ketika bedil menyalak, korban pun berjatuhan, termasuk korban yang tewas karena dijadikan "sansak hidup" tentara di Gedung KNPI tadi.
Kondisi para korban, seperti disaksikan wartawan TEMPO di Rumah Sakit Lhokseumawe, koyak-moyak. Ruang gawat darurat berbau anyir darah. Ketika perawat menyiramkan air ke lantai ruangan 5X5 meter persegi itu, air berubah merah kecokelatan. Dokter Mulya A. Hasjmy--putra tokoh Aceh Ali Hasjmy--bersama perawatnya bekerja keras malam itu. Dua korban berusia 19 dan 20 tahun yang tewas dengan kepala bonyok dimasukkan ke kamar mayat, dua orang yang koma dan 19 yang luka parah dikirim ke ruang perawatan. Seorang polisi militer mengawasi kerja para dokter ini.
Di bangsal, korban tergeletak di tempat tidur, di antaranya hanya beralaskan papan. Ada yang satu tempat tidur berdua. Bangsal itu sunyi, tak ada lenguhan manusia, karena semua korban tak sanggup merintih sekalipun, meski mulut mereka menganga. Jika ada suara, itu dari korban yang mengigau sesekali. "Latifah?Latifah?," ujar seorang korban lirih, entah menyebut siapa, karena korban tak bisa ditanya apa-apa. Ada yang menyebut nama lain, ada yang tak jelas menyebut apa.
Dari sejumlah korban itu, hanya seorang yang bisa diajak bicara. Cairan infus di tangannya hampir habis. Darah merah masuk melewati selang. Dengan bahasa Indonesia seadanya, lelaki 38 tahun dengan sorot mata tajam ini mau menjawab pertanyaan. Dia bekerja sebagai tukang "RBT"--di Jakarta disebut ojek, di Aceh itu singkatan dari "rakyat banting tulang". Anaknya lima, tinggalnya di wilayah Kandang, di Meunasah Blang. Ketika Kandang diserbu, ia tengah berada di sana. "Keretaku ditendang tentara, aku jatuh, langsung ditangkap, dibawa pakai truk tentara. Aku tidak tahu keretaku ada di mana sekarang," ceritanya. Yang dimaksudnya "kereta" tentu saja adalah sepeda motor. Di atas truk itu mereka dipukuli dan diinjak. Ketika sampai di markas, azab terus mendera. "Tentara itu tidak memeriksa, mereka menyepak di kepala, di badan, di kerongkongan. Sekarang saya tidak bisa makan, suaraku rusak. Katanya aku ini anak buah Ahmad Kandang, padahal saya bukan anak buah dia," katanya pelan. Ketika pembicaraan usai, ia menggamit tangan reporter TEMPO dan berkata, "Tolong aku, Pak. Anak-istriku belum tahu kalau aku ada di sini. Aku tidak bersalah apa-apa."
Di sebuah pojok tergeletak Rahman Husen, lelaki 30 tahun, ditemani istri dan anak perempuannya yang baru tiga tahun. Husen dalam keadaan koma. Ia penduduk Desa Meunasah Blang, dan karena itu ia dituduh anak buah Ahmad Kandang. "Suami saya diperlakukan seperti binatang. Saya ini orang miskin, tidak tahu apa-apa. Mengapa tentara tega melakukan hal itu. Semua laki-laki di Meunasah Blang dipukul dengan senjata, ditendang-tendang," kata istri Husen dalam isak tangis yang pilu. Husen adalah satu-satunya korban yang sudah ditunggui oleh keluarganya.
Mengapa tentara begitu bernafsu menangkap Ahmad Kandang? Benarkah ia tokoh penting dalam peta Gerakan Aceh Merdeka ini? Jika benar ia dalang perampokan Rp 400 juta di BCA Lhokseumawe, agaknya kekuatan Kandang perlu dicatat. Soalnya, ketika itu BCA diberondong dengan senjata AK 47 dan pistol Colt 38. Seorang satpam tewas, tiga polisi juga luka-luka, kantor polisi lalu-lintas di dekat BCA juga dihujani peluru. Keahlian senjata itu dikabarkan diperoleh Ahmad Kandang dari pelatihan di Malaysia. Ia juga tercatat sebagai anggota Angkatan Perang Aceh Merdeka. Dan ia sejak kecil memang sudah merantau, antara lain ke Malaysia. Ayahnya, Rasyid, adalah pensiunan ABRI, yang berpindah-pindah tempat tugas. Itu sebabnya Ahmad tak dikenal luas di desanya. Sebagian orang mengenalnya sebagai teungku, semacam ustadz yang paham ilmu agama. Namanya baru terdengar setelah "peristiwa Semenyih", insiden pemulangan secara paksa tenaga kerja Indonesia dari Malaysia pada April 1998.
Ada banyak versi soal Kandang. Sebelum kerusuhan, kata banyak orang, ia sering terlihat berseliweran memanggul senjata. Tapi, anehnya, ia tak dijamah aparat keamanan. Sumber TEMPO menceritakan bahwa pada hari penyerbuah tentara ke desanya, Ahmad malah bebas berkeliaran di desa tetangga. Seseorang yang diperiksa KTP-nya oleh anak buah Kandang diminta menemui Kandang yang tengah duduk di atas Vespa. Sangat mungkin cerita begini jauh dari kebenaran. Tapi ada yang menduga, Kandang bekerja untuk ABRI. Sangkaan ini ditampik banyak kalangan karena Kandang dan komplotannya dianggap yang melakukan penculikan dan pembunuhan atas anggota ABRI.
Lahirnya tokoh Kandang dan jatuhnya korban jiwa justru pada saat Aceh dibebaskan dari status DOM ini mengundang pertanyaan. Otto Syamsuddin Ishak, aktivis organisasi masyarakat dari Banda Aceh, menuturkan bahwa sejak DOM dicabut ada rentetan kejadian panas: pembakaran rumah geudong, kerusuhan Lhokseumawe, dan gerakan rakyat mempersenjatai diri. Ia menganalisis ada tiga skenario yang mungkin menjawab kekerasan tadi. Yaitu, masyarakat memang tidak puas dengan penyelesaian pemerintah yang hanya mencabut DOM--seraya pemerintahan Habibie meminta maaf--tanpa adanya penyelesaikan secara hukum. Lalu, bisa saja kekerasan yang terjadi memang menunjukkan bahwa Gerakan Aceh Merdeka bangkit lagi. Selanjutnya, ada rekayasa orang-orang tidak dikenal yang melakukan sweeping dan menyandera anggota marinir. Padahal, marinir selama ini mendapat tempat di hati rakyat Aceh. "Apakah ini skenario untuk melibatkan marinir dalam kekacauan ini?" tanya Otto. Sulit untuk menjawab Otto.
Yang lebih mudah adalah menjelaskan bahwa derita rakyat Aceh memang sudah bertumpuk-tumpuk. Dua tahun sejak DOM diberlakukan, pada tahun 1989 saja diduga sudah dua ribu penduduk sipil Aceh--termasuk wanita dan anak-anak--hilang, dibunuh, atau ditahan tanpa persidangan. Amnesty International yang mencatat data tadi juga melaporkan soal kekerasan yang dialami mereka yang dituduh pengikut Gerakan Aceh Merdeka di penjara. Kesultanan Islam pertama di Indonesia yang kini punya 3,4 juta jiwa penduduk itu pada 1992 dilaporkan mempunyai 134 ribu janda--75 persen akibat suami mereka hilang atau dibunuh.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada Agustus 1998 mengeluarkan data yang "seram": 781 orang telah tewas di Aceh, 163 orang hilang, seratus orang perempuan diperkosa, sejak Aceh menjadi daerah operasi militer. Komnas punya angka bahwa janda akibat suami terbunuh atau hilang sekitar 3.000 orang.
Kasum ABRI Fachrul Razi mengatakan bahwa tindakan ABRI untuk pengamanan Aceh itu diminta oleh kepala daerah setempat. Tapi operasi belakangan hari ini terjadi karena "niat baik" ABRI menarik pasukan dimanfaatkan oleh kelompok gerombolan pengacau liar sisa Hasan Tiro untuk membangun kekuatan. "Pada operasi lalu, ditemukan ratusan ribu senjata yang berasal dari luar negeri," tutur Letjen Razi. Diakuinya, prajurit ABRI sangat marah dengan pembantaian terhadap anggotanya. Kendati begitu, Letjen Razi--yang segera berganti posisi--menegaskan bahwa DOM tak akan diberlakukan lagi. Tentu karena perwira tinggi bintang tiga asal Aceh itu tahu benar soal penderitaan rakyat di daerahnya.
Dan penderitaan akibat kekerasan itu tak sanggup ditutupi oleh pendapatan melimpah akibat bangkitnya industri di Aceh. Malah, hasil bumi yang dikeruk dari Aceh sungguh tak sepadan dengan dana dari pusat yang dikembalikan ke bumi Serambi Mekkah. Industri di Aceh tumbuh pesat sejak Mobil Oil menemukan gas alam di Arun, Aceh Utara. Industri lain segera menyusul: PT Aceh ASEAN Fertilizer, Pupuk Iskandar Muda, Kertas Kraft Aceh. Semua industri itu ada di Aceh Utara, sampai ada data bahwa 75 persen kehidupan Aceh bergantung pada Aceh Utara. Potensi gas alam Arun saja adalah yang terbesar di dunia. Tapi, menurut data 1997, anggaran pusat untuk Aceh hanyalah Rp 102 miliar atau hanya 0,05 persen dibandingkan dengan kekayaan alamnya. Maka, Ibrahim Hasan, bekas gubernur Aceh, dalam sebuah wawancara televisi mengatakan, "Aceh menyumbang 11 persen dari pemasukan negara. Tolong, berilah kami sedikit lebih banyak dari selama ini. Kalau tak mau melihat kami dengan dua mata, sebelah mata pun jadilah."
Perlakuan pusat yang timpang itu juga tak bisa diterima kalangan mahasiswa Aceh. Ketika ribuan mahasiswa menduduki Gedung RRI Aceh, 20 November 1998, contohnya, mereka menuntut kasus-kasus di Aceh segera diselesaikan. "Kalau tidak, kami akan menjadi aktivis-aktivis Aceh Merdeka di kemudian hari!," kata mahasiswa di depan corong RRI. Kasus-kasus itu adalah: pelanggaran hak asasi, atau sumber alam yang terus dikeruk tapi rakyat Aceh tidak menikmatinya.
Berbagai kekecewaan itu menyulut pentingnya referendum di Aceh. "Referendum lebih aman. Dengan begitu, kalau sudah pisah, Indonesia tak akan menyakiti Aceh, dan Aceh tak akan menyakiti Indonesia," ujar Otto Syamsuddin Ishak, yang juga Direktur Yayasan Cordova, sebuah lembaga swadaya masyarakat di sana.
Jika pemikiran Otto dan sebagian mahasiswa meluas, tuntutan untuk memisahkan diri dari RI agaknya akan jadi persoalan baru bagi Jakarta. Dan itu sama peliknya dengan memadamkan pemberontakan Aceh Merdeka.
Setiyardi, Mustafa Ismail, Zainal Bakri (Lhokseumawe), TH (Jakarta)
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini