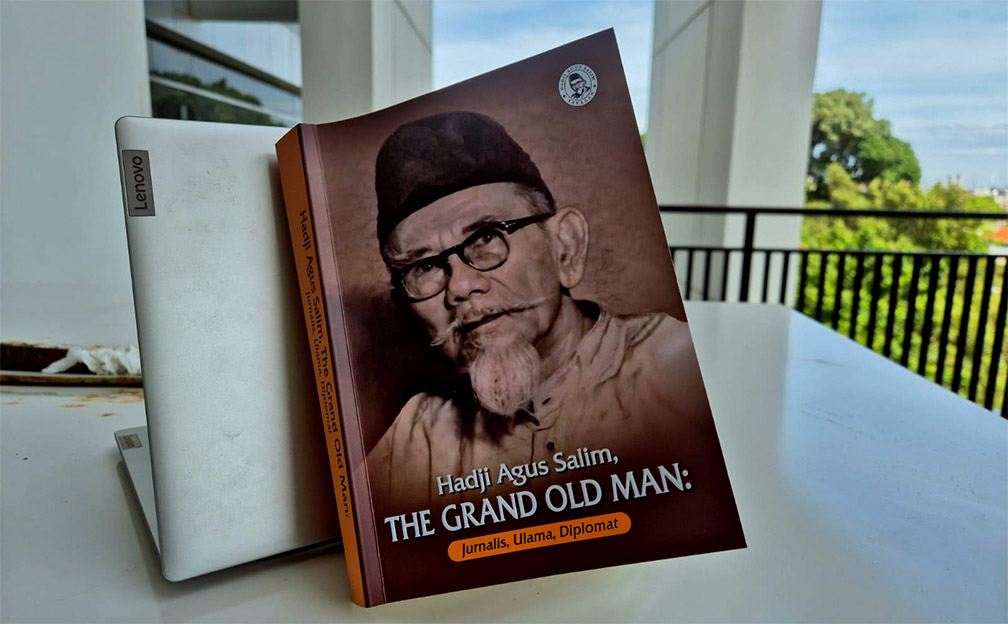Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pleidoi Sastra
Kontroversi Cerpen Langit Makin Mendung Kipandjikusmin
Editor: Muhidin M. Dahlan, Mujib Hermani
Penerbit: Melibas, Jakarta, 2004
Tebal: 484 hlm.
Seakan-akan ini keasingan jenis kedua.
Dulu, di tahun-tahun 1970-an, terdapat konstatasi mengenai betapa kesusastraan Indonesia hakikatnya barang yang minoritas. Ia hanya diterima oleh sebagian kecil masyarakat kota, yang berjumlah 15 persen dari keseluruhan penduduk. Status minoritas ini sebermula dihubungkan dengan predikat "modern" yang disandangnya, yang dilawankan dengan sifat tradisional sastra lama yang hanya dituturkan secara lisan. Jadi, kesusastraan modern kita mendapat sifat modernnya dari tulisan, dan pemakaian tulisan (Latin, bukan Jawi) itu menandai terjadinya akulturasi dengan budaya Barat, alias asing, seperti bisa dilihat khususnya sejak akhir abad ke-19.
Tetapi ciri-ciri akulturasi tersebut jarang kita bincangkan: keasingan itu tak pernah kita tunjuk. Seperti semua hal sudah begitu saja "menjadi milik kita", dan berjalan dengan semestinya. Juga ketika sebuah cerita pendek berjudul Langit Makin Mendung (LMM), dari pengarang dengan nama samaran Kipandjikusmin, yang dimuat majalah Sastra edisi Agustus 1968 mengguncangkan sekaligus dunia sastra dan dunia hukum kita waktu itu. Sebenarnya (atau seharusnya) itu menyadarkan kita akan hadirnya keasingan yang lebih dari sekadar menyangkut ciri-ciri lahiriah kesusastraan yang sudah disebut, yang lalu tampak seolah keasingan jenis kedua. Kita malah hanya merasakan munculnya "dua aliran".
Yakni yang memberi kebebasan penuh pada penggunaan imajinasi dalam sastra, di satu pihak, dan yang tidak. Itulah yang muncul sampai-sampai dalam perdebatan di pengadilan—ketika H.B. Jassin, Pemimpin Redaksi Sastra, diajukan ke sana untuk dakwaan penghinaan kepada Tuhan, Nabi Muhammad, agama Islam, dan seterusnya, dengan pemuatan LMM, sementara ia tak bersedia membukakan identitas si pengarang yang seharusnya bertanggung jawab.
Yang bisa mengejutkan sebenarnya ialah munculnya, untuk pertama kalinya, perdebatan mengenai imajinasi itu. Tapi itu hakikatnya hanya percikan-percikan di sebelah depan dari latar belakang jeram keterbelahan ini: antara yang meyakini bahwa sastra, dan itu berarti imajinasi, sebagai praktis alternatif agama, dan yang menganggapnya—dengan pembatasan imajinasi—sebagai sarana indah pengucapan seseorang yang sangat mungkin masih menyandarkan segala normanya pada agama. Inilah, sebenarnya, gunung es yang dibawa akulturasi.
Yakni relativitas agama, atau wacana sekitar itu. Inilah yang akan melatarbelakangi semua tulisan yang "bikin ramai" karena dianggap orang agama menghina keyakinan mereka. Dan kedua pihak itu tak akan bertemu. Bila penulis seperti Kipandjikusmin tidak merasa salah dengan melukiskan Tuhan (kebetulan Tuhan Islam, kelihatan dari segala atributnya) berkacamata emas, atau berbagai gambaran antropomorfis lain, dengan laku menyindir atau olok-olok, bagi orang agama yang dilakukannya itu bukan "semata-mata sastra, tak ada hubungannya dengan agama".
Tak ada hal yang "tak ada hubungannya dengan agama"—bila agama itu, di sini, tidak seperti di Barat, paling tidak, hidup, dan kelihatan bukan makin diingkari melainkan makin diinginkan dipahami. Sastra, imajinasi, kemerdekaan, dengan begitu dipersilakan berkembang, dan dipersilakan juga bikin sastra yang dikagumi dan asing.
Buku ini, yang cantik dan penuh salah-tulis, memuat "semua" karangan pro-kontra kasus Sastra—termasuk dari Hamka, di samping Jassin. Yang menarik ialah sangat miskinnya informasi tentang Kipandjikusmin. Jangankan lagi usaha untuk menemuinya—seperti yang dilakukan Usamah, wartawan Ekspres dahulu, yang sebenarnya bisa dirunut. Juga keterangan yang menyesatkan mengenai si pengarang yang, katanya, "berdiam di Yogyakarta dan kuliah di salah satu perguruan tinggi Islam". Penelitian yang lebih serius menyebut Kipandjikusmin dididik sebagai Protestan, lalu Katolik, lalu kembali ke Islam. (TEMPO, 30 April 2000, Layar).
Syu'bah Asa
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo