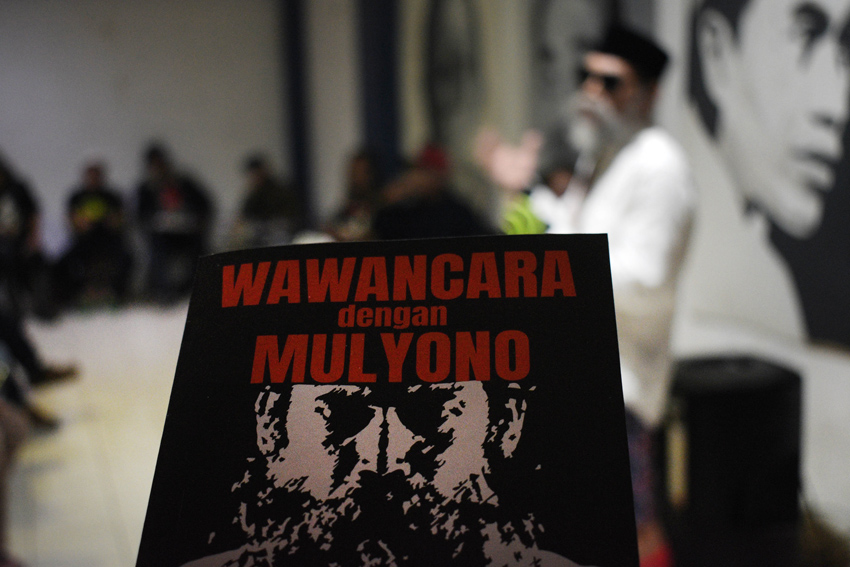Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TORIQ Hadad berpulang pada Sabtu subuh, 8 Mei lalu. Selepas sahur, saya mendapati telepon seluler saya mengabarkan pesan tak berjawab dari nomor telepon almarhum. Saya menelepon balik. Di ujung saluran terdengar suara istrinya bicara sambil terisak. Setelah seminggu sebelumnya mendapat kabar dia masuk rumah sakit, pagi itu saya tahu saya kehilangan seorang sahabat.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Saya bayangkan dia pergi dengan tenang—tak peduli pada pelbagai slang medis yang berseliweran di tubuhnya. Juga bunyi bip dari mesin-mesin yang memberi pelbagai isyarat kesehatan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Di ruang jenazah, beberapa saat kemudian dia terbujur di dipan dari logam. Wajahnya bersih. Putih seperti bayi. Rambutnya rapi tersisir ke belakang. Misai tipis membayang di pipinya yang tirus.
Tiga pekan sebelum berpulang, sehari setelah mendapat vaksin Covid-19, dia mengeluh mengalami sesak napas dan sulit tidur. Mula-mula dia menyangka itu hanya efek vaksin. Tapi penyakit itu berlanjut. Dia lalu meminta cuti untuk berobat. Dalam periode perlop, dia masih muncul dalam rapat Tempo dan buka puasa virtual yang diselenggarakan sebuah perusahaan. Seminggu di rumah sakit, dia didiagnosis mengalami penurunan fungsi ginjal, pembengkakan jantung, dan gangguan pada paru-paru.
Berpulang pada usia 61 tahun, Toriq telah mencapai semuanya—setidaknya jika “semuanya” itu adalah ukuran dalam jalan hidup seorang wartawan.
Masuk Tempo pada 1985, dia memulai kariernya sebagai reporter di biro Jakarta. Dia pernah menjadi pemimpin redaksi majalah Tempo dan Koran Tempo, lalu naik menjadi direktur dan direktur utama. Ketika wafat, Toriq adalah Chief Executive Officer PT Tempo Inti Media, korporasi dengan 11 anak perusahaan.
“Saya belajar menulis dari Mas Santo,” katanya. Yang dimaksud adalah mendiang Susanto Pudjomartono, redaktur pelaksana majalah berita mingguan Tempo yang belakangan menjadi pemimpin redaksi harian The Jakarta Post lalu menjadi duta besar di Rusia. “Saya duduk di samping Mas Santo melihat bagaimana tulisan saya disunting,” tuturnya.
Pada 1994, ia terlibat dalam liputan pengadaan kapal dari Jerman oleh Menteri Riset dan Teknologi Bacharuddin Jusuf Habibie. Karena liputan itu, Tempo ditutup pemerintah.
Toriq-lah orang yang mewawancarai Deputi Analisis Industri Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Suleman Wiriadidjaja. Saat itu, ada kehebohan di kantor Suleman yang satu gedung dengan kantor Habibie. Para pegawai kasak-kusuk. Penasaran dengan keriuhan itu, Toriq meninggalkan wawancara dan bertanya kepada seorang pegawai: ada apa? “Ada kapal Jerman tenggelam di teluk di Spanyol,” ujar seorang petugas. Toriq meninggikan antena jurnalistiknya. Tenggelam? Kapal perang Jerman Timur yang baru saja dibeli pemerintah Indonesia? Kok bisa? Kabar itu dibawa ke sidang redaksi. Beberapa minggu kemudian, Tempo terbit dengan judul “Habibie dan Kapal itu”—edisi yang mengakhiri nasib Tempo pada era Orde Baru.
Menjadi wartawan, dia disiplin dalam bekerja. Ia dikenal angker dalam soal tenggat. Saat menjadi redaktur eksekutif—jabatan semacam sekretaris jenderal di kementerian—dia tak segan menghardik penulis yang mengabaikan deadline dan reporter yang duduk di kantor. “Reporter itu tempatnya di lapangan. Bukan di kantor!” ujarnya. Sebagai pemimpin majalah berita yang mengutamakan cerita di balik berita, ia harus memastikan anak buahnya mendapat story, bukan hanya news. Dia antusias kepada reporter yang membawa “daging” informasi. Tapi dia kembali menghardik jika informasi itu berhenti pada info—omong-omong yang tak terkonfirmasi kebenarannya.
Tulisan Toriq lincah. Ia bisa menggunakan kalimat ringan bergaya staccato untuk menjelaskan persoalan yang rumit. Reportasenya “basah”. Alur tulisannya lancar. Kutipan, deskripsi, data, dan humor diaduknya dengan memikat.
Sebagai wartawan olahraga, dia bisa menjelaskan pertarungan tinju atau catur dengan sama baiknya. Pengetahuannya tentang sport mengagumkan. Ia bisa menjelaskan bet pingpong—olahraga yang diminatinya—dari pelbagai aspek: sejarah, siapa atlet penggunanya, bahan baku, hingga kaitannya dengan teknik menepok. Sebagai editor, dia piawai meluruskan tulisan yang bengkok dan memperjelas apa yang semula berkabut. Ia memang bukan prosais yang gemulai. Setahu saya, dia jarang menulis ulasan seni atau pertunjukan.
Ia tipe orang yang patuh pada aturan main. Dia penulis yang ketat menjaga angle—diam-diam beberapa teman menjulukinya “Mat Angle”. Sebagai pemimpin, dia tipe “bapak buah” yang cemas jika organisasi tak berjalan sesuai dengan tata cara. Ia bisa masuk ruang rapat dengan wajah garang, lalu cair beberapa menit kemudian ketika disadarinya semua oke-oke saja.

Direktur Utama PT Tempo Inti Media Tbk , Toriq Hadad, 20 Februari 2019. TEMPO/Rully Kesuma
Bambang Harymurti, bekas pemimpin redaksi yang kini menjadi Komisaris Tempo, dalam pidato di pemakaman menyatakan berutang budi kepada Toriq saat almarhum mendampinginya sebagai sekondan. Tak seperti Bambang yang pecicilan—sebentar di kantor, sebentar di luar kota, lalu ke luar negeri untuk kembali ke kantor lagi—Toriq setia mengendalikan “dapur”. Esais dan mantan pemimpin redaksi Tempo, Goenawan Mohamad, menyatakan, “Kehilangan orang yang teruji dalam gelombang yang naik dan yang turun”.
Kesetiaan pada nilai-nilai itu dipraktikkan Toriq ketika sebagai pemimpin redaksi ia menolak iklan sebuah bank pemerintah. Manajemen bank menawarkan kontrak advertensi bernilai puluhan miliar rupiah dengan syarat Tempo membatalkan liputan tentang skandal korupsi yang melibatkan pemimpin bank tersebut. Sikap Toriq tentu “mengecewakan” bagi divisi bisnis. Tapi Toriq memegang prinsip yang tidak bisa ditawar.
Itu sebabnya, ketika mengendalikan lini usaha sebagai direktur utama, Toriq menghargai kebebasan editorial. Tak pernah dia mencampuri urusan redaksi. Jika tidak sreg, ia akan menyampaikannya pada forum evaluasi—sesuatu yang post factum. Betapa pun independen, ruang redaksi tak boleh imun dari kritik.
Setelah saya tak lagi menjadi pemimpin redaksi, sesekali dia menelepon mengeluhkan berita yang menurutnya tak kukuh atau bahkan meleset. Sedapat mungkin saya mengolah kritik itu dan menyampaikannya ke sidang redaksi dengan bahasa yang tidak mencampuri.
Dengan kata lain, Toriq menghargai dinding api—tembok imajiner yang memisahkan kerja jurnalistik dan kerja bisnis. Toriq sadar produk jurnalistik yang baik hanya dapat tercipta jika ada kebebasan editorial.
Kesetiaan Toriq pada profesi di luar batas imajinasi. Ketika Tempo ditutup pada 1994, dia tak berganti profesi—sesuatu yang sebenarnya wajar di tengah kesulitan hidup para wartawan akibat pemberedelan. Bersama Goenawan Mohamad, dia bergabung dengan gerakan bawah tanah di Utan Kayu, Jakarta Timur, dan memimpin Institut Studi Arus Informasi, lembaga yang menyelenggarakan pelbagai diskusi dan menerbitkan buku-buku yang tak disukai pemerintah. Kepada sejarawan Janet Steele yang menulis buku sejarah Tempo berjudul Wars Within, ia mengaku bukan aktivis. “Itu bukan dunia saya”. Tapi dia menjalaninya dengan sukacita, meski kadang ngomel melihat para pegiat demokrasi yang, menurut dia, “Tak tertib membuat laporan keuangan”.
Toriq Hadad setia pada ruang lingkup. Dia bukan orang yang melampaui batas. Ia kadang cemas terhadap banyak hal, sesuatu yang kerap membuatnya gusar. Tapi saya melihat hal itu merupakan ekspresi tanggung jawabnya yang besar. “Dia memikul terlalu banyak pekerjaan. Kepada anak dan istrinya, saya meminta maaf,” kata Bambang Harymurti, terisak.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo



![Toriq Hadad, saat presentasi untuk terbitnya Koran Tempo, tahun 1999. [TEMPO/ FERNANDEZ H]](https://images-tm.tempo.co/all/2021/05/09/771819/771819_1200.jpg)