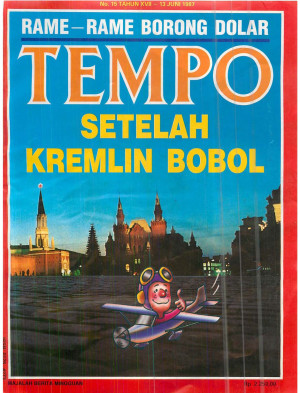DI tanggal 17 Agustus 1824, di Indonesia tak ada kemerdekaan. Tepat di hari itu, pada pukul 03.00 sore hari, seorang Arab berdiri di anjungan sebuah kapal yang tengah berkeliling Pulau Bali. Tiba-tiba ia melihat sebuah kejadian yang amat memilukan, yang kemudian dicatatnya baik-baik. Catatan itu seabad berikutnya jadi satu sumber sejarah yang berharga. Begini: Sore itu, di pantai Buleleng, berlabuh sebuah sekunar bertiang ganda yang dipimpin seorang kapten dengan awak 25 orang Prancis. Kapal itu dilengkapi dengan enam meriam dan sejumlah besar bedil, pistol, serta pedang. Tak ada barang dagangan di dalamnya. Yang ada hanya mata uang Spanyol. Gunanya: membeli budak. Salah seorang penjual budak konon adalah Raja Buleleng. Hari itu dijual seorang wanita dan dua anaknya. Wanita itu berumur sekitar 40, sedang kedua anaknya - laki-laki dan perempuan - berumur sekitar sembilan dan enam tahun. Karena si ibu sudah tua, kapten Prancis itu tak hendak membelinya. Ia hanya mau kedua anak itu. Tatkala sampai di pantai, Kapten menyuruh agar sepasang bocah itu dibawa, dan ibunya ditinggal. Kedua anak itu tak mau. Mereka memeluk leher ibu mereka erat-erat. Si ibu juga tak hendak berpisah dengan mereka, dan orang bertiga itu pun menangis kuat-kuat. Kapten marah. Ia menyuruh dua kelasinya memisahkan ketiga orang itu. Maka, kedua anak itu pun diangkut dengan paksa ke atas perahu, yang dengan sigap dikayuh ke sekunar. Si ibu, yang tertinggal di pantai, roboh, dan tergolek di sana bagaikan orang mati. Selama satu jam ia demikian. Ketika malam tiba, ia pun menangis dan menyeru, memanggil anak-anaknya. Tapi sekunar itu telah berangkat, orang-orang Prancis itu telah berangkat dan juga kedua budak belian mereka. Sang ibu tetap di pantai itu sampai beberapa hari, seperti menunggu, seperti mencari. Sia-sia. Sebab, (begitulah catatan itu kemudian berkata) "hati mereka yang telah menyebabkannya dalam keadaan demikian itu lebih keras ketimbang besi." Dan perdagangan budak pun jalan terus. Adegan di pesisir Buleleng itu hanya satu saja dari sekian kejadian di abad ke-19 dan sebelumnya. Saya mengutipnya dari sebuah buku yang disunting oleh Sejarawan Anthony Reid, Slavery, Bondage Dependeny in Southeast Asia, sebuah karya yang menarik, yang menunjukkan bagaimana perbudakan merupakan salah satu ciri sosial-ekonomi kawasan ini di masa silamnya. Budak, tulis Reid mengutip sebuah definisi, adalah seseorang yang merupakan milik orang lain, secara politik dan sosial lebih rendah ketimbang orang kebanyakan, dan menjalankan kerja paksaan. Di dalam sejarah Asia Tenggara, makhluk semacam itu amat besar jumlahnya di kota-kota: orang-orang yang ditaklukkan dalam peperangan atau si miskin yang terjerat utang, yang jatuh menjadi abdi, dan di dalam abad ke-17 dan ke-18, dijual ke Makassar maupun ke Batavia. Praktis, merekalah mayoritas penduduk pribumi. Baru dalam perkembangan kemudian, jumlah dan persentase mereka mengecil, terutama karena kian bertambah banyaknya keturunan orang yang sudah bebas dari perbudakan - dan karena seringnya budak-budak belian itu mati. Tak berarti hidup sebagai budak adalah hidup yang nestapa - setidaknya secara materiil. Ada memang di antara mereka yang jadi pekerja tanpa bayaran di usaha pertenunan milik seorang saudagar atau bupati. Tapi ciri utama pekerjaan para budak adalah sebagai pembantu rumah tangga dan penghibur nyonya & tuan besar suatu fungsi yang juga bisa menaikkan status sosial si empunya rumah. Dalam peran itu, konon, dibandingkan dengan para jelata kota yang hidup bebas di luar, para budak bisa makan lebih baik tidur lebih rapi, dan berpakaian lebih keren. Maka, yang mememilukan dalam peristiwa di pantai Buleleng itu mungkin bukanlah karena dua anak menjadi budak, melainkan karena seorang ibu harus direnggutkan. Tak mengherankan bila salah satu versi kisah Surapati, yang berbeda dari novel Abdoel Moeis yang terkenal itu, bercerita bahwa anak muda ini jadi budak karena ialah yang memohon kepada rajanya di Bali agar ia dijual sebagai budak. Alasan: agar ia bisa melihat Batavia. Konon, ada pepatah Siam yang mengatakan bahwa orang biasa menjual kemerdekaannya untuk bisa membeli sebutir durian. Namun, Surapati kemudian membebaskan diri, dan legendanya jadi ilham kita ketika melawan penjajah. Mungkin bukan kebetulan. Seorang penulis mengemukakan bahwa tak ada kata dalam bahasa-bahasa Asia untuk menerjemahkan arti freedom, tapi Reid mencatat bahwa kata "merdeka" sudah cukup lama ada dalam bahasa yang digunakan di Indonesia. Ketika orang Wajo di tahun 1737 membebaskan diri dari Bone misalnya, mereka memaklumkan: "Maradeka-lah bangsa Wajo: mereka hanya takluk kepada adat". Tapi tentu saja mereka tak berbicara tentang budak-budak mereka. Kemerdekaan sebuah negara memang tak selamanya menjamin kemerdekaan orang-orang yang lemah di dalamnya. Goenawan Mohamad
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini