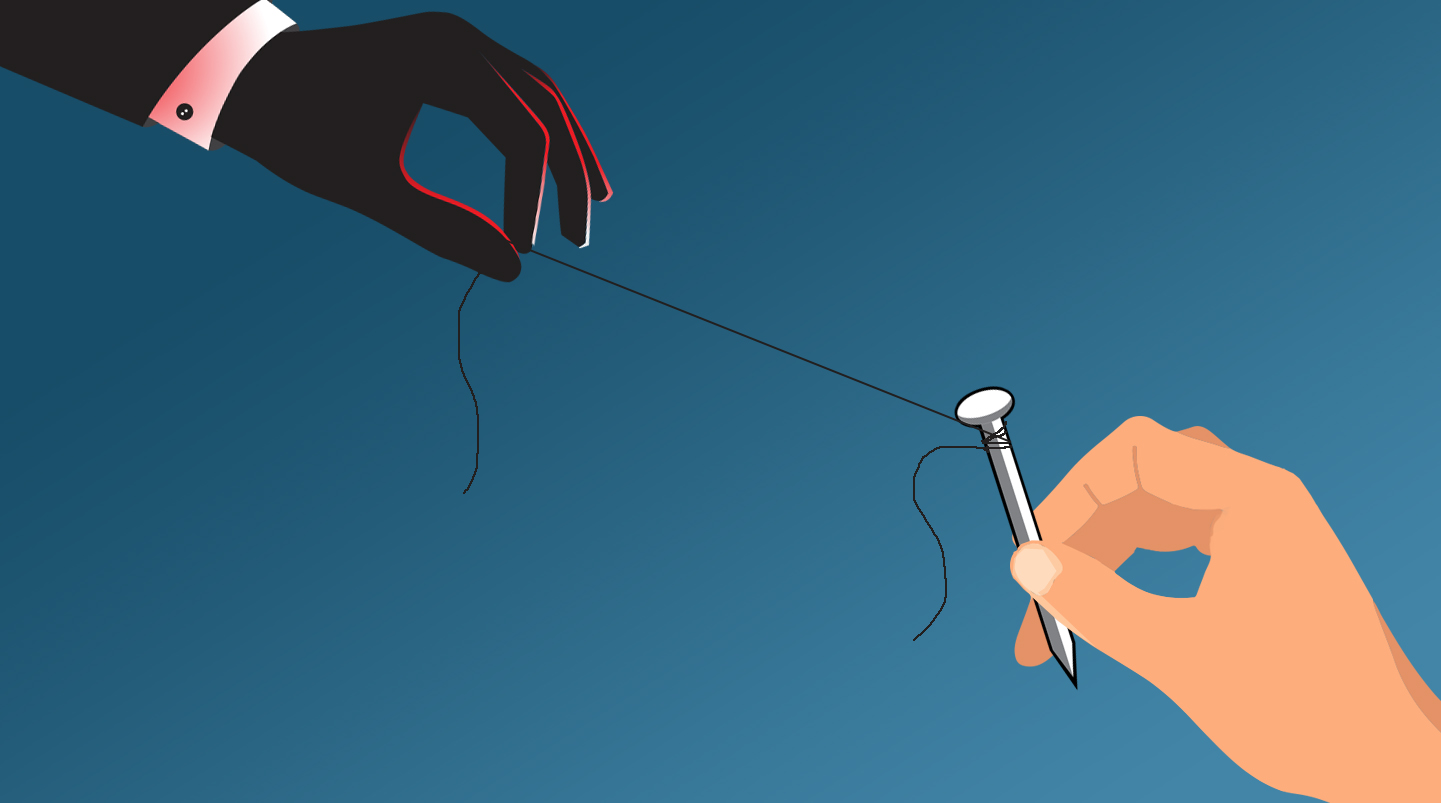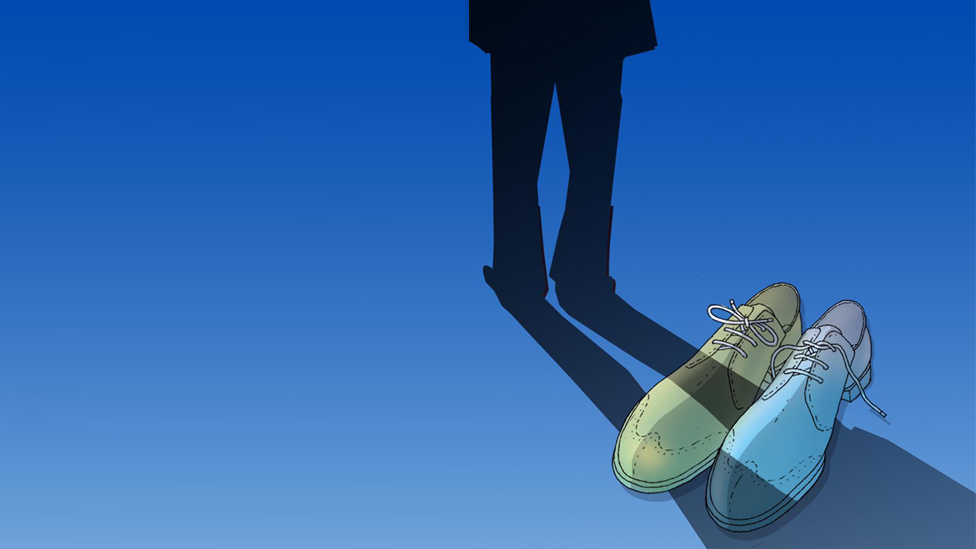Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Seno Gumira Ajidarma
PanaJournal.com
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Tentang politik, apa pandangan dari luar tentang Indonesia? Masih pertengahan April, sebulan sebelum pengumuman resmi hasil Pemilihan Umum 2019, mingguan analisis The Economist telah menulis artikel berjudul "The Wrong Way to Win" ("Cara Salah untuk Menang"). Apakah media Inggris itu menuduh Jokowi curang? Tidak. Bagaimana mungkin bukan-kecurangan dinyatakan salah? Rupa-rupanya bukan kecurangan, melainkan kompromi atas demokrasi yang menjadi masalahnya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Dalam laporan pada edisi yang sama, "A Reformer Reduced" ("Seorang Reformis yang Menyurut"), kompromi itu terutama disoroti dari berbagai manuver, yang meski kurang demokratis, berfungsi untuk mendongkrak popularitas demi Pemilu 2019. Disebutkan bahwa dalam nasionalisasi tambang emas dan tembaga di Grasberg pada Desember, Jokowi telah menjadi seorang economic interventionist. Pengambilalihan mayoritas saham dari Freeport-McMoran dan Rio Tinto ini tentu populer di dalam negeri, tapi investor asing akan ragu menanam modal sampai sekian tahun ke depan.
Istilah dodgy tactics (taktik enggak level) disematkan atas tekanan kepada para pengecamnya, seperti tak kurang dari 20 unjuk rasa kelompok oposisi #2019GantiPresiden yang dicegah polisi; pemanfaatan taktis kebijakan Jaksa Agung; dan sikap mendua terhadap Hary Tanoesoedibjo setelah aset medianya mengalihkan keberpihakan kepada Jokowi. Bergabungnya jenderal-jenderal purnawirawan semasa Orde Baru ke lingkaran dalam disebut sebagai "menaikkan posisi".
Yang paling disorot adalah usaha merangkul golongan Islam konservatif. Ketika Jokowi langsung terbang ke Mekah untuk beribadah umrah begitu masa kampanye berakhir, itu jelas efektif untuk menghapus rumor dirinya seorang Nasrani, meski lebih baik dipercaya sebagai ibadah yang tulus.
Namun, dalam politik, pilihan kepada Ma’ruf Amin sebagai calon wakil presiden adalah bentuk kompromi. Ma’ruf Amin, menurut The Economist, beraspirasi agar syariah berlaku lebih luas, cenderung melarang kegiatan kelompok minoritas, dan bahkan kelompok Islam minoritas yang kritis terhadapnya.
Penunjukannya membuat Jokowi seperti tak tertarik membela minoritas. Apalagi Ma’ruf Amin adalah saksi ahli yang menjatuhkan Basuki Tjahaja Purnama, yang notabene merupakan pasangan politik ideal Jokowi sebelumnya.
Disebutkan bahwa Jokowi sering salah dimengerti dari luar. Di luar Indonesia, demikian dinyatakan The Economist, politikus yang memilih reformasi dan pembangunan diandaikan akan berjuang untuk nilai-nilai liberal pula. Namun Jokowi, dalam berbagai cara, adalah seorang konservatif dan sangat tidak menyukai risiko.
Dengan kecerdasan politis yang tidak diragukan dan keberuntungan yang mengorbitkannya, berarti pula kuasa dan popularitas Jokowi jarang tertantang, memungkinkan sisi ini tetap tak terperiksa. Majalah ini pun lantas mengutip pernyataan analis politik Kevin O’Rourke, "Ia (memiliki) cadangan kapital politis dan tak banyak membelanjakannya." Jokowi disebut akan menginvestasikannya kalau perlu. Namun, jika dengan memberikan secuil ruang buat para jenderal dan ulama efek keterpilihannya sama, bagi Jokowi, hal itu baik-baik saja.
Disebutkan betapa naluri Jokowi adalah sekuler. Dengan otoritasnya sebagai presiden, ia melarang satu kelompok ekstremis dan secara preventif menghalangi yang lain. Ia merupakan penggemar musik heavy metal, istrinya tidak berkerudung, dan partainya populer bagi kelompok agama minoritas. Yang terakhir ini, menurut The Economist, belum cukup untuk membuat Jokowi percaya diri sekalipun dia memimpin perolehan suara dalam setiap penjajakan awal.
Sebetulnya, para pemilih tahu benar perbedaan antara religius dan intoleransi, seperti tecermin dari perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang moderat. Namun kemoderatannya tidak akan membantu jika politikus, dimulai dengan Jokowi, tidak berminat membela tradisi panjang toleransi Indonesia.
Saya tidak menyatakan The Economist benar, tapi juga tidak menyatakannya salah. Saya mengutipnya untuk menunjukkan pandangan dari luar tentang politik di Indonesia. Hal itu selalu berguna, bukan karena lebih benar, melainkan karena mungkin memperlihatkan yang tidak dapat kita lihat, terutama dalam cara memandangnya. Dari suatu jarak, terdapat "keuntungan obyektif" tertentu. Namun jarak adalah jarak.
Penggolongan seperti liberal, moderat, ekstremis, sekuler, oposisi, dan konservatif dilakukan seolah-olah penggolongan sosial-politik di sini terpilah sekat seketat keterpilahan konsep-konsep itu. Politik di Indonesia memang bisa menjadi wacana politik menggunakan konsep-konsep global, tapi konstruksi budaya setiap golongan termaksud bukanlah praksis yang disiplin dari konsep-konsep tersebut. Bahkan, ketika Jokowi disebut sebagai politikus, benarkah Jokowi itu politikus? Di sini semua orang mengerti belaka siapa Jokowi-mengingkarinya atau tidak.