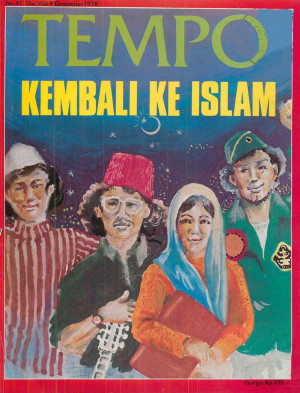7 NOPEMBER 1978, Harian Rakyat Peking memuat sepucuk surat.
Penulisnya seorang prajurit, bernama Kao Chen-tung. Isinya
mengejutkan. Surat itu mengandung tuntutan ke arah suatu sistem
politik yang lebih demokratis.
Pak Mao mungkin merasakan gempa sejenak dalam kuburnya.
"Kenapa massa rakyat tak dapat memilih para pejabat yang akan
mengatur mereka, dan akan mencerminkan kepentingan serta
tuntutan mereka?", si surat bertanya. Pagi hari itu di RRC
pertanyaan tadi seakan menodong dan harapan yang dikemukakan
seolah menggampar. Sebab Kao Chen-tung menulis: "Pemilihan akan
memberi rakyat rasa yang lebih kuat sebagai yang berdaulat."
Di RRC, di mana para pemimpin sebagian besar ditentukan dari
atas, Pak Mao mungkin merasa listrik menyelomot di musoleumnya.
Tapi di dua pojok jalan di Peking, dan mungkin di ruang-ruang
tersembunyi para inteligensia, bahkan di rapat tertutup Partai
sendiri barangkali, sejarah Cina modern sedang dicoba tulis
ulang. Atau akan diberangkatkan lagi -- dengan suasana lain.
Bayangkan. Seorang prajurit Tentara Pembebasan Rakyat menulis
surat macam itu! Mungkin ia sebuah nama palsu, tapi toh koran
resmi Partai sendiri yang memasangnya ....
Pak Mao memang sudah mati.
Tapi agaknya terlampau cepat untuk memperkirakan, bahwa
demokratisasi akan segera terorak dari sebuah sistem
kediktaturan seperti di RRC. Para pemuda, ribuan jumlahnya, yang
beberapa hari yang lalu berkumpul di lapangan Tienanmen, agaknya
tahu untuk berhati-hati. Banyak di antara mereka yang mungkin
kecewa, bahwa pemegang kekuasaan, termasuk Teng Hsiao-p'ing si
bekas musuh Mao itu, tidak mau berangkat lebih jauh.
Kediktaturan proletariat akan terus. Tapi jika para pemuda itu
membelot juga, apakah yang akan terjadi?
Sejarah RRC sendiri memberikan cukup contoh. Di musim semi 1957
Mao mengumandangkan slogan "Biarkan Seratus Bunga Merekah dan
Seratus Aliran Fikiran Berbantah!" Semboyan ini sendiri berasal
dari Tiongkok kuno, guna mengilhami perdebatan bebas agar
fikiran berkembang maju. Ketika dihidupkan kembali oleh Mao,
semangat itu pun disambut hangat oleh para cendekiawan Cina.
Suasana demokratis pun tiba-tiba hadir. Partai Komunis misalnya
dengan tandas dikecam oleh Menteri Kebudayaan Chang Hsi-jo (ia
bukan seorang komunis, tapi didudukkan di atas) sebagai sebuah
partai yang anggotanya hanya berpegang kepada dogma. Para
pejabat dilabrak sebagai congkak, munafik dan tak mengenal
"dukacita massa rakyat. "
Tiga minggu semburan semacam itu dibiarkan. Tiba-tiba, segalanya
distop. Mereka yang sudah terlanjur ngomong ditangkap. Beberapa
penulis kiri sendiri disingkirkan. Agaknya sastrawan
revolusioner Lu Hsun benar: "Sebelum kemenangan revolusi, kaum
revolusioner menyetujui para penulis berbuat itu, tapi sejak
saat revolusi berhasil, politisi mulai berbuat terhadap para
penulis dengan cara yang dipergunakan para penindas sebelumnya
dan jika para penulis itu terus saja menyuarakan ketidakpuasan,
. . . mereka pun ditindas."
Yang mengherankan, dan menakjubkan, ialah bahwa suara itu toh
terus saja. Semacam estafet. Revolusi Kebudayaan sepuluh tahun
kemudian cukup bisa menghimbau anak-anak muda bukan hanya karena
mereka diagungkan dan ditantang Mao untuk jadi pejuang. Tapi
juga karena kepada mereka disajikan apa yang disebut "demokrasi
yang diperluas." Mereka boleh memaki-maki, menangkap dan
menghukum tokoh-tokoh yang berkuasa. Meskipun korban mereka
hanya terbatas kepada para pemimpin musuh Mao dalam Partai,
"demokrasi" buat anak-anak muda selama Revolusi Kebudayaan itu
cukup membuktikan kehausan untuk ikut bersuara dari bawah adalah
kehausan yang tak habis-habisnya.
Apakah sebabnya? Adakah para pemuda terlalu banyak membawa buku
Barat, yang susah didapat? Ataukah karena mereka muda, dan hidup
dengan pengalaman tertekan yang pahit? Siapa tahu mereka tak
mengerti adakah mereka inginkan suatu demokrasi liberal. Yang
jelas: sesuatu yang tak menghimpit seperti kemarin.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini