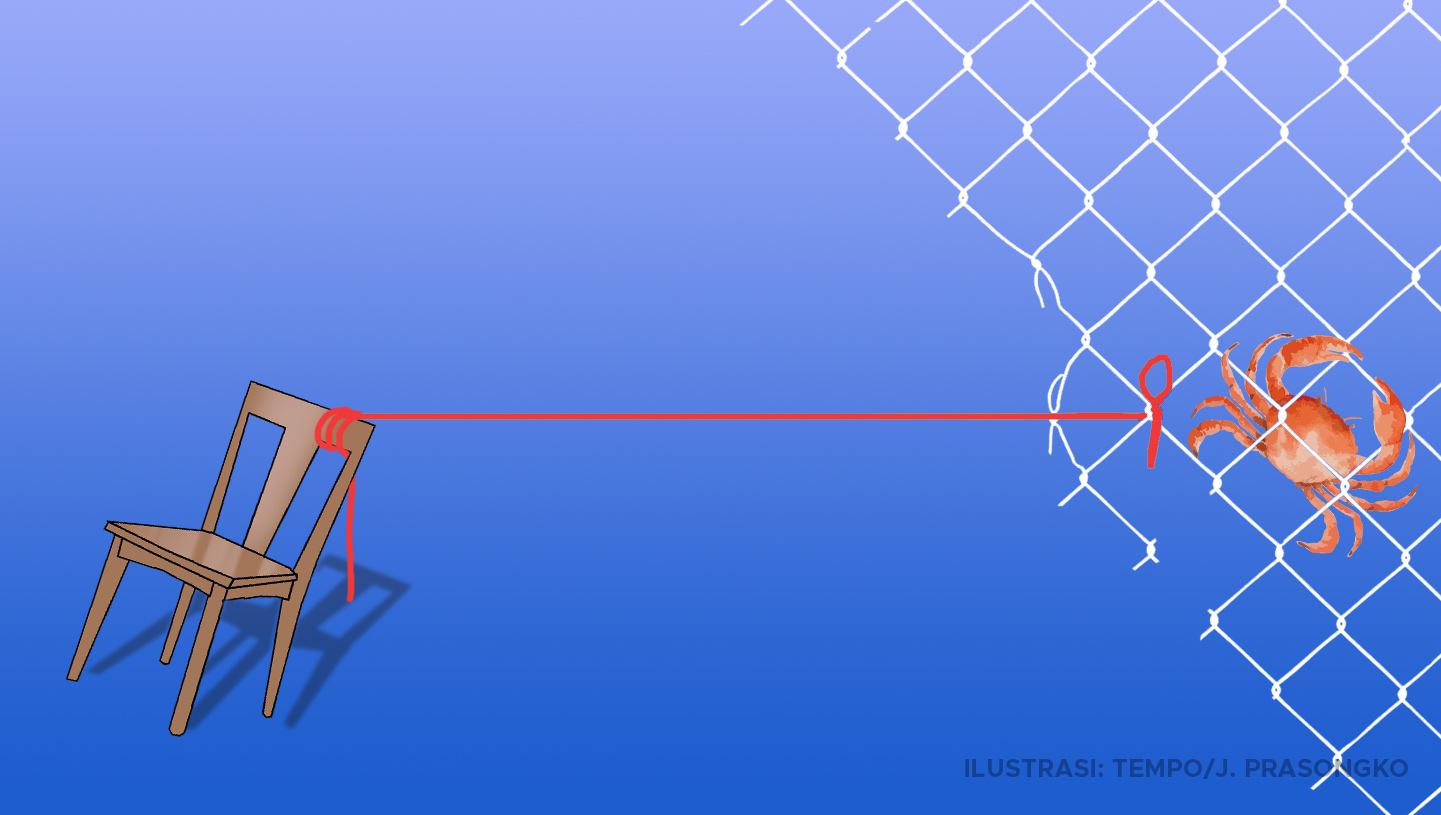Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
I. Wibowo
*) Pengajar di Departemen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI, Ketua Centre for Chinese Studies Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI
SELAMA 30 tahun terakhir, pembuat kebijakan luar negeri Cina mengikuti petuah Deng Xiaoping yang dirumuskan dalam empat kata: tao guang yan hui. Terjemahan bebasnya: jangan pamer, jangan sok. Deng agaknya sudah melihat bahwa Cina akan bangkit dan kebangkitan Cina dapat membuat tetangga-tetangganya, baik dekat maupun jauh, merasa ketakutan. Taiwan paling pertama khawatir, lalu Jepang, Korea Selatan, dan menyusul negara-negara di bagian tenggara Cina, seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Indonesia.
Kecemasan bahkan menyeberang ke Samudra Pasifik, sampai ke daratan Amerika Serikat. Di lingkungan pengambil kebijakan Amerika, muncul ”China Threat Theory”. Teori ini sangat dipercayai kalangan hawkish, tapi juga sempat menular ke masyarakat luas. Sebagai satu-satunya negara adikuasa, semestinya Amerika Serikat tak perlu risau dengan ancaman Cina.
Tidak mengherankan, pada 2002, Cina mengeluarkan pernyataan bahwa kebangkitan Cina tidak akan menimbulkan ancaman. Dua kata dipakai: heping jueqi (bangkit dengan damai). Cina benar-benar ingin menangkis pandangan bahwa kebangkitan ekonomi Cina akan menimbulkan keguncangan pada tatanan internasional. Pada 2007, dalam Kongres Partai Komunis ke-17, dikemukakan konsep hexie shejie (dunia yang harmonis). Konsep heping jueqi sendiri diperbaiki menjadi heping fazhan.
Pada saat yang sama, Sekretaris Jenderal Partai, Hu Jintao, melontarkan gagasan bahwa Cina harus mengembangkan soft power (ruan shi). Istilah ini sebenarnya dipakai Joseph Nye—profesor Kennedy School of Government, Harvard—untuk menjelaskan kondisi Amerika Serikat saat ini. Dengan soft power, sebuah negara dapat membuat negara lain tunduk kepadanya karena adanya rasa kagum dan tertarik. Amerika Serikat ”menaklukkan” dunia dengan senjatanya (hard power) dan juga dengan soft power berupa produk-produk kebudayaan yang digemari orang di seluruh dunia. Ketertundukan dan kekaguman seperti itulah yang diimpikan oleh Cina akan muncul di antara negara-negara di dunia.
Maka Cina sungguh giat mengadakan langkah-langkah mengembangkan soft power-nya. Negara ini membuat siaran radio dan televisi setara dengan BBC, CNN, dan Al-Jazeera. Saluran CCTV 4 (bahasa Mandarin) dan CCTV 9 (bahasa Inggris) kini dapat dijangkau di mana-mana. Cina bersemangat mengirim misi kebudayaan ke seluruh dunia.
Langkah paling mengesankan adalah bantuan keuangan kepada negara-negara yang sedang berkembang. Bantuan ini diberikan dalam berbagai skema—disesuaikan dengan jenis dan tingkat kebutuhan negara tersebut. Di Afrika dan beberapa negara di Asia Tenggara, bantuan diberikan dalam bentuk bangunan, seperti rumah sakit, stadion olahraga, dan bendungan. Bantuan Cina semakin menarik karena tak dikaitkan dengan syarat-syarat berat seperti yang dituntut oleh negara-negara donor dari Eropa atau Amerika.
Soft power Cina di Indonesia
Hubungan Indonesia-Cina tumbuh dan menjadi erat persis ketika Cina sedang mengembangkan soft power-nya. Pada 2004, ketika pantai barat Aceh disapu badai tsunami, Cina termasuk negara pertama yang membantu Indonesia. Begitu pula ketika daerah Bantul, Yogyakarta, diguncang gempa pada 2007. Berturut-turut pemerintah Cina memberikan bantuan kemanusiaan kepada Indonesia, yang selama lima tahun terakhir terus-menerus dilanda malapetaka alam.
Bantuan finansial paling besar yang diberikan oleh pemerintah Cina kepada pemerintah Indonesia adalah pembangunan Jembatan Suramadu. Proyek yang berjalan sejak 2003 ini mengalami beberapa kali kesulitan pembiayaan, tapi pemerintah Cina tetap memberikan dukungan penuh, sehingga jembatan itu selesai pada Juni 2009. Tidak diketahui persis berapa besar sumbangan Cina—diperkirakan di kisaran US$ 800 juta atau sekitar Rp 8 triliun. Bagi pemerintah Cina, pembangunan jembatan ini merupakan simbol eratnya hubungan kedua negara dan sekaligus bukti kepedulian Cina terhadap Indonesia.
Cina berusaha memperkenalkan diri kepada sebanyak mungkin orang Indonesia. Urusan visa ke negeri itu dibuat sederhana dan tak berbelit-belit, sehingga banyak turis Indonesia berkunjung ke sana. Khusus untuk birokrasi, pemerintah Cina menyiapkan paket khusus. Setiap tahun, lewat Konselor Ekonomi, pemerintah Cina mengundang sejumlah pejabat untuk datang berkunjung.
Acara ini biasanya kombinasi antara seminar dan sightseeing. Ini belum termasuk kunjungan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan pemimpin-pemimpin partai. Pemerintah Cina percaya pepatah lama yang mengatakan ”bai ting buru yi jian”. Artinya, seratus kali mendengar tidaklah sama dengan sekali melihat! Semakin banyak orang Indonesia melihat kemajuan Cina, semakin terasa pengaruhnya.
Respons masyarakat Indonesia terhadap soft power Cina juga positif. Secara perlahan-lahan masyarakat kita menyukai produk kebudayaan Cina. Lagu-lagu Cina kini dinyanyikan dalam pesta dan bilik-bilik karaoke. Film-film Cina sudah lama disukai, terutama sinema Hong Kong bertema silat.
Film Cina nonkungfu juga diterima baik, terutama yang memenangi piala di festival-festival internasional, antara lain Raise the Red Lantern, Farewell to My Concubine, dan To Live. Pada 1999, kota-kota besar di Indonesia pernah dilanda ”demam F4” melalui film melodrama yang menampilkan bintang-bintang dari Taiwan itu.
Masyarakat Indonesia sedang mengalami semacam ”pembebasan” dalam segala perihal yang terkait dengan kebudayaan Cina. Undang-undang dan peraturan dari masa Orde Baru yang melarang ekspresi kebudayaan Cina telah dibatalkan di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Pembatalan itu berlaku hingga kini.
Kian banyak orang dapat berbicara bahasa Mandarin dan berpakaian cheongsam dengan bebas. Pementasan tari barongsai dan naga liong kini dapat ditonton dengan bebas di tempat umum—dan bukan hanya pada tahun baru Imlek. Pembukaan restoran, peresmian toko atau mal, bahkan kampanye pemilihan kepala daerah atau pemilu diramaikan pula oleh tari barongsai dan naga liong.
Yang paling menarik perhatian adalah bahasa Mandarin. Selama tiga dekade, bahasa ini dilarang dipakai dan dipelajari. Ketika larangan dicabut, bahasa Mandarin seakan-akan meledak. Di mana-mana orang berbicara bahasa Mandarin. Tempat-tempat kursus didirikan di banyak kota besar di Indonesia. Sejumlah universitas mendirikan jurusan bahasa Mandarin. Sekolah-sekolah menengah memasukkan bahasa Mandarin ke kurikulum mereka.
Padahal, selama masa Orde Baru, bahasa Mandarin hanya dapat dipelajari di Universitas Indonesia. Itu pun dengan pengawasan. Di masa itu pula setiap penumpang pesawat terbang harus melaporkan kepada pabean sekiranya dia membawa barang bertulisan bahasa Mandarin.
Pemerintah Cina—secara kebetulan—tengah melancarkan program pengajaran bahasa Mandarin ke seluruh dunia. Di banyak negara di dunia telah didirikan ”Institut Konfusius” (Kongzi xueyuan). Kini kabarnya telah ada sekitar 250 Institut Konfusius di 75 negara. Beberapa universitas di Indonesia juga menyambut kehadiran Institut Konfusius, termasuk Universitas Al-Azhar dan Universitas Brawijaya. Pemerintah Cina pun menyediakan jalur lain agar pengajaran bahasa Mandarin makin luas dipelajari, yaitu melalui Hanban, bekerja sama dengan Departemen Pendidikan Nasional. Lewat jalur ini, sekolah-sekolah menengah mendapatkan guru-guru penutur asli.
Sejauh mana soft power Cina merebak di Indonesia? Pertanyaan ini sulit dijawab. Untuk sementara dapat dikatakan Cina dan kebudayaannya telah diterima lagi di Indonesia. Kerja sama kedua pemerintah juga berjalan tanpa hambatan. Indonesia-Cina telah bersepakat bekerja sama di bidang energi (2002), yang disusul kerja sama di bidang pertahanan (2007). Pada 2005, kedua kepala negara menandatangani deklarasi ”Kemitraan Strategis”.
Sukses Cina di Indonesia juga berulang di tempat-tempat lain di dunia. Banyak negara ingin merangkul dan dirangkul Cina. Namun, harus pula dikatakan, soft power Cina masih perlu dilengkapi promosi di bidang nilai-nilai. Pada akhirnya orang akan bertanya nilai-nilai kemanusiaan apa yang hendak ditebarkan Cina sehingga negara-negara lain kagum dan tertarik secara total.
Nilai demokrasi yang diperlihatkan Amerika Serikat terbukti menjadi daya tarik tersendiri sehingga soft power Amerika sulit dibendung. Tapi orang juga dibuat terkejut atas langkah-langkah keras Cina. Cina menggunakan kekerasan untuk memadamkan kerusuhan di Tibet (2008) dan di Xinjiang (2009). Orang seakan diingatkan pada hal-hal yang tidak bisa dikagumi di Cina. Demikian pula perlakuan pemerintah Cina terhadap Dalai Lama yang mengundang banyak kritik dan protes.
Soft power Cina sudah besar, tapi belum cukup besar. Supaya dunia yakin negara itu tak mengandalkan hard power, Cina sebaiknya tak hanya menyebarluaskan bahasa, tapi juga nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai ini sudah ada akarnya dalam kebudayaan mereka. Soft power harus dikembangkan bukan sebagai strategi diplomasi semata, melainkan juga komitmen yang otentik. Mungkin ini pekerjaan rumah penting untuk Cina 60 tahun ke depan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo