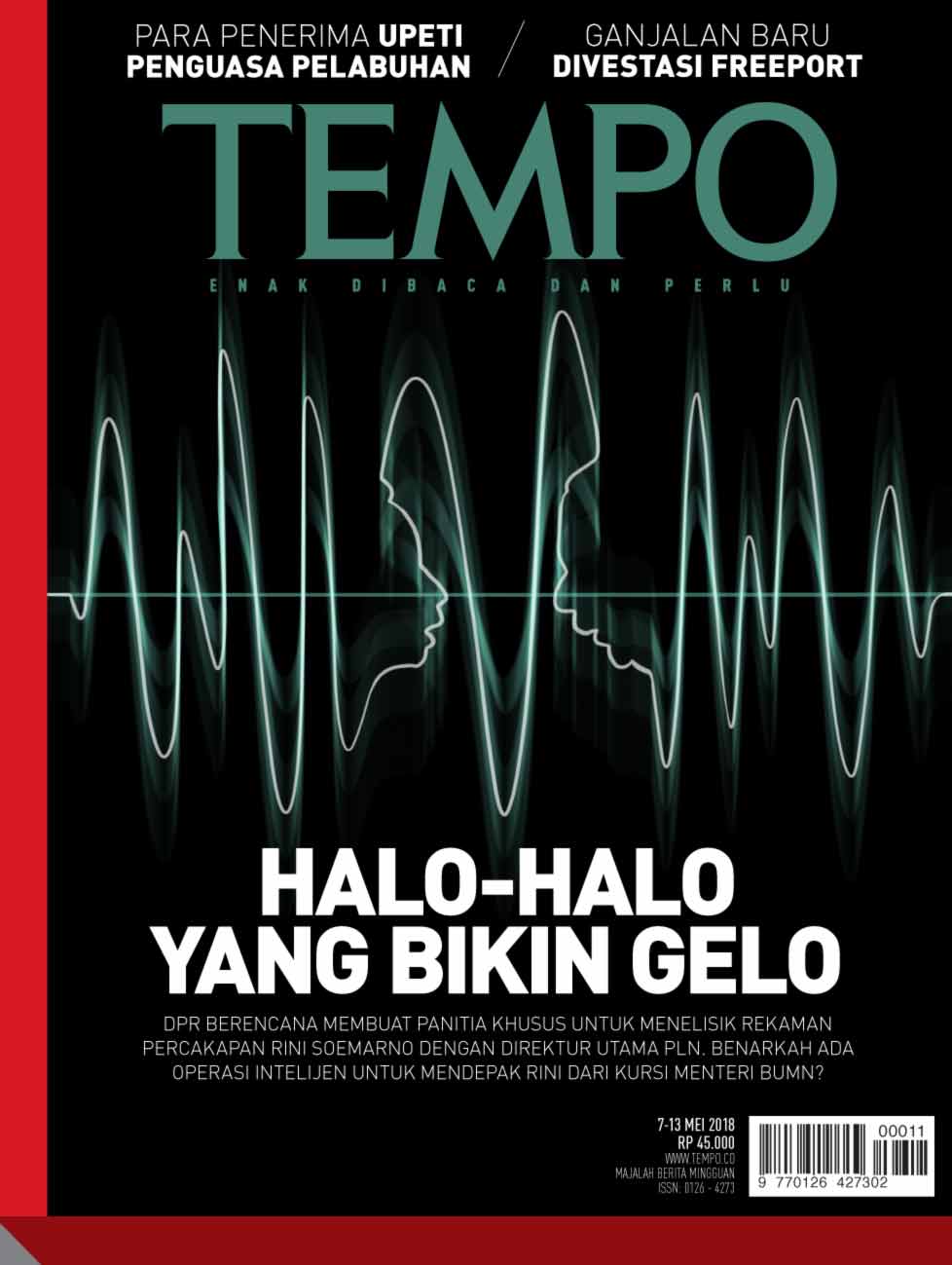Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
KITA mengenal dalang sebagai orang yang punya kemampuan retorika di atas rata-rata sekaligus piawai merangkai cerita. Masyarakat Jawa tradisional dengan enteng berujar "dhalang ora kurang lakon" ("dalang tidak kurang cerita") bagi mereka yang pandai berkelit dari kegaduhan yang sebenarnya diciptakan "dalang" sendiri. Menariknya, selain mengartikan dalang sebagai orang yang mahir memainkan dan menceritakan wayang, kamus memaknakan dalang sebagai orang yang membujuk dan menyebabkan tindakan jahat.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kamus Bausastra Jawa (Balai Bahasa Yogyakarta, 2001: 143) mengartikan dalang sebagai "wong sing njalari (ngojok-ojoki) tumindak kadurjanan (rerusuh)", orang yang menyebabkan (membujuk) tindakan kejahatan (tidak sopan secara kelakuan, perkataan, dan sebagainya). Kita melihat ada dua tegangan dalam pemaknaan menurut kamus. Pertama, dalam memainkan dan menceritakan wayang, masyarakat Jawa tradisional meyakini bahwa dalang memiliki misi ngudhal piwulang (membabar pitutur). Dalam konteks ini, dalang menjadi dhutaning Gusti (wakil Tuhan) yang memaparkan ihwal baik dan buruk kehidupan lewat cerita yang dibabar semalaman. Masyarakat meyakini bahwa dalang adalah mereka yang nampa (menerima) wahyu karena kepiawaian yang dimiliki itu. Kedua, dalang adalah juga mereka yang bertindak jahat karena mengatur perkara kejahatan. Dalam hal ini, dalang adalah orang yang tak menampakkan diri tapi licik.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Dalam realitas masyarakat Jawa, posisi dalang dalam struktur sosial sangatlah dihormati. Dalang lumrah dan sudah semestinya hidup mewah. Secara duniawi, masyarakat Jawa melihat dalang memiliki tanah yang luas, yang di atasnya dibangun rumah berikut pendapa luas. Jika bepergian, dalang naik kendaraan yang relatif tak terjangkau masyarakat kelas bawah dan menengah. Syarat itu, sebagaimana syarat kelengkapan satria Jawa yang disebut dalam Bumi Manusia (Toer, 1980: 463), adalah bagian dari lima kelengkapan yang mesti dimiliki, yaitu wisma (rumah) dan turangga (kendaraan). Kini, turangga itu mungkin kuda, chopper, atau Alphard….
Beberapa dalang kenamaan menggelar acara pada hari tertentu yang dihadiri banyak orang, biasanya pada saat weton (hari lahir dengan pasaran)-nya. Tidak jarang dalang juga membuat pelbagai kegiatan dalam rangka mengembangkan kesenian. Bukan rahasia pula jika dalang memiliki "kelaziman" beristri lebih dari satu. "Wis samesthine, wong ya dhalang (sudah semestinya, wong dia dalang)." Begitu masyarakat Jawa tradisional acap memaklumi sikap hidup seorang dalang.
Terhadap hal tersebut, Jazuli dalam buku Dalang, Negara, Masyarakat (2003: 241) memberikan sindiran. Ia menulis, "Dhalang tenar tansah digatekake pasar, sanajan ora duwe dhuwit dolar, nanging uripe tansah gumebyar-gebyar (dalang terkenal selalu diperhatikan pasar; meski tak punya uang dolar, hidupnya selalu gebyar)." Meski tak laris benar, dalang perlu berhias dengan citra. Dalang lantas menjadi representasi salah satu komponen masyarakat priayi Jawa. Ia ditabalkan secara kolektif oleh masyarakat sebagai orang yang linuwih (punya kelebihan), baik secara kemampuan mendalang maupun kapital ekonomi.
Majalah berbahasa Jawa Waspada edisi 20 Maret 1964 menulis perdebatan kubu Humanisme Universal versus Lekra yang santer ketika itu. Di halaman 15-16 ditulis "Humanisme Padhakaro Angen-angene Djaka Nganggur". Artinya, Humanisme (Universal) sama halnya dengan angan-angan jejaka yang menganggur. Kubu seniman bercap rakyat menuduh pihak seberang menodai revolusi. Petikan ejekan itu antara lain berbunyi "Manifes Kebudajaan Merevisi Pantjasila" dan "KK-PSI Didalangi Orang-orang Manipolis Munafik".
Politik butuh dalang. Dalang politik lebih sering mengatur keriuhan dari balik kelir sehingga sengaja tak menampakkan diri. Riuh politik di permukaan sejatinya sekadar dimainkan wayang-wayang yang menjaga muruah cerita yang dirancang dalang. Semiotika citra menjadi bagian tak terpisahkan dari kontestasi politik. Upaya menjaga citra politik tiada lain adalah upaya wayang untuk menjaga cerita sekaligus citra dalang.
Tak ayal jika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia versi dalam jaringan kita menemukan makna dalang sebagai "orang yang mengatur (merencanakan, memimpin) suatu gerakan dengan sembunyi-sembunyi". Namun, melihat realitas faktual kontestasi politik kita belakangan ini, naga-naganya makna mendalang bakal bergeser lagi menjadi "mimpin tumindak kadurjanan (gawe rusuh, gawe kisruh)"-memimpin tindakan kejahatan (membuat gaduh, membuat kacau)-sebagaimana diartikan Bausastra Jawa. l
Dhoni Zustiyantoro
Dosen Sastra Jawa Universitas Negeri Semarang
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo