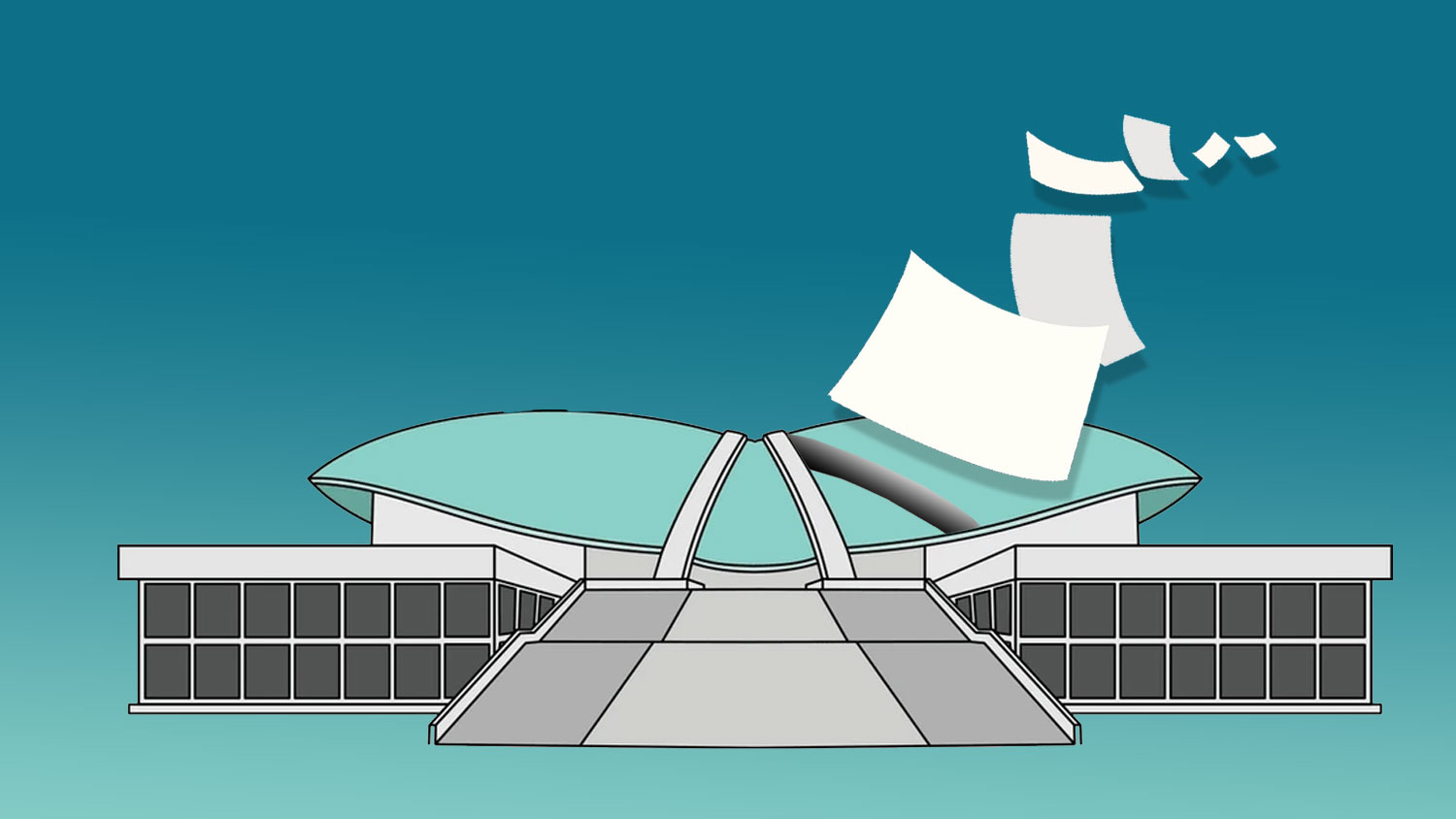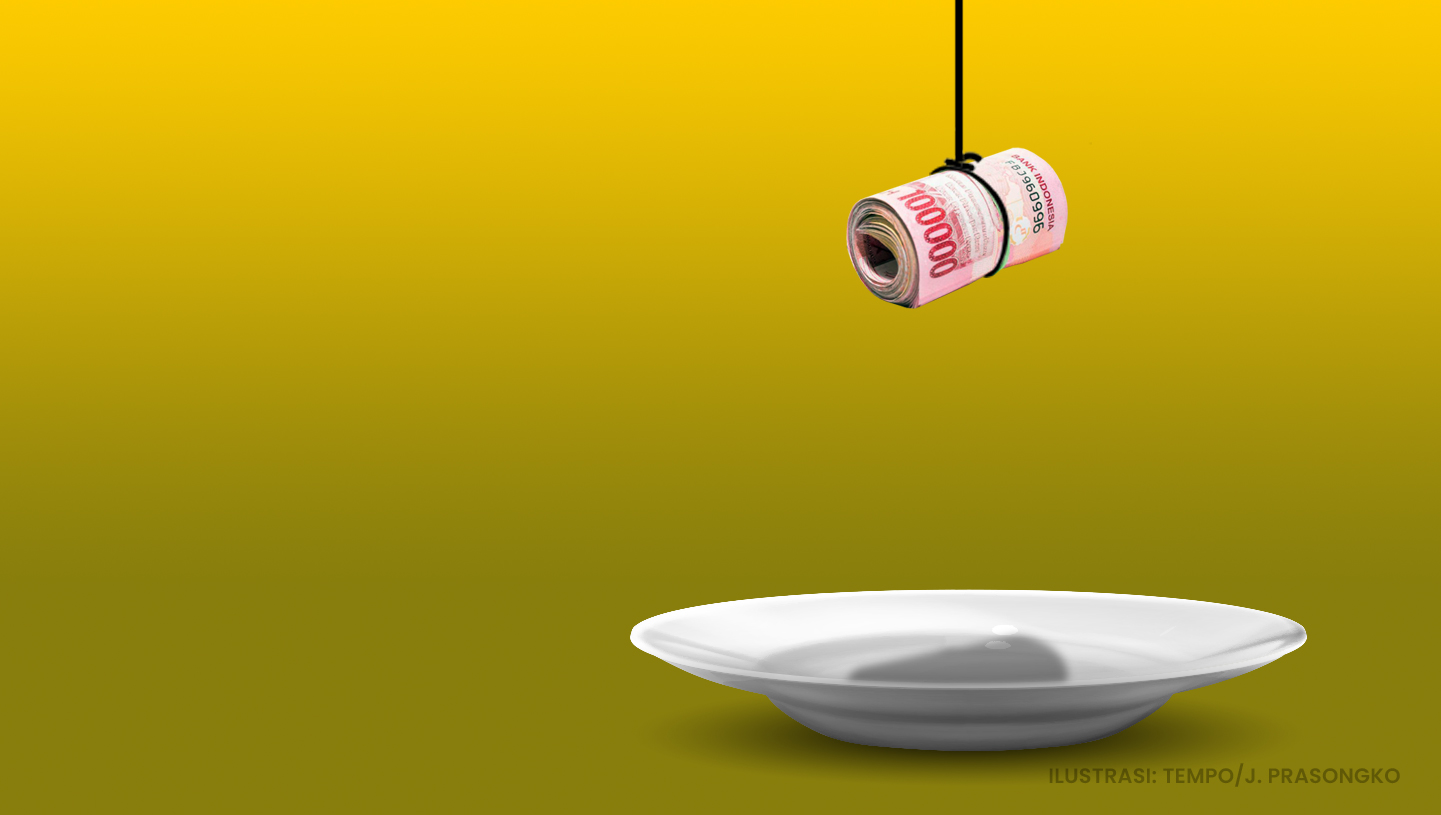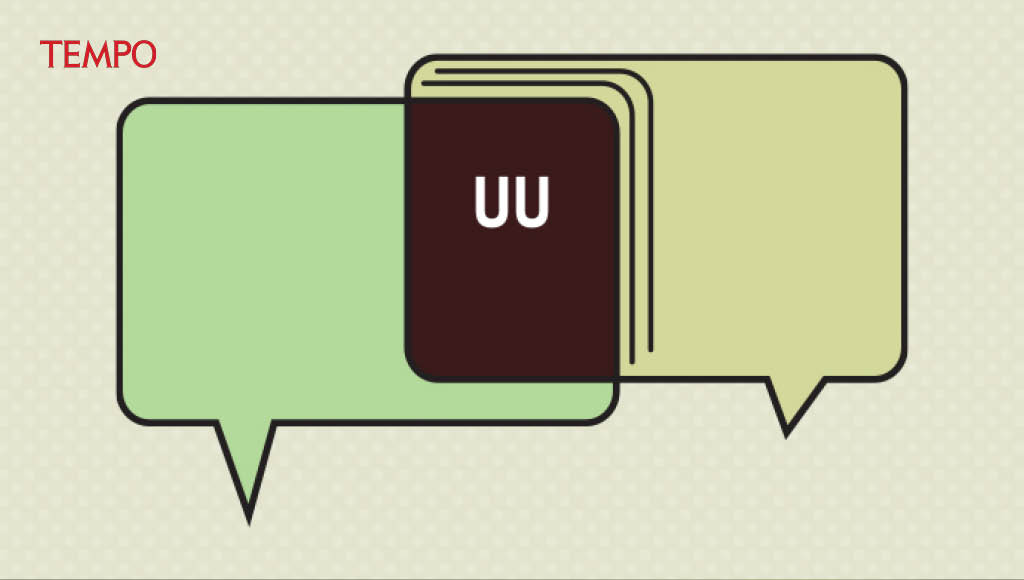Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
KEPUTUSAN Kementerian Komunikasi dan Informatika tentang multipleksing televisi digital membuat kita melewatkan kesempatan besar dalam proses digitalisasi siaran televisi: demokratisasi penyiaran. Digitalisasi penyiaran di Indonesia dipastikan gagal membuat penguasaan frekuensi publik berpindah dari segelintir pengusaha yang mendapat hak istimewa sejak masa Orde Baru.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dua pekan lalu, pemerintah menetapkan multipleksing televisi digital di 43 wilayah layanan di seluruh Indonesia. Pemenangnya adalah Emtek Group (induk usaha SCTV dan Indosiar), Metro TV Group, RCTI-MNC, Viva (pemilik ANTV dan TVOne), serta Trans TV. Kelima perusahaan itu adalah bagian dari konglomerasi lama yang selama ini menjadi raja-raja industri televisi analog. Hanya ada satu pemain relatif anyar dalam keputusan itu, yakni Nusantara TV. Dengan kata lain: pemerintah melanggengkan oligopoli industri penyiaran di negeri ini.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Kita tahu Indonesia sudah tertinggal jauh dalam soal digitalisasi siaran televisi. Padahal pemutakhiran televisi analog ke digital merupakan keputusan International Telecommunication Union sejak 2006. Banyak negara lain telah menghentikan siaran analog—dikenal dengan analog switch off atau ASO—sejak lima tahun lalu. Dengan demikian, frekuensi 700 megahertz yang sebelumnya dipakai industri penyiaran bisa dimanfaatkan untuk kepentingan publik yang lebih urgen, misalnya komunikasi bencana dan Internet nirkabel.
Indonesia, yang memulai proses peralihan pada 2012, jalan di tempat akibat tersandera kepentingan pemain lama. Frekuensi publik di 700 MHz digunakan oleh 14 stasiun televisi nasional yang setiap tahun menangguk lebih dari Rp 140 triliun pendapatan iklan atau 85 persen dari total belanja pariwara nasional. Penting dicatat bahwa mayoritas pendapatan itu hanya dinikmati oleh segelintir pengusaha kakap, tidak terbagi merata ke semua pelaku penyiaran di pelosok negeri.
Kritik atas model kepemilikan stasiun televisi di Indonesia yang oligopolistik sudah banyak disuarakan masyarakat sipil dan akademikus. Bukan hanya soal pembagian kue ekonomi yang tak fair, penguasaan frekuensi publik yang sentralistik juga membuat keberagaman informasi terancam. Suara minoritas dari kelompok-kelompok yang terpinggirkan menjadi sulit mendapat tempat.
Kementerian Komunikasi dan Informatika seharusnya menggunakan momentum digitalisasi untuk menata kembali industri penyiaran Indonesia. Salah satunya dengan memisahkan penyedia infrastruktur multipleksing dari perusahaan penyedia konten siaran. Perusahaan telekomunikasi bisa diundang menjadi pemilik multiplekser sehingga semua stasiun televisi bisa bersaing dengan setara.
Sayangnya, pemerintah melewatkan kesempatan berharga ini. Dengan memberikan izin penyediaan multipleksing teve digital kepada semua konglomerat stasiun televisi, tidak bakal ada yang berubah dalam sistem penyiaran nasional kita. Para pemilik stasiun teve yang selama ini kerap dikritik karena memanfaatkan frekuensi publik untuk mempromosikan kepentingan politik ataupun bisnis pribadinya bisa terus melenggang melakukan hal serupa. Mereka bahkan bisa mengontrol isi siaran stasiun teve lain yang menyewa saluran digital mereka.
Pemerintah memang bisa berdalih sistem multipleksing jamak yang kini diterapkan justru mendorong kompetisi bisnis yang sehat. Soalnya, tak ada pemain lama yang mendapat konsesi jauh lebih besar dari pesaingnya. Namun kompromi model itu justru menegaskan kembali kepada publik: betapa berkuasanya para konglomerat pemilik stasiun televisi di negeri ini.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo