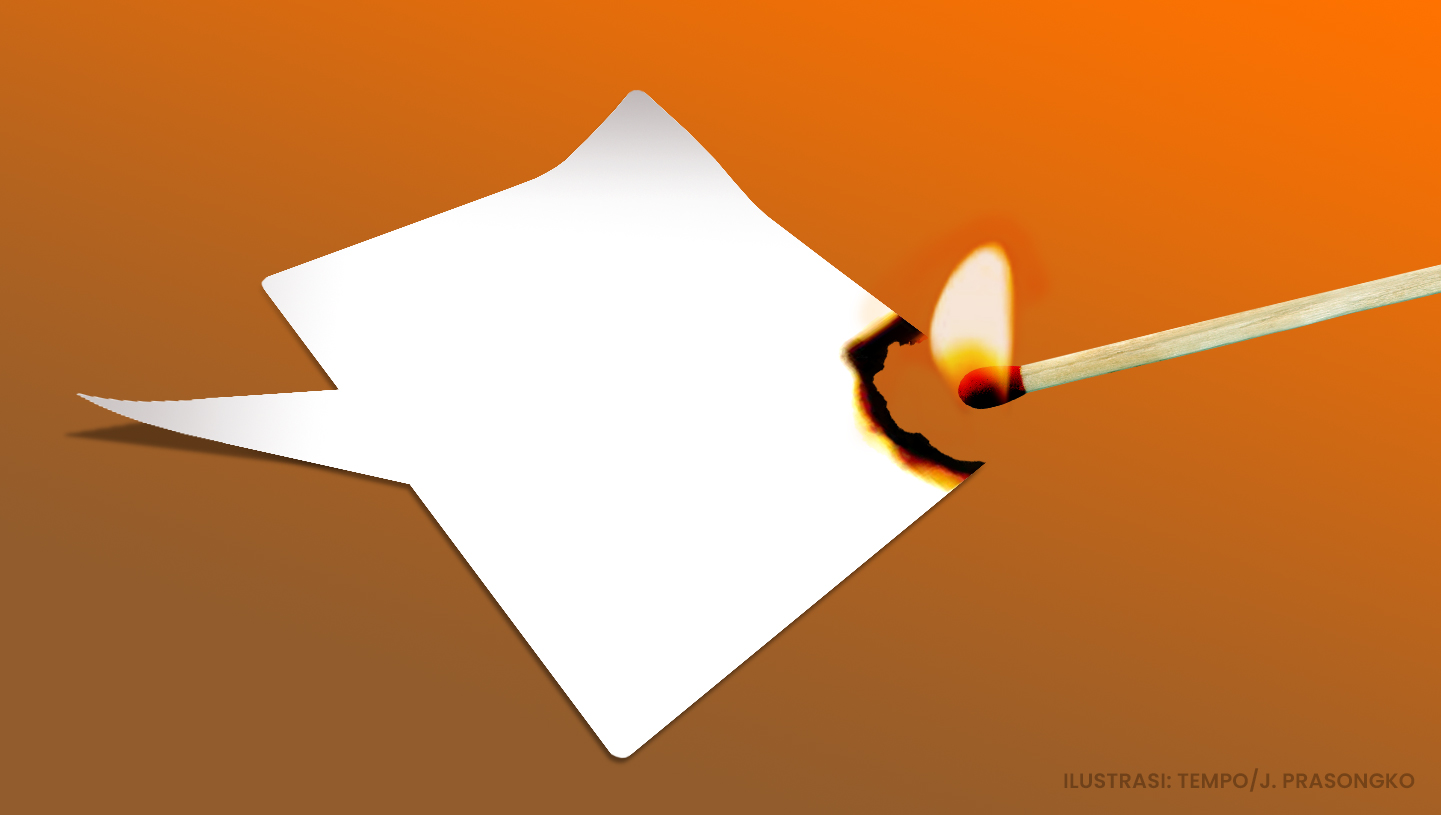KEBIJAKAN otonomi pemerintah kolonial Hindia Belanda didorong oleh dua motif. Pertama, daerah sudah menjadi lebih kompleks daripada di masa lalu. Sistem pemerintahan sentralistis sudah tak mampu lagi memerintah. Beban pemerintah pusat harus dipikul sebagian oleh pemerintah daerah. Motif kedua, sejalan dengan politik etis yang mulai muncul pada awal abad ke-20, penduduk lokal harus diberi kesempatan turut serta dalam mengelola struktur kepentingannya yang sudah makin kompleks.
Omong Kosong Federalisme
Menurut A.A. Schiller, penulis The Formation of Federal Indonesia, 1945-1949 (Den Haag, 1955), "?Hindia Belanda perlahan tapi pasti berubah menjadi suatu negara federal di bawah kebijakan Belanda yang berlaku di sepanjang abad XX." Pendapat semacam ini, yang tampak menggambarkan jernihnya pandangan jauh ke depan pemerintah kolonial, adalah omong kosong belaka.
Memang benar, pada 1903 pernah diupayakan semacam desentralisasi dengan cara menciptakan dewan-dewan lokal yang diberi tugas pemerintahan. Eksperimen ini gagal, baik dari segi isi maupun penyebaran geografisnya. Dewan-dewan dibentuk di daerah keresidenan, atau bagian-bagian dari keresidenan, dan pada tingkat kabupaten di Jawa. Kecuali pada dewan-dewan yang dibentuk di kabupaten khusus untuk mengurusi kepentingan penduduk Belanda di perkotaan, yang disebut desentralisasi tak lebih dari desentralisasi administratif.
Dewan-dewan setempat dianggap sebagai sekadar pembantu tugas pemerintah pusat. Anggota dewan pada mulanya diangkat dari kalangan pegawai pemerintah, baik yang berkebangsaan Eropa maupun pribumi. Kekuasaan tetap di tangan para ketua dewan tersebut, yang semuanya pejabat pemerintah pusat. Yang disebut desentralisasi pada dasarnya lebih mementingkan efisiensi ketimbang otonomi.
Begitu pula, ketika mengembangkan usul agar Indonesia berbentuk federasi setelah mencapai kemerdekaan, pihak Belanda sama sekali tidak menyentuh apa yang sudah ada pada masa jajahannya. Federasi usulan Belanda adalah usulan yang baru guna memecahkan masalah yang belum muncul di zaman kolonial. Pihak Indonesia curiga bahwa usul ini bertujuan memecah belah persatuan para pejuang kemerdekaan. Apalagi setelah Belanda secara sepihak membentuk negara-negara bagian Pasundan, Indonesia Timur, Sumatra Timur, Banjar, Kalimantan Barat, dan seterusnya.
Warisan Belanda
Legge mengakui, memang ada kebutuhan untuk memenuhi tuntutan identitas lokal, apakah bersumber pada identitas etnis, ekonomis, ataupun identitas yang tercipta semata-mata karena jarak yang jauh dari Jakarta. Ada pula kebutuhan akan pemerintahan secara umum, tidak hanya untuk memenuhi tuntutan elite lokal yang sadar-politik dan ingin kewenangan lebih besar, tapi juga mencapai rakyat jelata yang belum sadar-politik dan jumlahnya lebih banyak.
Yang mengherankan, untuk dua kebutuhan yang berbeda itu, akhirnya disediakan satu pemecahan. Undang-undang pokok yang diberlakukan mempunyai persamaan dengan peraturan yang digantinya, termasuk struktur hierarki otoritas lokal dalam tiga tingkat. Pada tingkat pertama ada provinsi, yang kemudian diberi nama daerah tingkat satu (dati I). Di wilayah provinsi masih ada daerah-daerah lebih kecil, yang disebut dati II.
Di bawahnya ada lagi lapisan ketiga dengan wilayah-wilayah yang lebih kecil. Dati I diharapkan memenuhi kebutuhan akan identitas suatu daerah tertentu. Tingkat yang lebih rendah dimaksudkan untuk membangkitkan inisiatif lokal, sekaligus mengambil alih beban administrasi pemerintah pusat. Ini persis konseptualisasi permasalahan yang dirumuskan pemerintah kolonial.
Menurut Legge, pengaturan otonomi daerah dari 1950 hingga 1956 agak berbau kolonial, dan ini sangat beralasan. Walaupun Indonesia sudah menjadi negara yang merdeka dan berdaulat, masalah pemerintahannya sama saja dengan masalah yang dihadapi para penjajah.
Legge mengkaji sistem pemerintahan lokal, kepala daerah dan masalah pengawasan, dewan-dewan perwakilan dan partai politik, dan keuangan?singkatnya, semua masalah yang hingga kini pun belum terpecahkan. Yang paling menarik adalah kajiannya tentang hakikat masalah "kedaerahan", yang merupakan saka guru pembentukan konsep desentralisasi pemerintah kolonial maupun Republik Indonesia.
Asumsi dasar persiapan otonomi adalah bahwa masalah daerah hanya dapat dipecahkan dengan memberikan kewenangan sebesar-besarnya kepada daerah. Itu juga yang dijadikan asumsi Belanda ketika memaksakan federasi pada Indonesia yang baru merdeka. Asumsi ini tidak sepenuhnya salah. Tapi apakah obat yang secara aksiomatis diberikan tepat?
Legge juga menganalisis gejala "daerah-isme" sebagai suatu gumpalan emosi dan rasio yang sedikitnya terdiri atas tiga unsur. Pertama, kebutuhan memproyeksikan identitas etnis?unsur ini tidaklah sepenting yang lain. Kedua, kecemasan akan "imperialisme Jawa". Penelitian di beberapa daerah menunjukkan adanya keluhan bahwa sejumlah cabang pemerintah pusat didominasi oleh pejabat Jawa. Namun, perlu dikemukakan, semua posisi pemerintahan daerah diduduki oleh putra daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dugaan dominasi Jawa itu tidak berdasar.
Unsur ketiga bersifat lebih rasional. Beberapa daerah pengekspor seperti Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi (sekarang juga Irian) memberikan sumbangan kepada ekonomi Indonesia yang tidak seimbang dengan manfaat yang diperolehnya. Unsur inilah yang mempunyai dasar yang kukuh. Dan ketimpangan ini memang perlu dikoreksi.
Tapi apakah koreksi atas apa yang dirasakan sebagai ketidakadilan pembagian rezeki, yang notabene hanya dialami 3-4 daerah, perlu ditanggapi dengan pemberian otonomi besar-besaran kepada semua daerah di Indonesia? Tidakkah jalan keluar dari masalah kecil secara berlebihan justru akan menimbulkan masalah yang jauh lebih besar?
Menurut Legge, sebagian besar dari apa yang disebut "kedaerahan" atau "daerahisme" bersumber pada oposisi terhadap kebijakan pemerintah pusat, dan bukan pada ketimpangan distribusi fungsi-fungsi antara pusat dan daerah. Contohnya adalah kasus memuncaknya ketidakpuasan daerah terhadap pusat di Sumatra Barat dan Sulawesi Utara. Dua daerah ini tidak semata-mata ingin lebih bebas dari cengkeraman pusat. Mereka juga tidak menyumbang lebih banyak pada ekonomi Indonesia daripada yang diterimanya.
Fenomena Sumatra Barat dan Sulawesi Utara sulit dimasukkan ke dalam tiga unsur "daerahisme" yang dikaji Legge. Ia lebih terpengaruh oleh politik oposisi kepartaian. "Coup" militer di Sumatra Tengah, menurut Legge, merupakan gerak taktis guna menjatuhkan kabinet Ali Sastroamidjojo. "Coup" di Sumatra Barat cepat disusul oleh penarikan lima menteri Masyumi dari kabinet. Desentralisasi macam apa pun tak akan mampu mengatasi problem seperti ini.
Otonomi Batal
Kolonel Zulkifli Lubis gagal melancarkan kudeta di Jakarta pada 16 November 1956. Sebulan kemudian, 20 Desember 1956, Letnan Kolonel Achmad Husein merebut kekuasaan di Provinsi Sumatra Tengah. Saat itu muncul apa yang disebut "Konsepsi Presiden" dalam bentuk "meja berkaki empat", yaitu pemerintahan yang dipimpin oleh Sukarno sendiri dan didukung oleh tiga partai terbesar hasil Pemilihan Umum 1955 serta satu golongan perwakilan kekaryaan.
Usul ini disambut dengan serangkaian kudeta di berbagai daerah. Pada 2 Maret 1957, Letnan Kolonel Sumual, Panglima Daerah Militer Indonesia Timur (Sulawesi, Maluku, dan Nusatenggara) merebut kekuasaan dari pemerintahan sipil. Beberapa hari kemudian menyusul peristiwa serupa di Sumatra Selatan dan Kalimantan. Kabinet Ali Sastroamidjojo jatuh.
Sukarno memproklamasikan keadaan perang. Kampanye merebut Irian memanas. Posisi parlemen melemah dan kekuatan militer meningkat di balik perisai suatu staat van oorlog en beleg (SOB?keadaan perang). Saat itu pemberian hak otonomi kepada daerah sudah hampir sempurna.
Pada Januari 1957, Undang-Undang Nomor 1/1957 mulai berlaku, menggantikan UU No. 22/1948. Meski sama-sama mewarisi sistem hierarki pemerintahan daerah dari masa penjajahan, perubahan terpenting dalam undang-undang baru adalah diperlemahnya kewenangan kepala daerah. Seluruh sistem pengawasan yang tercantum dalam UU No. 22 pun dirombak. Inilah yang diinginkan oleh partai politik, dan ini pula kemenangan besar partai atas birokrasi, suatu hal yang jarang terjadi di Indonesia. Akibatnya, kemandirian daerah menguat. Sayang, situasi dan kondisi rupanya tak membiarkan eksperimen demokrasi ini berlangsung.
Belanda terus menolak berunding mengenai penyerahan kedaulatan atas Irian. Amerika Serikat dan Australia membantu Belanda dengan gigih dan antusias. Suhu politik memanas dalam kampanye "rebut Irian" yang bergelombang. Politik mengarah ke jurusan radikal.
PKI, yang sudah menang besar pada Pemilu 1955, makin jumawa. PNI ikut saja apa yang diperintahkan Sukarno. Nahdlatul Ulama saat itu dikenal sebagai partai yang ikut pada siapa saja yang tampaknya akan menang. Masyumi disibukkan oleh sayap Natsir, yang menonjolkan kekakuan prinsip-prinsip perjuangan yang sewajarnya diperjuangkan suatu LSM, bukan sebuah partai politik. Mungkin ini yang dimaksud Legge sebagai melemahnya peran parlemen.
Sukarno bersikeras mengikutkan PKI sebagai salah satu partai terbesar. Sukarno didukung PNI, NU, TNI, dan sudah tentu PKI, yang sedang menuju posisi partai komunis terbesar di dunia di luar blok sosialis. Masyumi terus bersikeras menentang masuknya PKI dalam pemerintahan. Tiada satu pun kekuatan politik yang mendukung Masyumi.
Pada September 1957 diadakan Musyawarah Nasional yang dihadiri sekitar 200 pemimpin sipil dan militer. Mereka berupaya mencari jalan keluar dari krisis nasional yang diakibatkan oleh pergolakan di daerah. Indonesia berupaya keras menghindari perpecahan yang kian lama kian keras menggedor pintu.
Lima bulan kemudian, proklamasi berdirinya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) berkumandang dari Sumatra, yang dijawab dengan pernyataan keadaan perang. Sukarno melepaskan serigalanya: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Legge mengutip keluhan seorang gadis Minang di Jakarta: "Mereka mengebom negeri saya." Pernyataan keadaan perang itu menandai tibanya periode diktator di Indonesia, yang berlangsung 40 tahun lebih.
Dan diktator tak suka hidup berdampingan secara damai dengan desentralisasi dan otonomi. Ia membungkam partai politik dan demokrasi parlementer.
J.D. Legge, Central Authority and Regional Autonomy in Indonesia: a Study in Local Administration 1950-1960, Cornell University Press, Ithaca, New York, 1961
Nono Anwar Makarim
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini