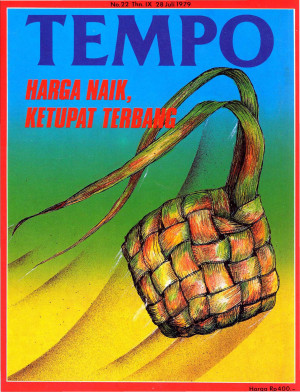MOBIL itu mengaum, menikmati aspal. Jarum di bawah kemudi
bergerak 80 km. 100 km. Lalu 120 km. Kecepatan kian meninggi.
Tapi tak terasa. Dan jalan itu terus saja meliuk, mulus,
ramping, rapih, panjang -- seperti tak habis-habisnya memuaskan.
"Ini seperti di Amerika, bah!" seru Ronggur.
Ia sudah dari tadi terkesima di belakang stir. Tiga hari yang
lalu ia baru datang dari pedalaman Irian yang masih gelap,
setelah 5 tahun berada di sana. Kini, di Jakarta, ia menempuh
Jagorawi -- jalan besar yang menghubungkan dengan megahnya
Jakarta-Bogor-Ciawi. Apa yang dilihatnya, apa yang dialaminya,
belum pernah terjadi pada dirinya seumur hidup.
"Bayangkan?" katanya lagi, "lima tahun yang lalu jalan ini belum
ada. Sekarang seperti di Amerika, bah!"
Di sebelahnya Hambali tersenyum. Ia memaklumi perasaan Ronggur.
Baginya sendiri, biar pun ia penduduk Jakarta dan sudah tiga
kali menempuh high way ini, Jagorawi tetap merupakan suatu
sensasi. "Kita memang tak serasa berada di pulau Jawa yang sesak
dan ruwet," katanya mengiyakan, dengan kalimat lebih panjang.
Di luar, memang tidak ada seorang manusia pun nampak melintas.
Yang ada adalah suatu bentangan kesunyian yang hampir-hampir
lengkap -- kesunyian dalam arti khusus sebuah suasana yang diisi
hanya oleh gerak mobil-mobil, benda-benda yang tak saling
menyapa, yang saling mengambil jarak, sementara seakan-akan
mereka hidup untuk berkejaran sengit di bawah matahari sore.
"Kau tahu apa artinya ini, Hambali?" tanya Ronggur, masih
bersemangat. "Ini namanya kemajuan!" Dan di kejauhan, agak
tersembunyi oleh jarak dan bukit-bukit, nampak bangunan yang
mengkilap dengan menara logam mencuat -- seolah istana dalam
dongeng peri atau dalam science fiction. Itulah pabrik semen
Cibinong.
"Bukan cuma kau yang terpesona," Hambali menyahut.
"Ya, aku lihat orang-orang itu juga terpesona," ujar Ronggur
seraya menunjuk ke luar.
Di tepi jalan, agak di sebelah atas, di mana kampung-kampung
setengah tersembunyi di antara warna hijau pohonan, nampak orang
duduk-duduk. Mereka seperti menghabiskan waktu sorenya, setelah
mandi sepulang kerja: menonton tamasya Jagorawi dan puluhan
mobil yang berlari.
"Tapi mungkin mereka bukan terpesona," tiba-tiba Hambali seperti
menemukan sesuatu. "Mungkin mereka termangu-mangu kini mereka
tak bisa lagi bebas berjalan dari sebelah sini ke seberang
sana."
"Yah, bisa ketabrak, dong."
"Dulu mereka tak usah takut ketabrak. Bagian kiri jalan dengan
bagian kanan mungkin dulu satu desa. Kini terbelah. Seorang
pemuda dari kampung sml yang punya pacar di sebelah sana mungkin
jadi sukar ketemu. Aneh, 'kan? Jalan ini memperlancar hubungan
dua kota, tapi memisah sebuah wilayah dan mungkin sepasang calon
suami isteri."
"Alah. Dalam soal begitu memang selalu ada yang jadi korban.
Merdeka pun perlu pakai perang."
"Untung juga bukan kita yang jadi korban. Kita yang menikmati."
"Suaramu seperti suara orang merasa bersalah."
"Barangkali karena aku tak merasa punya jerih-payah dalam
membangun jalan ini -- cuma tinggal memetik buahnya doang."
"Memangnya bagaimana, sih, bisa membikin kau merasa ikut punya
jerih-payah? Orang 'kan kerja masing-masing."
Ronggur lalu mengendurkan kaki kanannya sedikit dari pedal gas,
dan jip itu pun meredakan derunya. Sebuah sedan melintas.
Melihat warna birunya yang bagus, ia berfikir: barangkali ada
seorang gadis cantik di dalamnya. Tapi anak muda itu tak sempat
menangkap sosok yang jelas. Mungkin saja itu mobil seorang
sahabatnya, atau mobil bajingan yang menyamar. Siapa tahu?
Di Jagorawi, ia pun mulai berfikir, ada yang mengagumkan, ada
yang jadi korban, ada yang menikmati, dan ada yang merasa
bersalah. Masing-masing tak saling menyapa.
Masing-masing seakan melambangkan "pembangunan" yang bergerak
tapi terasa sepi. Sendiri-sendiri.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini