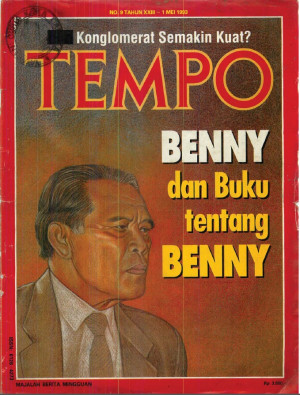Seorang sahabat mengunjungi saya setelah ia membaca ''Pembaruan dalam Islam'' (TEMPO, 3 April 1993, Laporan Utama). Sesudah memberikan salam, ia bertanya, apakah saya telah membaca Laporan Utama tersebut. Saya mengangguk. Lantas ia langsung menarik napas berat sambil berkata, ''Sayang sekali, banyak di antara kita yang belum bisa memahami fenomena-fenomena gerakan keagamaan secara cukup adil, bahkan terkadang disimplifikasi''. Maksudnya, kita sering memilihkan kata-kata yang cenderung diberi tendensi negatif oleh awam, seperti militan, fundamentalis, dan eksklusivisme, untuk menyifati gerakan- gerakan tersebut. Padahal, makna kata-kata itu cukup terikat dengan waktu, tempat, dan sejarah tertentu. Sahabat saya ini, sejauh yang saya tahu, memang punya perhatian cukup besar pada persoalan-persoalan agama, mulai dari yang paling sakral hingga yang paling profan. Tapi, dalam perhatiannya itu, muncul kesadaran bahwa pendengar-pendengarnya bersifat sangat pribadi dan ilmunya tentang agama masih sangat kurang. Ketika berbicara tentang sebab munculnya harakah pun, katanya, kita cenderung menyimplifikasi motif-motifnya. Kita terjebak pada materialisme yang menyatakan bahwa satu-satunya hal yang berperan dalam diri manusia hanyalah hukum-hukum fisik dan biologis. Karena itu, kita pun menyatakan bahwa umumnya mereka yang ekonominya terjamin dan merasa aman tak mudah ditarik menjadi militan. Saya tahu bahwa kalimat itu dikutipnya dari salah satu bagian terakhir di Laporan Utama tersebut. Ini akan punya implikasi cukup luas, katanya. Kasarnya, kita menganggap bahwa bila perut telah terisi sebaik-baiknya, orang pun akan diam dan tidak lagi mencari sesuatu yang harus diperjuangkan, bahkan dengan nyawa sekalipun. Tapi coba lihat negara-negara yang punya statistik ekonomi sangat baik: ternyata perilaku masyarakatnya menunjukkan ''statistik spiritual'' yang sangat rendah dan tidak bisa ditiru. Lihat pula, betapa banyak pemilih harakah di sini berasal dari kalangan yang tidak cukup puas dengan kestabilan ekonomi dan ''kehangatan'' keluarga yang sesungguhnya bisa dinikmatinya. Di sini, pemilih harakah bukanlah orang yang ragu besok makan apa, bukan pula orang yang tidak pernah kenal deposito. Bahkan, sebagian besar dari mereka berada pada tataran intelektual yang cukup elite. Tapi, tak bisa juga dimungkiri, kata saya pula, bahwa di sebagian negara di dunia, seperti di Afrika, gerakan-gerakan Islam dimotivasi oleh tekanan-tekanan ekonomi yang terlalu berat. Jadi, katanya, sebuah perilaku, apalagi perilaku beragama, bukanlah sebuah reaksi kimia yang reversibel begitu saja. Ekonomi bisa menjadi salah satu motif perilaku. Namun, kita tidak mengatakan bahwa untuk ''mengantisipasi'' perilaku tersebut, ekonomi merupakan ''segala-galanya'' yang perlu diperhatikan. Sebab, harakah, sebagai suatu perilaku keagamaan, sesungguhnya tak bisa dipahami dengan menganggapnya sebagai sesuatu yang hanya disebabkan oleh semacam frustrasi sosial. Ini pandangan marxisme. Yakinlah, kata teman saya itu, pandangan seperti ini sangat sempit, bahkan mungkin akan membuat kita semakin 'tidak mengerti' tentang fenomena beragama yang terjadi. Saya hanya menjadi pendengar pasif. Meskipun monolognya belum menyinggung persepsi-persepsi esoterik, saya menjadi semakin paham mengapa sahabat saya itu bisa akrab berpelukan dengan rekan-rekan lain yang bergamis dan berjanggut ketika bertemu, dapat bertukar pikiran dengan hangat dan bercanda seperti rekan-rekan yang ber-Levi's belel, dan sesekali masuk bioskop. NASH AZFA MANIK Mahasiswa Fapsi Unpad Bandung
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini