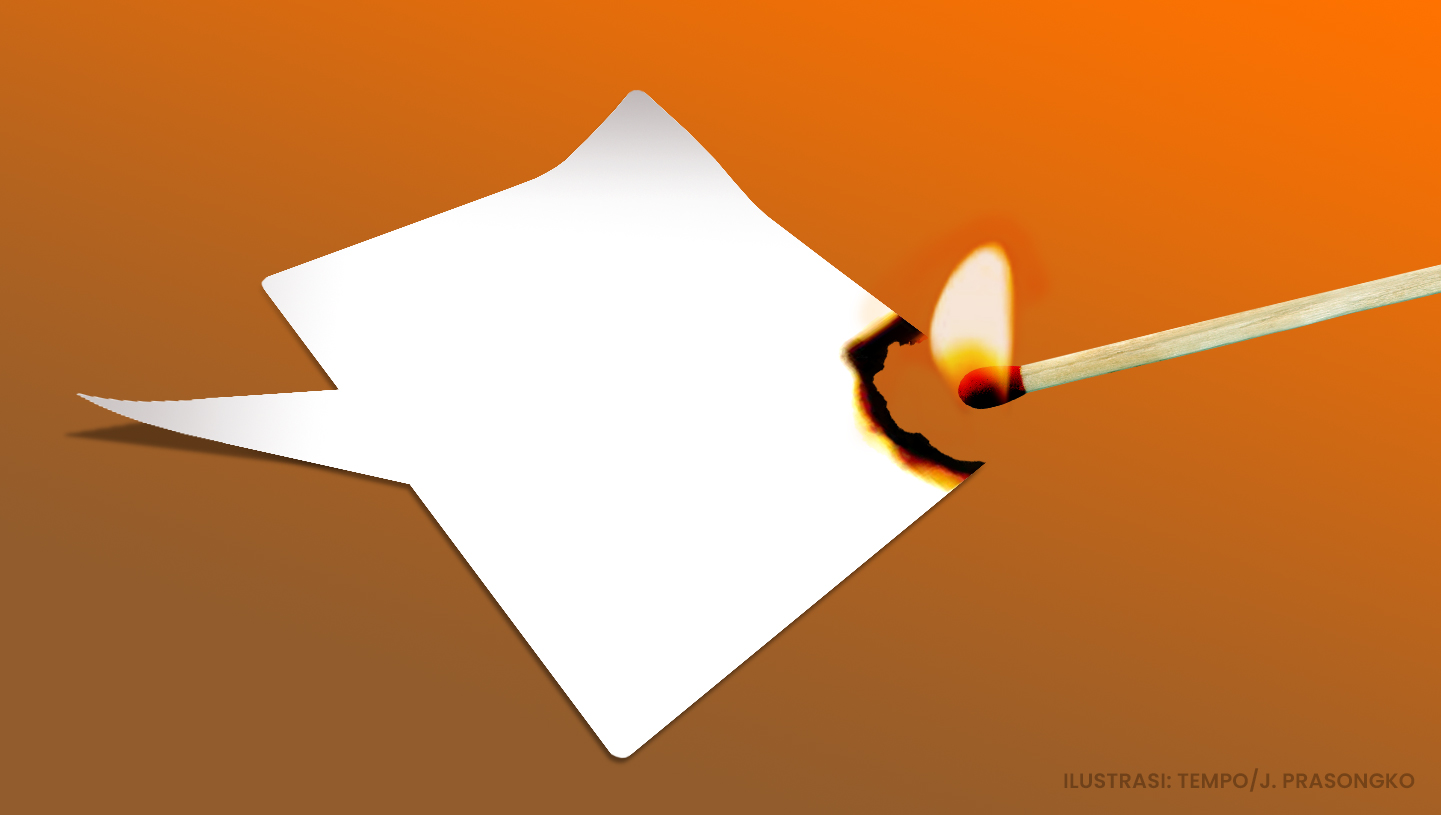Perang punya sebuah tata buku. Perang adalah sang pembuat dua lajur. Dengan teratur data yang negatif disusun di satu tempat dan data yang positif di tempat lain, semacam neraca laba rugi, semacam catatan tentang pengeluaran dan pemasukan. Logistik, persenjataan, dan personel diterjemahkan ke dalam angka dan diletakkan berdampingan dengan kuantitas korban dan kerugian. Keduanya dicatat, keduanya dapat tempat.
Ukuran untuk menentukan prestasi pun bisa rapi; dalam Perang Vietnam, Pentagon memperkenalkan satu istilah yang persis meskipun brutal: body counts. Sekian puluh tahun sebelumnya, Hitler membasmi sekitar enam juta orang yang didaftar sebagai ?Yahudi? dan ?bukan Arya? di kamar-kamar gas di Auschwitz, dan dengan bulu roma berdiri kita mendengar apa yang disebut oleh Adorno sebagai ?pembunuhan administratif?.
Dengan tata buku seperti itu kekejaman pun dicoba diubah menjadi keperluan, bukan lagi keniscayaan. Korban menjadi benda-benda digital yang terang dan dingin seperti cahaya fosfor di gelas yang gelap. Tapi kemudian, pada hari ini, antara teror dan perang hanya ada tanda batas yang jadi kabur, dan saya tak tahu apa yang terjadi dengan pengertian ?korban?. Di New York, di pagi 11 September, ketika Mohammad Atta dan kawan-kawannya membunuh hampir 6.000 orang dengan cara menabrakkan dua pesawat ke dua gedung World Trade Center, Tuhan disebut-sebut dengan syahdu atau sangar. Tapi bisakah korban dihadirkan seperti dulu, ketika agama menghendaki?dan mewajibkan?kekerasan?
Pada suatu hari, sekian ribu tahun yang silam dan tak terekam, Ibrahim diberi tahu bahwa ia harus menyembelih anaknya sendiri untuk menguji kepatuhannya kepada Tuhan. Pada suatu hari yang lain, sekian ribu tahun yang lalu pula, seorang raja Hindu juga diminta membunuh, dan seekor kuda harus dibantai untuk para dewa dalam upacara yajòa. Ritual yang kemudian terjadi menunjukkan bahwa ?obyek? yang dibunuh atau disakiti mendapatkan kualitas lain. Bagi saya, ini tanda awal berakhirnya apa yang ?alamiah??kekerasan dan kematian seperti ketika seekor ular sawah melahap celurut dan ketika benalu mamatikan ara.
Dan itu berakhir, dan kebudayaan pun ambil peran. Si calon korban disiapkan secara khusus sebelum batang lehernya dipotong; dengan itu ia dianggap sebagai bagian dari yang sakral, dan dengan itu sebuah keluarga, atau sebuah kaum, atau sebuah dusun, atau sebuah negeri, pun selamat: kematian telah datang dan membawa kehidupan baru. Kekejaman mendapatkan makna. Sang korban, untuk memakai kata-kata René Girard, adalah sebuah ?penanda transendental?.
Tapi yang demikian itukah yang terjadi ketika langit bagian selatan Pulau Manhattan tiba-tiba menjadi sebuah pentas, dan sebuah adegan yang spektakuler dan mengharu-biru perasaan terjadi, ketika dua bangunan seluas 10 juta kaki persegi yang menjulang itu kena gempur? Yang segera tampak pagi itu: asap yang membubung, api yang seperti belantara besar, rasa kaget di seluruh penjuru, rasa ngeri di seantero New York, dan pemandangan yang akan terus meneror mimpi kita ketika tampak tubuh-tubuh manusia yang berjatuhan dari jendela lantai keseratus sekian. Semuanya tak menyusun sebuah altar yang agung. Yang suci tak terpancar melingkari pentas itu. Seandainya itu semua adalah sebuah upacara korban yang gigantis, kita juga tak tahu komunitas apa yang sedang harus diselamatkan hari itu: Islam? Palestina? Dunia Ketiga? Amerika Serikat sendiri?
Tentu, horor pada hari itu bukan sebuah ritual. Tapi pada saat yang sama, menara kembar itu, bahkan orang-orang yang tewas itu, dalam kehancuran mereka, menjadi semacam sebuah ?penanda transendental? pula. Mereka tak sekadar benda dan badan yang tak mewakili apa pun. Seperti domba yang disembelih pada Hari Raya Kurban, mereka adalah substitusi. Bagi para pembunuh mereka, mereka adalah pengganti sesuatu yang lain?mungkin kapitalisme, mungkin Amerika, mungkin dosa dan najis. Mereka bukan sekadar sejumlah kerugian yang dibinasakan melalui sebuah ?pembunuhan administratif?, yang hanya mencocokkan angka dengan kuota, lalu menutup buku. Kekejaman masih merupakan keniscayaan, bukan sekadar keperluan. Kita tahu para pembunuh itu pada saat yang sama juga tewas bersama yang mereka bunuh.
Dan kita pun akhirnya tetap terengah-engah untuk mengerti, begitu rumitkah korban untuk didefinisikan. Hidup seakan-akan hanya impuls. Tragedi terjadi pada hari itu, namun yang paling tragis adalah bahwa ketika ada hampir 6.000 orang tak bersalah yang tewas, ada ratusan juta manusia lain yang bertepuk tangan, di Dunia Arab, di Pakistan, di Indonesia: suara aplaus mereka yang miskin, kegembiraan mereka yang dihina, dan rasa bangga mereka yang dikalahkan. Barangkali keadilan adalah sejenis dewa yang diam, yang marah, dan tak terjangkau dan orang ramai membuat unggun dan memanggang apa saja sebagai daging pengorbanan.
Goenawan Mohamad
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini