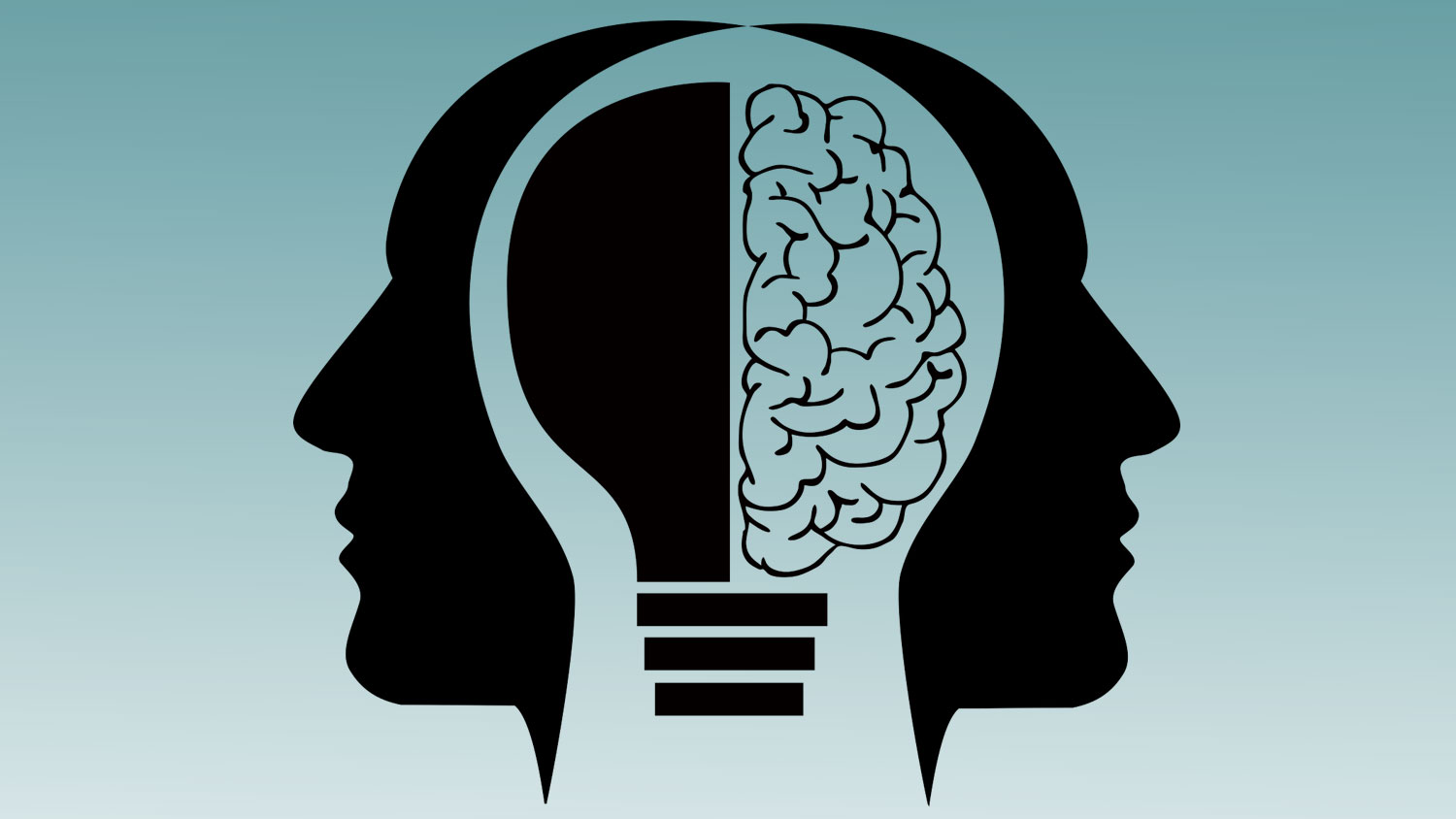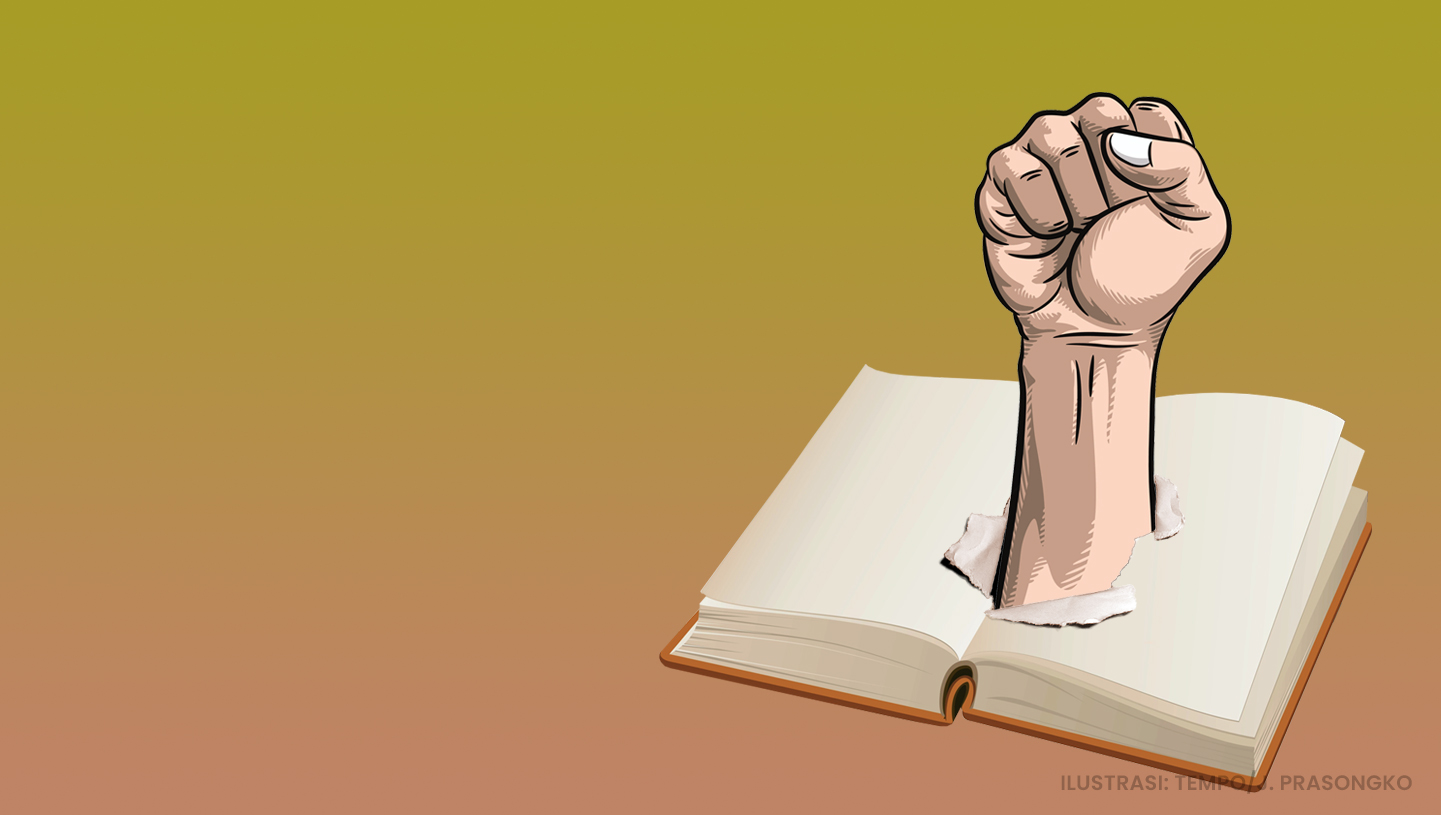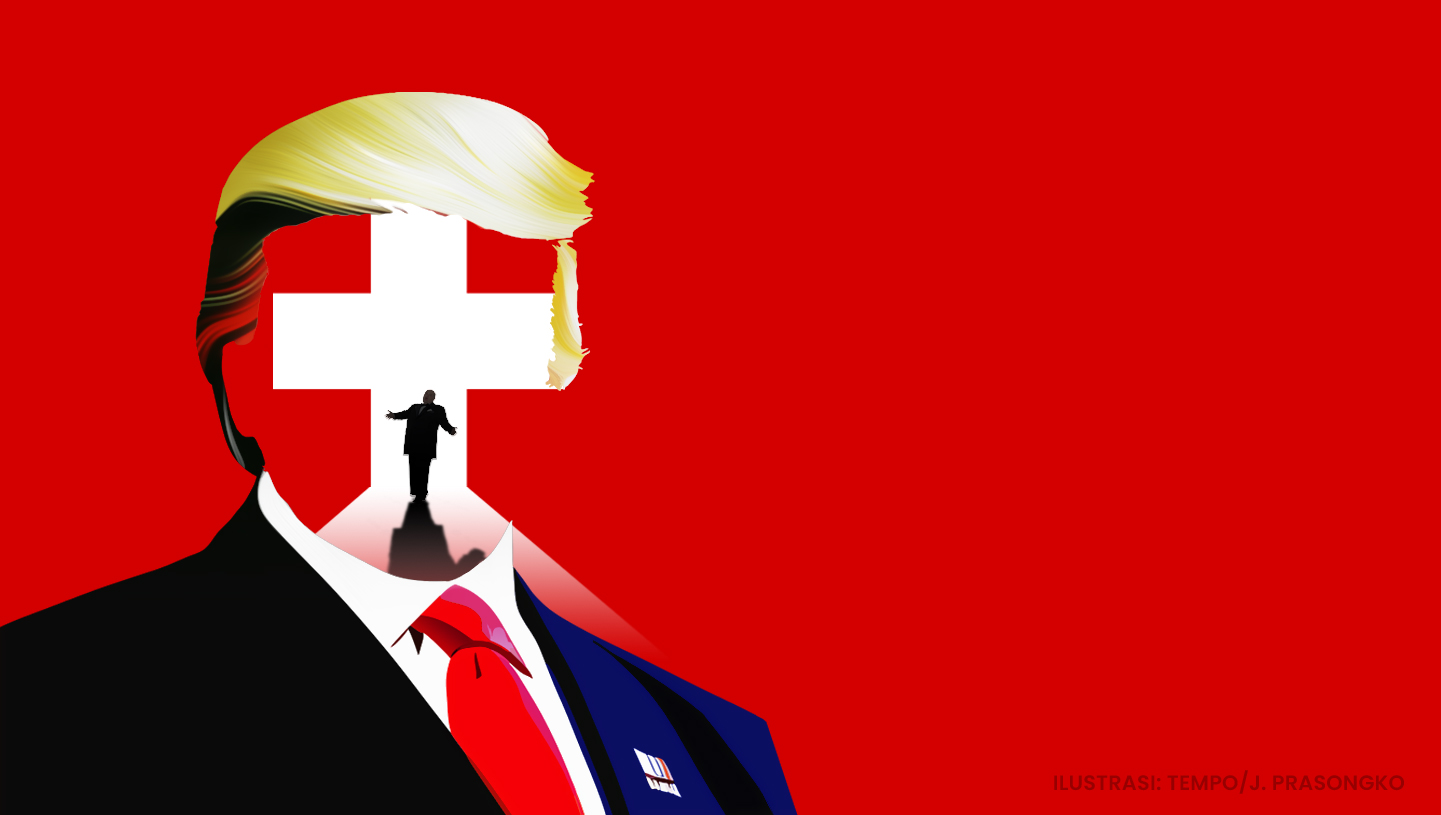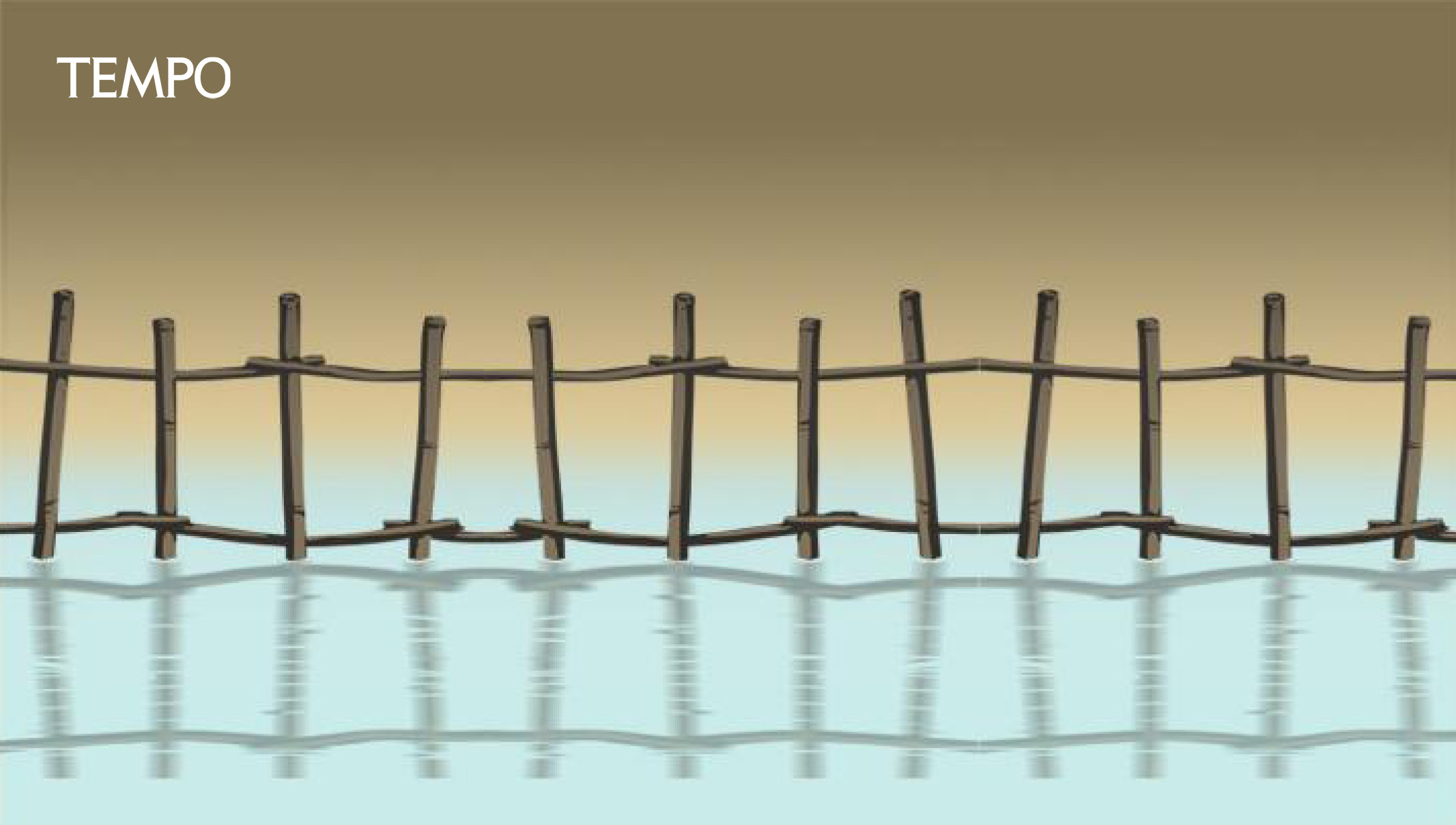Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Korupsi biasanya diasosiasikan dengan uang. Orang yang korup ialah mereka yang meraup uang dalam jumlah sangat besar dengan cara-cara yang melanggar hukum. Seseorang menggelapkan uang negara atau perusahaan dalam jumlah kecil, itu bukan koruptor. Guru yang mengajar di tiga sekolah dengan mencuri-curi waktu untuk mencukupi kebutuhan keluarga setiap bulan, itu juga bukan koruptor. Tetapi, orang yang mendapatkan uang beberapa miliar rupiah dengan membiarkan masuknya impor gula ilegal, itu baru namanya koruptor.
Betulkah pandangan ini?
Tidak juga, saya kira! Kalau pandangan ini diikuti, akan menjadi sangat susah untuk menentukan batas jelas antara tindak korupsi yang harus dikutuk dan tindakan mencukupi kebutuhan yang dapat dimaafkan. Hal inilah yang sekarang ini terjadi dalam masyarakat kita. Dalam kesadaran masyarakat, terdapat kekaburan mengenai hakikat korupsi secara etis. Salah satu akibatnya ialah bahwa mereka yang berkuasa atau berpengaruh tidak akan pernah dapat dikatakan terlibat korupsi, sedangkan orang kecil tanpa kekuasaan dan tanpa pengaruh akan mudah sekali dinyatakan sebagai manusia korup.
Menurut salah satu kamus saya, korupsi memiliki empat ciri dasar, yaitu (1) imoralitas dan pemutarbalikan kenyataan; (2) ada unsur penyuapan dan ketidakjujuran; (3) mengandung kesalahan-kesalahan atau ditandai adanya perubahan yang dipaksakan; dan (4) berupa tindakan tercela atau ternoda.
Berdasarkan keempat ciri di atas, tindak korupsi sebenarnya tidak selalu berupa perbuatan menggelapkan uang. Banyak sekali perbuatan yang kelihatannya baik-baik saja tetapi sebenarnya merupakan perbuatan korup. Menuntut wartawan dan pers dengan mempergunakan undang-undang kriminalitas dapat dengan absah dipandang sebagai suatu korupsi. Dalam praktek ini terdapat unsur kesalahan-kesalahan serta perubahan yang dipaksakan. Sebaliknya, koran yang memberitakan sesuatu yang merusak kehormatan orang lain tanpa didukung bukti-bukti meyakinkan juga merupakan suatu tindakan korup. Dalam hal ini ada unsur imoralitas dan pemutarbalikan kenyataan yang merupakan unsur penentu.
Menurut kamus saya tadi, perbuatan korup (to corrupt) mempunyai lima arti, yaitu (1) merusak atau mengganggu citra baik atau nama baik orang, lembaga, atau sesuatu yang lainnya; (2) secara moral meremehkan atau merusak seseorang, lembaga, dan sebagainya; (3) mencemarkan atau menodai nama orang, lembaga, atau sesuatu yang lain; dan (4) menyebabkan seseorang atau sesuatu menjadi busuk; dan (5) merusak keaslian suatu teks atau naskah.
Guna memahami secara lebih penuh makna generik dari korupsi, dapat ditambahkan bahwa kata "korup" atau corrupt mempunyai hubungan semantik dengan kata-kata "bangkrut" (bankrupt),"interupsi" (interrupt), disrupsi (disrupt), yang artinya "membuat kacau" atau "membuat bubar", dan juga dengan kata abrupt, yang artinya "mendadak atau sekonyong-konyong" dan juga "terputus-putus atau tidak lancar". Kata Inggris corrupt berasal dari kata Latin corruptus, yang artinya "rusak, busuk, atau binasa".
Jadi, berdasarkan penjelasan-penjelasan ini, korupsi tidak harus berbentuk perbuatan penggelapan uang. Segala perbuatan yang pada akhirnya merusak, membuat busuk, atau membinasakan adalah korupsi. Pemalsuan ijazah dan penganugerahan gelar-gelar—akademis ataupun keningratan—yang menyimpang dari ketentuan asli juga merupakan suatu perbuatan korup. Lalu, bagaimana dengan naskah Supersemar yang terkenal itu? Apakah telah terjadi suatu korupsi dalam hal ini? Kita tidak tahu dan saya takut kita tidak akan pernah tahu! Sebab, orang-orang yang mungkin pernah melihat naskah aslinya sudah tidak ada lagi di antara kita, kecuali satu orang: Pak Harto.
Jadi, di samping korupsi uang, ada juga korupsi kekuasaan, korupsi pengaruh, dan korupsi fungsi. Dengan demikian, dalam pandangan saya wabah korupsi dalam masyarakat kita sebenarnya jauh lebih luas dan lebih mendalam daripada apa yang disadari masyarakat selama ini.
Betulkah korupsi telah menjadi bagian dari budaya bangsa kita? Saya rasa tidak. Kalau korupsi betul-betul telah merasuk ke dalam budaya kita, setiap manusia Indonesia dewasa akan secara rutin terlibat dalam salah satu jenis perbuatan korupsi tadi. Apa yang terjadi menurut pandangan saya ialah: sebagian kelompok manusia Indonesia dengan kekuasaan, kedudukan, dan pengaruh melakukan tindak korupsi, sementara masyarakat tidak kuasa mencegahnya. Menegur mereka pun kita tidak berani! Bagi saya, ini berarti bahwa toleransi kita terhadap berbagai bentuk korupsi sudah menjadi terlalu longgar. Dan suatu generasi dengan kesadaran nilai yang terlampau longgar tidak akan pernah mampu membentengi dirinya terhadap godaan-godaan untuk korupsi, yang memang selalu ada dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, ini merupakan masalah hati-nurani bangsa, masalah nationaal geweten (conscience of the nation) menurut idiom Bung Karno.
Situasi ini tidaklah kekal. Menurut pandangan saya, ini merupakan suatu situasi nasional yang bersifat temporer. Kita tidak harus terus-menerus menjadi bangsa dengan hati nurani yang terlalu longgar, yang menisbikan semua nilai dan menganggap enteng setiap pelanggaran norma. Kita dapat mengusahakan lahirnya suatu generasi dengan hari nurani yang lebih ketat, dengan disiplin diri yang lebih ketat, dengan moralitas yang lebih ketat. Jalan utama untuk mencapai tujuan nasional ini ialah pendidikan.
Harus ada catatan yang saya tambahkan secara cepat di sini. Pendidikan menuju ke sasaran seperti ini tidak mungkin dilaksanakan dengan cara-cara konvensional yang kita kenal selama ini. Pendidikan menuju terbentuknya hati nurani bangsa yang cukup ketat harus memberikan perhatian dan tekanan yang cukup kuat kepada usaha-usaha pedagogis untuk mengenal dan memahami nilai-nilai atau norma-norma. Program pendidikan, antara lain, perlu menegaskan perbedaan antara norma-norma legal pada satu pihak dan norma-norma moral pada pihak yang lain mengenai tindak korupsi. Pada dasarnya, korupsi merupakan suatu pelanggaran terhadap norma moral. Instrumen untuk menjerat pelaku korupsi adalah norma-norma legal. Susahnya ialah bahwa penerjemahan norma-norma moral ke norma-norma legal jarang sekali bersifat sempurna. Selalu terdapat celah-celah yang bersifat hampa dalam proses penerjemahan ini. Lalu, yang terjadi ialah suatu tindakan yang dipandang masyarakat sebagai korup tetapi tidak demikian dalam pandangan hakim. Maka, timbullah situasi ketika suatu tindakan bersifat korup secara moral tetapi absah secara legal.
Menurut Prof. Phillip H. Phenix, kerancuan ini berasal dari kegagalan kita untuk mengetahui perbedaan antara makna (meaning) ketentuan legal dan makna ketentuan etis atau moral. Ketentuan legal mengandung makna yang bersifat simbolis-empiris, yang esensinya ialah suatu konvensi formal mengenai sesuatu yang dapat dilukiskan dan dijelaskan secara faktual. Ketentuan etis atau moral pada lain pihak mengandung makna yang bersifat "right deliberate action", yaitu apa yang seharusnya dilakukan oleh seseorang secara sukarela. Logika yang terdapat dalam wilayah etika atau moral bersifat khas dan berbeda dari logika yang berlaku dalam wilayah simbolis-empiris. Dalam wilayah simbolis, kita dapati makna-makna yang secara etis atau moral bersifat netral. Dalam wilayah empiris, kita dapati makna yang bersifat faktual. Sedangkan dalam wilayah etika atau moral, terdapat makna yang menurut Stephen Toulmin bersifat gerundives, artinya bersifat "worthy of " atau sangat pantas untuk dilaksanakan.
Berdasarkan ketentuan ini, David Hume (1711-1766) menyatakan bahwa kita tidak akan pernah dapat menarik inferensi dari "apa yang ada" (what is) kepada "apa yang seharusnya ada" (what ought to be). Fakta dan kewajiban moral (moral obligation) pada dasarnya terletak dalam tatanan logika yang berbeda.
Bagaimana mengajarkan hal-hal ini di sekolah? Di lingkungan keluarga?
Ini adalah sebuah pertanyaan yang sungguh sangat sulit dijawab. Sekolah kita sampai saat ini masih bekerja dengan tradisi yang sangat mementingkan pengetahuan faktual dan sangat mengabaikan kepekaan terhadap nilai-nilai, baik estetis maupun etis. Rupa-rupanya harus ada reformasi pendidikan yang benar dan tuntas untuk memungkinkan terjadinya akselerasi reformasi.
Dan berdasarkan sifat korupsi yang saya paparkan di atas, sungguh tidak realistis untuk mengharapkan ada pemimpin yang akan dapat memberantas korupsi dengan segera. Janji perubahan seperti ini merupakan sebuah janji yang korup. Atau janji yang dibuat oleh mereka yang tidak tahu apa yang mereka janjikan. Apa yang dapat kita lakukan ialah mengendalikan dan menyusutkan korupsi secara berangsur-angsur. Pendidikan yang benar akan melahirkan transformasi sistem nilai dalam diri kita sebagai bangsa. Generasi demi generasi akan melahirkan kehidupan bangsa dengan nationaal geweten yang lebih ketat, dengan disiplin diri yang lebih ketat.
Dirgahayu bangsa Indonesia!
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo