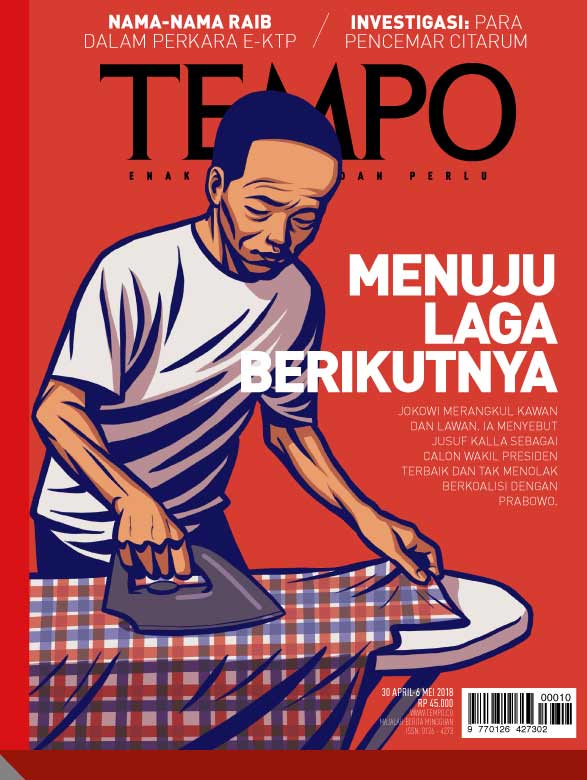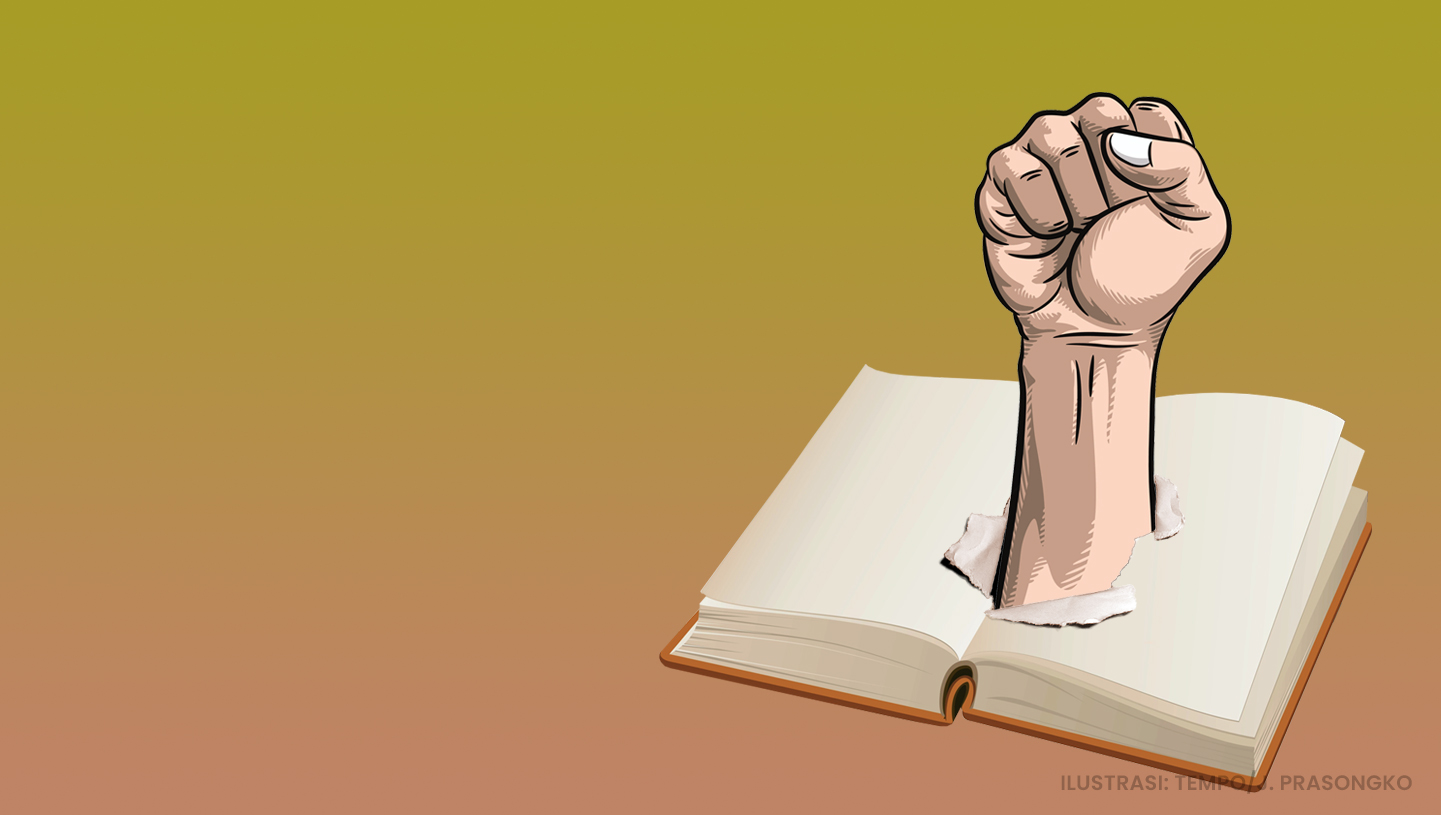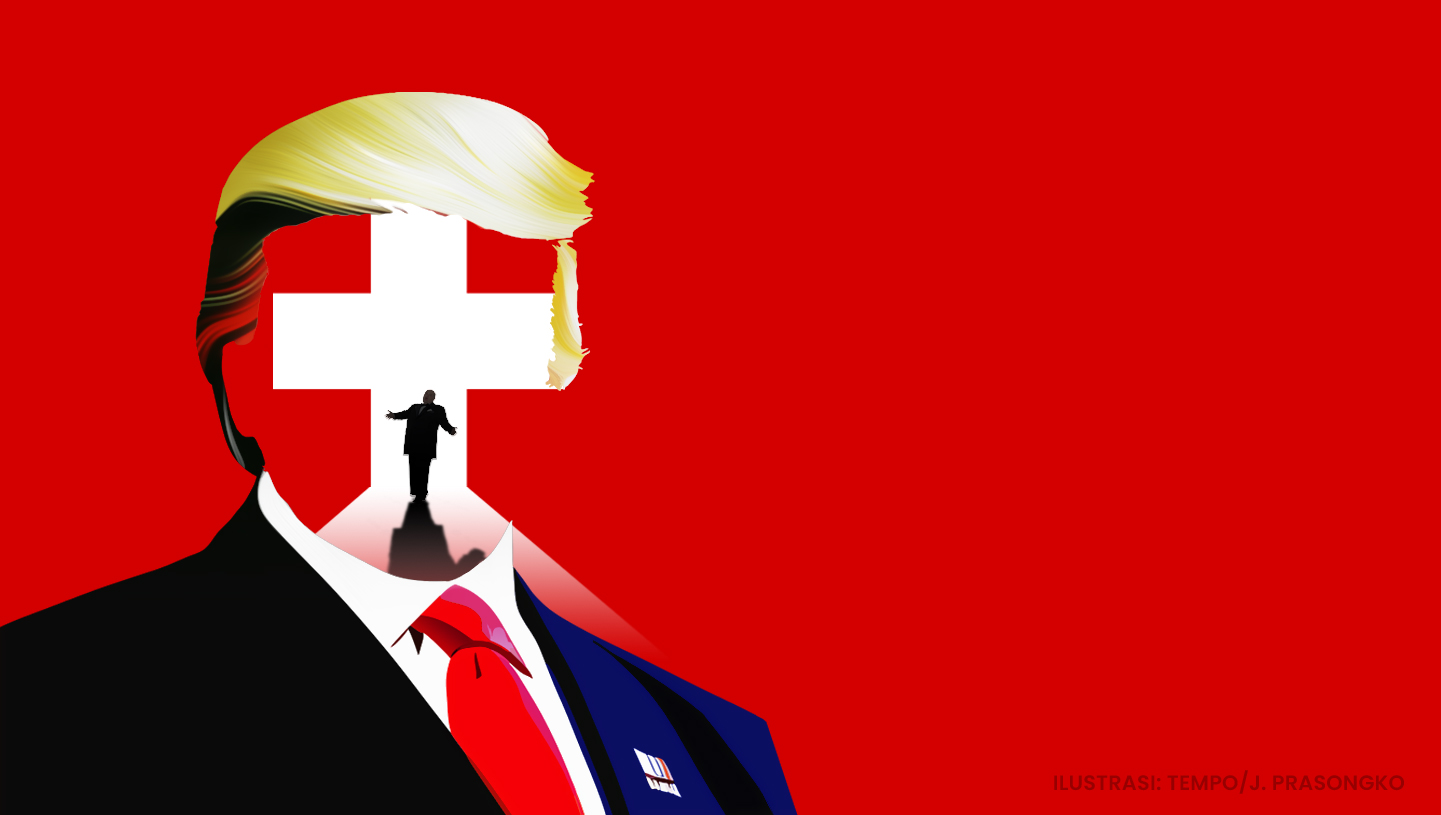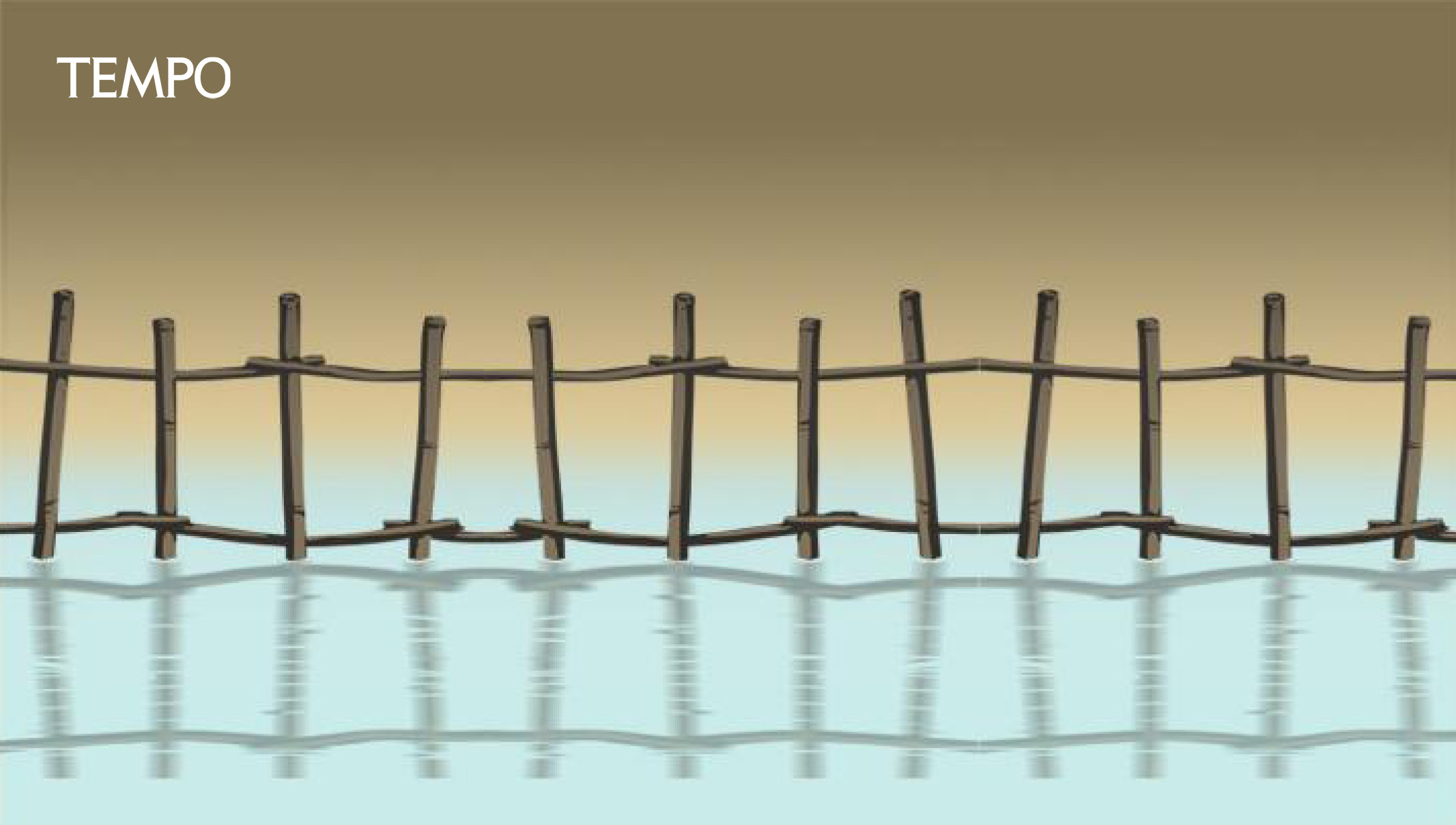Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
APAKAH licentia poetica (Latin), poetic license (Inggris), atau lisensi puitika itu? Lisensi puitika secara mudah diartikan sebagai hak untuk melanggar aturan bahasa. Menurut Ensiklopedia Britannica, lisensi puitika adalah hak yang diasumsikan oleh penyair ada padanya untuk mengubah sintaksis standar atau melakukan penyimpangan dari diksi ataupun pengucapan umum untuk mencapai kecukupan aturan tonal dan metrum yang hendak dicapai dalam karyanya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kita bisa mengendus bahwa aroma definisi Britannica itu sangat formal. Yang dikejar adalah metrum dan tonal, yang menjadi syarat mutlak dalam sajak formal, sajak-sajak dalam bentuk tetap. Dalam pantun dan syair, dua bentuk formal puisi kita, sering kita temukan pembalikan sintaksis dan pengolahan diksi untuk mengejar syarat bunyi, metrum, yang menjadi ukuran keberhasilan atau keindahan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Lantas, ketika yang ditulis adalah sajak bebas, yang tidak lagi mempertaruhkan keberhasilan dan keindahannya pada aturan bunyi dan terutama metrum, apakah masih ada gunanya lisensi puitika itu? Masih perlukah hak itu dipakai? Perlu dan bisa, dengan pengertian yang diperluas. Tapi, harus diingat, pemakaian lisensi puitika tidak lantas membuat sebuah puisi berhasil dan bagus, juga tidak serta-merta menunjukkan penyairnya hebat. Itu justru bisa menjadi batu uji bagi kualitas karya dan kepenyairannya.
Di luar penggunaan bahasa untuk puisi, penutur bahasa, terutama bahasa lisan, juga punya hak untuk melanggar dan diberi toleransi untuk salah. Beberapa waktu lalu, saya punya kesempatan mengasuh keponakan yang masih berusia empat tahun. Kami membelikan dia boneka. Dia tergolong bocah yang lantih (Banjar) alias ceriwis atau banyak omong. Katanya, "Dila sudah lama mau boneka ini, tapi Umi enggak mauin." Saya mengerti apa yang dia maksudkan. Dia ingin boneka itu sudah lama, tapi ibunya tidak memberinya atau tidak membelikannya.
Saya tidak mengoreksi bahasa keponakan saya itu. Saya tidak menuntut dia berbahasa dengan sempurna. Saya memberinya toleransi untuk salah. Di sinilah mungkin penerapan teori langue dan parole De Saussure itu berguna. Keponakan saya menguasai langue bahasa Indonesia belum seluas penguasaan saya. Maka yang muncul dari bahasa lisannya adalah parole yang unik, keunikan yang timbul karena keterbatasan penguasaannya atas langue. Tapi ia tetap bisa dimengerti dan komunikasinya sama sekali tidak gagal.
Di manakah batas kebolehan untuk melanggar dan membuat kesalahan tersebut? Tak ada patokan yang tetap. Itu bisa dibuat ketat atau dibikin longgar, bergantung pada siapa seseorang berkomunikasi dan dalam konteks apa dia berujar. Yang pasti, batasan itu tak boleh sama sekali tak ada karena hanya akan membikin komunikasi gagal dan gelap. Juga tak boleh menjadi sangat ketat karena hanya akan membikin bahasa menjadi kaku.
Sepiawai apa pun seorang penutur, selalu akan ada jarak antara langue (bahasa yang dibayangkan sesuai dengan kaidah baku) dan parole (bahasa dalam penggunaan para penuturnya). Jarak itu bisa menjadi ukuran kecerdasan berbahasa seseorang. Semakin dekat jaraknya, semakin cerdas seseorang dalam berbahasa.
Saya selalu beranggapan bahwa puisi adalah wilayah parole seorang penyair. Tentu saja penyair harus dianggap sebagai seorang penutur yang mumpuni dalam hal penguasaan atas langueatau senantiasa mewajibkan dirinya menguasai langue. Dengan lisensi puitika, tidak hanya dalam hal pengkhianatan atas diksi dan aturan sintaksis, serta seluruh perangkat puitika yang tersedia, penyair sesungguhnyadan seharusnya dengan sadarmenarik-ulur jarak antara langue dan parole.
Contoh terbaik dalam hal ini adalah penyair Sutardji Calzoum Bachri dengan kredo puisinya itu. Kredo Sutardji menunjukkan betapa dia sebagai penyair menguasai linguistik dengan kuat. "Dalam puisi saya, saya bebaskan kata-kata dari tradisi lapuk yang membelenggunya seperti kamus dan penjajahan-penjajahan lain seperti moral kata yang dibebankan masyarakat pada kata tertentu dengan dianggap kotor (obscene) serta penjajahan gramatika," ujar Sutardji. Kecuali fonologi, hal pokok dalam subsistem bahasa disebut oleh Sutardji di sana: leksikon, pragmatik, dan gramatika. Tapi yang penting adalah untuk apa itu dilakukan: "Bila kata telah dibebaskan, kreativitas pun dimungkinkan."
Maka lakukanlah apa pun dengan sadar untuk memungkinkan kreativitas. Kreativitas bukan cuma urusan bahasa. Kreativitas adalah urusan kehidupan. Jika bahasa bisa mendorong terciptanya iklim kreatif di semua unsur kehidupan, kita memang mutlak memerlukan bahasa yang demikian, bukan bahasa yang menyanjung formalitas yang kaku. l
Hasan Aspahani
Jurnalis, penyair, editor haripuisi.com
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo