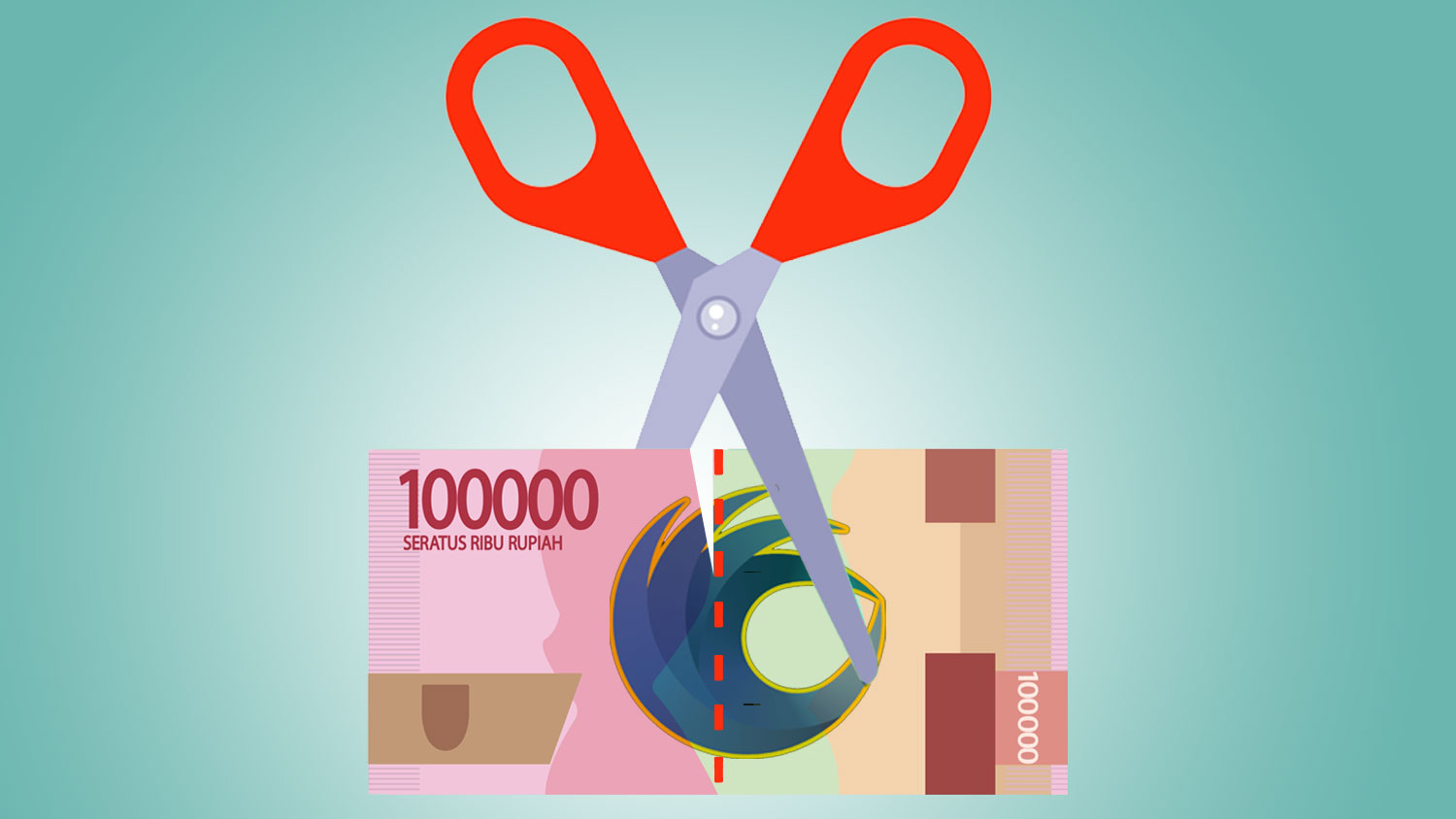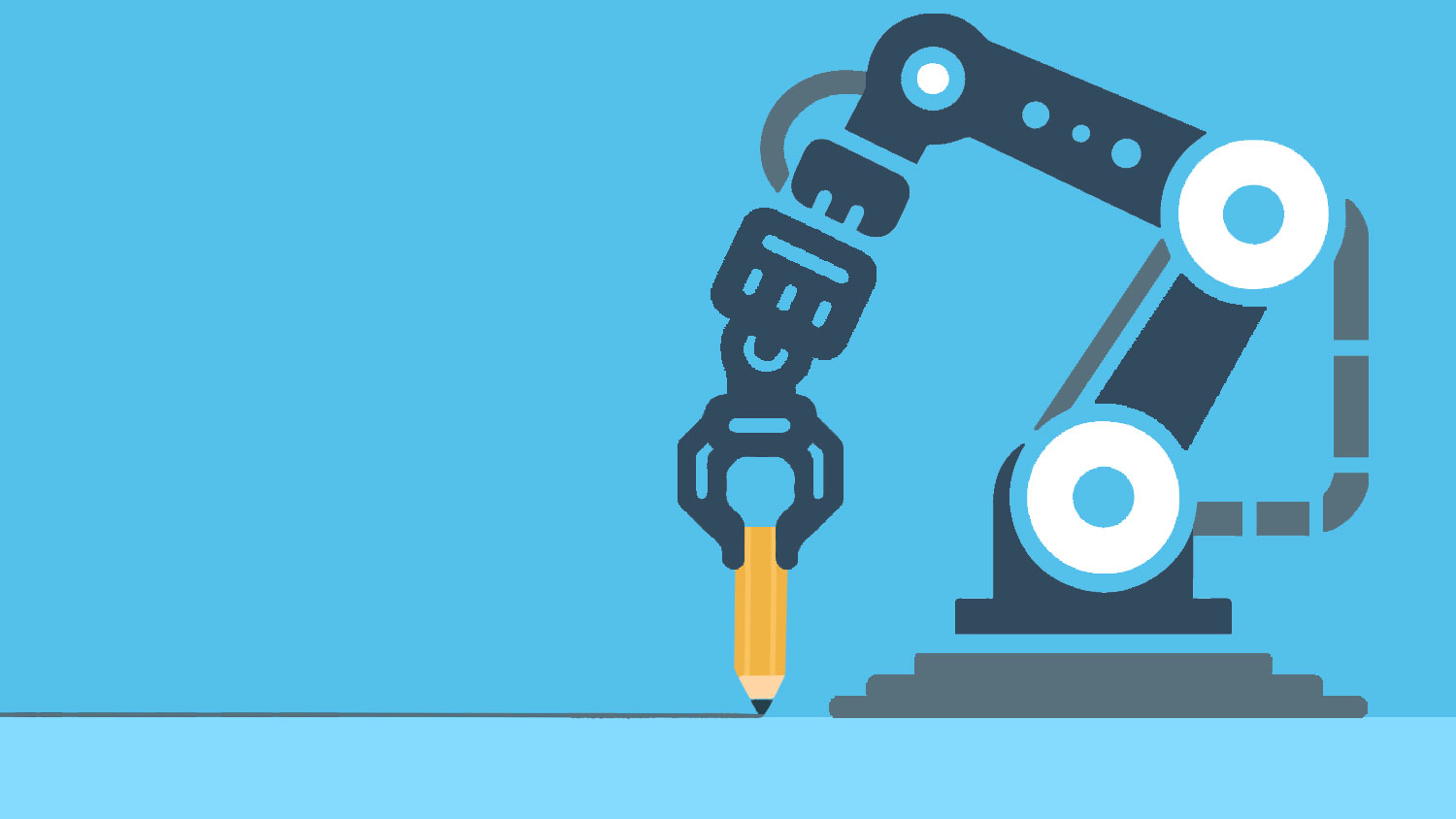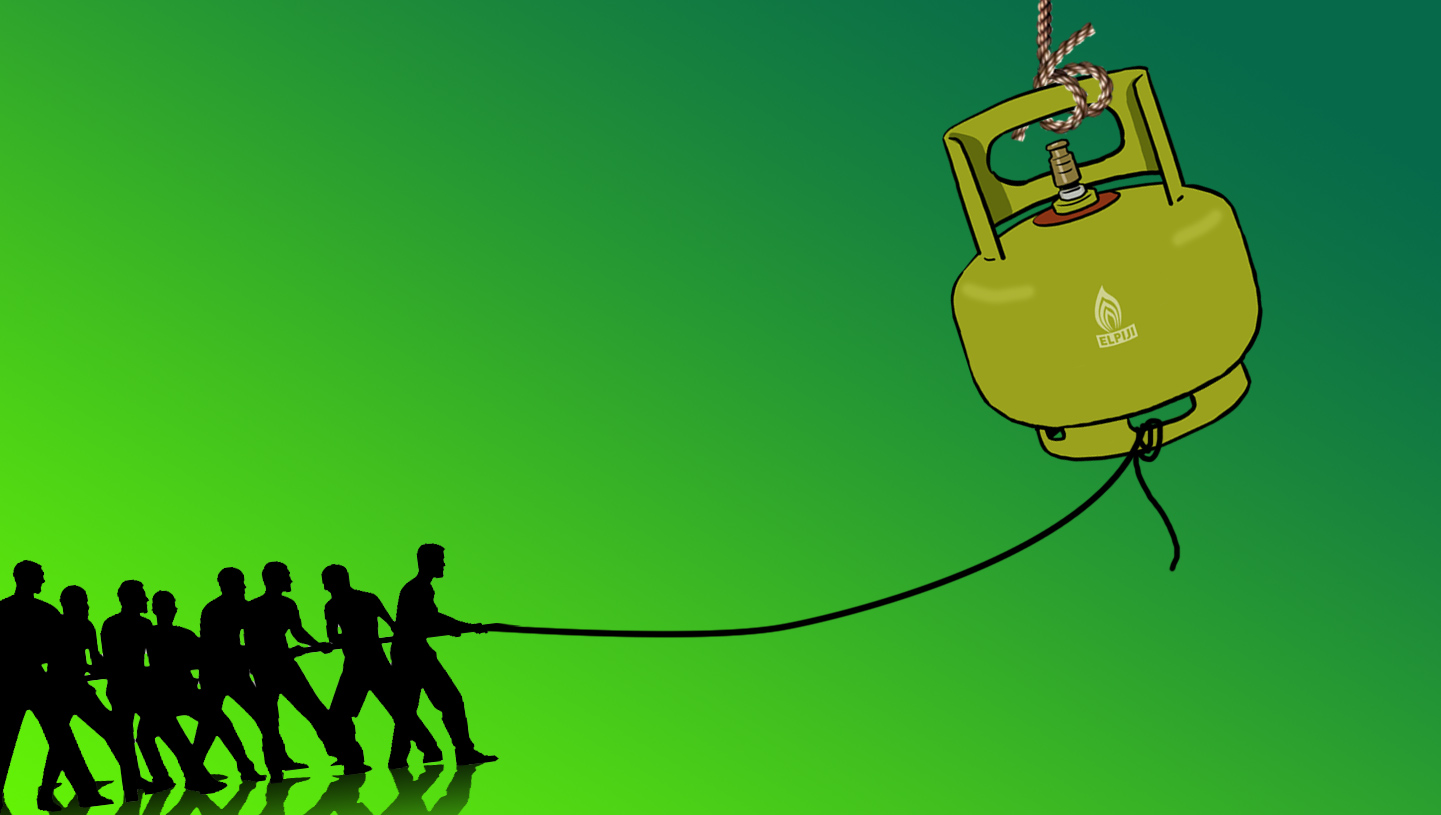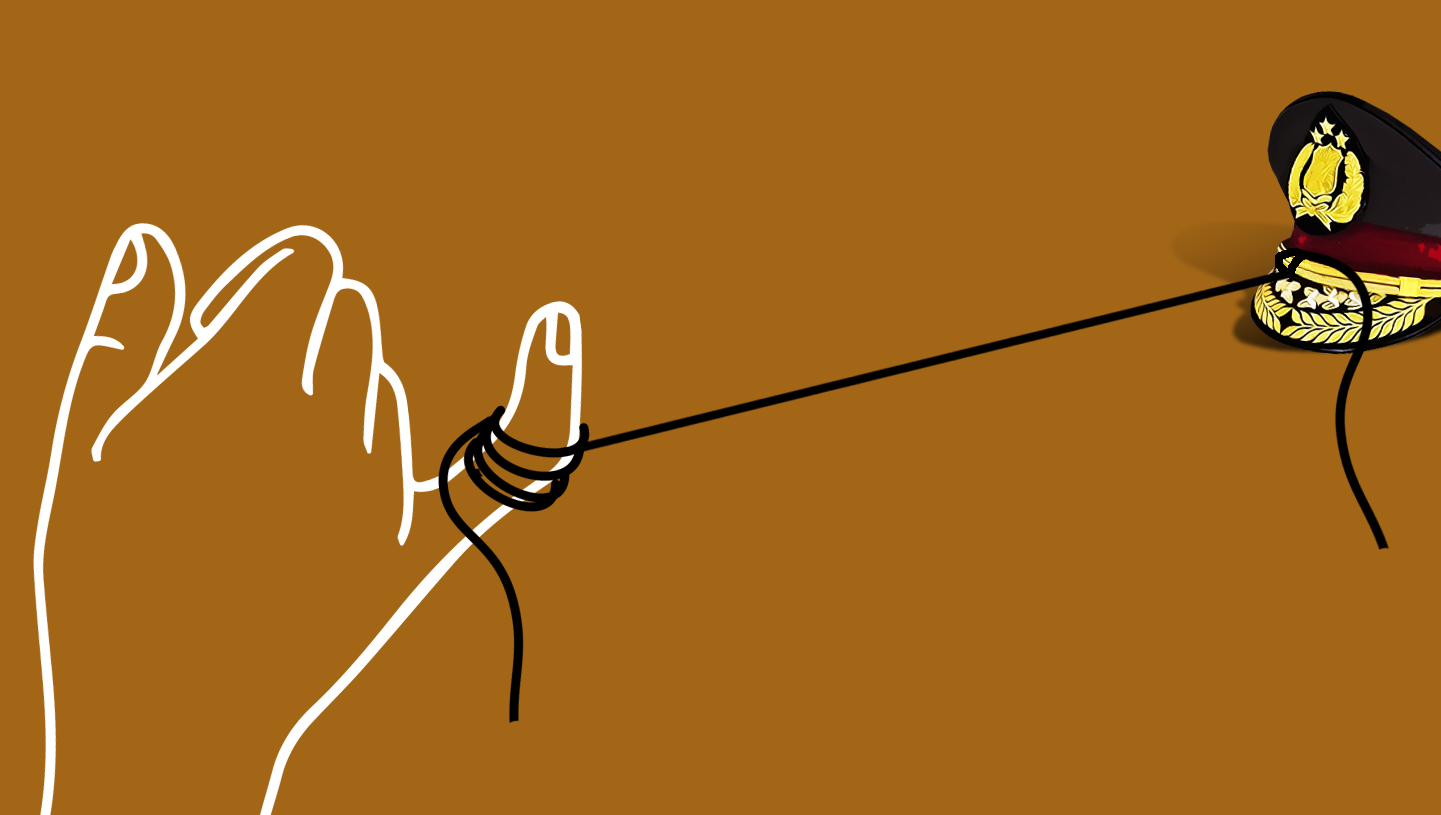Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Miko Ginting
Pengajar Hukum Pidana STH Indonesia Jentera
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dunia bergerak ditandai dengan perkembangan teknologi yang tak bisa ditepis, termasuk dalam upaya penegakan hukum. Sebagai contoh sederhana, dulu bukti dari suatu tindak pidana masih sangat konvensional, seperti surat atau dokumen. Saat ini, bukti tindak pidana dapat berupa surat elektronik, uang elektronik, atau bahkan dokumen elektronik yang tersimpan pada sistem cloud. Lantas bagaimana kesiapan regulasi Indonesia dalam menghadapi perkembangan dan situasi yang dinamis ini?
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Pada awalnya, keberadaan bukti elektronik diperkenalkan melalui Pasal 26A Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sejak itu, hampir semua undang-undang yang mengatur hukum acara pidana turut mengatur bukti elektronik, meskipun secara substantif berbeda-beda dalam pengkategoriannya. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mengkategorikan bukti elektronik sebagai alat bukti petunjuk. Namun Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Pemberantasan Terorisme, dan undang-undang lain menempatkan bukti elektronik sebagai alat bukti yang berdiri sendiri.
Selain soal ketidakseragaman pengkategorian, aspek yang krusial adalah prosedur perolehan bukti elektronik. Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 20/PUU-XIV/2016 memutuskan agar bukti elektronik menjadi bukti yang sah, perolehannya harus dilakukan secara sah pula. Perolehan yang tidak sah akan berimbas pada pengesampingan dan ketiadaan nilai dari bukti tersebut secara hukum.
Di sisi lain, soal perolehan bukti ini berkaitan erat dengan perlindungan hak asasi manusia, seperti perlindungan hak privasi dan hak milik terhadap data, informasi, atau dokumen. Pada derajat tertentu, bobot persinggungan perolehan bukti dengan hak asasi manusia semakin tegas apabila menyangkut data pribadi atau data sensitif.
Persoalannya, satu-satunya aturan yang memberikan landasan prosedural terkait dengan hal ini adalah Pasal 43 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Persoalan berikutnya, undang-undang ini menyatakan prosedur dalam pasal ini hanya berlaku untuk tindak pidana yang diatur dalam UU ITE. Artinya, untuk semua tindak pidana di luar UU ITE dan mayoritas tindak pidana berada di luar UU ITE, tidak terdapat ketentuan menyangkut prosedur perolehan bukti elektronik.
Secara konvensional, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan di sidang pengadilan, hingga status bukti pasca-persidangan. Namun karakteristik bukti elektronik sangat berbeda dengan bukti non-elektronik. Bukti elektronik bersifat rentan dan mudah direkayasa, dihapus, digandakan, atau disebarluaskan. Karena itu, menyandarkan pengaturan pada substansi KUHAP saat ini sudah jelas tidak memadai.
Misalnya, penggeledahan dalam KUHAP ditujukan pada rumah atau tempat tertutup lainnya dan terhadap badan. KUHAP tidak mengenal sama sekali penggeledahan terhadap perangkat atau sistem perangkat elektronik. Belum lagi apabila perangkat dan sistem itu terkunci atau berupa sistem berbasis server, seperti surat elektronik, media sosial, atau media penyimpanan berbasis cloud. Terdapat kesenjangan pengaturan antara KUHAP dan perkembangan penegakan hukum yang semakin dinamis mengikuti perkembangan teknologi.
Imbas kekosongan pengaturan ini adalah ketidakpastian dalam proses penegakan hukum. Penegakan hukum dalam situasi ini akan berhadapan dengan standar yang berbeda-beda. Bisa saja dalam kasus A, bukti elektronik yang diperoleh sama sekali tidak dipersoalkan. Namun, dalam kasus lain, bukti elektronik itu dipersoalkan dan bahkan ditolak oleh hakim.
Imbasnya pada sisi individu adalah ketiadaan jaminan perlindungan hak asasi manusia ketika berhadapan dengan penegakan hukum. Ini berlaku tidak hanya bagi tersangka/terdakwa, tapi juga saksi, atau bahkan bukan pihak yang tidak berperkara tapi memiliki data yang berkaitan dengan penegakan hukum. Padahal, secara filosofis, hukum acara berisi substansi hak asasi yang diciptakan untuk membatasi kekuasaan sekaligus melindungi hak asasi manusia.
Saat ini, kebutuhan untuk segera menyusun landasan regulasi terkait dengan bukti elektronik telah menemukan titik urgensinya. Ini terutama berkaitan dengan prosedur perolehan bukti elektronik, yang dimulai dari penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan di sidang pengadilan, hingga pengembalian atau pemusnahannya. Sebagai pengaturan yang bersifat prinsip, perubahan pada level undang-undang menjadi penting, terutama untuk memberikan standar yang seragam bagi pengaturan terkait.
Namun hal ini tidak cukup apabila tidak diikuti oleh regulasi atau pedoman di masing-masing institusi penegak hukum dan pengadilan. Sekali lagi, upaya menata regulasi yang berkaitan dengan bukti elektronik ini ditujukan untuk memberikan penguatan pada penegakan hukum sekaligus menyediakan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Kedua hal ini dapat berjalan beriringan tanpa harus dibenturkan satu sama lain.