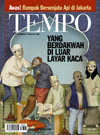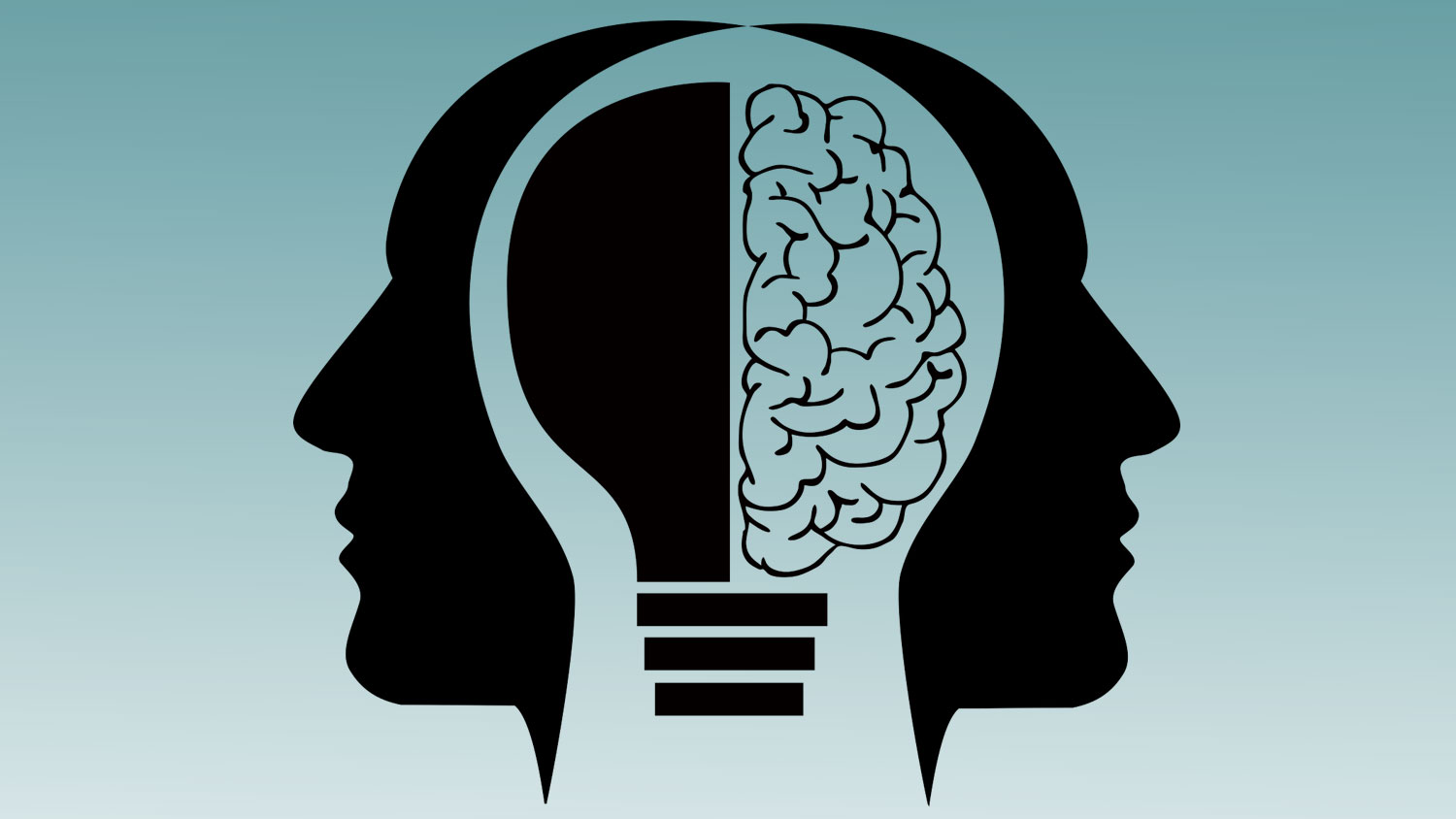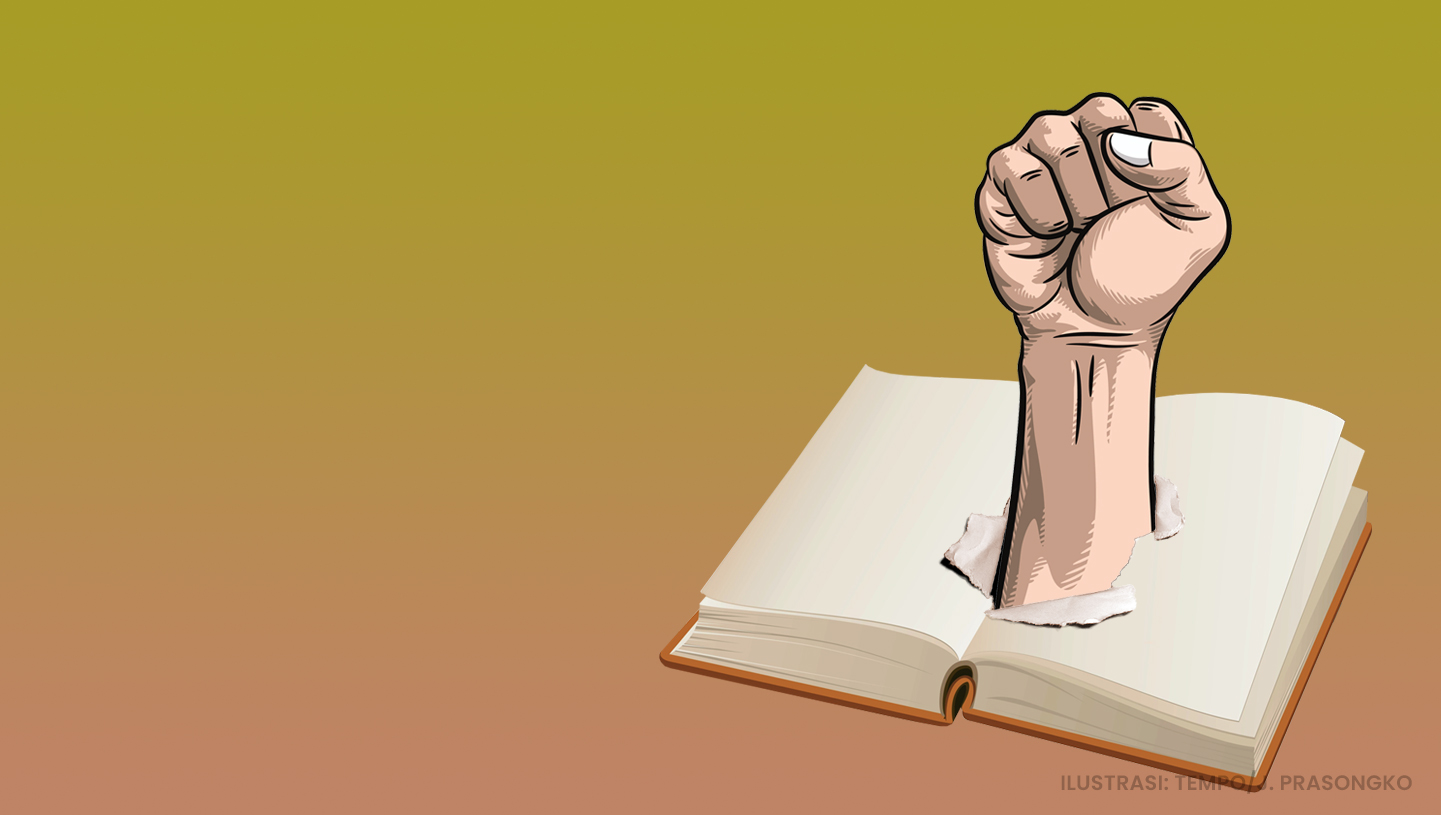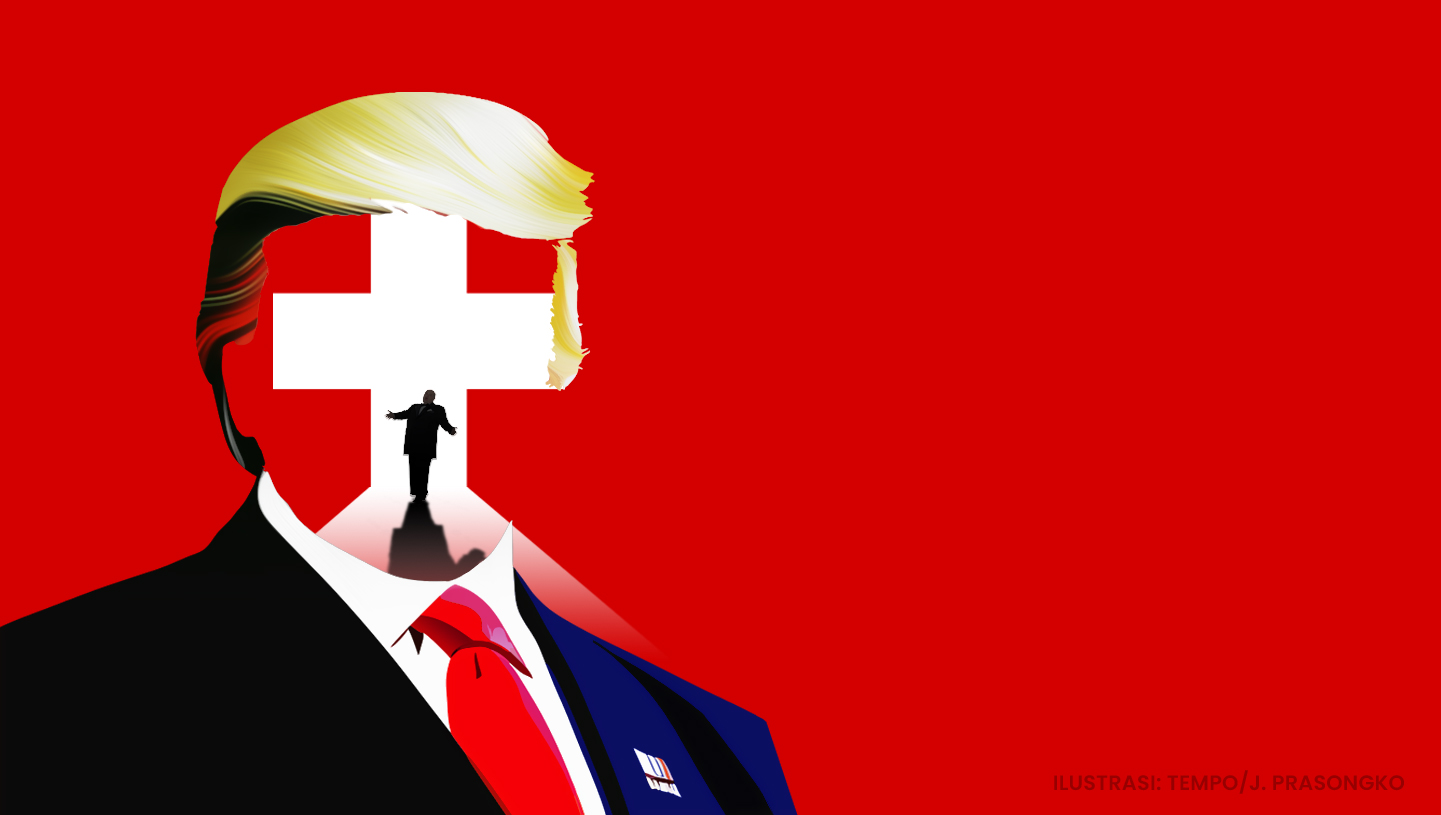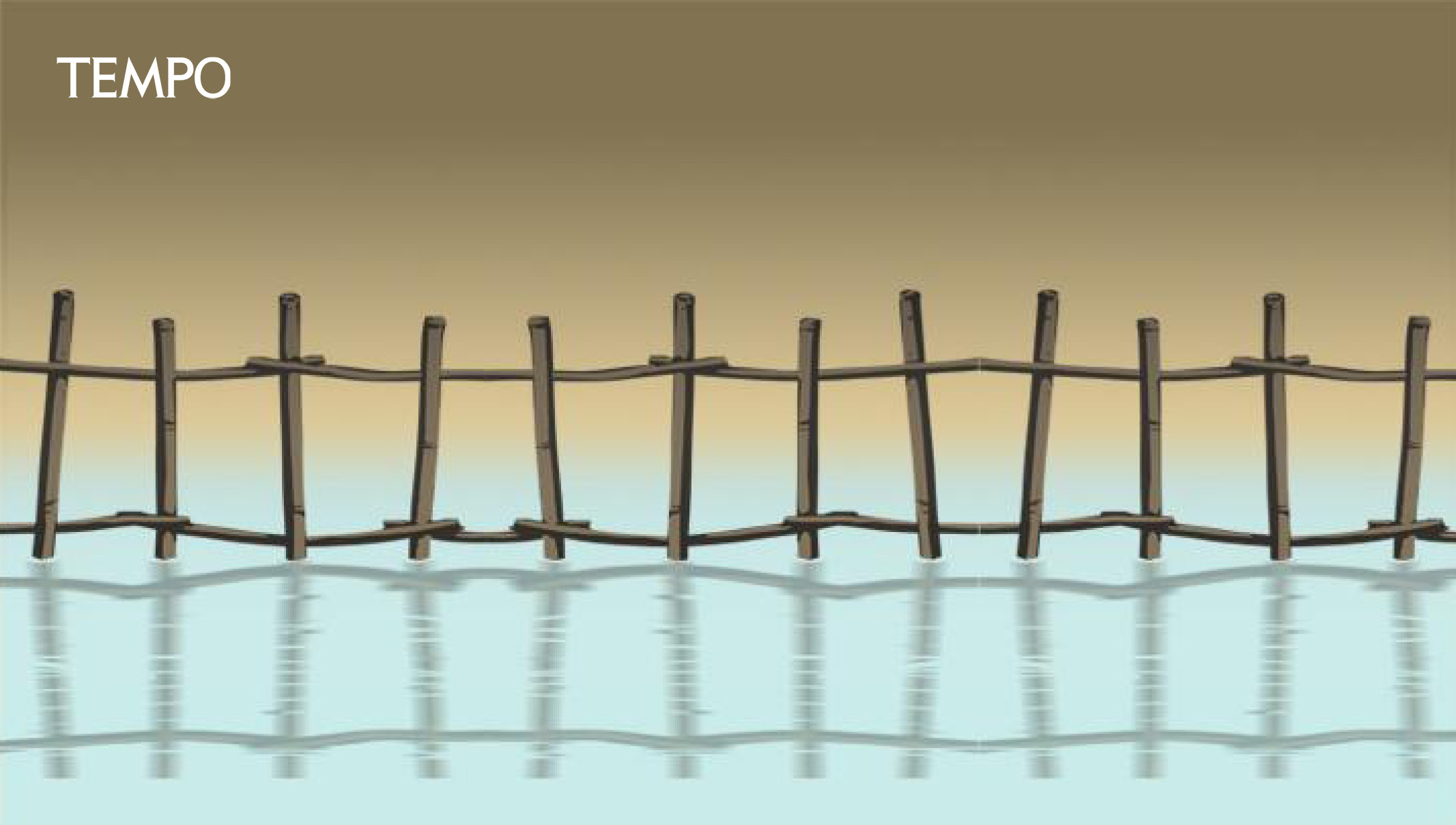Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
J.J. Rizal
Berani sumpah, kebanyakan orang Indonesia merasa lebih afdol dan sering menggunakan istilah ”Lebaran” ketimbang ”Idul Fitri”, sebagaimana juga mereka merasa lebih kena memakai istilah ”puasa” daripada ”shaum” atau ”bulan puasa” dibanding ”bulan Ramadan”. Istilah Idul Fitri, Ramadan, dan shaum memang tidak asing, tetapi istilah puasa dan Lebaran dirasa lebih klop karena merupakan buah proses sejarah masyarakat sendiri dengan kandungan fungsi sosial-budayanya yang khas dan lebih dapat dihayati.
Istilah Lebaran artinya ”selesai”, menyelesaikan suatu pekerjaan atau kewajiban berpuasa. Menurut Poerbatjaraka, istilah Lebaran memang sangat berkait erat dengan puasa yang berasal dari bahasa Sanskerta. Puasa berasal dari kata upawasa, artinya menutup, atau tidak mengeluarkan wasa. Wasa adalah kekuatan/kemampuan yang ada pada seseorang. Dari kata itu muncul kata kuwasa, lalu menjadi kuasa. Menurut Poerbatjaraka, di zaman pra-Islam, Lebaran itu upacara setelah 40 hari selesai menjalankan puasa. Jadi, Lebaran dan puasa sama tua.
Merujuk pada akar katanya yang berkait erat dengan kata kuasa, Lebaran dan puasa selain berdimensi religi juga berdimensi sosial-budaya-politik. Dan tradisi yang menyejarah pada bangsa ini memang menunjukkan Lebaran sebagai selesainya masa puasa. Bukan sekadar momentum kelahiran kembali manusia sebagai individu dengan sifat fitrinya, tetapi juga sebuah bangsa dengan segala kesuciannya sebagai kontrak sosial rakyat dengan pemimpinnya.
Krisis tahun 1929 dan diikuti oleh suatu masa depresi ekonomi yang lama disebabkan oleh keangkuhan politik-ekonomi pemerintah Hindia Belanda membuat rakyat hidup dalam kesengsaraan yang hebat. Pukulan-pukulan hebat dari gubernur jenderal saat itu pun menimbulkan krisis dalam kehidupan politik pergerakan.
Dalam situasi multi krisis itulah Lebaran tahun 1929 dijadikan momentum politis. Java Bode di halaman muka memberitakan umat Islam di Jakarta untuk pertama kalinya mengadakan sembahyang Id di lapangan terbuka Koningsplein (Gambir). Selain merupakan perlambang kepercayaan akan filosofi, doa perlu di samping ikhtiar ekonomi dan politik, dan para tokoh pergerakan nasional menjadikannya ajang bertemu dan menguatkan semangat rakyat sekaligus menghayati deritanya. Semoga Lebaran mengantar rakyat Indonesia sampai di ujung menang. Sebagai simbolisasi harapan-harapan itu, rakyat mengganti kartu Lebaran yang beredar pertama kali tahun 1927 dengan gambar orang berperahu sambil mengibarkan bendera Belanda dengan desain baru yang lebih sesuai dengan semangat zaman.
Koningsplein menjadi pusat salat Id di Jakarta sampai dengan zaman pendudukan Jepang, ketika lapangan itu berganti nama menjadi Ikada. Tahun 1942, kemenangan yang diharapkan kesampaian. Belanda dilibas lars militer Jepang dan Indonesia diserahkan dengan mudah ke ”saudara tua”-nya. Namun belum kemenangan sempurna. Seperti ditelaah oleh Harry J. Benda dalam Bulan Sabit dan Matahari Terbit, ternyata ”saudara tua”-nya Indonesia itu bukan saja penuh sikap militeristik, tapi juga menerapkan politik agama yang bikin naik pitam. Contohnya, Jepang mengimbau agar salat Id diadakan di pagi buta persis selesai subuh, sebab sebelum matahari terbit mereka akan bikin upacara sekerei (sembah matahari) di lapangan yang sama. Saat itulah rakyat kehilangan wahana sosial-politik-budaya yang mengikat secara khidmat para pemimpin untuk menghayati penderitaan rakyat.
Tetapi, setelah tiga setengah tahun dijajah Jepang, datanglah hari kemenangan. Saat itu bulan puasa. Jumat 17 Agustus 1945, Proklamasi Kemerdekaan dibacakan Soekarno-Hatta. Sebagai tanda syukur—bukan saja kelak dalam preambule UUD 45 disebut kemerdekaan atas berkat rahmat Tuhan—panitia Proklamasi Kemerdekaan RI pun merencanakan salat Id di halaman Gedung Proklamasi. Tetapi, balatentara Dai Nippon melakukan penjagaan ketat di sekitar gedung itu. Salat Id kemudian diadakan di Jalan Pegangsaan Timur 17.
Istilah Lebaran memang dipopulerkan orang Betawi. Orang Jawa menyebutnya Syawalan, dari kata dasar Syawal, nama bulan menurut kalender qomariyah (bulan). Atau sering juga dipakai istilah ”bakda”, artinya juga selesai. Tetapi istilah itu tidak serta-merta ditinggalkan ketika ibu kota RI diungsikan dari Jakarta ke The Heart of Java (Yogyakarta) pada akhir 1945. Belanda, yang kembali masuk Indonesia dan kepingin menjajah lagi dengan menebeng rombongan Sekutu, adalah musuh yang nyata. Tetapi di tengah revolusi yang mendengung-dengung itu, pecah perbedaan pendapat antara tokoh-tokoh revolusi itu sendiri. Brosur kontra brosur dikeluarkan oleh tiap tokoh yang ingin agar revolusi berjalan sebagaimana keinginan kelompoknya. Keadaan memprihatinkan. Rakyat terjepit.
Sejumlah tokoh di bulan puasa 1946 menghubungi Soekarno. Mereka minta agar ia bersedia di hari raya yang jatuh pada Agustus itu, mengadakan perayaan Lebaran dengan mengundang seluruh komponen revolusi yang pendirian politiknya beraneka macam, dan kedudukannya dalam masyarakat pun berbeda-beda. Biar Lebaran menjadi ajang saling memaafkan dan memaklumi serta menerima keragaman. Bukan sebagai laknat, melainkan rahmat, seraya sadar bahwa musuh yang nyata adalah Belanda yang come back dan jangan rakyat dibiarkan tersia-sia hidupnya oleh lilitan kesusahan akibat revolusi. Semoga di hari kemenangan, Tuhan membimbing ”orok republik” sampai di ujung menang. Lebaran jadi ajang menggalang potensi solidaritas nasional.
Menurut A.R. Baswedan, saat itulah lahir istilah halal bi halal yang sering digandengkan dengan acara Lebaran. Istilah dari bahasa Arab yang diracik sendiri oleh para pendiri RI sebagai perhelatan menghalalkan perbedaan, tapi kukuh dalam satu kebersamaan. Ketika Lebaran tiba, di Istana Yogyakarta diselenggarakan halal bi halal sebagai simbol kukuhnya semangat Yogya 45. Bukankah sejarah mencatat bahwa RI, berkat semangat Yogya 45, mampu mempertahankan kemenangan terbesarnya sebagai bangsa merdeka dan mewujudkan satu kesatuan utuh sebagai bangsa yang berdaulat?
Sekarang, apakah petinggi bangsa ini akan memetik buah tradisi Lebaran dalam konteks sosial-politik-budaya nasional yang telah menyejarah dan berperan menaikkan rasa solidaritas sebagai unsur penting dalam proses menjadi Indonesia tersebut?
Tahun 1981 di Kuala Lumpur terbit buku Umar Junus, Dasar-dasar Interpretasi Sajak. Di dalamnya Umar Junus menafsirkan sajak ”Malam Lebaran” Sitor Situmorang. Sajak yang dari kali pertama kemunculannya di majalah Zenith, No. 6 Juni 1953, terus menggemparkan sampai kini dalam penafsirannya. Sajak itu pendek, dua baris: Malam Lebaran / Bulan di atas kuburan.
Junus tidak mengaitkan makna sajak itu dengan proses kreatif dan keadaan lahirnya seperti yang dilakukan J.U. Nasution. Tetapi meneruskan langkah Subagio Satrowardoyo yang menyimpulkan ”Malam Lebaran” Sitor adalah puncak bicara berlambang di dalam sajak, sekaligus merupakan tingkat akhir bicara berlambang yang masih dimengerti orang. Junus melihat ada sebuah pertentangan antara pengertian ”bulan” dan ”kuburan”. ”Bulan” selalu dihubungkan dengan sesuatu yang romantis, sesuatu yang berhubungan dengan mimpi, pembentukan masa depan yang indah. Sebaliknya, ”kuburan” berhubungan dengan kesedihan, dengan tak adanya masa depan. Jadi, keseluruhan baris berarti ”kegembiraan” di atas ”kesedihan”. Keseluruhan sajak akhirnya berarti ”hari Lebaran merupakan kegembiraan di antara begitu banyak kesedihan”.
Rasanya bukan tak mungkin ”Malam Lebaran” Sitor yang ditafsirkan Junus itu adalah jawaban atas pertanyaan di atas. Sebab, betapa terasa jauhnya pemimpin bangsa ini meninggalkan tradisi Lebaran dalam konteks politik-budaya nasional yang telah menyejarah dan berperan dalam memupuk rasa solidaritas sebagai bagian penting dalam proses menjadi Indonesia. Lebaran belakangan tinggal pesta-pesta, solek-solek, dan pemborosan. Lebaran hampa kemenangan, sebab harapan tinggal kesia-siaan, dari hari ke hari persoalan terus bertumpuk tanpa penyelesaian, sementara pemimpin lebih sibuk dengan masalah sendiri. Sehingga proses menjadi Indonesia terasa diabaikan dan cita-cita untuk membangun Indonesia pun semakin jauh, dan hari depan seperti bayangan menakutkan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo