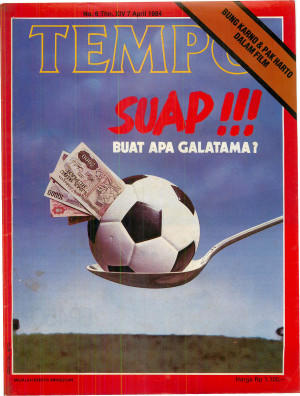KONON salah satu cacat pendidikan tinggi kita adalah bahwa para mahasiswa tidak membaca. Tapi ini masuk akal. Buku-buku berbahasa Indonesia masih belum dibuat. Sehingga, setiap kali dosen memberikan daftar buku yang harus dibaca, mahasiswa tidak dapat membacanya karena sebagian besar dalam bahasa Inggris. Nah, bergantunglah sang mahasiswa pada diktat. Dan pada waktunya kelak, menjadi sarjanalah mereka. Dan bekal ilmu yang ada di benak mereka, ya, cuma diktat itu. Sampai di situ saja pun keadaan ini sudah kedengaran tragis. Tapi seorang keponakan yang banyak tahu mengatakan, skenario itu sudah kuno, sudah berusia 15 sampai 25 tahun. Sebab, katanya, sebagian sarjana diktat itu sekarang bahkan sudah pada menjadi dosen. Dosen diktat, tentu. Dan, kalau dilacak dengan teliti, sekarang mungkin sudah ada para diktator dari generasi ketiga, bahkan keempat! Maka, kedengaranlah gagasan untuk penerjemahan. Kalau tidak, perkembangan ilmu di negeri ini akan terbelakang puluhan tahun. Jepang sudah mencobanya, dan berhasil, kata yang punya gagasan. Karena itu, akan kita terjemahkan semua buku yang pokok. Para dosen akan dapat mengajukan judul para buku, dan akan tersedia para tukang terjemah, dan akan ada para biaya. Akan kita terjemahkan buku-buku sains, akan kita terjemahkan buku-buku sosial, akan kita terjemahkan buku-buku humaniora. Dan akan kita terjemahkan buku-buku lainnya sebagai penunjang. Nah, ini dia, pikir saya. Sebagai guru bahasa Inggris yang sekali-sekali mendapat rezeki dari terjemahan, hati saya gedebak-gedebuk kegirangan. Terbayang order yang akan saya terima, dan bagaimana asap dapur akan sedikit menjadi lebih pekat dan hidangan di meja makan sedikit lebih meriah. Lama juga mengharap-harap, sehingga bayangan rezeki itu hilang sendinnya. Terutama karena ulah seorang keponakan lain yang kebetulan juga banyak tahu. Tidak bisa, katanya. Menerjemahkan tidak akan menyelesaikan masalah. Tidak banyak. Pertama, katanya, siapa yang akan melakukan terjemahan itu. Sambil menuding kepada saya dia bertanya, "Sebagai guru Inggris, apa yang Mas ketahui tentang ilmu kedokteran, hukum, kimia, atau ilmu jiwa-dalam punya Freud?" Betul juga, pikir saya. Lagi pula, katanya, buku-buku mana yang dipilih dari ribuan, bahkan puluhan ribu, yang tersedia? Kita harus ingat bahwa pada kita-kita ini sebenarnya masih berlaku apa yang oleh sementara orang disebut the psychology of the newly fiterate. Orang yang baru melek huruf cenderung mempercayai apa-apa yang dapat dibacanya. Nah, seperti itulah sebagian dosen kita, katanya. Mereka cenderung memuliakan dan bahkan mengeramatkan buku-buku yang mereka pakai ketika kuliah dulu, di Amerika atau negeri lain. Sebagian buku itu dicetak tahun 60-an, atau bahkan lebih dini. Kalau buku terbitan tahun 60-an dijadikan pegangan di sini, hitung saja berapa puluh tahun kita ketinggalan, ujarnya beringas. Di samping itu, tambahnya, di sono, setiap cabang, bahkan setiat ranting ilmu mempunyai beberapa jornal. Jurnal-jurnal inilah avant-garde ilmu. Beberapa tahun sebelum sebuah penemuan-baru masuk buku, biasanya dia muncul dulu dalam jurnal. Nah, akan kita terjemahkan jugakah jurnal-jurnal yang ratusan ribu itu? Seorang keponakan lain menimpali. (Mohon jangan heran, saya punya banyak keponakan yang banyak tahu). Lebih baik membaca asliya, katanya. Kalau para mahasiswa kita menguasai bahasa Inggris, walau yang pasiiif saja, tidak ada persoalan. Itulah masalahnya, balas saya. Mahasiswa kita tidak menguasai bahasa Inggris, walau yang pasiiif saja. Segera saya menyesal mengucapkan kalimat itu, karena tiba-tiba sang keponakan meledak marah: "Lantas apa saja kerja mereka di dalam kelas-kelas bahasa Inggris selama enam tahun di sekolah menengah?" Benar juga, pikir saya. Apa, ya, kerja mereka? Bayangkan, tambahnya. Sejak tahun-tahun 60-an pemerintah sudah memberikan perhatian istimewa pada pelajaran bahasa Inggris. Didatangkan para doktor dan profesor bahasa Inggris, diadakan pilot project di Malang dan Salatiga. Dijalankan penataran berkeliling di seluruh Nusantara. Untuk itu dikeluarkan berjuta-juta dolar. Kemudian dikeluarkan lagi berjuta-juta rupiah untuk membayar guru-guru bahasa Inggris di sekolah-sekolah. Ditambah lagi uang proyek buku. Belum lagi uang yang dikeluarkan para orangtua murid untuk membeli buku-buku itu, serta buku-buku stensilan ciptaan para guru. Nah, cobalah hitung berapa ini semua. Dan itu semua dianggap tidak ada hasilnya, atau hasilnya dianggap tidak bisa dipakai. Dan perlu dikeluarkan lagi biaya untuk proyek terjemahan. Apa gunanya diadakan pelajaran bahasa Inggris di sekolah menengah, hah? tanyanya ketus. Entahlah, bukan urusan saya, jawab saya lesu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini