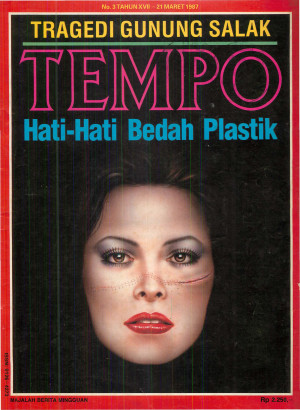PROF. Harsja Bachtiar tidak membandingkan Indonesia dengan Eropa secara geografis. Padahal, dalam hal itu akan tampak sekali persamaan dan perbedaannya. Persamaannya: luas Indonesia kira-kira memang sama dengan Eropa. Perbedaannya: Eropa terdiri dari daratan, kecuali beberapa kepulauan di sana-sini Indonesia terdiri dari lautan yang ditempati pulau-pulau besar-kecil. Komunikasi dari satu tempat ke tempat yang lain, di satu daratan besar seperti Eropa -- apalagi dengan teknologi yang lebih maju niscaya tidak sesulit di daerah lautan yang terdiri dari pulau-pulau. Kesukaran komunikasi itu menyebabkan perbedaan budaya dan adat-istiadat lebih bervariasi apalagi terdapat kenyataan bahwa sejarah mengulurkan tangannya secara tidak sama ke setiap daerah di Indonesia. Kalau kita berjalan dari Sabang sampai Merauke, yang kita temui bukan saja jarak geografis, melainkan juga jarak sejarah. Di samping masyarakat yang sudah modern, ada juga yang masih hidup di zaman batu -- yang oleh pemerintah telah diusahakan maju. Di samping itu para penggemar wayang tentu tahu membedakan tokoh-tokoh sabrangan yang biasanya raksasa (danawa) dari para satria yang lembut tetapi sakti. Meski begitu, semuanya seia sekata (dan berhasil) menciptakan persatuan dan dasar negara kesatuan. Kehebatan ini merupakan kredit bagi para bapak pejuang. Mereka, yang menerima Indonesia sebagaimana adanya sekarang, tentu sulit membayangkan kesukaran-kesukaran yang dihadapi para beliau itu. Di antaranya, untuk mencari tempat tegak kesatuan Indonesia, ada di antara mereka yang kembali jauh ke dalam sejarah, lalu ketemu Majapahit. Celakanya, kalau negara zaman baheula itu yang dijadikan model, timbul peristiwa Bubat (bagi orang Sunda) dan peristiwa Hang Tuah (bagi orang Melayu) di Minangkabau, Gajah Mada malah terpaksa hincit oleh kecerdikan keturunan Pagaruyung. Seperti kata Harsja, "Etnosentrisme atau kecenderungan untuk menganggap kebudayaan daerah sendiri sebagai satu-satunya kebudayaan yang wajar" masih merupakan rongrongan bagi kesatuan dan persatuan bangsa. Para satria ingin "meluruskan" para danawa sabrangan, menganggap kekesatriaan yang "lembut halus" sebagai kewajaran dan kedanawaan sebagai kebelumberadaban. Rongrongan etnosentrisme itu akan terasa "wajar-wajar" saja kalau kebetulan dilakukan oleh yang merasa dirinya mayoritas. Dan kalau perasaan "wajar-wajar" saja itu dimiliki para pemegang kekuasaan tertinggi, terjadilah "penyesuaian" dari pihak-pihak kelompok kecil yang berkebudayaan "kasar" itu. Celakanya, tidak semua nilai budaya "halus" para satria itu sejalan dengan cita-cita. Misalnya, yang kentara sekali, dalam soal bahasa. Ketika para pendiri bangsa dan negara kita merumuskan Sumpah Pemuda, secara sadar mereka memilih bahasa Melayu yang relatif demokratis itu sebagai bahasa persatuan, karena para bapak itu bercita-cita mendirikan sebuah negara demokrasi -- dan itulah pula yang kemudian tercermin dalam UUD 1945, yang dalam mukadimahnya terkandung pula Pancasila. Dengan jiwa besar, para bapak ang berasal dari kebudayaan Jawa dan Sunda yang mempunyai bahasa yang lebih tua, lebih kaya kesusastraannya, dan lebih banyak pemakainya, menerima bahasa Melayu. Peranan bahasa persatuan, yang kemudian menjadi bahasa nasional dan bahasa resmi Indonesia itu, dalam pembentukan bangsa dan negara kita, sangat besar. Untuk memperkayanya, kita juga tidak ragu menambahkan kata-kata, istilah, ungkapan, peribahasa, dari berbagai bahasa daerah dan bahasa asing. Karena sifat bahasa Indonesia, semua itu dapat diserap. Tetapi belakangan ini ada kecenderungan para pemakai bahasa Indonesia yang berasal dari kebudayaan yang mempunyai bahasa bertingkat-tingkat, sebagai manifestasi masyarakatnya yang feodalistis, memasukkan juga unsur-unsur unggah-ungguh ing boso atau undak-usuk basa itu ke dalam bahasa Indonesia yang pada dasarnya demokratis dan egalitarian. Misalnya rawuh mulai dipakai sebagai ganti datang atau tiba, kalau dikenakan pada orang-orang tertentu dalem sebagal ganti rumah, dan dahar untuk ganti makan. Kalau gejala itu dibiarkan, akan timbul kemunduran bahasa nasional kita sebagai sarana masyarakat yang demokratis. Dalam menghadapi kebudayaan-kebudayaan daerah sebagai sumber nilai bagi kebudayaan nasional kita yang masih dalam proses, kita sepakat berpegang pada rumusan: mengambil yang bermanfaat dan meninggalkan yang buruk. Tetapi tidak pernah dibicarakan tuntas: apakah yang baik, dan apakah yang buruk, dari kebudayaan-kebudayaan daerah itu. Misalnya, apakah (jor-joran dalam) melanjutkan "adat" yang mewah dalam perhelatan merupakan ciri yang baik dan bermanfaat dari kebudayaan daerah. Keengganan kita untuk membicarakannya secara terbuka itulah yang memberikan kesempatan masuknya secara menyelundup nilai-nilai budaya daerah yang sebenarnya tidak sejalan dengan cita-cita kita. Seperti terhadap bapak-bapak pembangun bangsa, terhadap para bapak penyusun UUD 1945 pun hendaknya kita tetap memegangi dasar pikiran mereka: jangan sampai kita menafsirkan UUD lepas dari konteks sejarah waktu penyusunan dilakukan. Kecenderungan demikian sudah kelihatan, misalnya adanya penafsiran terhadap kata kepercayaan dalam pasal 29 ayat (2), yang hendak memisahkannya dari agama yang disebut sebelumnya -- meskipun Bung Hatta sebagai salah seorang penyusunnya memberikan keterangan bahwa kata kepercayaan di situ ada dalam hubungan dengan kata agama yang disebut sebelumnya. Juga GBHN Tap MPR No. 11/MPR/1983, yang butir 7-nya berbunyi, "Pembinaan bahasa daerah dilakukan dalam rangka pengembangan bahasa Indonesia dan untuk memperkaya perbendaharaan bahasa Indonesia dan khazanah kebudayaan nasional sebagai salah satu sarana identitas nasional", seakan-akan mempersempit fungsi dan peranan kebudayaan (dan bahasa) daerah, yang dalam penjelasan pasal 32 UUD 1945 telah dirumuskan, "Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya, dan persatuan... serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia." Rumusan GBHN itu seakan-akan menyunat arti pembinaan bahasa daerah, yang sebenarnya memperkaya kita sebagai bangsa (jadi, bukan memperkaya khazanah bahasa nasional saja), dan mereduksi fungsi kebudayaan nasional hanya sampai sebagai ciri identitas nasional belaka, padahal harusnya meningkatkan peradaban dan mempertinggi derajat kemanusiaan kita sebagai bangsa. "Arah perkembangan . . . kita sebagai bangsa cukup baik," kata Harsja. Syukur. Mestinya bisa lebih baik. * Penulis sejak 1981 menjadi guru besar tamu pada Universitas Bahasa-bahasa Asing Osaka (Osaka Gaikokugo Daigaku), Osaka, Jepang.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini