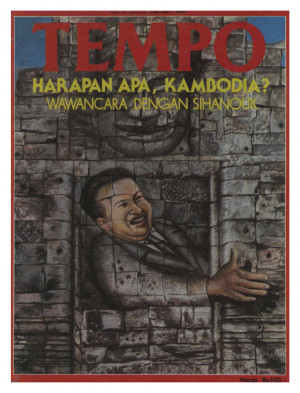SETIAP minggu saya pulang ke Jakarta, jajan syomai adalah acara
penting yang hampir-hampir khidmat bersa anak-anak saya.
Sore-sore, begitu penjaja meneriakkan "maaii . . . " anak bungsu
saya yang kegendutan, tetapi tidak pernah lamban dalam mengejar
setiap penjaja makanan yang lewat, akan dengan gesit
mengejarnya, meninggalkan pekrumnya berantakan di meja.
Ketepatannya mengira arah suara "maaii . . . " dan kecepatannya
berdiri mencegat penjaja itu di tikungan jalan sering
menumbuhkan optimisme saya akan hari depan anak bungsu perempuan
yang gendut ini.
Mau apa, pak? Kol, telor, kentang, pare, daging -- semua? Pake
sambel? Biasanya saya akan menyerahkan kombinasi itu kepada
kedua anak itu. Maka digiring udara sore Jakarta yang tetap
gerah dan suara sengau penyiar radio Prambors kami bertiga akan
melahap jajanan yang sudah melembaga di rumah kami.
Akan nilai gizi, kebersihan memasaknya, serta keotentikan etnis
bumbu-bumbunya siapa akan peduli dalam latar, setting, yang
sudah pas begitu?
***
Syahdan, pada suatu Sabtu sore terjadilah krisis itu. "Maaaii .
. . "
Si gendut tidak beranjak dari tempat duduknya, pekrum berantakan
di depannya. "Maaii .... " Si gendut cuma melirik ke arah saya
sebentar untuk kemudian menekuri pekrumnya. Setidak-tidaknya
kelihatannya begitu. "Maaii . . . "
"Lho kok nggak dikejar, ndut?"
"Biarin Sudah jauh tu! Sudah lewat tikungan!", katanya dengan
penuh keahlian.
"Lho kok?"
Sekarang si gendut meletakkan bolpoinnya, mukanya dipalingkannya
ke muka bapaknya. Astaga, belum pernah saya melihat ekspresi
wajahnya begitu serius sebelumnya.
"Ssst! Kita sudah berhenti makan syomai. Dagingnya, daging
kucing!"
"Ah, masa!"
Maka berhamburanlah keluar dari mulutnya satu cerita yang
amatlah fantastisnya. Konon, gara-gara daging sapi makin
melangit harganya, pengurus PSI (Partai Syomai Indonesia)
buru-buru mengadakan rapim terbatas di markas besarnya (yang
konon ongkos pengelolaannya disubsidi pemerintah) di bilangan
Tebet Utara.
Dalam rapim itu -- sesudah mendengarkan pengarahan dan perkiraan
keadaan dari ketua dan para sesepuh partai -- diputuskanlah
untuk mengganti daging sapi dengan daging kucing. Daging kucing
masih sangat murah di pasaran, masih akan memungkinkan marge
keuntungan yang lumayan dalam kalkulasi, dan yang penting nilai
gizi daging kucing ternyata adalah yang paling tinggi dari semua
daging. Maka sejak itu syomai di seluruh ibukota -- dan di mana
saja ada jajanan ini -- berubah menjadi syomai kucing ....
"Aah, anak-kecil sudah suka 'ngarang cerita'! Itu desas-desus,
bukan fakta," seruku geram bercampur kecewa. (Sebab syomai sudah
melembaga juga di lidah dan perutku).
"Lho, tanya deh sama mbak kalau nggak percaya!"
Maka kakak si gendut yang panggilannya "mbak" itu saya panggil.
Mbak ini delapan tahun lebih tua dari si gendut, baru diterima
di salah satu fakultas yang mengajar mistik dan guna-guna. Masuk
barisan oposisi, anti NKK dus anti-penalaran. Masa depannya
mungkin agak suram karena melihat gelagatnya dia akan sulit
diterima dalam masyarakat-akademik-yang-rasional-penuh-penalaran
yang insya Allah akan segera terwujud di ini negeri.
"eh, menurut si Inem dia lihat sendiri kucing-kucing itu
disembelihi di belakang pasar Tebet. Terus dipotong-potong
dagingnya dibagi antara anggota partai syomai itu."
Saya terhenyak kena schok mendengar penjelasan mbak yang
mahasiswi ini. Sudah satu semester jadi mahasiswi kok masih
belum tahu membedakan fakta dan desas-desus.
"Kau tahu, mbak, cah ayu, kalau itu baru desas-desus? Belum
fakta?"
"Dan daging itu sesudah dipotong, dicincang, digelindingi
dikukus. Rasanya sih gurih, tapi hiiih, kucing lho, pak! Kucing
'kan binatang rumah yang kudu dilindungi. Gunanya juga banyak.
Kalau habis nanti bisa merusak ekoloji. Tikus-tikus merajalela.
Petani-petani susah. Padahal tikus itu . . . " Saya schok lagi.
"Stop, dulu, mbak. Ngomongmu kok jadi molor nggak keruan. Kau
tahu, cah ayu? Omonganmu itu desas-desus kau tingkatkan jadi
fakta kau ruwetkan dengan opini! Mahasiswi lho, kau itu. Mbok
yang bisa nalar begitu to!"
"Lho, bapak jadi pro Daoed Joesoef?"
"Tentu saja, schaat. 'Kan bapak dosen anggota Korpri. Mesti
setuju dong! Ayo, panggil Inem sekarang!"
Inem datang. Sayang dia tidak secantik Doris dus Inem ini adalah
pelayan yang sama sekali tidak sexy.
"Betul kamu lihat dengan mata kepala sendiri kucing-kucing itu
disembelihi buat syomai?"
"Boten ! Tapi saya dengar dari si Yanem yang dengar dari si Suti
yang .... "
"Stop! Sana cuci piring sana!"
Waduh, rumahku sudah tidak terkendalikan lagi. Sudah kena polusi
pikiran yang ruwet. Desas-desus, fakta, opini sas-sus lagi,
sulapan fakta lagi, opini ditambah opini ditambah sas-sus lagi.
Rawan betul rumah ini situasinya.
Sebagai dosen yang juga sedang laku mengajar metode penelitian
secara grounded theory saya merasa terpanggil untuk membuka
penataran P3GM, Penataran Penelitian Penyimakan Grounded
Masyarakat. Tanpa kecuali semua anggota rumah tangga UK ini
harus ikut. Yang tidak mau . . . out!! Sebab ini prinsipiiil!
Kalau mereka sudah lulus P3GM ini mereka, semua mereka itu, akan
otomatis bisa menghayati masyarakat dan gejalanya lebih obyektif
lagi. Tidak ngaco seperti sekarang!
Maka perintah pun turun. Satu, penataran dibuka minggu depan.
Dua, syomai dipanggil lagi.
***
Sore berikutnya. Penjaja syomai baru saja meninggalkan rumah. Di
sekeliling meja. Saya, gendut dan mbak menghadapi piring syomai.
Saya mulai menggigit. Mbak dan gendut diam menatap piring. Saya
menggigit. Mereka masih diam. Saya menggigit. Lho, kok rasanya
agak anyir.
"Ayoh, makan. Sudah dibeli, kok!"
Mereka geleng kepala. Ibunya anak-anak datang dari kantor.
"Ini bagaimana! Rumah ini sudah jadi korban fakta-dan-opini.
Masa syomai begini tidak dimakan lagi!" seruku memrotes."
Ibu ini -- seperti ibu-ibu di seluruh dunia -- adalah seorang
oportunis yang kreatif bila menyangkut anggaran rumah tangga.
"Kebetulan. Menghemat pengeluaran toh!"
Saya menggeleng kepala. Saya menggigit. Lho. kok anyir. Ngeoong.
Seekor kucing melompat lewat jendela. Hitam lagi ....
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini