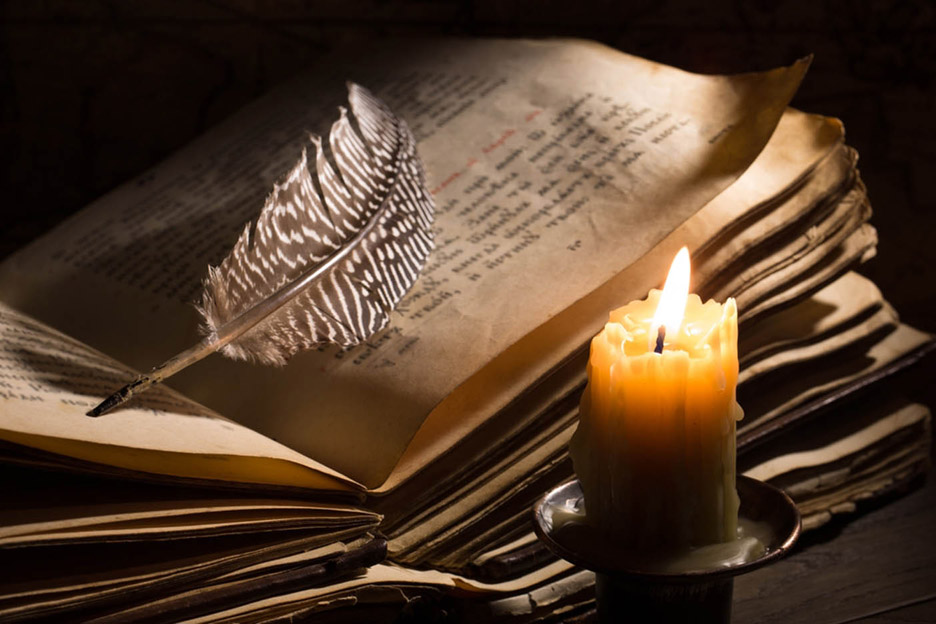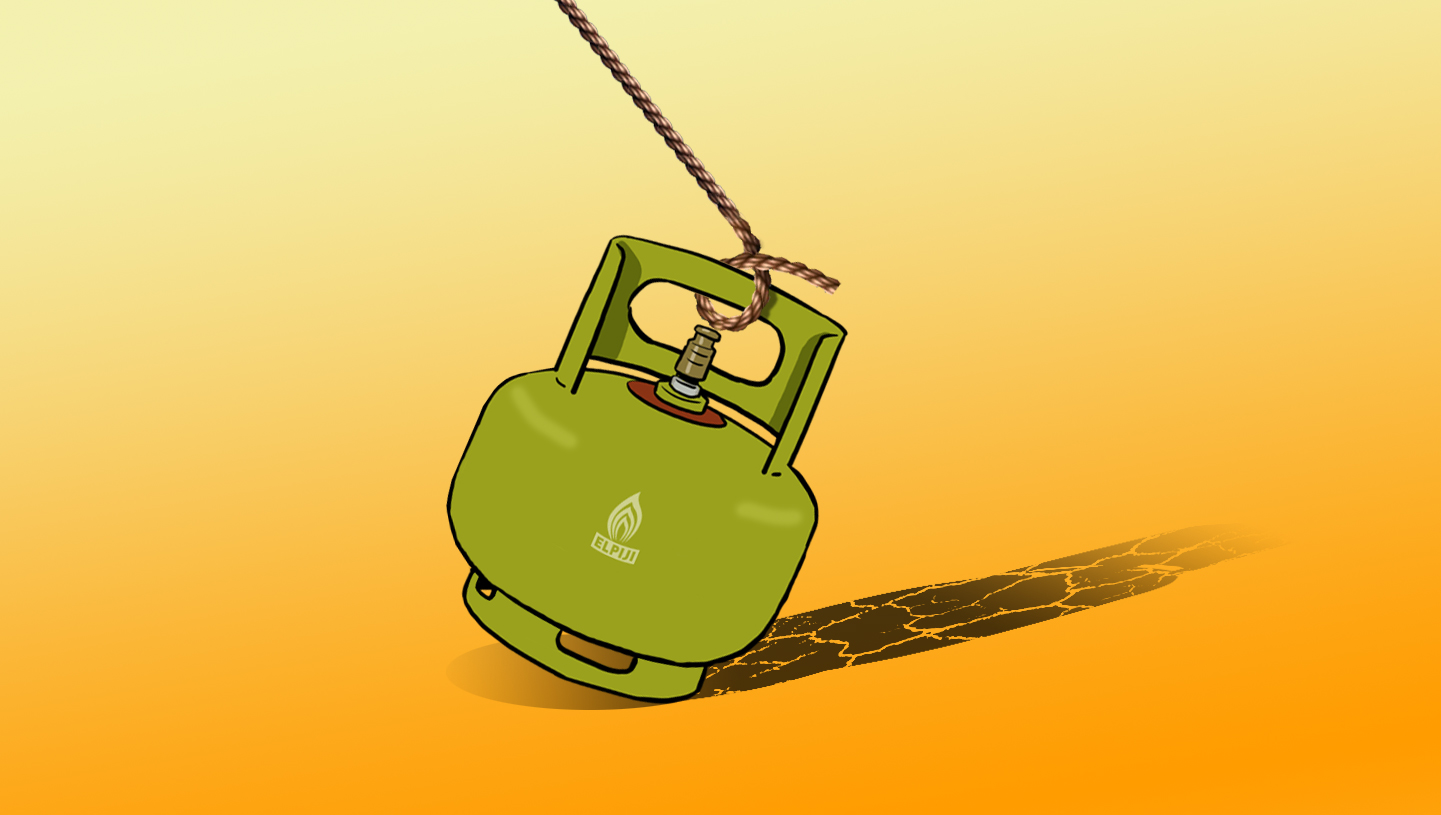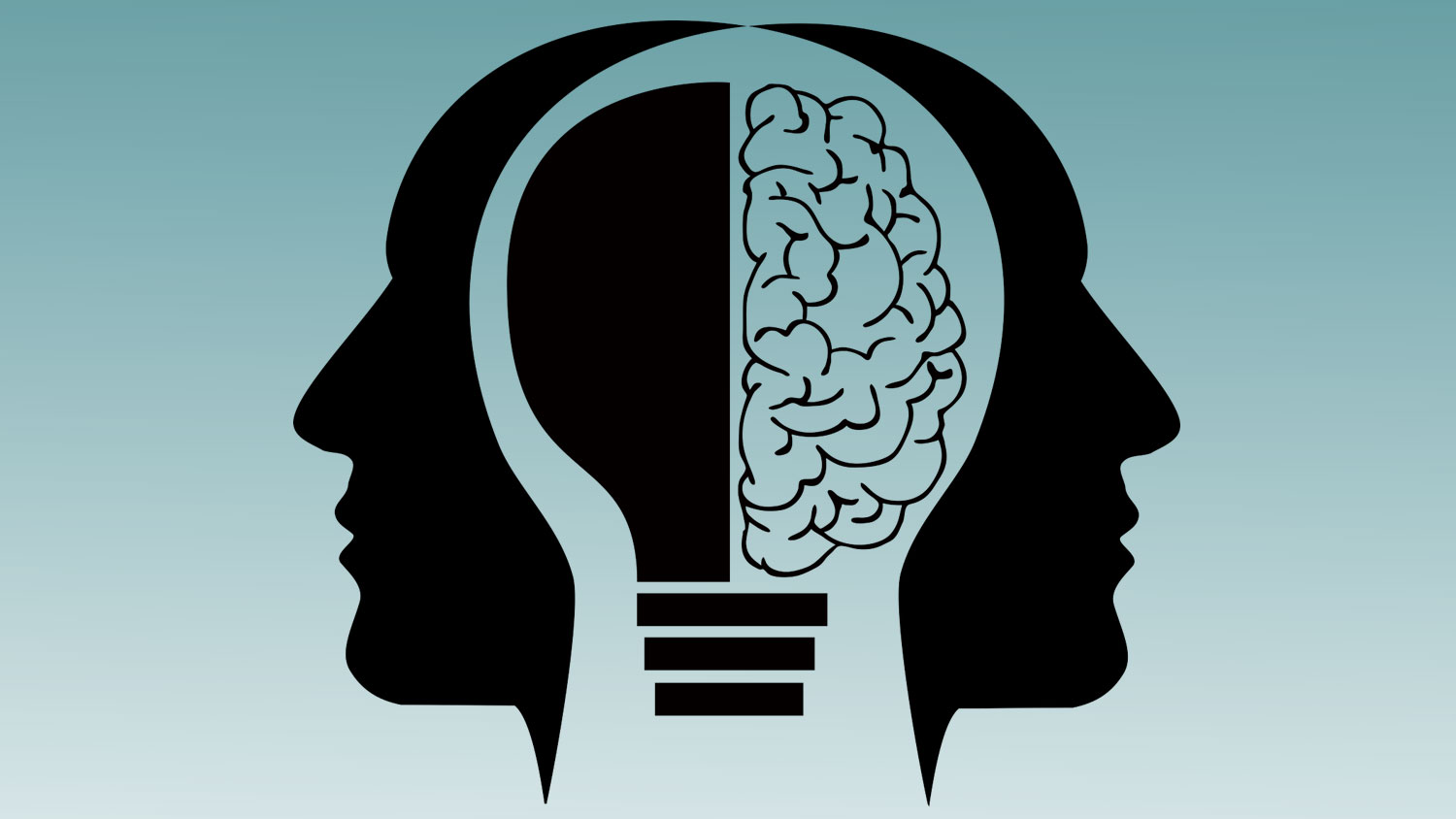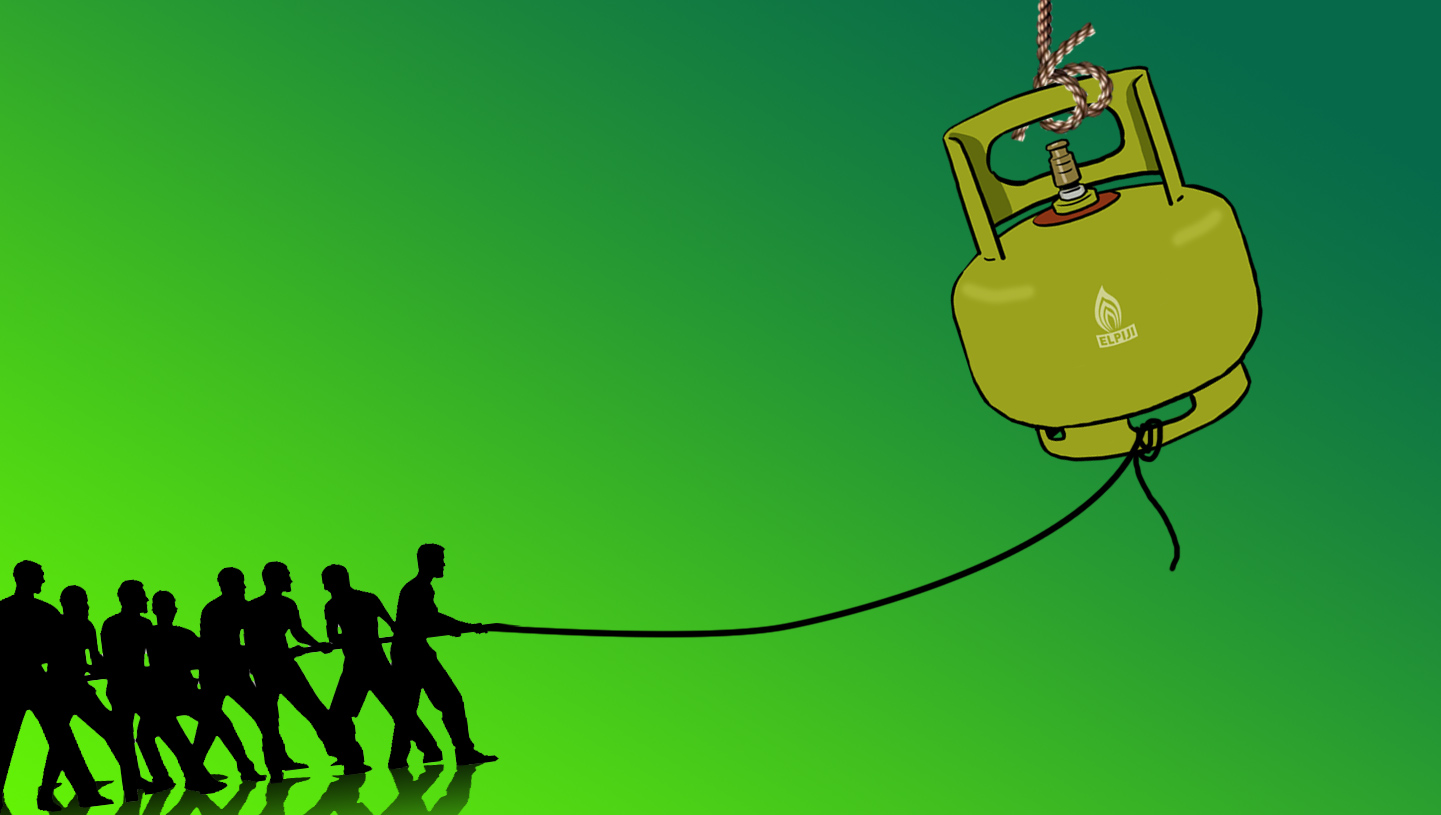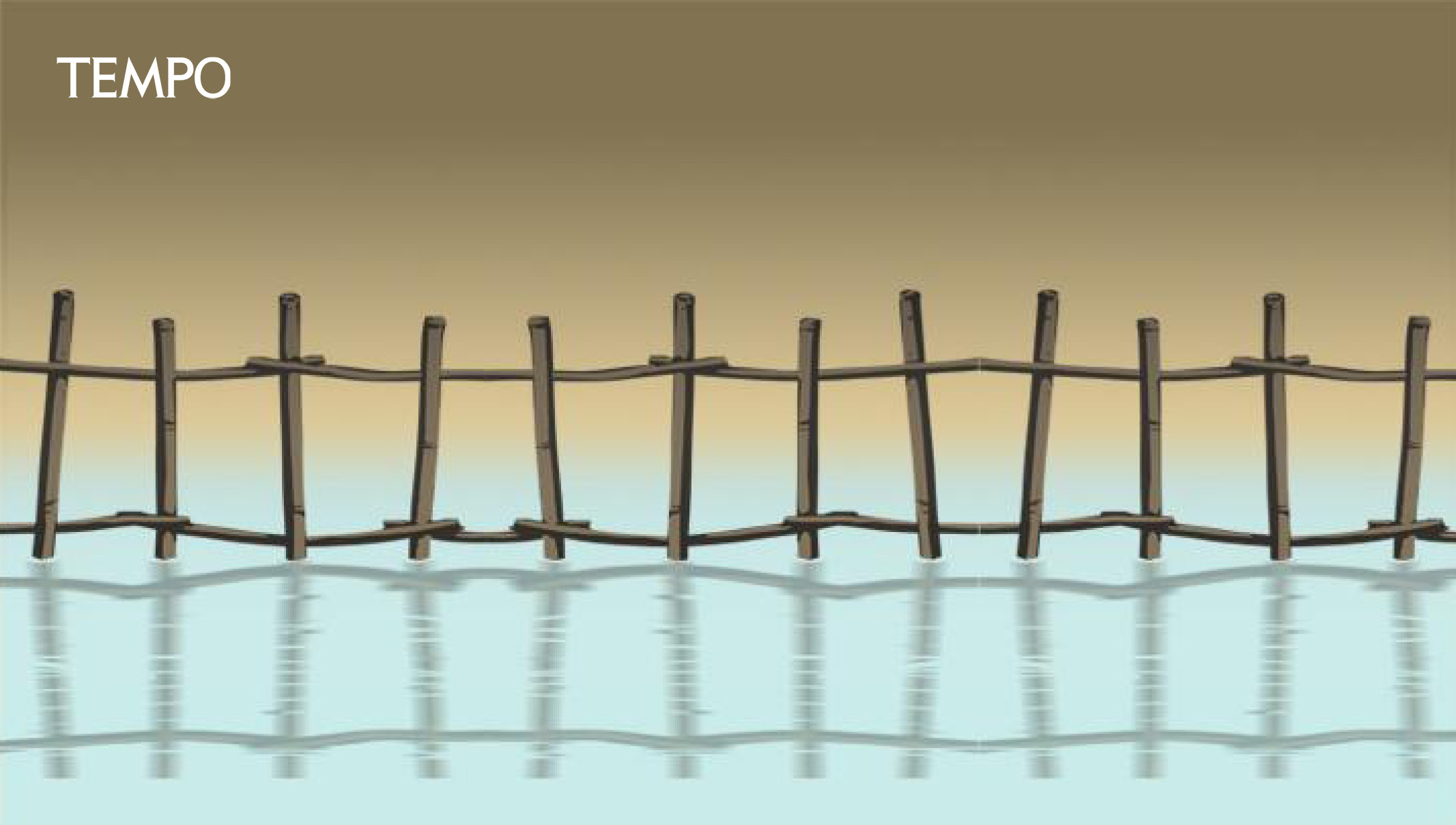Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ringkasan Berita
Indonesia berkomitmen turunkan emisi gas rumah kaca.
Upaya itu belum optimal karena berbagai alasan.
Pajak karbon dapat menjadi alternatif dana penanganan iklim.
Wiko Saputra
Peneliti Kebijakan Publik
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kenaikan suhu permukaan bumi itu nyata. Hal tersebut sudah disampaikan oleh Panel Antar-Pemerintah untuk Perubahan Iklim (IPCC) pada 2018 yang mengatakan bahwa bumi akan mengalami kenaikan suhu global melewati ambang batas minimum yang ditetapkan pada 2030, yakni 1,5 derajat Celsius. Pajak karbon dapat menjadi alternatif dana untuk memitigasinya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Laporan itu menjadi kabar buruk bagi Indonesia. Dampak perubahan iklim bagi negara tropis seperti Indonesia sangat besar. Terumbu karang akan banyak yang punah, krisis pangan akan terjadi, bencana alam akibat perubahan iklim semakin tinggi intensitasnya, dan ancaman terhadap kesehatan manusia meningkat.
Waktu menuju 2030 semakin sempit. Indonesia dihadapkan pada mitigasi perubahan iklim yang semakin ketat. Sebagai negara yang berpotensi menjaga kenaikan suhu bumi, Indonesia juga menjadi penyumbang emisi terbesar di luar negara maju. Kontribusinya mencapai 3,5-4 persen terhadap total emisi dunia. Karena itu, peran serta Indonesia dalam agenda global terhadap perubahan iklim menjadi penting.
Pemerintah sudah memiliki komitmen terhadap isu perubahan iklim. Pada 2016, Indonesia meratifikasi Kesepakatan Paris ke dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim. Pada saat bersamaan, pemerintah mengajukan komitmen penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen dengan upaya sendiri dan 41 persen dengan bantuan pendanaan internasional.
Meski demikian, pemerintah masih belum optimal dalam melaksanakan agenda kebijakan tersebut. Faktanya, penurunan emisi gas rumah kaca masih rendah. Sektor kehutanan menjadi penyumbang utamanya, yakni sebesar 48,5 persen, diikuti sektor transportasi sebesar 33,9 persen dan pertanian 8,2 persen.
Alih fungsi hutan untuk pertambangan dan perkebunan sawit sangat tinggi. Datanya bisa dilihat dari rata-rata laju deforestasi pada satu dekade terakhir yang masih sebesar 1,47 juta hektare per tahun (FWI, 2019). Penggunaan energi fosil yang tak ramah lingkungan masih sangat besar. Pengembangan food estate pun berpotensi meningkatkan emisi gas rumah kaca.
Dalam pendekatan ekonomi, sulit untuk menghentikan aktivitas penyumbang emisi tersebut karena perekonomian Indonesia sangat tergantung sektor-sektor ini. Yang perlu dilakukan segera adalah menghambat laju pertumbuhannya dan melakukan loncatan besar pada sektor-sektor yang mampu mengurangi emisi, seperti pengembangan energi terbarukan.
Salah satu caranya adalah menerapkan pajak karbon. Pajak karbon merupakan instrumen pajak yang dikenakan kepada pengguna bahan bakar fosil yang menghasilkan emisi. Pajak ini telah diterapkan di beberapa negara, seperti Singapura, Jepang, Perancis, Cile, Spanyol, dan Kolombia. Di Indonesia, agenda pajak karbon ini sudah masuk rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Tentu, masuknya nomenklatur pajak karbon dalam rancangan itu merupakan loncatan untuk menekan peningkatan emisi, terutama di sektor energi. Pajak karbon tidak sekadar dipandang sebagai sumber penerimaan negara karena cakupannya sangat luas untuk mereformasi kebijakan perubahan iklim.
Pajak karbon akan mampu mendukung upaya pemerintah untuk mengendalikan emisi gas rumah kaca serta mendorong investasi ramah lingkungan dan pertumbuhan yang berkualitas/berkelanjutan. Selain itu, pajak karbon akan mampu menutupi celah pembiayaan perubahan iklim di negeri ini.
Saat ini, kebutuhan pembiayaan perubahan iklim mencapai Rp 266,2 triliun per tahun. Sedangkan kesanggupan pemerintah baru sebesar Rp 86,7 triliun per tahun atau sekitar 32,5 persen. Ada defisit pembiayaan yang perlu ditutupi. Pajak karbon merupakan salah satu cara untuk menutupi defisit tersebut.
Meski demikian, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam merumuskan pajak karbon tersebut. Pertama, menentukan subyek pajaknya. Agar memenuhi aspek keadilan, subyek pajak karbon harus mencakup semua pengguna bahan bakar fosil yang menghasilkan emisi, baik orang maupun badan usaha. Pemerintah juga perlu mengkaji secara komprehensif sektor-sektor yang menjadi subyek pajak karbon. Saya mengusulkan beberapa sektor yang menjadi prioritas, yaitu transportasi, pembangkit listrik, industri, dan bangunan.
Kedua, untuk obyek pajaknya, sebaiknya pajak ini diberlakukan untuk semua bahan bakar fosil yang menghasilkan emisi. Ketiga, penentuan tarif perlu ditimbang dengan matang agar aspek kelayakan kebijakan ini sebagai disinsentif bagi usaha penghasil emisi bisa diwujudkan. Tapi penentuan tarif ini juga harus didasarkan pada kesanggupan bayar bagi subyek pajaknya. Karena itu, perlu kajian mendalam mengenai hal ini. Mekanisme perhitungan konversi emisi juga perlu dijelaskan agar masyarakat bisa memahami perhitungannya.
Keempat, penerimaan pajak karbon secara otomatis masuk sebagai komponen penerimaan pajak yang akan digunakan untuk pembiayaan dalam APBN dan APBD. Dalam hal penggunaan, karena pajak karbon termasuk sebagai pajak khusus, sebaiknya penerimaan dari pajak tersebut hanya boleh digunakan untuk pembiayaan program perubahan iklim.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo