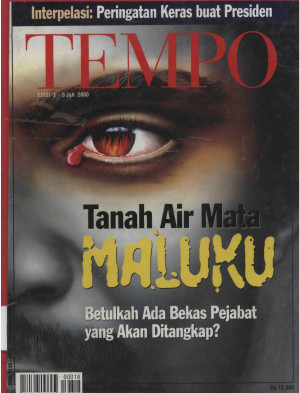Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR (PAH I) menjadwalkan tanggal 18 Agustus 2000 sebagai hari H untuk mengundangkan sejumlah amendemen UUD 45. Kalau jadwal itu ditepati, dan amendemen tersebut tidak mengalami banyak perubahan lagi, dalam tempo satu bulan dari sekarang, negara dan bangsa ini akan memiliki konstitusi yang berbeda. Masalahnya, siapkah kita?
Pertanyaan ini muncul karena tidak sedikit yang mempersoalkan, apakah perubahan yang dimanifestasikan dalam berbagai amendemen sudah mencerminkan aspirasi dan amanat hati nurani rakyat. Menyempurnakan UUD 45, ya, oke-oke saja, tapi perubahan yang bagaimana, itulah soalnya. Lalu, wewenang untuk mengubah, apakah sepenuhnya tugas badan legislatif DPR/MPR? Benar, ada landasan hukum yang digunakan untuk mengukuhkan wewenang tersebut, yakni Tap IX/MPR/1999. Tapi, kalau Tap MPR ini menggariskan bahwa tugas badan legislatif itu final, nah, Tap itu sendiri patut dipersoalkan.
Yang ingin ditekankan di sini bukanlah wewenang PAH I itu, tapi prosedur yang ditempuh setelah amendemen disusun dan sebelum amendemen tersebut diundangkan. Dipertanyakan, mengapa hasil kerja PAH I tidak harus ditelaah dulu—oleh para ahli hukum tata negara, misalnya—sebelum diundangkan. Lalu, apakah mengundangkan secara spontan, setelah mendapat suara terbanyak MPR, memang sesuai dengan prosedur? Jika prosedurnya begitu, salahkah kalau kemudian ada yang menilai bahwa hasil kerja PAH I bukan amendemen, tapi dekrit?
Kecerewetan semacam ini tentulah menjengkelkan sekali. Tapi, suka atau tidak suka, keunggulan demokrasi memang tak terlepas dari kecerewetan, ketelitian, dan kebertele-telean. Soalnya, yang diperlukan bukan sekadar amendemen atau sekadar perubahan, tapi amendemen yang memungkinkan UUD 45 menjadi tatanan perundang-undangan yang sempurna bagi sebuah bangsa yang mencita-citakan demokrasi nan sejati, kedaulatan hukum, dan kesinambungan ekonomi.
Singkat kata, sebelum UUD 45 diamendemen, perlu ada peraturan yang khusus menentukan bagaimana mestinya perubahan konstitusi dilakukan di republik ini. Apakah perubahan itu cukup dilakukan MPR, atau dibuat oleh tim ahli yang kemudian disahkan MPR, atau kerja sama kedua belah pihak, atau perlu juga referendum. Prosedur dan mekanismenya harus jelas, perangkat tata acaranya harus disiapkan lebih dulu. Bukan rahasia lagi, berbagai produk hukum di negeri ini salah implementasi atau tak bisa diimplementasikan gara-gara prosedur pelaksanaannya tak jelas. Akibatnya bisa fatal, apalagi kalau hal itu terjadi pada sebuah UUD.
Adanya tuntutan dari kalangan penegak hukum, agar sebuah Komisi Negaralah yang ditugasi menyusun draf konstitusi baru, tentu tak terlepas dari risiko yang mungkin fatal itu. Lalu, keberatan sejumlah purnawirawan TNI dan Polri terhadap prosedur pembuatan amendemen yang cenderung memudahkan—tanpa kajian mendalam—sungguh layak dipertimbangkan. Seperti juga MPR, masyarakat tidak ingin menyakralkan UUD 45. Bagaimanapun, kajian mendalam, keterbukan, dan kecerewetan tetap diperlukan, semata-mata demi menyukseskan desakralisasi itu sendiri.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini