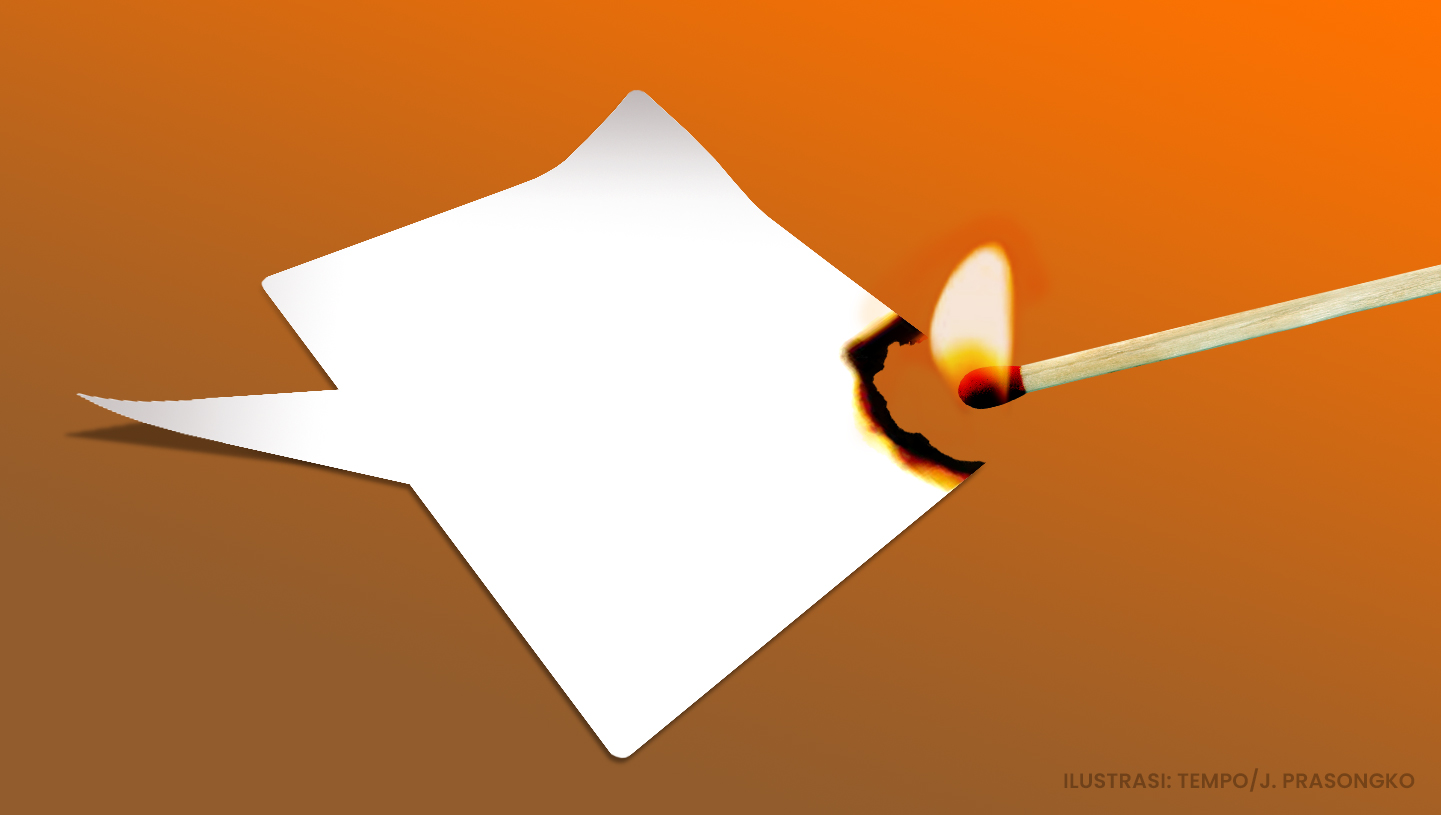Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Azis Khan
Peminat isu lingkungan hidup dan pernah bekerja pada Departemen Kehutanan
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengakhiri kerja sama dengan Yayasan WWF Indonesia (WWF) melalui Keputusan Menteri Lingkungan pada 10 Januari 2020. Kementerian memandang perlu untuk mengakhiri kerja sama yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor 188/DJ-VI/Binprog/1998 dan Nomor CR/026/III/1998 tanggal 13 Maret 1988 tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Landasannya adalah durasi perjanjian itu berakhir pada 5 Oktober 2019, juga hasil evaluasi Kementerian atas pelaksanaan kerja sama tersebut. Namun landasan ini dan berbagai informasi yang berkembang belum cukup menjawab perhatian banyak pihak. Apakah benar harus diakhiri, mengingat fakta bahwa kerja sama kedua lembaga sudah berlangsung relatif lama? Adakah alasan substantif selain hasil evaluasi? Seperti apa proses evaluasi itu dilakukan? Apa gerangan masalah di luar dua hal ini, yang justru menjadi akar masalah?
Perjanjian itu dibuat antara Departemen Kehutanan (kini Kementerian) cq Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam dan WWF dalam Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Kegiatan WWF dalam kerja sama ini mencakup kegiatan-kegiatan di dalam lingkup unit kerja dan bidang tugas Kementerian. Evaluasi atas pelaksanaan kerja-kerja inilah yang membuat Kementerian mengakhiri kerja sama tersebut.
Namun tidak ada informasi bagaimana proses, mekanisme, prosedur, tata waktu, dan tata laksana evaluasi dilakukan atau setidaknya prinsip-prinsip yang sepadan dengan dan menjelaskan hal itu semua. Misalnya, apakah proses evaluasi membuka cukup ruang dialog sehingga kedua pihak sama-sama memiliki kesempatan untuk berkontestasi dan bernegosiasi sehingga dicapai kesepakatan, termasuk untuk tidak sepakat? Tidak ada informasi mengenai dokumen hasil evaluasi Kementerian yang dirujuk dalam keputusan menteri tersebut. Tidak ada informasi apakah evaluasi itu dilakukan oleh pihak ketiga yang independen, layaknya due diligence atas keseluruhan kinerja perjanjian.
WWF melihat keputusan ini sepihak dan menyayangkannya karena tidak ada ruang komunikasi dan konsultasi langsung untuk mufakat sebagaimana tercantum dalam perjanjian. Hal ini dipandang telah merugikan reputasi WWF, tapi mereka tetap menghormati keputusan tersebut dan akan menindaklanjutinya.
Berbagai argumen dari kedua pihak menunjukkan bahwa keduanya belum optimal dalam menegakkan prinsip tata kelola. Ini tampak setidaknya dari argumen yang resiprokal, saling menganggap masing-masing lawannya sebagai "sepihak" untuk isu berlainan. Kementerian menilai WWF telah melakukan klaim sepihak yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan pada tingkat yang sangat serius. WWF menyayangkan keputusan menteri itu "sepihak" tanpa menyediakan ruang komunikasi dan konsultasi.
Dari perspektif tata kelola, klaim sepihak perlu ditunjang oleh data dan informasi mengenai proses dan substansi, selain ada-tidaknya ruang dialog. Maka, hasil evaluasi menjadi penting untuk ditelusuri, terutama yang berkaitan dengan mekanisme dan prosedur pelaporan seluruh kegiatan, layaknya manajemen sebuah kerja sama. Absennya semua hal ini mengisyaratkan ada persoalan kinerja tata kelola perjanjian tersebut.
Dari pola dan kualitas relasi kedua pihak, tampak pola yang terjadi dalam perjanjian tidak ubahnya patron-klien. Kementerian bertindak lebih sebagai patron, terutama karena unsur kekuasaan dan kewenangannya. Kesan yang kemudian menyeruak di ruang publik adalah bahwa pola relasi itu kental dengan ciri patronase. Terlebih saat WWF menyayangkan putusan Kementerian sebagai sepihak dan tidak menyiapkan ruang dialog. Secara fungsional, pola relasi sejatinya dapat dikonstruksi untuk bisa lebih saling membutuhkan dan menguntungkan.
Dengan jumlah kawasan konservasi sebanyak 552 unit, luas total 27,14 juta hektare, yang 54 unit di antaranya merupakan taman nasional dengan luas hampir 60 persen total kawasan konservasi (KSDAE, 2017), kerja sama dengan banyak pihak menjadi keniscayaan. Terlebih saat ditakar oleh kapasitas dan kapabilitas riil Kementerian dalam mengelola kawasan konservasi seluas itu, baik dari aspek anggaran, sarana-prasarana, infrastruktur, maupun personel lapangan.
Alokasi anggaran konservasi ini sangat minimal. Kajian NRM (1999) menunjukkan anggaran itu hanya sekitar Rp 6.000-an per hektare. Pada 2014, menurut Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung Kementerian saat itu, anggarannya hanya Rp 1,4 triliun untuk total 27,14 juta hektare atau rata-rata Rp 51 ribu per hektare. Menurut sang direktur, diperlukan dana sekurang-kurangnya Rp 300 ribu per hektare untuk konservasi.
Jadi, terlalu mahal bagi kedua pihak untuk menghentikan kerja sama, apalagi tanpa alasan yang masuk nalar publik. Kebiasaan kerja sama ada di kedua pihak. Kementerian selama ini bekerja sama dengan banyak pihak baik dalam kerangka penguatan fungsi maupun pembangunan strategis. WWF bersikap senantiasa siap bekerja sama dengan pihak mana pun. Artinya, pintu menuju rekonsiliasi terbuka lebar. Dengan demikian, persoalan keputusan menteri ini perlu diarahkan untuk mewujudkan upaya rekonsiliasi dan melanjutkan kerja sama. Apa pun hasilnya nanti, kedua pihak memiliki pekerjaan rumah penting: berkewajiban mendongkrak kinerja tata kelola masing-masing dengan bungkusan dialektika yang jauh lebih berkualitas.