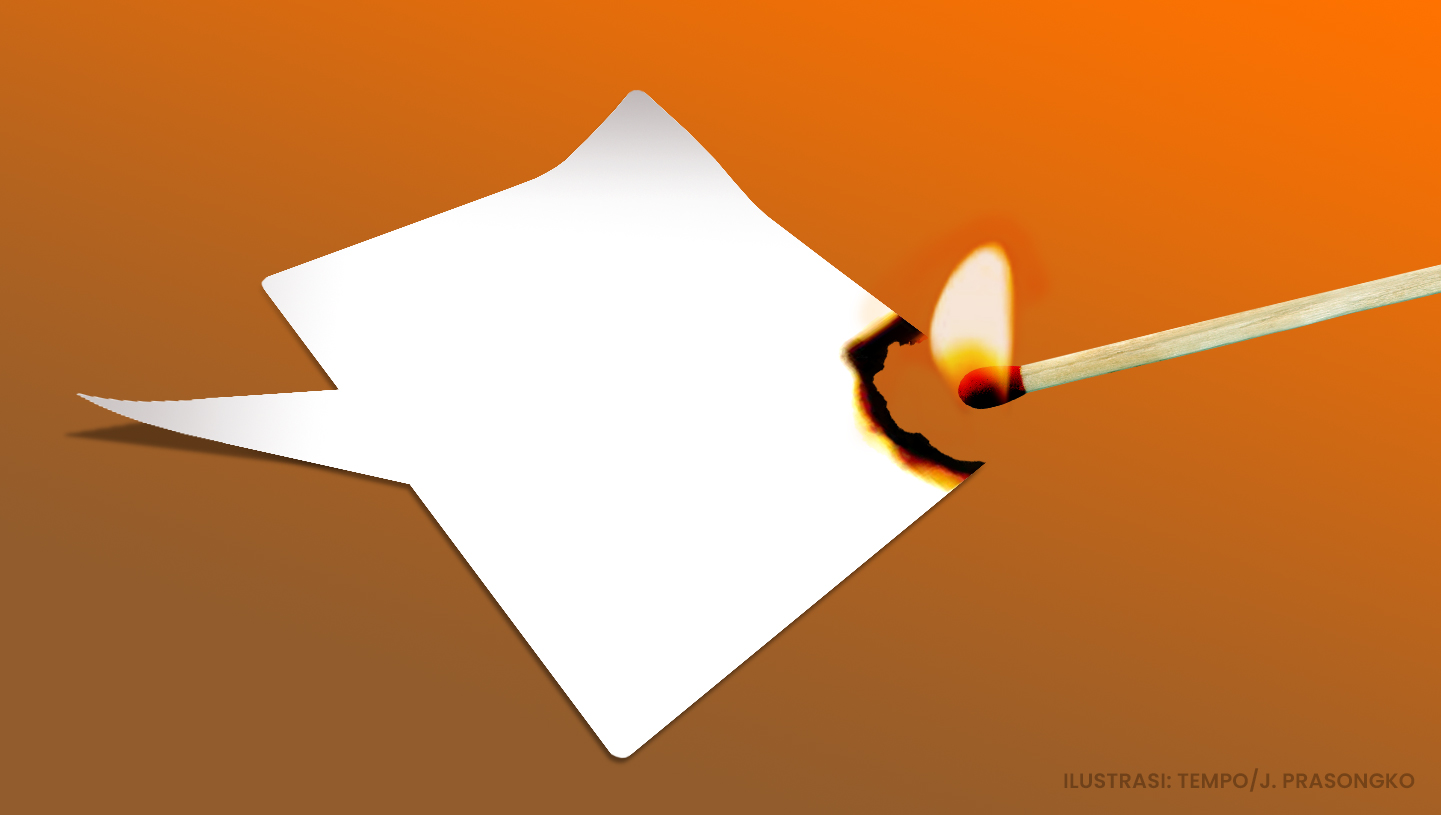Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sebagai akademisi saya mesti hati-hati membuat penilaian atau evaluasi terhadap jalannya pemerintahan saat ini. Sebab memerlukan data dan argumen yang kuat untuk menilai sebuah rezim pemerintahan, apalagi rezim ini tergolong rezim populis, terkesan mengabaikan rasionalitas dan memberi ruang dominan bagi subyektifitas egoistik. Fenomena rezim populisme ini juga terjadi di sejumlah negara.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Evaluasi tahunan itu wajar dilakukan, sebab waktu satu tahun suatu pemerintahan untuk dievaluasi adalah waktu yang cukup untuk melihat apa yang telah dilakukannya. Sebab pemerintah telah menggunakan uang APBN atau uang rakyat lebih dari dua ribu triliun.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Izinkan saya menggunakan perspektif kritis dalam menilai pemerintahan ini. Dalam kajian akademik perspektif kritis memiliki posisi penting sejak awal hingga akhir abad 20 di Eropa dan dunia sampai saat ini. Evaluasi memang secara akademik mensyaratkan proses kritik di dalamnya.
Dalam buku Signaling and Monitoring in Public Sector Accounting yang ditulis Evans & Patton (1987) disebutkan bahwa cara kritis adalah hal utama dalam melakukan proses evaluasi sebuah program. Evaluation is a process that critically examines a program. It involves collecting and analyzing information about a program’s activities, characteristics, and outcomes (Evans & Patton,1987). Demikian Evans & Patton menjelaskan.
Selain proses yang kritis evaluasi juga memuat indikator data aktivitas apa yang dilakukan, karakteristik performanya seperti apa dan hasilnya. Indikator -indikator ini bisa menjadi pijakan penting untuk melakukan evaluasi suatu rezim yang seharusnya memang berkuasa untuk melayani kepentingan publik, kepentingan warga negara.
Jika dibuat satu kesimpulan umum berdasarkan data aktivitas rezim, performa dan hasil yang ditunjukkan pemerintah maka satu tahun pemerintahan ini lebih terlihat sebagai pertunjukan pengingkaran amanat publik di tengah rakyat sedang menderita secara ekonomi.
Tentu pembaca, publik maupun pihak penguasa bertanya, dari mana kesimpulan tersebut muncul?
Bukti
Banyak bukti untuk menunjukkan kesimpulan tersebut. Saya mulai dari soal kasus korupsi di BUMN asuransi, PT. Jiwasraya yang terkuak pada Januari 2020. Uang negara Rp 16,8 triliun lebih diduga menguap (BPK RI, 2020).
Tetapi pemerintah dengan DPR melalui APBN justru memberikan suntikan modal sebesar Rp 22 triliun, yang memberi kesan untuk menambal akibat dari kasus tersebut. Uang negara ditilap16,8 triliun lebih lalu negara menyuntikkan dana 22 triliun ke perusahaan asuransi pelat merak tersebut. Secara logika sederhana ini aneh. Langkah tak bijak di tengah rakyat sedang menderita akibat pandemi Covid-19.
Soal suntikan dana ini, pemerintah berargumen uang itu digunakan untuk asuransi pelat merah baru yang bernama Indonesia Financial Group (IFG) Life dengan diikuti pemindahan atau pengalihan seluruh polis Jiwasraya menjadi polis IFG Life.
Mestinya Pemerintah membantu penegak hukum mengusut tuntas ke mana aliran uang skandal tersebut. Melalui Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan pihak terkait lainnya bisa melacak atau tracing aliran dana dalam megaskandal korupsi di Asuransi Jiwasraya ini. Ke mana saja uang puluhan triliun tersebut dialirkan di saat rakyat sedang menderita.
Presiden Jokowi pernah mengatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah memasuki episode kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) , tetapi faktanya pemerintah tidak melakukan cara-cara yang luar biasa untuk memberantas korupsi.
Manakala rakyat mengkritik kebijakan presiden yang terkesan tidak melakukan tindakan luar biasa dalam pemberantasan korupsi, aparat justru berbuat semena-mena pada peserta unjuk rasa. Tindakan represif terjadi saat mahasiswa demonstrasi menolak pelemahan KPK dengan tagar #reformasidikorupsi meluas di seluruh Indonesia.
Kemudian semua tokoh bangsa pada waktu itu datang ke Istana untuk meminta Presiden keluarkan Perpu (Peraturan pemerintah pengganti undang-undang) tetapi Presiden tetap ngotot tidak mau mendengar aspirasi itu. Hingga kini posisi KPK semakin lemah. Publik terkesan semakin diabaikan. Saat turun ke jalan menyuarakan aspirasi, rakyat disambut tindakan sewenang-wenang aparat.
Rakyat ingin korupsi diberantas sampai ke akar-akarnya dengan cara yang luar biasa karena sangat merugikan rakyat banyak. Tetapi aspirasi rakyat ini tidak didengar. Jika itu terus terjadi maka demokrasi tentu makin memburuk.
Bahkan penembakan terhadap mahasiswa terjadi di Universitas Halu Oleo Kendari hingga menewaskan dua mahasiswa, presiden terkesan tidak melakukan tindakan yang luar biasa. Penembakan mahasiswa ini pelanggaran HAM baru. Kasus pelanggaran HAM yang lama belum satupun ditangani sudah muncul kasus pelanggaran HAM baru.
Dari sisi demokrasi, satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin juga memiliki rapor merah. Presiden pernah mengatakan rindu mendapat masukkan dari publik. Tetapi saat rakyat menyuarakan kepentingannya lewat demonstrasi, ia malah terkesan tidak mau mendengarkan. Rakyat menuntut keadilan tetapi kemudian justru direpresi oleh aparat dengan gas airmata dan tembakan senjata.
Para aktivis pro-demokrasi ditangkap dipenjara seperti diantaranya terjadi penangkapan terhadap Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, Anton Permana dll. serta percobaan penangkapan terhadap Ahmad Yani. Penangkapan juga terjadi pada mahasiswa dan pelajar saat demonstrasi. Rakyat justru sekarang takut berpendapat.
Sebuah lembaga internasional yang kredibel The Economist Intellegence Unit pada awal tahun 2020 merilis indeks demokrasi di dunia dan menyebut angka kebebasan sipil di Indonesia mendapat angka 5,59 dari skala 10 atau rapornya merah, saat ini kualitas demokrasi kita semakin terpuruk, rapornya bisa sangat merah.
The Economist baru-baru ini di media sosialnya menyebut secara keras tentang kondisi Indonesia. Indonesia is lurching back into authoritarianism under Joko Widodo (The Economist, 22/10/2020). Indonesia kembali ke otoriterianisme di bawah kekuasaan Joko Widodo saat ini. Demikian The Economist menilai secara keras rezim saat ini.
Dari sisi kualitas demokrasi juga memburuk karena berkembangnya politik dinasti, bahkan kini lebih parah karena dicontohkan oleh Presiden sendiri. Presiden merestui anaknya dan menantunya untuk menjadi calon wali kota. Anak dan menantu menjadi calon wali kota di saat ayahnya sedang berkuasa menjadi Presiden.
Dalam etik politik yang berkebudayaan itu sesuatu yang tabu, tidak elok. Presiden mempertontonkan dirinya di hadapan rakyat banyak. Lebih dari itu tentu politik dinasti merusak kualitas demokrasi, merusak kaderisasi di tubuh partai politik.
Demokrasi semakin memburuk ketika rakyat menolak UU Omnibuslaw Ciptaker yang menguntungkan oligarki ekonomi. Dimana Presiden? Presiden justru makin cuek. Tinggalkan rakyat.
Padahal yang menolak UU Omnibuslaw adalah rakyat banyak. Dari organisasi terbesar seperti NU (Nahdhotul Ulama), Muhammadiyah, organisasi buruh, mahasiswa, akademisi, aktivis lingkungan, aktivis HAM, lembaga swadaya masyarakat, lembaga bantuan hukum, kelompok oposisi, sampai rakyat banyak secara umum.
Presiden tetap cuek dan tidak mau mengeluarkan Perpu padahal Perpu adalah opsi penting ketika situasi genting menemui jalan buntu. Lagi lagi Presiden cuek dan meninggalkan demonstran yang ditembaki aparat.
Presiden bilang UU Ciptaker Omnibuslaw itu akan menarik investor asing. Presiden pura-pura tidak tau bahwa riset World Economic Forum (2019) menemukan angka tertinggi investor asing tidak mau investasi di Indonesia itu karena tingginya praktek korupsi. Mestinya yang dikuatkan adalah KPK nya. Ini KPK nya dilemahkan. Dunia bisnis butuh kepastian pemberantasan korupsi tetapi justru diberi UU Omnibuslaw yang ditolak rakyat, mementingkan oligarki, merusak lingkungan dan merugikan masa depan buruh dan generasi millenial.
Terlalu banyak data untuk menunjukkan betapa pemerintah dalam satu tahun ini telah mengingkari amanat rakyat. Janji ekonomi membaik tetapi faktanya justru ekonomi memburuk. Bukan hanya karena Covid-19 tetapi lebih dari itu adalah karena tata kelola pemerintahan yang perlu dibenahi. Akibatnya pertumbuhan ekonomi minus 5 % lebih, PHK terus terjadi, pengangguran terus bertambah. Pemerintah egois dan gegabah dalam mengelola negara. Survei terakhir dilakukan oleh media mainstream nasional (10/2020) semakin menunjukkan buruknya tata kelola ekonomi pemerintah, hanya 45,2 persen rakyat yang puas terhadap pemerintah saat ini.