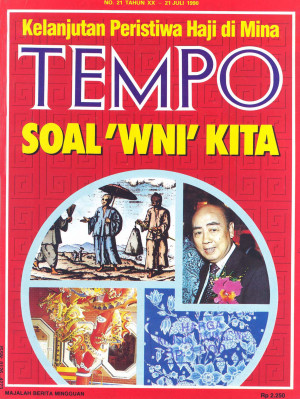PARA pembunuh yang membantai Kakek Sudana di Dusun Wangunparaya -- mereka bukan garong profesional dari pedalaman Cianjur. Para pengroyok yang membinasakan Pak Jaya di hutan bambu di Kampung Gunungkembang -- mereka bukan pemberingas dari Pagelaran. Mereka adalah sejumlah penderita sebuah virus kelam. Virus itu menyusup ke jiwa orang-orang yang tampaknya sehat lahir batin, orang seperti Anda dan saya. Virus itu tak bisa dideteksi oleh para dokter, tapi bisa sewaktu-waktu mengganas. Saya menamakannya virus "santeto-fobia". Orang-orang dusun bertepuk tangan ketika leher Kakek Sudana digorok sampai putus di lapangan sepak bola di malam yang jahanam itu. Mereka telah lama berbisik-bisik menuduh aki berusia 65 tahun itu dukun santet. Serombongan laki-laki dengan gemas memotong kemaluan Jaya dan memasukkan tubuhnya ke sebuah liang, tanpa merasa bersalah, karena bagi mereka Jaya adalah tukang teluh. Bukan lantaran mereka orang "kampung" maka mereka percaya adanya "santet" dan "teluh". Orang kota, yang terpelajar, yang gemar baca koran dan mendengarkan TVRI dan RCTI juga bisa menderita "santeto-fobia". Dan tak cuma di Indonesia. Dan tak cuma di zaman kita. "Santeto-fobia" itulah yang menyebabkan orang Kristen di zaman Nero dilemparkan ke mulut singa, dan disoraki rakyat banyak. Mereka dituduh bersekongkol membuat kebakaran besar ibu kota. "Santeto-fobia" itu pula yang beratus tahun kemudian menyebabkan sejumlah orang Kristen beringas, ketika di abad ke-14 penyakit menular menyerang Eropa: mereka menuduh orang-orang kusta sengaja menyebarkan penyakit itu "atas perintah rahasia orang Yahudi dan orang Islam di Granada". Maka, ratusan manusia pun dipanggang di api pembakaran. "Santeto-fobia" juga yang menyebabkan di awal tahun 1940-an Hitler membunuh orang Yahudi anak beranak dan Stalin di tahun 1930-an mengirim ratusan orang ke pembuangan. "Santeto-fobia" itu pula yang di tahun 1950-an di Amerika Serikat menyebabkan Senator Joe MacCarthy bisa menghabisi karier puluhan orang, termasuk Oppenheimer sang ahli atom dan Charlie Chaplin sang aktor termasyhur. Senator MacCarthy, bersama masyarakat Amerika waktu itu, menuduh di tiap sudut ada teluh, dan itu adalah "komplotan komunis" yang memakai taktik yang sangat, amat, bukan main, duilah lihainya, hingga tak nampak dan tak bisa dibuktikan dan sebab itu tak perlu dibuktikan. Sejarah penuh dengan adegan sedih dan kesewenang-wenangan karena virus "santeto-fobia" itu. Tapi manusia tak kunjung imun. Kita selalu gampang percaya ada rencana-rencana berbahaya nun di seberang rumah kita. Kita selalu punya teori konspirasi atau gampang menelan suatu teori yang "menjelaskan" adanya "komplotan". Ketika oknum-oknum pemerintahan Tsar Rusia ingin mencekik orang Yahudi, polisi rahasia pun menyebarkan Protokol Zion: dokumen palsu tentang "rencana rahasia" bangsa Yahudi untuk menguasai dunia. Pada gilirannya, kini, ketika di Amerika Serikat kian banyak orang bersuara kritis kepada Pemerintah Israel dan bersimpati kepada orang Palestina, sejumlah propagandis Israel pun menulis bahwa ada "strategi" dan "taktik" baru kaum rasialis anti-Semit.... Singkatnya, kita gemar berbisik, "Itu dia, tanda santetnya", setiap kali kita melihat "bukti". Tapi apakah "bukti" itu? Pelbagai kejadian yang kebetulan berdekatan disusun jadi suatu "teori". Pelbagai indikasi dirangkai untuk mengukuhkan sebuah "skenario" yang sudah dibikin sebelumnya. Dengan kata lain, suatu proses berpikir yang jungkir balik: bukan "skenario" itu yang harus dibuktikan, melainkan "skenario" (yang belum tentu sahih) itulah yang justru membuktikan. Kenapa jungkir balik itu bisa terjadi? Apa yang menyebabkan kita rentan terhadap "santeto-fobia"? Para ahli psikologi rasanya belum pernah menelaahnya. Tapi saya punya satu hipotesa: mungkin karena orang belum terbiasa membaca cerita detektif. Dalam sebuah cerita detektif yang klasik, misalnya yang ditulis Agatha Christie, "skenario" yang paling meyakinkan sekali pun ternyata akhirnya bisa dibantah. Di sini proses penalaran yang ulet memang diperlukan: setapak demi setapak, bukan saja tiap bukti diuji, tapi juga hubungan antara insiden yang satu dan yang lain ditelusuri secara rinci dan tekun. Tapi siapa yang betah dengan itu, kecuali Hercule Poirot dan Sherlock Holmes? Kita umumnya tak sabar. Kita umumnya bernafsu menunjuk hidung -- dan kemudian memotong hidung itu dengan golok. Kita umumnya ketakutan bahwa kita tak akan dapat memperoleh satu gambaran, satu cerita yang bisa dengan enak kita telan, atau satu sosok yang bisa dengan gemas kita biang keladikan. Kita perlu cerita setan dan hantu: hantu "Kristen", hantu "Islam", hantu "Zionis", hantu "PSI", hantu "Masyumi", hantu "PKI", hantu "CIA", hantu "Cina", hantu "rasialis", dan entah apa lagi. Kita umumnya ingin berteriak, "Bunuuuh ....!" dan ingin melihat sejumlah tubuh bergelantung dibakar. Kita sering tak tahu ada virus keji di tubuh kita. Goenawan Mohamad
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini