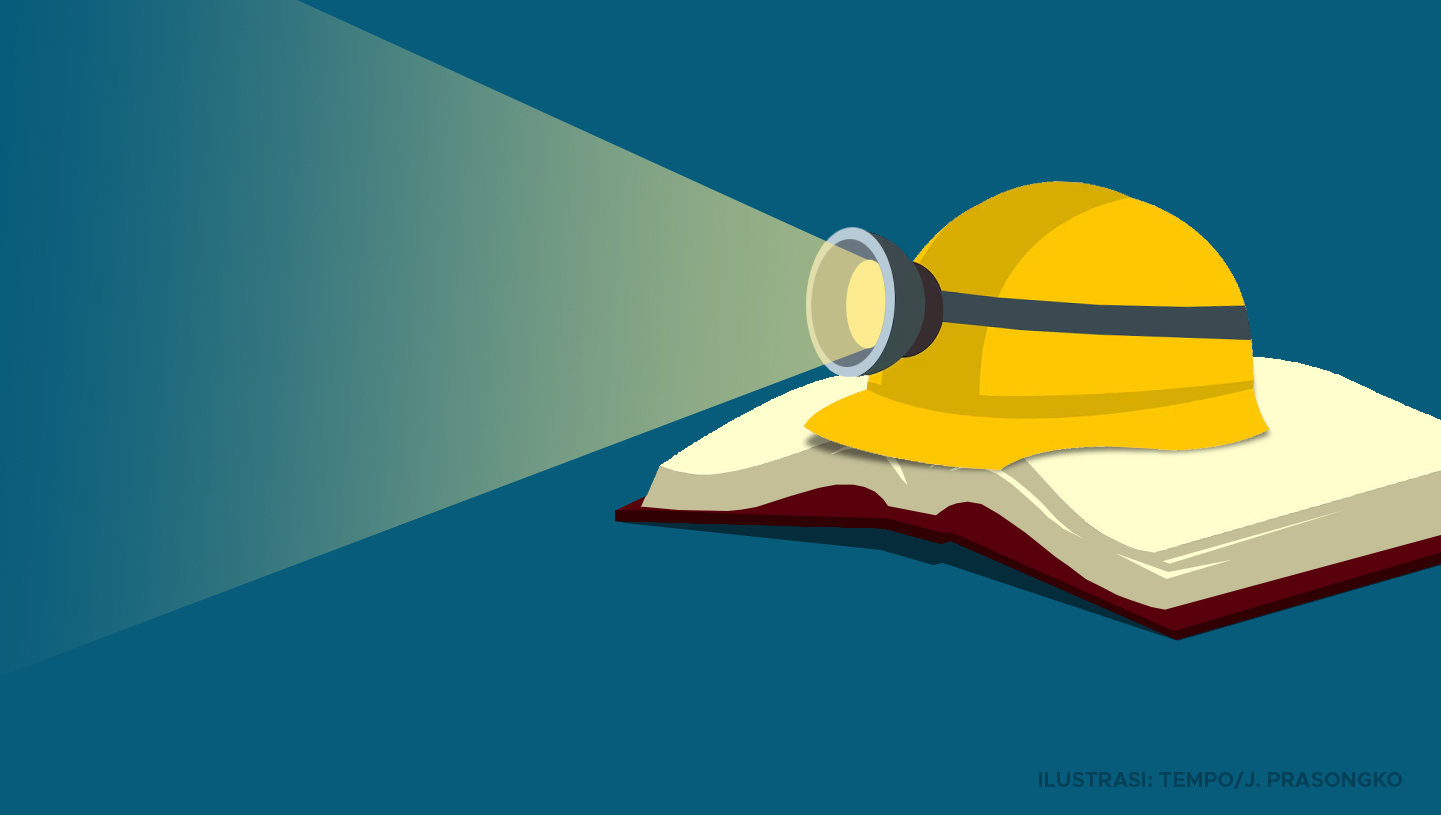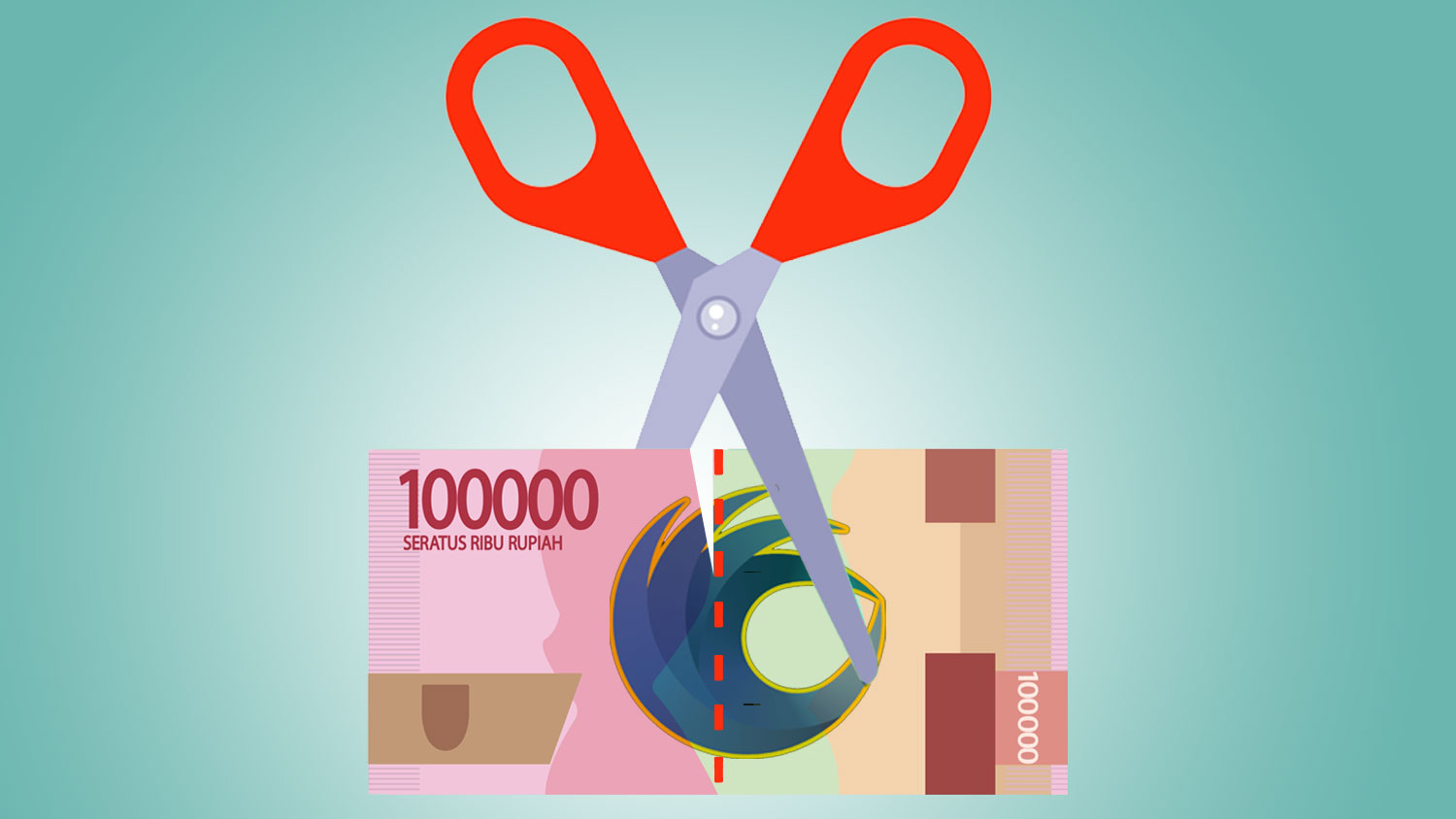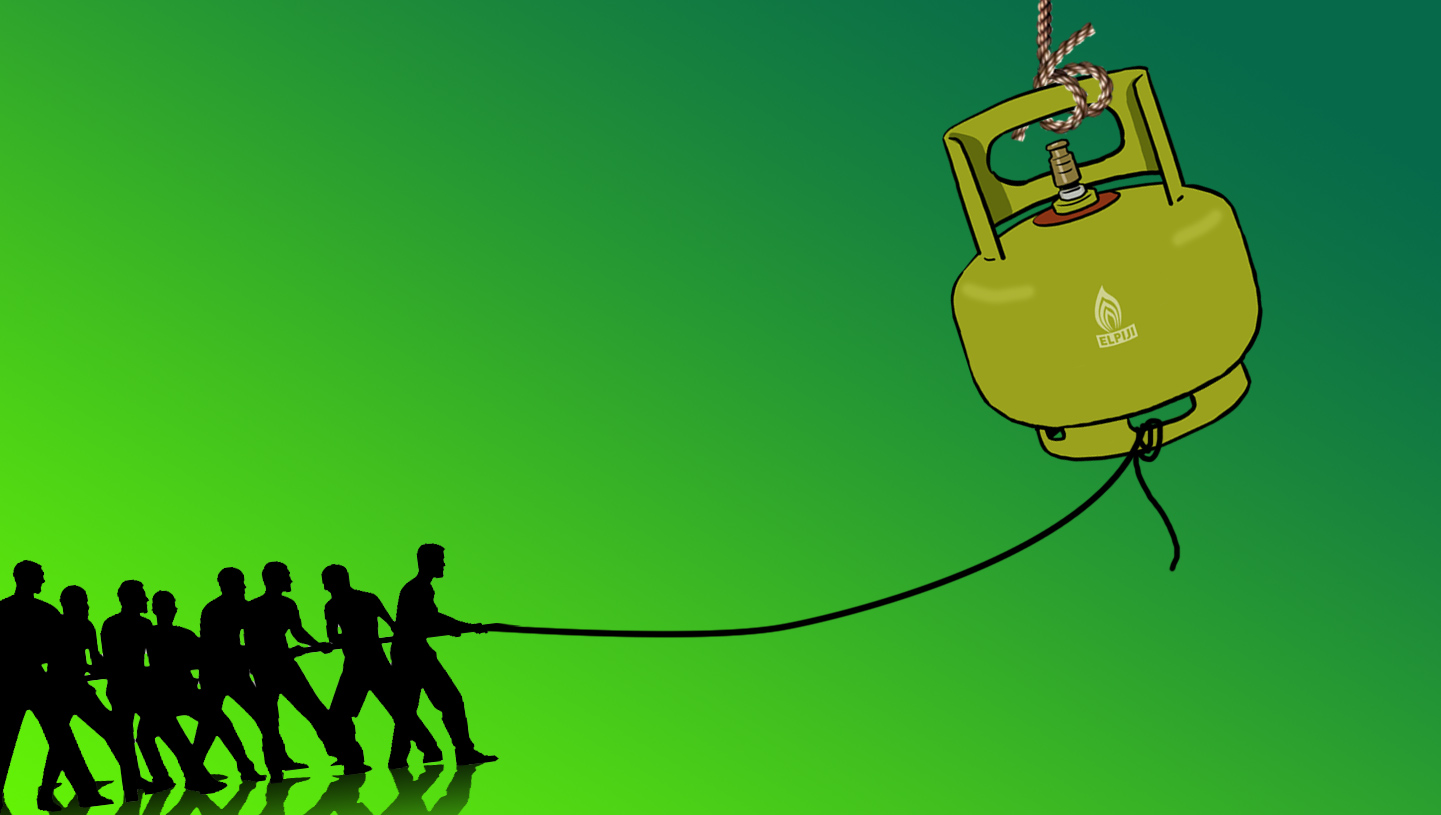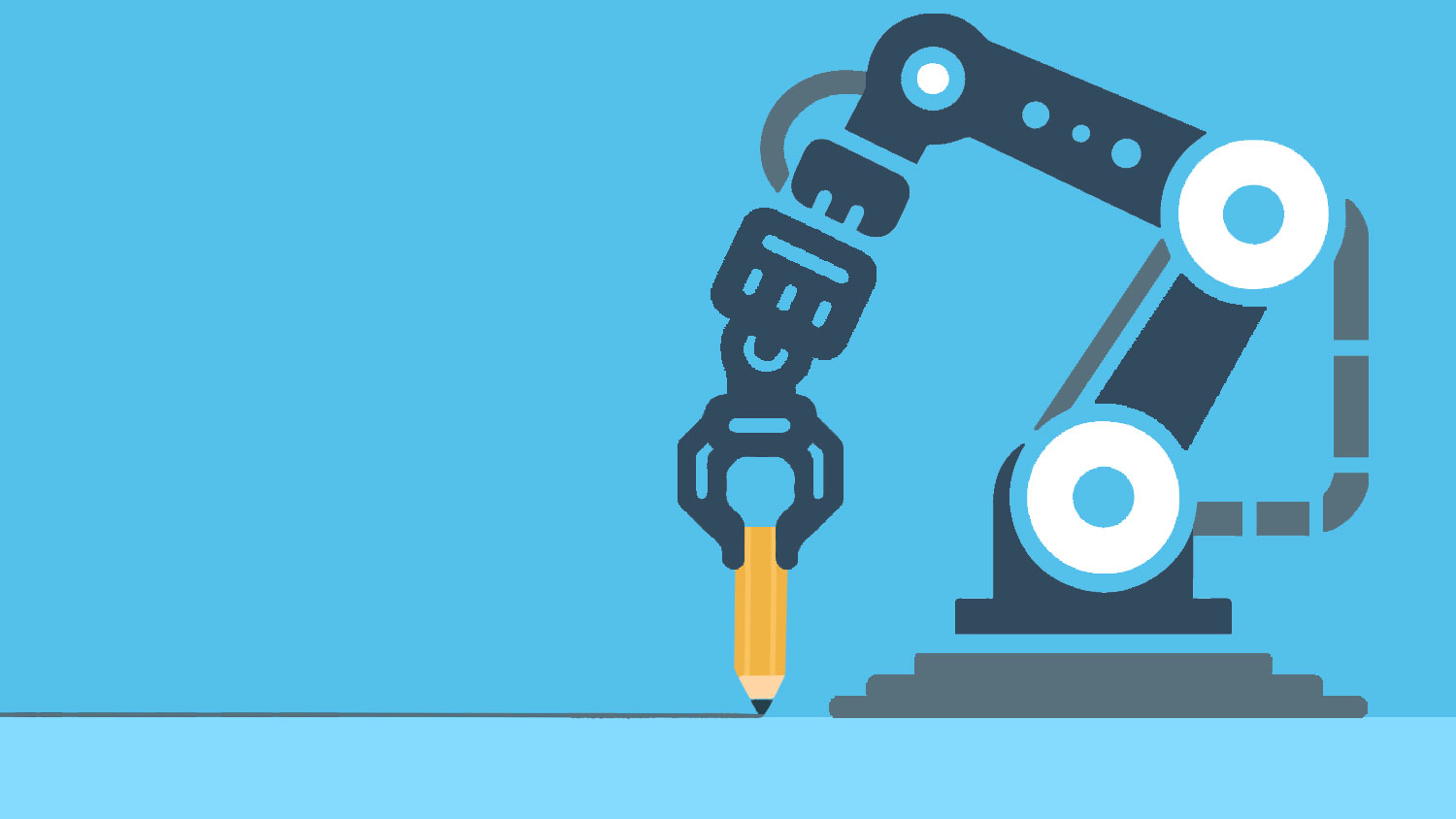Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Perempuan tua itu senantiasa bernama:
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

duka derita dan senyum yang abadi
tertulis dan terbaca jelas kata-kata puisi
dari ujung rambut sampai telapak kakinya…
(Ibunda Tercinta, Umbu Landu Paranggi, 1965)
Diiringi bait puisi Umbu Landu Paranggi yang dinarasikan suara Jefri Nichol, serangkaian gambar puitik Sumba Timur membuka film dokumenter berjudul The Woven Path: Perempuan Tana Humba.Mengutip karya penyair asal Sumba Timur itu adalah sebuah pilihan tepat karena film ini menjanjikan dua hal: kebudayaan Sumba Timur dan para perempuan Sumba yang berperan penting dalam kehidupan Kawasan yang tengah menjadi perhatian sineas itu.
Serangkaian gambar dengan scoring liris dari Thoersi Argeswara itu kontras: antara keindahan sabana yang seolah bertemu dengan ujung langit biru Sumba. Perkenalan dengan gambar dan warna kain Sumba dan warganya pada 10 menit pertama hampir seperti sekumpulan sketsa tentang lansekap kebudayaan Sumba ,terutama bagi penonton Indonesia yang sama sekali tak pernah mendengar atau menyentuh bagian timur Indonesia yang luar biasa ini: tentang Marapu, tentang Pasola , tentang tenun, dan padang sabana yang terus menerus menarik para sineas untuk membentangkan pada layar putih mereka.
Memilih Sumba memang sudah cukup lama menjadi setting pilihan para sineas film Indonesia. Sutradara Garin Nugroho pada tahun 1994 sudah memulainya dengan film “Surat untuk Bidadari” karena bagi Garin “Sumba penuh paradoks, ada tradisi kuat tetapi kita bisa symbol modernitas seperti parabola; ada kesetiaan tapi ada juga kekerasan,” kata Garin. Tak heran dia juga melahirkan ide cerita “Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak” yang juga mengambil lokasi Sumba yang kemudian disutradarai oleh Mouly Surya tahun 2017 lalu.
Produse Mira Lesmana merasa Sumba Timur hampir seperti ‘rumah kedua’nya. “Saya jatuh cinta pada Sumba,” katanya menjawab pertanyaan mengapa film-film produksinya mengambil Sumba sebagai lokasi, seperti “Pendekar Tongkat Emas” (Ifa Isfansyah, 2014) dan yang akan beredar tahun ini “Humba’s Dream” (Riri Riza, 2019). Menurut Mira, Sumba adalah salah satu wilayah di timur Indonesia dengan kelengkapan cerita : Budaya Marapu yang masih dipraktekkan hingga hari ini, dan menjadi bagian dari kehidupan sehari hari,” katanya. Mira juga tertarik dengan lansekap alam Sumba yang tidak ada duanya. Begitu cintanya Mira pada Sumba hingga dia mengaku setiap tahun minimal dia satu kali berkunjung ke sana. “Kadang-kadang lebih dari satu kali.
Adapun Lasya Susatyo menyatakan ia tertarik mengangkat kisah tenun, perempuan dan kebudayaan Sumba Timur karena diawali dari aktivis perempuan Olin Monteiro yang “sudah bertahun-tahun melakukan penelitian tentang perempuan dan kebudayaan di Sumba,” kata Lasya. Seperti Mira Lesmana, Lasya juga mengagumi Sumba dengan padang Sabana yang selalu memperlihatkan kuda yang berlari lepas serta masyarakatnya yang masih lekat dengan tradisi yang tengah mengalami transisi. Tapi lebih lagi , Lasya menemukan bagaimana “para mama yang masih bekerja sangat keras menopang kehidupan masyarakat dan hidupnya sendiri.” Lasya merasa bagaimana para perempuan tengah menggeliat atas “peraturan tradis yang berimbang”.
Maka Lasyapun bekerja sama dengan Olin Monteiro dan produser Mandy Marahimin dengan dukungan dari Ford Foundation film ini kemudian berupaya mendokumentasikan kebudayaan Sumba Timur. Kita melihat ritual pemakaman tarik batu yang merupakan bagian dari pemakaman di mana mereka dikuburkan di bawah batu besar keluarga; ritual para perempuan yang menenun; upacara perkawinan dan diskusi tentang Belis.
Belis, yang agaknya menjadi dominasi diskusi dalam dokumenter ini, adalah tradisi seserahan dalam pernikahan masyarakat Sumba. “Biasanya seserahan berbentuk kuda,” kata Olin Monteiro yang beberapa tahun terakhir melakukan penelitian tentang perempuan Sumba . “Pria yang ingin meminang perempuan Sumba wajib memberikan sejumlah hewan ternak sebagai seserahan, mulai kerbau, sapi hingga Kuda Sandalwood atau Pasola,” kata Olin lagi.
Selebihnya kita melihat beberapa narasumber antara lain Rambu Margaretha, Sarah Hobgen dan Rambu Ana yang memberikan pendapat mereka tentang posisi perempuan dan mengapa Belis mulai menjadi persoalan bagi generasi muda ketika permintaan seserahan menjadi begitu tinggi.
Khususnya Rambu Ana, misalnya, salah satu perempuan muda yang merupakan puteri dari Tamu Rambu Margaretha, Mama raja Prailiu, yang lebih terbuka mempertanyakan bagaimana perempuan diharapkan untuk mematuhi saja. Rambu Ana mungkin mewakili generasi muda perempuan yang mulai menyatakan keberatan-keberatannya atau mempertanyakan hal-hal yang tak disetujuinya dalam ketentuan dalam hidupnya.
Film sepanjang 30 menit ini sesungguhnya sebuah perkenalan awal yang menurut Lasya, lebih ditujukan untuk anak-anak sekolah. Itu sebabnya, mungkin film ini masih berbentuk “perkenalan” kepada Sumba, ketimbang betul-betul menyorot persoalan “Perempuan Tanah Humba” seperti judulnya (karena bukankah jika memang tentang Perempuan, maka kita ingin mengetahui bagaimana peran perempuan sebagai isteri dan ibu; bagaimana pendidikan anak , bagaimana sikap mereka terhadap pendidikan bagi perempuan; siapakah yang sesungguhnya bertugas mencari nafkah di dalam keluarga dan seterusnya). Pada dasarnya, ketika memberi judul dengan elemen gender seperti “perempuan”, maka dengan sendirinya pertanyaan mendasar pertama yang diutarakan adalah “bagaimana pembagian kerja dan peran antar lelaki dan perempuan di daerah tersebut?”
Bagaimana pun, upaya perkenalan pertama ini tetap sesuatu yang bagus dan menimbulkan keinginan tahu penonton awam, seperti saya, untuk mengetahui lebih jauh tentang kebudayaan Sumba yang tampaknya menjadi magnet bagi para sineas terkemuka di Indonesia ini.
The Woven Path: Perempuan Tana Humba
Sutradara: Lasya Susatyo
Skenario: Lasya Susatyo
Produksi: Tanakhir Films
LEILA S. CHUDORI