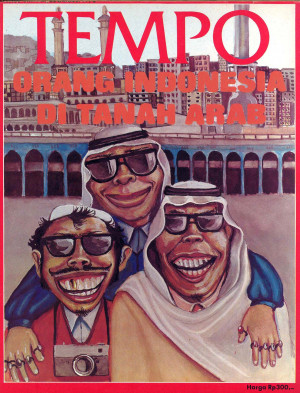SUATU peristiwa terjadi. Dan ia sesungguhnya hanyalah sebuah
titik dalam lautan peristiwa. Tetapi barangkali perisiwa itu
secara riil ataupun dalam anggapan terkait pada yang lain,
hingga ia menjadi bagian dari suatu proses yang menentukan arah
perkembangan masyarakat. Barangkali pula peristiwa itu makin
dirasakan sebagai sesuatu yang penting, sesuatu yang berarti
dalam kesadaran. Maka peristiwa itupun disebut peristiwa
"sejarah". Peristiwa itu dicatat dan kadang-kadang dikenang.
Jika nasibnya baik, ya, jika nasib peristiwa itu baik, maka ia
pun dirayakan pada saat-saat tertentu. Peristiwa itupun
diceritakan berulang-ulang. Ia telah jadi bagian dari proses
sosialisasi. Padanya telah dilekatkan berbagai nilai yang
dianggap mendukung norma yang berlaku. Maka peristiwa itupun
telah dinaikkan kepada tingkat yang lain -- ia telah menjadi
bagian dari simbol. Ia dianggap sebagai perwujudan nilai-nilai
yang demikian tinggi dan demikian sulit untuk dirumuskan.
Maka tersebutlah suatu peristiwa di Krarnat Raya 106 (Jakarta)
pada tanggal 28 Oktober 1928, mengalami nasib baik. Peristiwa
itu dikenang dan semacam "supra-sejarah" dilekatkan padanya.
Sepintas lalu pengkaitan nilai-nilai mulia terhadapnya mungkin
hanyalah hasil karya para myth-makers saja. Peristiwa sederhana,
ketika beberapa puluh anak muda berjanji dan mengakui tentang
bangsa dan tanah air yang satu dan tentang hahasa persatuan yang
harus dijunjung, telah "diangkat" ke tingkat yang jauh melampaui
kesederhanaannya.
Mungkin saja peristiwa itu dipakai karena diperlukan bagi sutu
tujuan tertentu -- peneguhan integrasi nasional, dan entah
berapa lagi nilai lain. Jika begitu apa salahnya kalau padanya
dilekatkan nilai lain, seandainya tujuan lama telah tercapai dan
sekiranya tujuan baru harus dirintis? Katakan saja bahwa
peristiwa tersebut dipakai untuk jadi Hari Pemuda (dan
kaitkanlah nilai apa yang dicitakan). Memang, jika masalahnya
hanya sesederhana itu tak ada salahnya. Kita "menemukan" saja,
tanpa perlu "mengenangnya". (Ada yang mengatakan sejarah itu tak
hanya "dikenang", tetapi juga 'ditemukan").
Persetankanlah rekaman para peserta dari peristiwa yang kini
disebut "Sumpah Pemuda" itu. Dan tak usahlah digubris ocehan
para ahli sejarah tentang "peristiwa kimiawi" yang diciptakan
"sumpah" tersebut dalam perkembangan masyarakat dan pembentukan
kesadaran kita. Lupakan saja. Bukankah para peserta peristiwa
biasanya terbuai dengan nostalgia? Dan, bukankah ahli sejarah,
konon, tak sepenuhnya terbebas dari konvensi zamannya?
Puncak Kesungguhan, Keprihatinan
Tetapi inilah soalnya, masalahnya tidaklah sesederhana ini.
Peristiwa "Sumpah Pemuda" itu jadi penting bukan pada apa yang
terlekat di dirinya sendiri. Tetapi pada kaitannya dengan apa
yang mendahului dan apa yang mengikutinya.
Jika soal tekad "Indonesia" yang jadi soal, peristiwa itu memang
tidaklah terlalu penting. Jauh sebelumnya, Perhimpunan Indonesia
di negeri Belanda, di bawah pimpinan Bung Hatta, telah gigih
berjuang dan mengumandangkan ide yang kemudian tertuang sebagai
mantra dalam "Sumpah Pemuda" itu. Dan di tahun 192, Bung Karno
telah mendirikan Partai Nasional Indonesia, tanpa hari lahirnya
harus dirayakan oleh yang bukan anggota PI (baru) -- yang kini
telah "marhum" itu. Jadi, bagaimana?
Peristiwa 28 Oktober adalah puncak dari usaha yang dengan penuh
kesungguhan, malah, keprihatinan, menghadapi masalah
"penciptaan" suatu bansa yan baru. Peristiwa itu bermula
dengan keterharuan akan perasaan atas tak berlakunya lagi makna
dan pengertian "bangsa" yang selama ini dihayati. Dari keharuan
ini dan dalam usaha pencarian atas "bangsa" yang baru ini
konfrontasi pikiran diadakan. Malah konflik dari berbagai
organisasi pemuda yang tengah sibuk mempertanyakan identitas
diri itupun terjadi.
"Sumpah Pemuda" tidak keluar dari renungan ilmiah, yang dijiwai
oleh nasionalisme saja. Juga tidak hanya alat perjuangan untuk
melawan kolonialisme. Peristiwa itu bermula dengan
mempertentangkan segala anggapan dan prasangka tradisional. Dan,
kemudian, ketika segala kemacetan yang menjenuhkan telah
berentetan, maka terjadilah itu -- ikrar dipatrikan.
Mungkin ini juga tak akan ada artinya apa-apa. Tetapi itulah,
ikrar ini kemudian menjadi patokan dari sikap yang diambil
organisasi-organisasi pemuda. Mereka meleburkan diri pada
sesuatu yang baru. Kematangan sikap dan kebulatan nilai telah
tercapai. Karena itulah perisitwa tersebut dikenang, dirayakan.
Ikrar tersebut bukanlah suatu hasil renungan kontemplatif
belaka, tetapi didahului oleh pencarian, konflik dan,
pertentangan. Peristiwa itu didukung oleh pengorbanan yang luar
biasa - kisah sepuluh tahun dari organisasi-organisasi pemuda,
dileburkan pada halaman baru sejarah. Dan, bukan itu saja, malah
lebih penting lagi, pertanyaan sederhana harus pula dijawab.
Apakah artinya bahasa kesatuan dalam penciptaan bangsa dan
negara kita? Biarlah para ahli mengukurnya, dan biarlah yang
menghayatinya merenungkannya.
Demikianlah jadinya, pada peristiwa 50 tahun yang lalu itu
berbagai cita kebangsaan -- "bangsa" baru yang kini telah
diciptakan -- dilekatkan. Dengan begini, antara
"peristiwa-sebagaimana-terjadinya" dan
"makna-yang-terlekat-padanya" telah menampakkan dua hal yang
berbeda, yang tak lagi bisa dipersamakan. Tetapi keduanya telah
menjadi mithos nasional. Dan sebagai mithos ia telah makin
menjadi kenyataan -- ia makin riil dalam kesadaran kita.
("Kita", tanpa pembatasan generasi).
Tidak Lagi Terpana
Bila rasionalitas telah berkembang, kata orang, maka "dunia tak
lagi terpana". Mungkinkah kita tak lagi terpana pada mithos
"Sumpah Pemuda" karena kita sudah tambah rasional? Hanya saja
dalam ke-rasional-an ini, apakah telah terasa pula bahwa nilai
yang dianggap yang mewakilinya tak lagi sesuai dengan tuntutan
keadaan dan tuntutan kesadaran?
Baik, hilangkanlah segala romantik sejarah itu, dan marilah kita
menuju hari depan lugas dan berperhitungan. Program yang
penting. Kita hilangkan "Sumpah" yang keramat. Hari Pemuda kita
canangkan. Cuma dengan begini ke-irrasional-an yang tanpa
romantika telah di hadapan kita. Seakan-akan dengan memberikan
makna baru pada 28 Oktober itu dan menjadikannya mithos baru
(ya, mithos, kalau tidak mengapa harus pakai Hari Pemuda
segala?) masalahnya telah selesai.
Cuma saja pelepasan keterpanaan kepada "Sumpah Pemuda" tidaklah
menjamin, malah jauh daripada itu, kelekatan hati kepada sesuatu
yang baru itu. Hari Pemuda hanya akan sama dengan hari-hari
lain, Hari Kanak-kanak, Hari Ibu, Hari Wanita, dan apa lagi,
tanpa keprihatinan historis yang dirasakan semua. Maka yang lama
terlepas yang baru kececeran. Begitulah. Mestikah kita ucapkan
"Selamat Tinggal, Sumpah Pemuda"?
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini