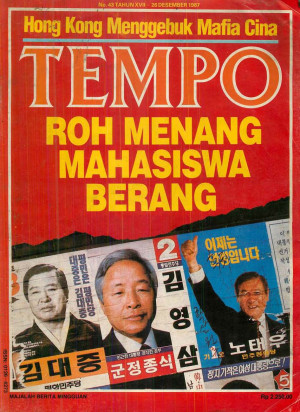JEPANG pernah merasakan betapa sakitnya sebuah perubahan. Sebab, perubahan itu, yang prosesnya dipercepat oleh sebuah mata uang, menyentuh dan melukai nilai-nilai mereka paling mendasar. Empat puluh tahun setelah hancur oleh Perang Dunia II, Jepang muncul sebagai kekuatan ekonomi paling agresif, efisien, dan produktif di dunia. Mereka telah mencapai apa yang sudah dicapai Amerika Serikat dan Inggris, dan mampu menghasilkan lebih baik dari apa yang dihasilkan negara industri lain. Tak heran bila pengamat ekonomi meramalkan, abad ke-21 akan menjadi abad Jepang. Sejak nilai mata uang yen naik terus, Jepang terpaksa merenungkan kembali perubahan yang sedang terjadi pada dunia industri mereka -- yang selama ini merupakan simbol kekaguman, ketakutan, dan kejengkelan lawan. Meski tantangan yang berasal dari apresiasi yen mereka hadapi dengan keluwesan dan kegigihan khas samurai, toh tetap tak mudah bagi Jepang menerima kenyataan bahwa industri baja dan perkapalan, dua industri awal yang mengangkat derajat Jepang, nyaris bangkrut. Keuntungan tahun ini hanya sepersepuluh dari keuntungan yang diperoleh dua tahun lampau. Ternyata, tak cuma dua industri baja dan perkapalan yang melorot. Industri-industri lain juga merasa terpukul. Tahun ini keuntungan industri mobil dan kimia turun 20%, industri mesin turun 30%, elektronik turun 50%, dan transpor turun 80%. Maka, kini, Jepang dipaksa merenungkan kembali nilai kultural yang melekat erat di bawah sadar mereka selama ini: adalah tercela membeli dari orang lain yang bukan kelompok sendiri. Itulah yang membuat Jepang berkembang menjadi sebuah pasar tertutup, terutama untuk hasil industri negara lain. Apabila ada celah yang terbuka, berbagai ikhtiar dilakukan untuk menambalnya. Sumbat yang mereka buat macam-macam: ada soal tarif, standar yang ketat distribusi yang ruwet, dan lain-lain, sampai akhirnya barang asing itu kehabisan napas sebelum sempat bersaing di pasar dalam negeri Jepang. Jepang, sekalipun kaya, alam bawah sadar mereka merasa tetap miskin, dan tidak aman, karena mereka tak punya bahan mentah, dan merasa selalu dimusuhi. Selain itu, umur rata-rata orang Jepang makin panjang, maka mereka makin butuh banyak uang untuk menghadapi hari tua yang mahal. Kini, misalnya, mereka tak pernah lagi bermimpi bisa membeli tanah di Ginza, daerah pertokoan Tokyo, yang berharga Rp 350 juta per meter persegi. Mereka sudah puas kalau bisa membeli sebidang tanah yang layak di pinggiran kota. Di sampmg ltu, mereka juga perlu uang banyak untuk biaya pendidikan yang makin mahal. Prospek yang brutal ini memaksa orang Jepang menabung dan berhemat. Tak heran kalau tingkat tabungan orang Jepang beberapa kali lipat tingkat tabungan orang Amerika dan Eropa. Karena orang Jepang tak banyak membelanjakan penghasilan mereka, maka pasar di dalam negeri tidak cukup luas. Untuk terus tumbuh, industri Jepang harus mengekspor. Maka, yang terjadi selama tiga dekade terakhir adalah sebuah perekonomian yang digerakkan oleh mesin ekspor bertenaga tinggi. Setiap tahun kekayaan yang dikumpulkan Jepang dalam bentuk surplus neraca pembayaran berjumlah US$ 90 milyar. Kekayaan yang dikumpulkan Jepang itu berarti pengorbanan bagi kekayaan orang lain. Karena itu, proses ini tak bisa berlangsung terus. Jepang tak bisa terus melakukan, apa yang disebut Ekonom Peter Drucker, adversarial trade -- menjual, dan menjual terus Jepang juga harus membeli. Kalau tidak, rekan dagangnya, yang penghasilannya terus disedot Jepang, cepat atau lambat akan bangkrut. Atau, mereka terpaksa menutup pasar dalam negeri bagi barang Jepang. Membeli akhirnya memang dilakukan Jepang, sekalipun karena nilai yen membaik, dan atas imbauan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Internasional (MITI). Impor Jepang, antara kuartal ketiga 1987 dan tahun lalu, naik 20% dalam yen atau 30% dalam dolar. Impor yang dilakukan dengan berat hati, karena pemerintah Jepang terpaksa memberi subsidi buat perusahaan kecil dan menengah yang melakukan impor, dan harus menurunkan tarif bea masuk 2.000 jenis barang impor. Perubahan ini terasa menyakitkan buruh dan karyawan perusahaan-perusahaan Jepang. Masa kerja seumur hidup tidak lagi merupakan sesuatu yang otomatis diperoleh dari sebuah patronisme sosial. Mereka tak lagi kebal terhadap PHK. Alasannya ialah pasar yang menciut, akibat yen yang mahal, memerlukan usaha penghematan yang kejam. Dan, usaha mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan menduduki tempat teratas, termasuk di atas rasa aman dari sebuah hubungan sosial yang harmonis. Kenyataan ini bagi perusahaan Jepang bukan hanya berarti melakukan penghematan dan peningkatan efisiensi di dalam negeri. Mereka juga terpaksa memindahkan pabrik ke luar negeri, baik untuk lebih dekat dengan konsumen (Honda dan Toyota ke Amerika, dan Nissan ke Inggris), maupun untuk mencari ongkos buruh yang murah (Matsushita ke Taiwan dan Singapura, dan Casio ke Hong Kong). Yen yang mahal telah memaksa mereka mengekspor modal, pabrik, dan kesempatan kerja. Kalau masih ada yang bertahan di Jepang, seperti Seiko, hal itu adalah pengecualian. Penyebabnya ialah, Seiko merasa robot-robot mereka masih bisa memproduksi arloji lebih rapi dan lebih murah dari pada wanita-wanita Hong Kong. Sebenarnya, Jepang ingin nilai yen dan dolar stabil. Bukan saja untuk daya saing industri mereka, tapi juga untuk tabungan yang sudah dikumpulkan selama ini. Jepang mungkin tak bisa tidur nyenyak dengan simpanan mereka di AS, yang melonjak dari US$ 34 milyar (1983) menjadi US$ 119 milyar (1987). Mereka sadar bahwa tabungan mereka telah menjadi sandera AS. Bayangan buruk itulah yang menyebabkan Jepang rela berubah, betapapun sakitnya perubahan itu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini