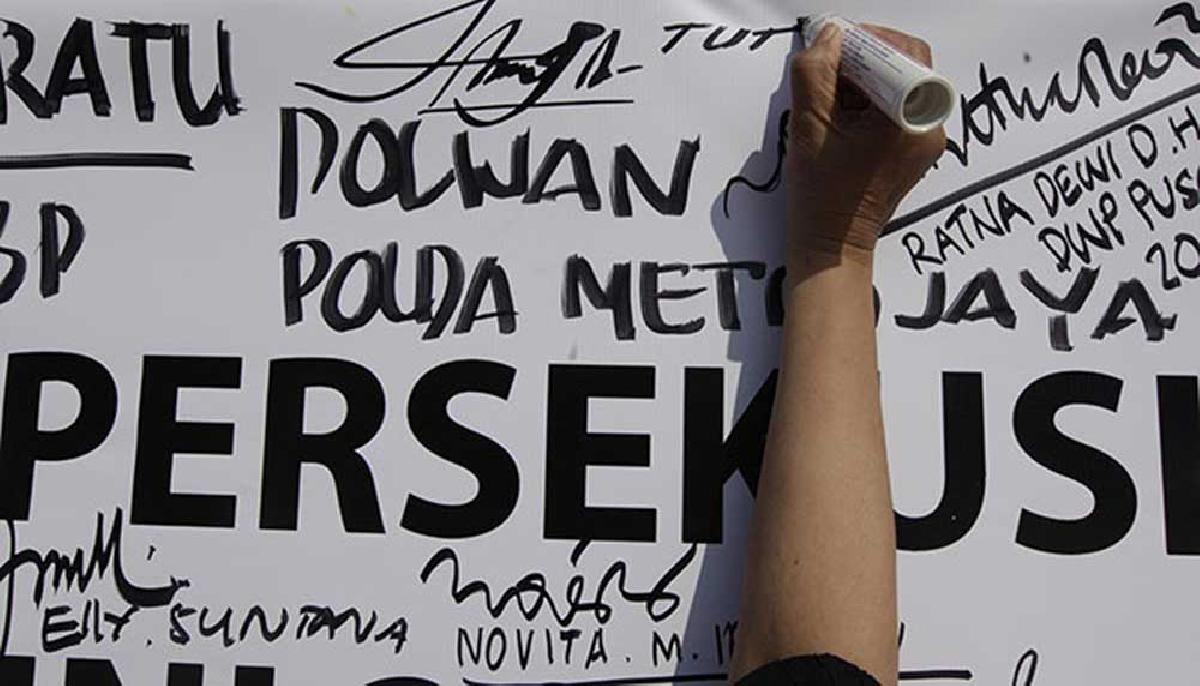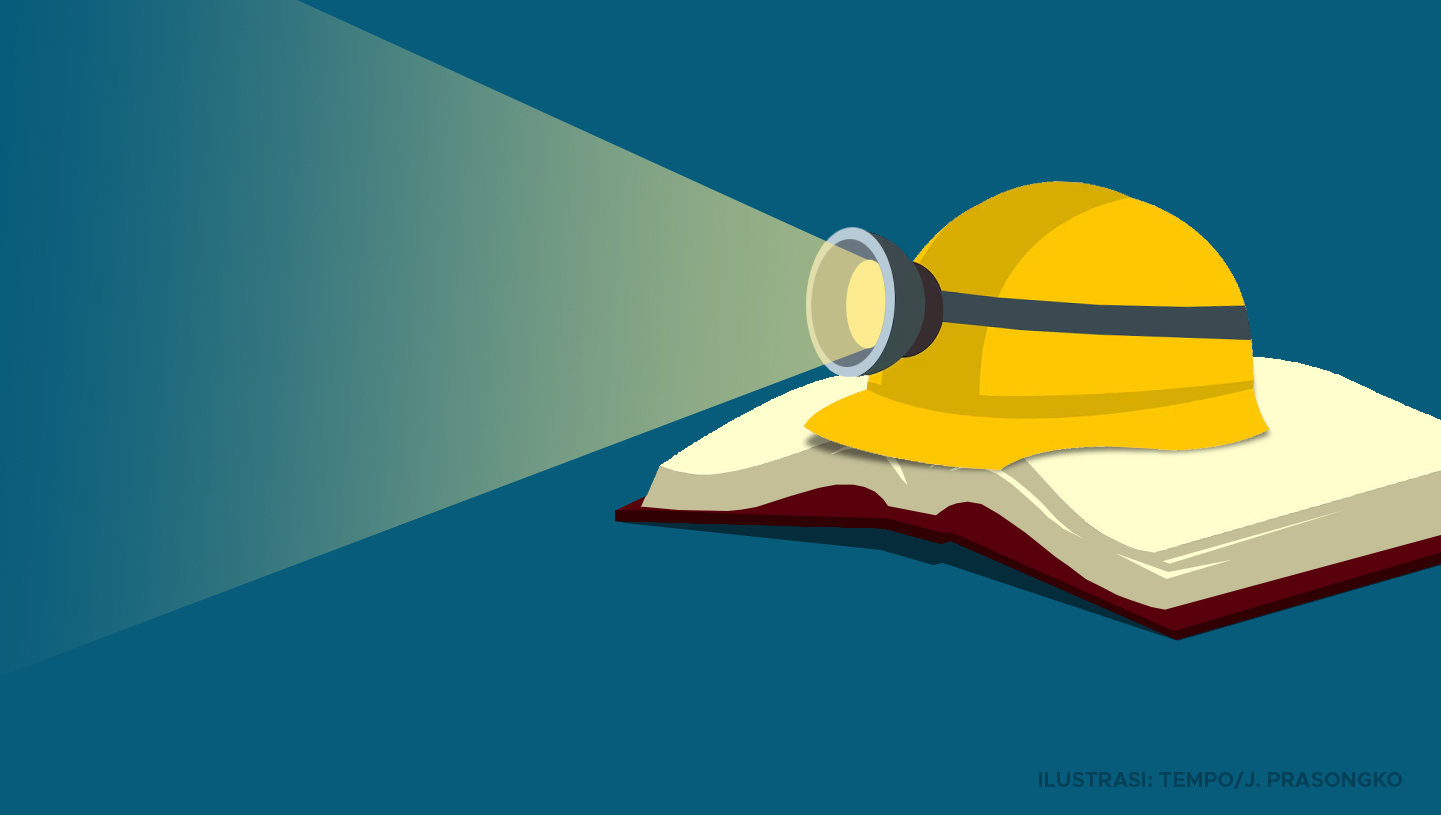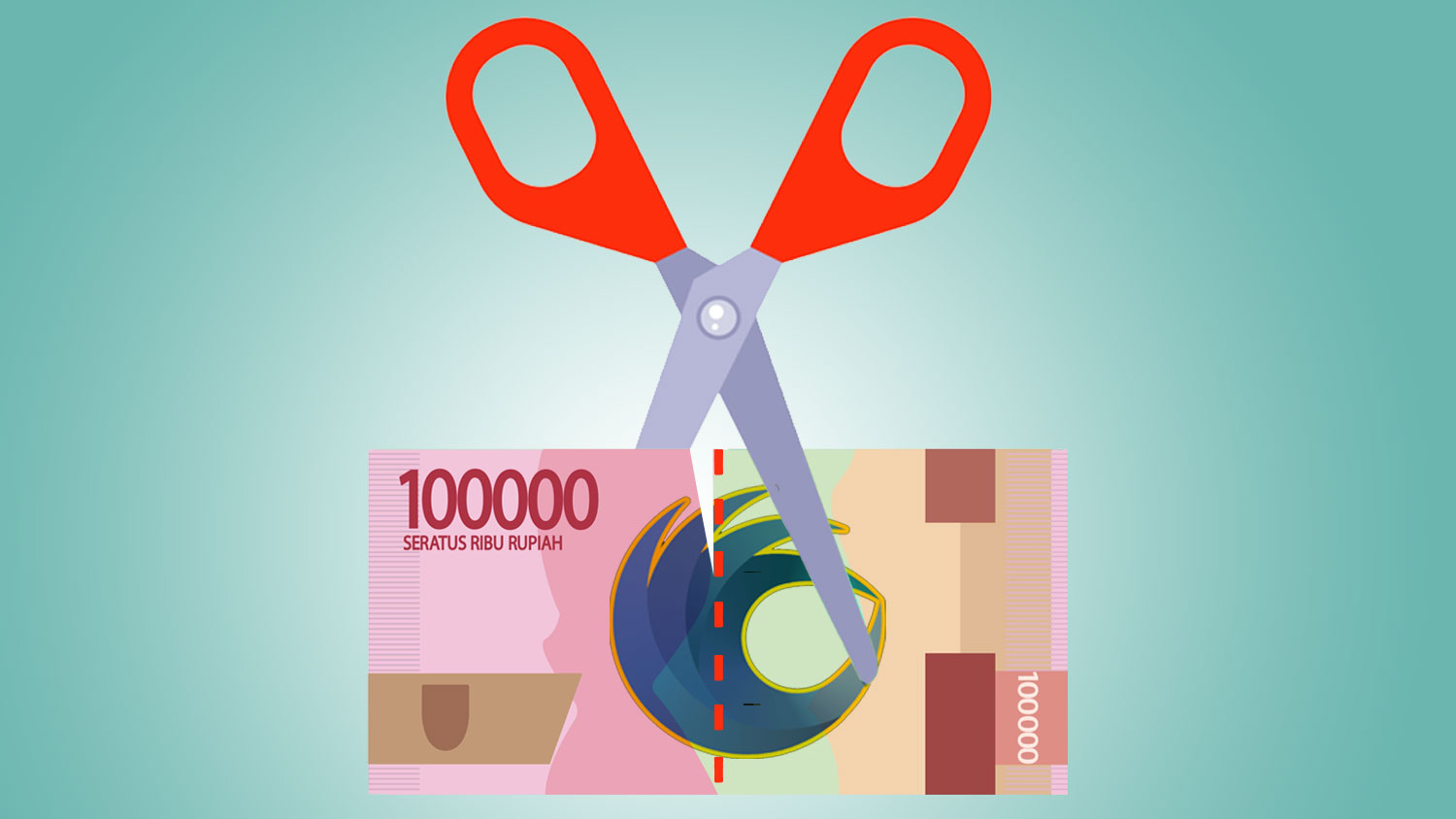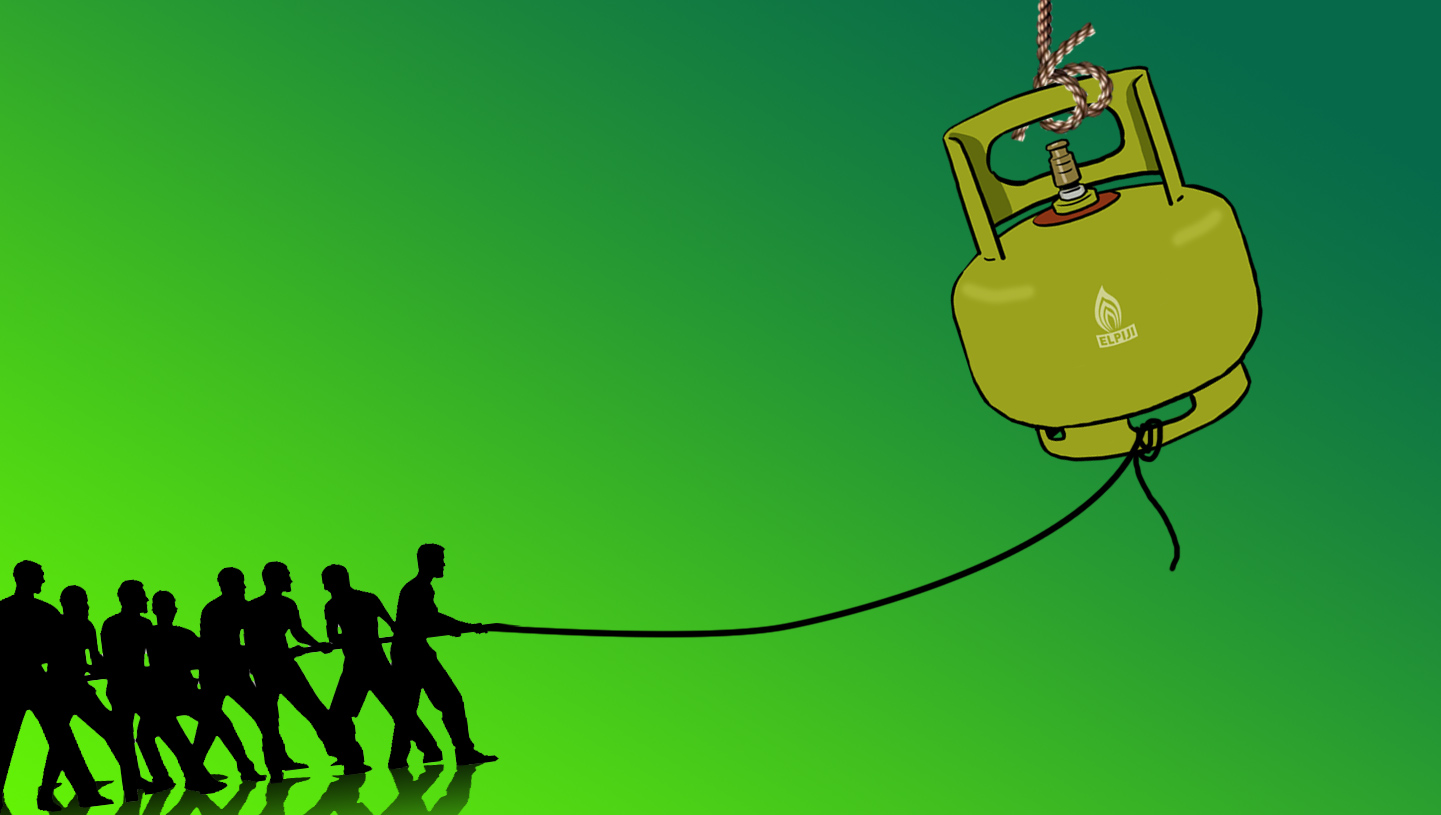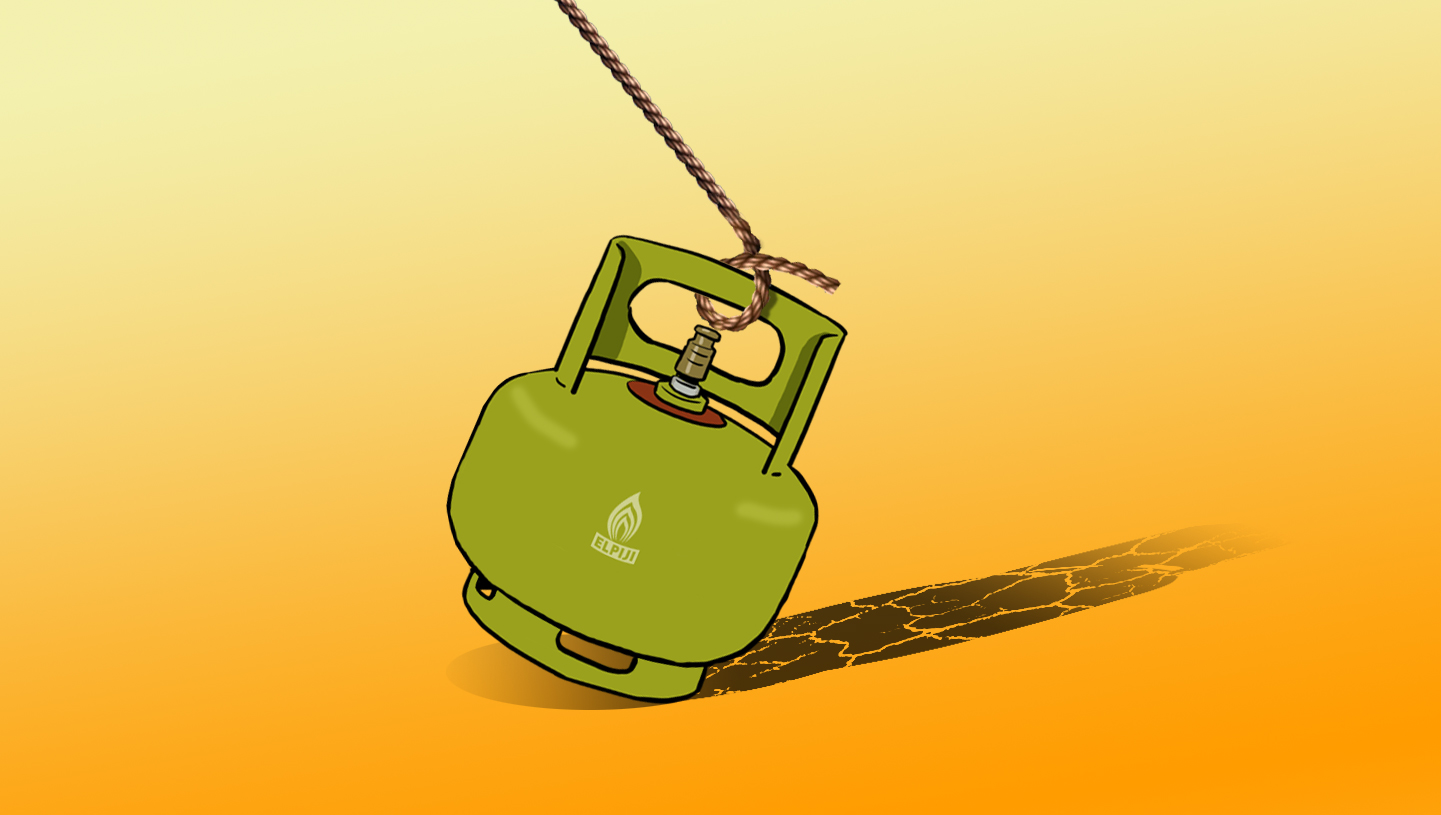Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Runyam betul kondisi bangsa ini dalam urusan menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan. Konstitusi kita sudah jelas-jelas menjamin kemerdekaan penduduk dalam memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, tapi persekusi terus-menerus terjadi terhadap kalangan minoritas. Penyerangan atas warga Ahmadiyah di Lombok Timur dua pekan lalu menunjukkan ketidakberdayaan negara dalam melindungi kebebasan mendasar tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Yang lebih memprihatinkan adalah fakta bahwa kekerasan atas komunitas Ahmadiyah di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, sudah terjadi tiga kali. Sungguh ironis, ketika kita memperingati 20 tahun gerakan reformasi, delapan rumah warga Ahmadiyah di Sakra Timur, Lombok Timur, diobrak-abrik dan beberapa sepeda motor dirusak. Selama penyerangan berlangsung, 21 ibu dan anak-anak di sana dicekam ketakutan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Kekerasan semacam itu tak hanya terjadi pada kaum Ahmadiyah. Penyerangan terhadap kelompok minoritas sudah terjadi beratus kali di negeri ini. Organisasi nonpemerintah, Setara Institute, mencatat ada 155 kasus intoleransi di 29 provinsi dalam sepuluh tahun terakhir. Mayoritas kasus intoleransi terkait dengan penodaan agama dengan warga Ahmadiyah dan Syiah menjadi komunitas yang paling sering menjadi korban.
Dalam setiap insiden persekusi, selalu korban yang ketiban kerepotan. Mereka harus menghuni tempat-tempat penampungan dengan kualitas hidup yang lebih rendah dari semula. Jikapun ingin kembali ke rumah, mereka dipaksa memenuhi syarat yang diminta kelompok radikal yang menyerang mereka. Sedangkan para pelaku hampir tak pernah tersentuh hukum.
Biang keladi tumpulnya hukum dalam kasus-kasus ini adalah masih diterapkannya soal penodaan agama dalam Pasal 156-a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta norma Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1/PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Pasal-pasal itu memberikan kewenangan kepada negara untuk memonopoli tafsir terhadap ajaran agama dan menetapkan mana ajaran yang "benar" dan mana yang "menyimpang".
Tengok saja Pasal 1 Undang-Undang Penodaan Agama. Pasal ini selalu dijadikan dasar untuk menghukum kelompok yang dinilai berbeda dengan mayoritas. Kelompok minoritas selalu menjadi korban diskriminasi karena dianggap lancang melakukan penafsiran atas agama, yang berbeda dengan penafsiran kelompok mayoritas. Buntutnya, yang terjadi bukan hanya penghakiman terhadap urusan keyakinan, melainkan juga perampasan hak sosial, hak politik, dan hak hidup kelompok yang berbeda.
Upaya mengubah aturan ini sudah dicoba di Mahkamah Konstitusi pada 2013, tapi kandas. Sekalipun Mahkamah menyatakan undang-undang tersebut masih diperlukan, para hakim konstitusi meminta pasal-pasalnya disempurnakan agar tidak menjadi senjata persekusi atas minoritas. Namun, bukannya merevisi, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat justru memperluas pasal itu dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Kekerasan atas kaum minoritas jelas bertentangan dengan semangat Pancasila dan konstitusi. Ketidakmampuan kita mencegahnya adalah awal berkembangnya intoleransi dan radikalisme. Jika kecenderungan ini dibiarkan, adagium yang sejak dulu kita banggakan, yakni "bangsa Indonesia adalah bangsa yang toleran", harus dilupakan dan dikubur dalam-dalam.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo