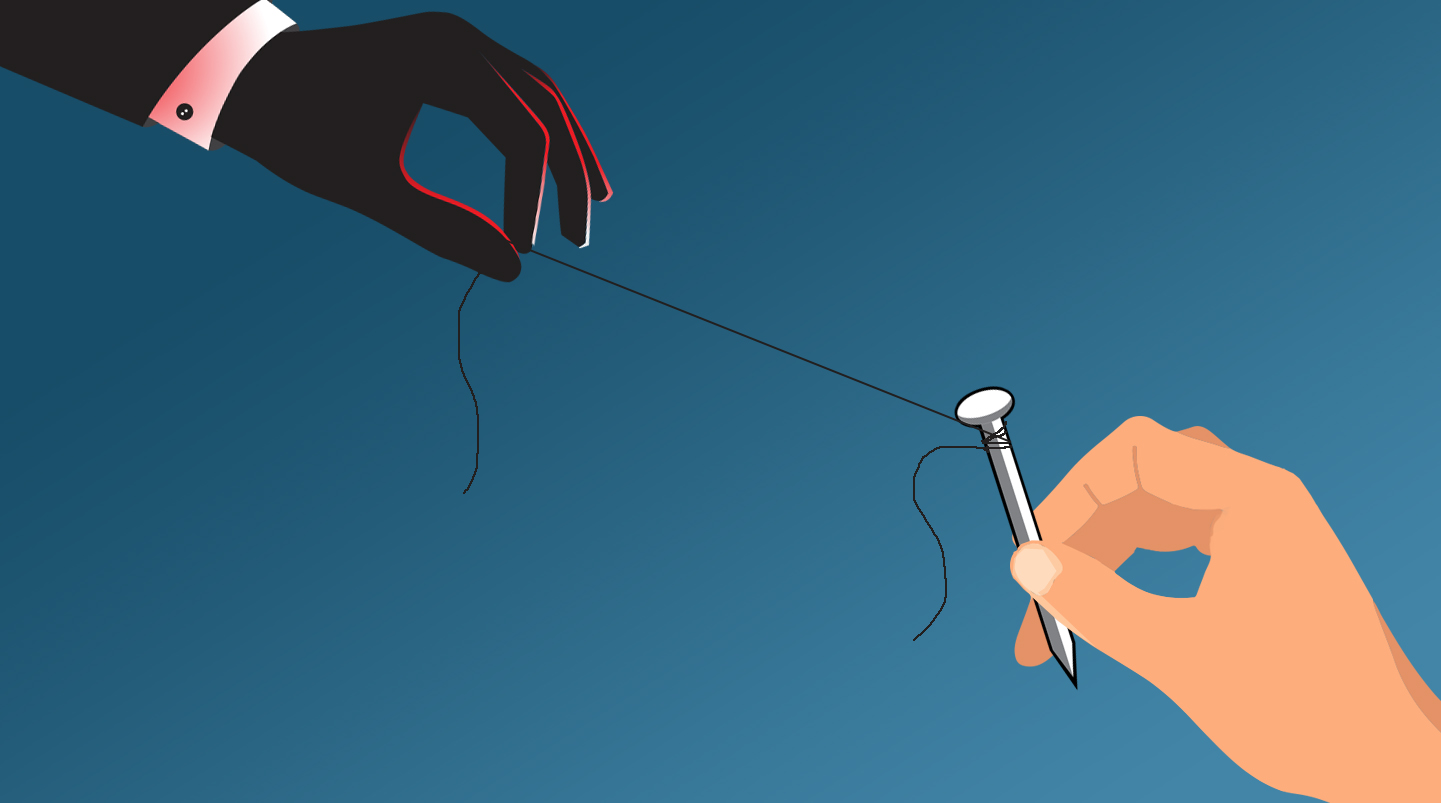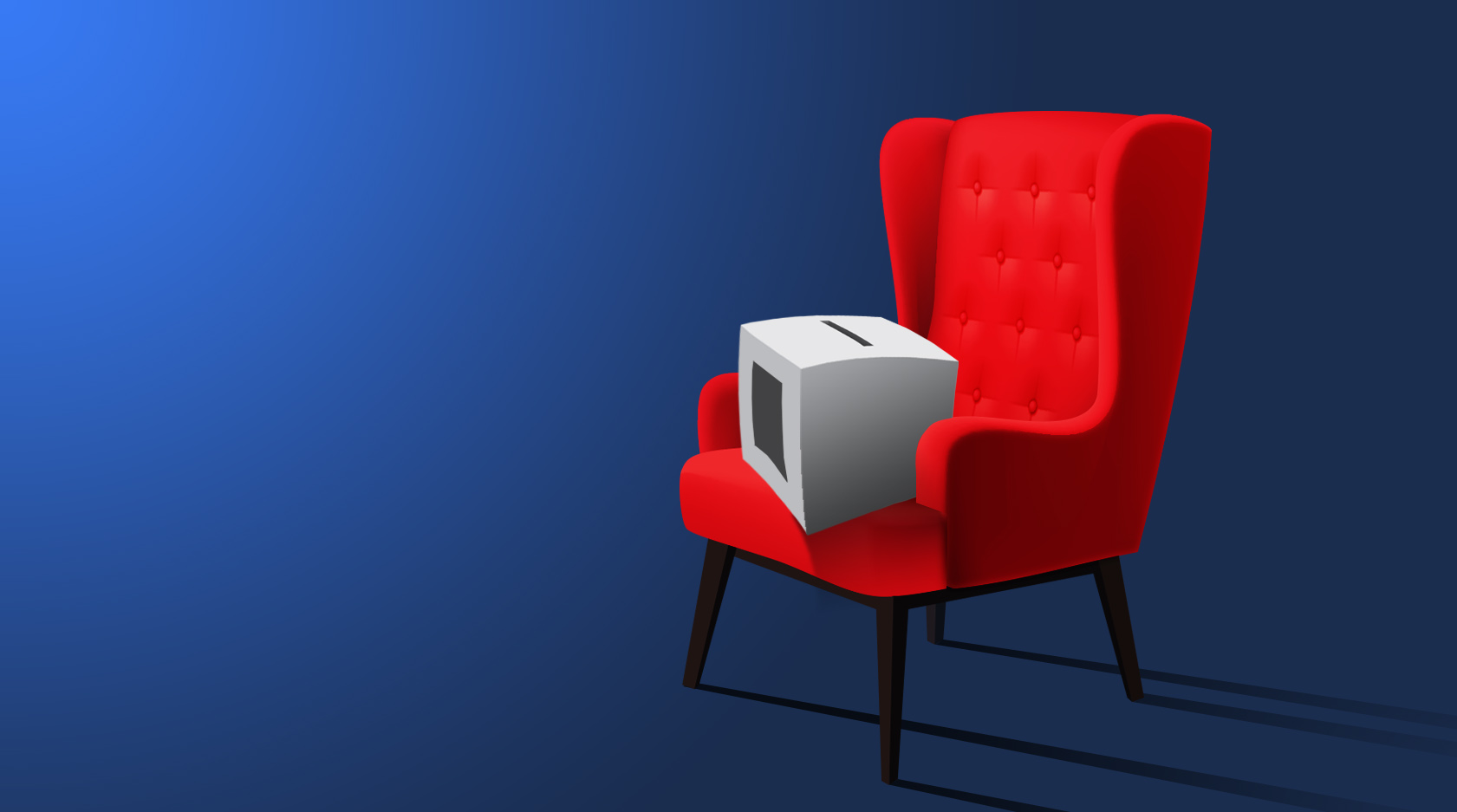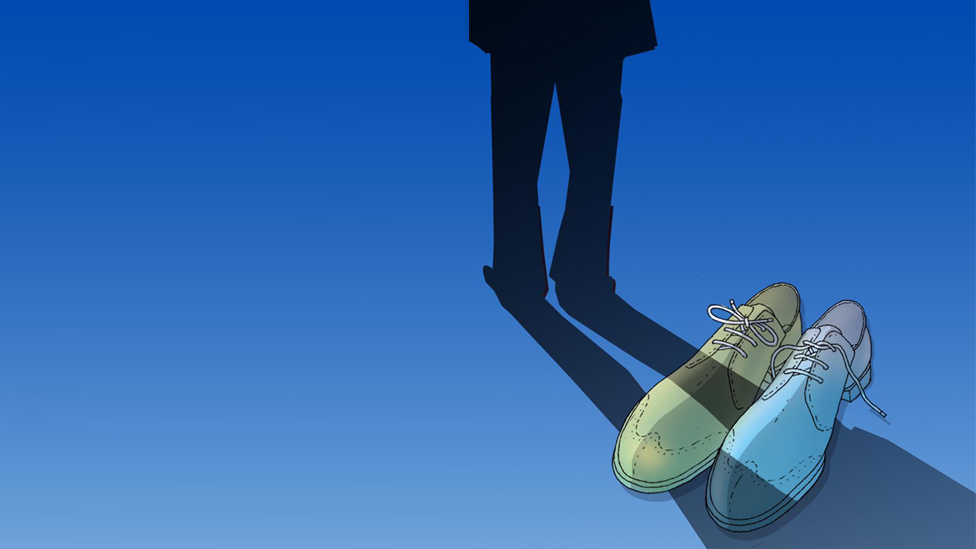Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Seno Gumira Ajidarma
PanaJournal.com
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sudjojono, Nasjah Djamin, dan Nashar adalah para pelukis yang pandai sekali menulis. Begitu juga Dullah. Keberuntungan Dullah, antara 1950 dan 1960, ia berstatus “pelukis Istana” yang selalu berada di dekat Sukarno sehingga dapat menulis catatan tentang Sukarno yang bergaya surat kepada Bibi Fatimah, istrinya. Surat-surat ini dimuat harian Merdeka edisi Minggu, dari 14 Maret 1982 sampai 22 Mei 1983, dan terputus sebelum tamat.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Terkumpul dalam buku Bung Karno: Pemimpin, Presiden, Seniman (2019), tampak Dullah membatasi sudut pandangnya untuk tidak berbicara apa pun tentang politik. Namun apakah dengan begitu lantas tidak ada wacana politik sama sekali dalam buku ini? Seperti pembuktian terbalik, hal itu bisa diperiksa ketika politik tidak ada, justru saat berpeluang mengungkapnya.
“Dullah, andaikata aku ini tidak terjun dalam politik, kalau tidak jadi dalang, ya, jadi pelukis,” kata Sukarno, yang memang pandai mendalang dan melukis (Susanto, 2009: 68). Sukarno juga membuat empat karikatur alias political cartoon, dengan nama Soemini, di harian Fikiran Ra’jat yang didirikannya setelah dibebaskan dari penjara Sukamiskin pada Mei 1932. Dalam menjalani pembuangan di Ende (1934-1938) maupun Bengkulu (1938-1942), tertulis 12 naskah drama yang kemudian dipentaskan dengan sutradara dan pemimpin produksi Sukarno sendiri.
Dalang, sutradara, pemimpin produksi, tidakkah ini kemampuan yang paralel dengan kelayakan politikus dalam posisi memimpin? Bagaimana dengan seni rupa? “Dullah, kalau Affandi dengan tangannya begitu rupa meremas dan mengolah tanah liat menjadi karya patung bermutu, itu tidak bedanya dengan aku mengolah rakyat.” (Susanto, 2009: 56). Diucapkan dengan sadar, kiranya sahihlah ditafsirkan sudut pandang Sukarno: berpolitik itu seperti berkesenian, dengan rakyat sebagai bahan mentahnya.
Adapun perbedaannya, tentu, bahwa rakyat, kumpulan bermacam manusia itu, tidaklah begitu mentah seperti tanah liat bagi patung. Bukan hanya berjiwa, tapi juga berpikir, sampai tahap kritis, dan berkemungkinan melawan dengan sedikit maupun banyak siasat. Kiranya di sanalah Sukarno diuji kemampuannya sebagai “seniman politik”, dan sejarah telah mencatat apa yang terjadi selama empat dekade pergulatannya dalam dunia politik. Dalam konteks buku Dullah ini, politik macam apa yang berlangsung selama 1950-1960?
Dullah menulis bahwa dirinya harus selalu siap dipanggil Sukarno, begitu rupa sampai ketika istirahat siang di tempat tidur pun tetap mengenakan sepatu. Sukarno selalu butuh ngobrol, terutama tentang seni, seperti kompensasi bagi apa pun yang berlangsung dalam dunia politik. Jika apa yang berlangsung selama 1950-1960 sebagai masa kesaksian Dullah ditengok, kronologi 1950-1959 (Demokrasi Liberal), dan 1959-1966 (Demokrasi Terpimpin), menjelaskan potongan masa tempat Dullah berada di pusarannya: setahun setelah Sukarno “memimpin demokrasi” di tangannya sendiri saja, Dullah tak lagi di Istana.
Disiplinnya untuk hanya berbicara tentang Sukarno dan seni justru menegaskan betapa pengetahuannya atas Sukarno bukanlah sisi kesenimanannya saja. Setidaknya dua kali Dullah mencatat, sebagai kolektor lukisan yang produktif dan bukan hanya konsumtif, Sukarno suka memilih sebuah lukisan untuk dicermatinya selama berjam-jam: “Kau tahu Dullah, di larut malam yang sunyi itu, apabila aku sendirian sedang merenungi sebuah lukisan, bukannya jarang di waktu itu timbul ide-ide penting yang berguna bagi negara.” (Susanto, 2009: 94).
Namun, dengan caranya sendiri, Sukarno tentu juga belajar dari Dullah, ketika dimintanya mengulang kisah-kisah tertentu dari Babad Tanah Jawi (1836) seperti berikut: Sunan Prawoto sedang berada di Pesanggrahan ketika seekor kerbau mengamuk dan tidak bisa diatasi. Baru hari berikutnya Joko Tingkir yang terusir dari Istana, dan tampak di antara kerumunan, dipanggil Raja Demak keempat itu. Joko Tingkir diberi janji, jika mampu membunuh kerbau itu, kedudukannya sebagai kepala prajurit Keraton Demak dikembalikan-dan Joko Tingkir berhasil.
Apa yang sebenarnya terjadi? Joko Tingkir diusir karena dengan arogan membunuh Dadungawuk, seorang pelamar untuk jadi prajurit yang kebal tapi ia ketahui kelemahannya. Mengetahui acara Sunan ke Pesanggrahan, adalah Joko Tingkir yang memasukkan tanah ke mulut kerbau itu sehingga amukannya tak teratasi. Dullah sendiri mengatakan kiasan yang tidak terkupas membuat maksud pujangga menjadi kabur. Betapa pun kiranya Sukarno terlalu cerdas untuk tak dapat membaca terdapatnya taktik bagi politik yang cukup licik.
Penyuntingnya, Mikke Susanto, menyebut isu desukarnoisasi pada dekade 1980-an sebagai “kemungkinan belum terbukti”, yang membuat surat-surat Dullah ini berhenti pemuatannya sebelum tamat. Begitulah wacana Sukarno akan selalu diikuti oleh bayang-bayang politik.