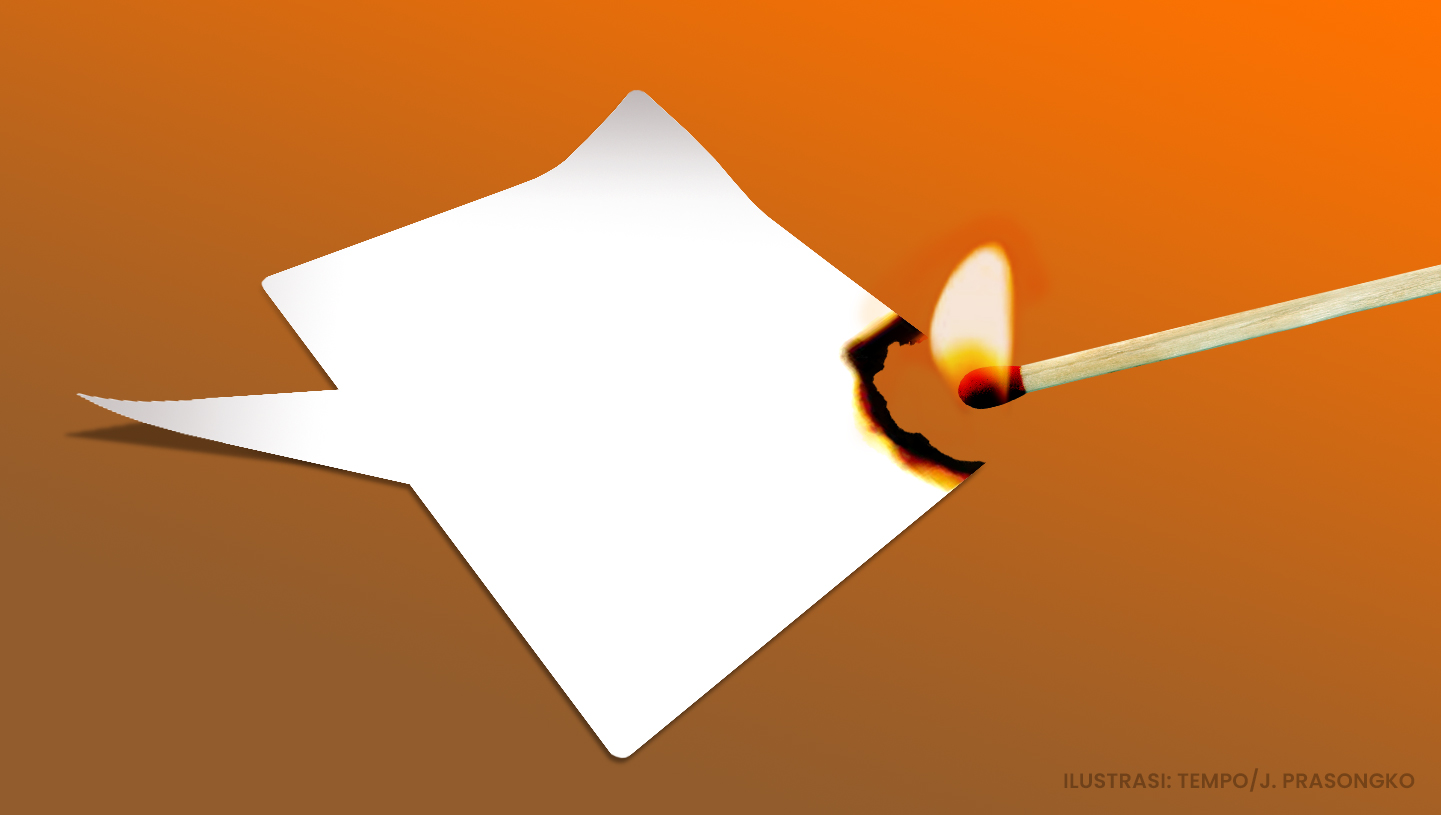Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang terdesentralisasikan pada daerah besar dan kecil. Pasal 18 Ayat (1) UUD 1945 (amandemen 2000) berbunyi: "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang."
Selama 55 tahun perjalanan RI, undang-undang yang mengatur pembagian kekuasaan negara dan daerah didasarkan pada asas klasik: desentralisasi, dekonsentrasi, medebewind (pembantuan), serta vrij bestuur. Pembagian ini diatur hierarkis berjenjang, mula-mula tiga: daerah tingkat I provinsi, daerah tingkat II kabupaten/kota madya, daerah tingkat III kecamatan/desa. Kemudian, dengan Undang-Undang No.5/1974 dan Undang-Undang No.22/1999, dijadikan dua: provinsi dan kabupaten/kota.
Undang-Undang No.22/1999, yang efektif sejak 1 Januari 2001, menyudahi "pakem" itu. Perubahan yang dianggap radikal adalah dihapusnya hierarki daerah tingkat I dan II. Seluruh wewenang diserahkan langsung kepada kabupaten atau kota yang merupakan titik berat otonomi, tanpa melalui provinsi. Menempatkan provinsi dan kabupaten/kota tidak lebih tinggi atau rendah menyalahi Pasal 18 UUD 1945 tentang pembagian daerah besar dan daerah kecil.
100 Dokumen Per Hari
Mendadak pusat berurusan langsung dengan 368 kabupaten dan kota. Dr. Ben Mboi, mantan gubernur NTT (1978-1988), takjub membayangkan rentang kendalinya. "Kalau setiap kabupaten menerbitkan 50 perda dan 50 keputusan sesuai dengan wewenang dan urusan yang ada pada mereka," katanya, "akan ada 36.800 dokumen yang harus dibaca dan diputuskan oleh Depdagri." Itu belum termasuk perda-perda yang dibuat oleh 30 provinsi. Maka, setiap hari akan ada seratus lebih peraturan dan keputusan daerah yang harus diputuskan ditolak atau diterima. "Ini pekerjaan suatu departemen tersendiri."
Ben Mboi melihat undang-undang yang dibuat pemerintahan transisi Habibie untuk mereformasi Undang-Undang No.5/1974 itu berpretensi mampu secara sempurna mem-bagi-bagi urusan tata usaha negara dalam satu dokumen. Memang, paradigma pemerintahan daerah tersebut selama 40 tahun terakhir dijalankan dengan kendali sentralistis. Tapi, menurut dia, mengubah kultur administrasi negara yang telah berjalan 55 tahun tidak bisa semudah membelah duren.
Salah-pikir Undang-Undang No.22/1999 terletak pada kelewat optimistisnya menyerahkan wewenang yang luas dan banyak kepada daerah, tanpa memperhatikan heterogenitas, daya dukung, dan kompetensi mereka. Kabupaten di luar Jawa tidak sama bobot dan semangatnya dengan kabupaten di Jawa, yang punya tradisi kekuasaan bupati dan adipati sejak masa kerajaan-kerajaan lama serta berotonomi sejak awal desentralisasi Hindia-Belanda. Kabupaten-kabupaten di luar Jawa kebanyakan administratif dan lebih muda, apalagi yang baru dimekarkan. Kadar kompetensi mereka benar-benar perlu dipertimbangkan.
Di satu sisi, motivasi di balik Undang-Undang No.22/1999 itu karena kekhawatiran, takut satu per satu akan melepaskan diri kalau wewenang penuh diberikan kepada provinsi. Namun, di sisi lain, tanpa terpaut supervisi dan kontrol provinsi, ia akan melahirkan raja-raja kecil di kabupaten. Padahal di negara mana pun otonomi itu, "Berjenjang naik, bertangga turun," kata Dr. Mochtar Naim, anggota Badan Pekerja MPR. Dimulai dari tingkat provinsi, berurut ke bawah sampai ke tingkat desa sekalipun.
Pelayanan Publik?
Titik berat desentralisasi Undang-Undang No. 22 lebih pada dimensi teritorial ketimbang fungsional. Tiada rincian tentang fungsi spesifik apa yang didesentralisasi, apa yang masih diemban pusat. Bila yang dikedepankan adalah fungsi pelayanan kepentingan publik, bukan kepentingan daerah, titik berat itu bisa berada di provinsi, bisa di kabupaten, bisa pula di kecamatan dan desa. Bukan di pusat. Masalah kesehatan, misalnya, sangat dekat pada rakyat. Maka, puskesmas yang cepat dijangkau rakyat menjadi urusan kecamatan.
Tanpa uraian fungsi, akan timbul penafsiran sepihak dan nafsu daerah-daerah titik berat untuk mengambil fungsi sebanyak-banyaknya. Yang diincar tentunya yang ada duitnya. Bagaimana aturannya bila daerah ternyata tidak becus karena fungsi itu melampaui daya pikul mereka, lalu terjadi kemacetan dalam pelayanan publik? Undang-undang menyatakan, kalau kabupaten tidak mampu, pekerjaan itu diserahkan kepada provinsi (kontinjensi).
Dalam kapasitas apa provinsi menampung "limbah" itu? Daerah besar otonom? Keranjang sampah? Sesungguhnya asas-asas desentralisasi, dekonsentrasi, medebewind, dan vrij bestuur serta pelimpahan wewenang berjenjang itu adalah jaring pengamannya.
Kewenangan dapat dirinci satu per satu. Tapi tidak ada satu pun undang-undang yang mampu memprediksi masalah-masalah kemasyarakatan yang berkembang sangat dinamis. Diadakanlah asas vrij bestuur. Intinya: kalau ada keragu-raguan tentang siapa yang berwenang terhadap suatu masalah, dengan azas vrij bestuur daerah yang terdekatlah yang mengambil wewenang itu. Dalam situasi Indonesia yang sangat rumit sekarang ini, Undang-Undang No. 22 malah meniadakan vrij bestuur.
Provinsi dan kabupaten mempunyai kewenangan kelautan yang ternyata telah menimbulkan benturan antarwarga antarkabupaten. Namun Undang-Undang No. 22 alpa tentang sungai dan danau, yang jelas berkaitan dengan kepentingan ekonomi dan lingkungan, yang membutuhkan penanganan serius dan berkelanjutan. Mereka malah menebang hutan, mengusik pesut dan bekantan, demi uang.
Undang-Undang No.22/1999 tentang Pemerintah Daerah menghidupkan kembali desa (atau yang disebut dengan nama lain) yang mempunyai susunan asli ke dalam subsistem pemerintahan. Ini berarti membangun lagi masyarakat hukum adat serta kepemimpinan adat.
Pertanyaannya: apakah mereka masih ada setelah 40 tahun dimatikan? Bagaimana relasi masyarakat (berdasarkan) hukum lama itu dengan masyarakat hukum yang dibentuk dengan stratifikasi provinsi-kabupaten-desa?
Hindia Belanda dulu membuat undang-undang masing-masing untuk desentralisasi ala Barat dan otonomi daerah berdasarkan hukum asli Indonesia. Suku-suku (dan nilai budayanya) yang dominan mendiami suatu daerah juga menjadi dasar pembagian wilayah administrasi. Negara Kesatuan RI yang berpaham kebangsaan mewarisi amalan yang telah berjalan seratus tahun ini. Undang-undang yang berlaku sekarang pun menempatkan faktor sosial-budaya, struktur sosial, dan pola budaya setempat sebagai pertimbangan dalam pembentukan dan pemekaran daerah (Pasal 5 Undang-Undang No.22/1999 dan Pasal 3 dan 6 PP No.129/2000).
Isu Minoritas Baru
Bagaimana kita menjaga agar keinginan untuk menerapkan susunan masyarakat asli dan hukum adat itu tidak bertabrakan dengan paham kebangsaan dan kesatuan kita? Bagaimana membangun pagar-pagar hukum formal yang lebih tinggi untuk menjaga otonomi adat asli agar tidak menciptakan minoritas baru, yaitu golongan kecil yang bukan bagian dari etnis di situ? Bagaimana menjamin mobilitas sosial, mobilitas ekonomi setiap warga negara ke setiap pelosok Indonesia? Sekarang saja kabupaten sudah diterjemahkan sebagai suku.
Di satu sisi, kita ingin memberdayakan masyarakat daerah agar jangan terpinggirkan, tapi di lain pihak ia menciptakan warga pinggiran yang baru. Tengoklah kejadian ketika sesama warga negara RI diperlakuan diskriminatif dalam penerimaan dan pengangkatan pegawai di pemerintahan setempat. Karena dia bukan "putra daerah", seorang pegawai akan dikesampingkan dalam promosi jabatan, sementara seorang "putra daerah"?tanpa peduli golongan pangkat dan kemampuannya?diangkat untuk jabatan itu.
Itu semua menyarankan dibuatnya satu undang-undang pokok yang secara umum mengakui adanya kekhasan yang murni lokal pada setiap provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, masyarakat hukum adat (seperti pesan Pasal 18b UUD 1945). Di samping undang-undang pokok itu, perlu diterbitkan undang-undang organik untuk tiap provinsi beserta daerah-daerah kabupatennya, sampai desa-desanya dengan ciri khas dan kemurnian lokal masing-masing. Dalam undang-undang pembentukan provinsi itu sekalian dirinci pembagian hak dan wewenangnya yang sesuai dengan kekhasan tersebut.
Masih perlukah daerah istimewa atau daerah khusus? Tidak, karena setiap undang-undang pembentukan provinsi sudah mengandung kekhasan masing-masing. Sebab, semua punya kekhususan, masing-masing daerah menjadi istimewa dibanding lainnya. Jadi, bukan hanya Aceh yang punya Undang-Undang Nangroe Aceh Darussalam, bukan hanya Papua yang punya Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Pembagian kekuasaan negara RI galibnya asimetris, entah ia unitaris ataupun federalis.
Revisi Abad Ke-21
Undang-Undang No.22/1999 mau menyelesaikan sekaligus semua masalah dan dibuat secara terburu-buru demi merebut kepercayaan rakyat dan menenangkan daerah yang ingin memisahkan diri. Namun, ketika datang pemerintahan baru hasil pemilu, undang-undang itu segera diganti lagi. Ben Mboi, anggota tim revisi Undang-Undang No. 22, menyarankan agar revisi itu jangan juga terburu-buru.
Revisi undang-undang itu hendaknya di-lakukan dengan visi abad ke-21. Pertanyaan pokoknya misalnya: apakah konsep tiga lingkaran masih tepat untuk mengatur hubungan pusat-daerah dalam pembagian kekuasaan negara? Ini perlu pembandingan dengan pengalaman negara lain dan kearifan yang pernah ada dalam sejarah kita.
Sementara itu, yang bisa dilakukan saat ini adalah memeriksa semua peraturan dan keputusan daerah yang telah dikeluarkan untuk mengidentifikasi mana yang cocok dan mana yang tidak tepat. Dari situ bisa dirumuskan masalah-masalah yang bisa didalami untuk memperbarui undang-undang.
Daerah-daerah perlu disadarkan untuk hanya mengambil beberapa urusan yang benar-benar mampu mereka jalankan. Urusan-urusan lain di luar daya-pikulnya, sekalipun itu wewenangnya, dikembalikan atau "dititipkan" dulu untuk dikerjakan oleh pusat atau provinsi.
(*Dari percakapan dengan dr. Ben Mboi, mantan Gubernur NTT, dan kumpulan tulisan Dr. Mochtar Naim , anggota BP MPR utusan daerah Sumatra Barat)
Daud Sinjal
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini