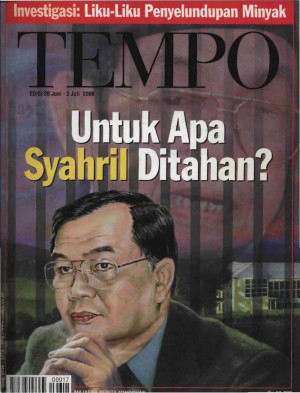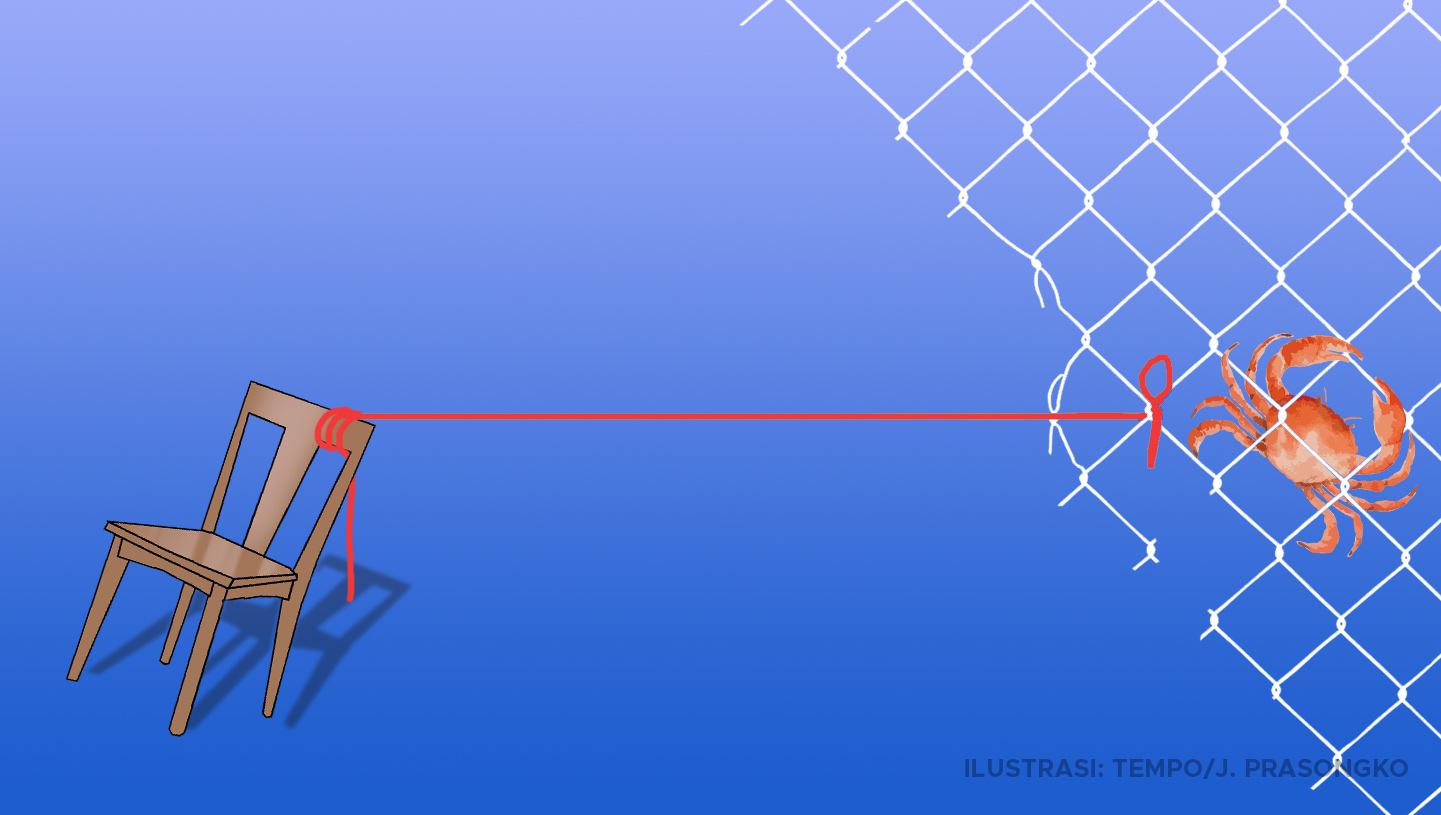Akhirnya, pemerintah pusat turun tangan juga di Maluku, dengan menerapkan keadaan darurat sipil yang mengacu kepada undang-undang lama, UU Nomor 23/Prp/1959. Apa boleh buat, walau pemerintah dan DPR sudah berhasil membuat UU PKB pada zaman pemerintahan B.J. Habibie, karena mendapatkan banyak kecaman saat itu, UU ini belum diundangkan oleh pemerintah, meski sudah disetujui DPR.
Keputusan untuk menentukan darurat sipil yang efektif berlaku pukul 00.00 WIT 27 Juni lalu itu sebenarnya sudah sangat terlambat. Ratusan orang—atau mungkin benar ribuan—sudah tewas, ribuan pengungsi dalam keadaan memprihatinkan di tenda-tenda darurat, bahkan ada 400 lebih pengungsi yang hilang ditelan ombak bersama kapal yang mengangkutnya. Kepedihan tak terkira sudah dilalui, tanah air sudah jadi bergelimang air mata, sebagaimana ditulis dalam sajak Tanah Air Mata oleh penyair Sutardji Calzoum Bachri. Setelah sekian banyak kepedihan dilalui, baru sekarang ini ada langkah nyata dari pemerintah pusat. Bagaimanapun, kita perlu mendukung keadaan darurat sipil ini. Cuma, kita hanya perlu mengingatkan pemerintah bahwa status darurat sipil itu harus diperlakukan hati-hati, tidak boleh dipakai di sembarang tempat tanpa alasan yang kuat. Untuk kasus Maluku, alasan itu sudah sangat kuat.
Kenapa untuk Maluku keadaan darurat sipil ini sesuatu yang penting, dan sesungguhnya sudah sangat-sangat terlambat? Karena saling bunuh di Maluku, antar sesama bangsa, sudah berlangsung pada Januari 1999. Sopir angkot asli Ambon beragama Kristen itu bertengkar dengan pemuda Bugis yang kebetulan muslim. Barangkali tak ada lagi yang ingat siapa kedua orang itu, mungkin namanya Jacob, atau Usman, atau Salim, atau Yohanes. Tapi dari pertengkaran kecil antara kedua orang itu, perkelahian terjadi. Mula-mula percekcokan kecil, lalu meluas, meluas lagi, dan kini "perang saudara" sudah tak bisa lagi diatasi oleh rakyat Maluku sendiri. Seandainya saja pertengkaran itu bisa ditangani lebih awal, dilakukan tindakan tegas kepada sopir angkot dan pemuda Bugis itu, lalu tindakan tegas kepada para perusuh, situasinya tidak akan separah ini. Apa yang terjadi sekarang ini karena tak ada penyelesaian cepat. Lalu, spiral kekerasan terus memuncak dan kian berdarah. Hukum sudah dilecehkan oleh semua orang. Inilah sebuah pelajaran terpenting dari kasus Maluku, di mana pemerintah pusat selalu bilang dengan enteng: kasus Maluku harus diselesaikan oleh orang Maluku.
Orang-orang Maluku sudah jelas tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, ketika kasusnya menjadi besar begini. Pernyataan Presiden Abdurrahman Wahid bahwa kasus Maluku hanya bisa diselesaikan oleh orang Maluku sendiri adalah cermin dari sikap lepas tangan pemerintah pusat. Dalam konflik horizontal (seperti antaragama di Maluku), mereka yang terlibat tak akan bisa menyelesaikan konflik itu. Mereka memerlukan penengah yang adil dan punya otoritas serta kredibilitas. Dan penengah seperti itu umumnya adalah instansi atau lembaga yang lebih tinggi. Dalam kasus yang terjadi di tingkat provinsi, yang bisa menjadi penengah seperti itu tentulah pemerintah pusat.
Kita bisa mengambil analogi kasus lain: konflik antaranegara bagian di Yugoslavia, yang hanya bisa ditengahi oleh otoritas yang lebih tinggi, yakni Uni Eropa, dan bahkan PBB. Dalam kasus ini bahkan kemudian digelar mahkamah internasional untuk mengadili para pelanggar hak asasi, siapa pun mereka. Hukum ditegakkan. Dengan mengambil contoh kasus Yugoslavia, pernyataan Amerika Serikat bahwa pihaknya menawarkan diri untuk menjadi penengah dalam konflik di Maluku menjadi sesuatu yang logis. Begitu pula keprihatinan Sekjen PBB juga sesuatu yang wajar. Tetapi, jika kita tersinggung dengan tawaran AS itu, dan jika kita tak ingin negara lain mencampuri urusan kita, marilah kita atasi secara tuntas kasus Maluku. Bangsa Indonesia sendirilah yang harus menghentikan pertumpahan darah di Maluku, rakyat dari Sabang sampai Merauke. Sekali lagi, kita tak bisa menyerahkan kepada orang Maluku sendiri untuk menyelesaikan konfliknya.
Tentu saja status darurat sipil belumlah cukup. Ini baru langkah awal. Langkah berikutnya adalah penguasa darurat sipil harus menjadi penengah yang adil. Ada baiknya, semua petinggi di Maluku yang menjabat selama konflik itu terjadi diganti dengan orang-orang baru. Tugas "penguasa baru" ini yang pertama-tama adalah memisahkan kubu-kubu yang sedang konflik (Islam vs Kristen) dalam garis demarkasi yang jelas. Jika perlu, mereka harus dikelompokkan dalam wilayah yang jelas batasnya. Ini mungkin sulit dan memakan waktu, karena pada masa lalu penduduk Islam dan Kristen bercampur, bahkan mereka sebenarnya masih berhubungan keluarga. Namun, setelah saling bunuh terjadi, percampuran itu pasti terganggu. Kita bisa ambil contoh dua orang saudara yang berkelahi, yang pertama-tama bisa kita lakukan sebagai penengah adalah memisahkan mereka. Setelah mereka pisah, baru kita ajak omong masing-masing, apa masalahnya, apa tuntutan dan permintaannya, lalu bagaimana menyelesaikan masalah. Penyembuhan dendam sudah pasti akan makan waktu lama. Prinsip dari pemisahan ini adalah untuk pertama-tama menghentikan banjir darah, baru setelah itu dilakukan dialog rujuk. Aparat keamanan bisa masuk ke kedua kubu untuk menjadi mediator dialog, sembari merampas senjata yang masih dikuasai penduduk. Tapi aparat keamanan jangan larut di salah satu kubu.
Karena itulah, "pasukan perdamaian" yang dikirim pemerintah pusat itu harus adil, tanpa pandang bulu, serta disegani kedua pihak. Dan hanya dengan demikian dia mampu menjadi penengah yang baik. Mari kita akhiri kasus Maluku—tragedi yang mengingatkan sajak Sutardji Calzoum Bachri: Tanah Air Mata —secara bersama-sama, dan menjadi tugas semua anak bangsa, bukan hanya tugas Nyong Ambon.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini