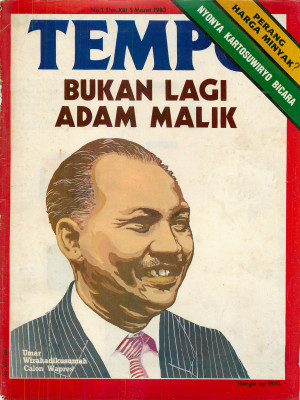IA seorang Zionis. Nenek moyangnya lari dari Negeri Belanda
ketika Spanyol menduduki tanah rendah itu dan orang Yahudi
diburu atas nama Kristus. Ia sendiri lahir di Ukraina, tapi
kemudian - belum lagi berumur 10 - ia harus ikut mengungsi pula
ke Argentina.
Jacobo Timmerman karena itu punya alasan buat merindukan sebuah
tanah air, sebuah tanah air yang tak membiarkan satu kaum
membasmi kaum lainnya atau menyimpannya di pojok terpisah. Ia
seorang Zionis yang pada dasarnya seorang demokrat dan sosialis,
yang menjadi demikian sejak umur belasan tahun. Ia memilih
sebuah dunia yang nampaknya tak bakal tenteram.
"Sebuah dunia yang kadang mengambil bentuk Zionisme, kadang
perjuangan hakhak asasi manusia, kadang pergulatan untuk
kemerdekaan bicara, dan kadang juga solidaritas dengan para
pembangkang yang melawan semua totaliarianisme." Begitulah
Timmerman merumuskan kehidupan yang ia pilih dan tak akan ia
tinggalkan.
Mungkin karena itu, seraya memuja Israel, tetap tinggal di
Argentina yang penuh kontroversi. Ia memang ternyata jadi
wartawan terkemuka. Korannya, La Opinin, cepat jadi makmur
dengan oplah 150 ribu. Timmerman toh tetap seorang sosialis.
Tapi pendiriannya yang kiri-tengah dengan segera memakunya pada
kesulitan di Argentina yang robek oleh konflik dan luka oleh
teror.
Ia jadi sasaran dari kiri serta kanan. Juli 1972 rumahnya dibom
kaum Montoneros yang ultra-kiri. April 1977 ia ditahan
pemerintah militer yang pro-kanan. Ia nyaris jadi salah satu
desaparecidos, orangorang yang lenyap. Tapi ia begitu terkenal,
meskipun ia menuliskan pengalamannya dalam sel dengan judul
"Tahanan Tanpa Nama, Sel Tanpa Nomor". Tak kurang tokoh seperti
Henry Kissinger dan Alexander Solshenitsyn yang ikut mendesak
pemerintah Argentina buat melepaskannya.
25 September 1979 ia memang dibebaskan. Tapi dengan cara yang
khas: Timmerman dimasukkan ke alam sebuah pesawat terbang, dan
langsung dikirim ke Israel. Statusnya sebagai warganegara
Argentina dicopot.
Kita mungkin menyangka bahwa Timmerman akhirnya jadi berbahagia,
satu perasaan yang konon tak perna drasakannya. Bukankah ia
telah meninggalkan sebuah negeri, di mana, seperti
dituliskannya, "kaum Peronis membunuh kaum Peronis, militer
membunuh militer, anggota serikat buruh membunuh anggota serikat
buruh ...."? Bukankah ia telah berada di Israel, dan berkata,
"Akhirnya saya pulang"?
Tapi rupanya kasus Timmerman bukanlah kasus seorang yang mencari
tempat teduh. Seperti konon diucapkan novelis Israel Amos Oz
kepadanya waktu ia tiba, manusia tak perlu berbahagia. Juga tak
dapat. Timmerman kemudian tahu makna kata-kata itu. Bulan Juni
1982, Israel menyerbu Libanon.
Ia, yang menyangka bahwa bangsa yang pernah jadi korban Hitler
tak akan tega mengebom Beirut, ternyata khilaf. Bukunya, The
Longest War, mengungkapkan perasaan seorang pencinta yang
gemetar oleh kecewa, amarah, kecemasan.
Apalagi buku itu sempat mencatat peristiwa yang tersohor itu:
ketika anak kecil dan orang tua Palestina - hanya lantaran
mereka orang Palestina - dibunuhi kaum Phalangis di Sabra dan
Chatilla, dengan restu tentara Israel. Timmerman mengungkapkan
apa yang akhirnya menimpa bangsa Yahudi yang terserak-serak:
mereka tak lagi akan punya hak penuh untuk jadi lamban
keDedihan abad ini.
"Kita adaah korban yang telah menciptakan korban kita sendiri,"
tulis Timmerman. "Mulai sekarang, untuk seterusnya, tragedi kita
akan tak dapat terpisahkan dari tragedi orang Palestina."
Mungkin seharusnyalah demikian. Israel yan disaksikannya memang
telah menyebabkan ketidakterpisahan itu kabur, karena Israel
yang diimpikannya ternyata telah jadi gunung api kekuasaan,
dengan kekeian seperti negeri yang lain.
Syahdan, beberapa jam sebelum pertempuran meletus di Beirut,
penyair Palestina, Mahmud Darwish, berkata kepada wartawan Roer
Rosenblatt dari majalah Time: "Israel adalah kubur bagi
kebesaran Yahudi." Tapi Darwish juga cemas: bila suatu hari
nanti orang Palestina mendapatkan tanah air mereka, hal yang
sama akan bisa terjadi.
Adakah tanah air proyek kebahagiaan yang mustahil, karena
manusia tak perlu berbahagia dan lagi pula tak dapat? Tapi
soalnya bukan itu, kita akan menjawab. Soalnya bukanlah perlu
berbahagia, melainkan perlu adil. Tapi kita toh mencari bahagia
dan mencari tanah air dan tak sadar bahwa karena itulah kita tak
dapat. Tak dapat, seperti Jacobo Timmerman.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini