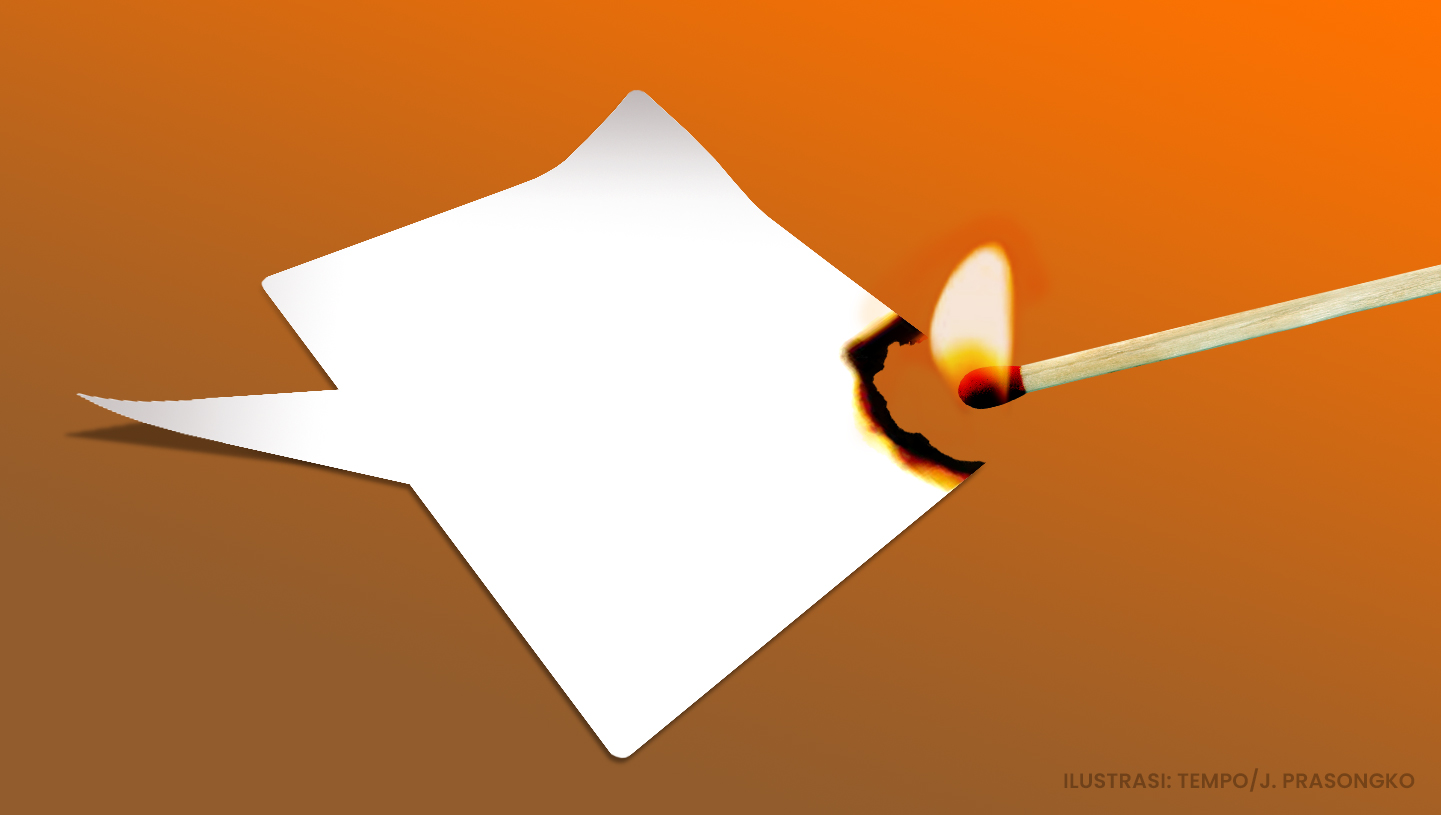Tradisi Baru PUTU WIJAYA PADA tahun 1968 Taman Ismail Marzuki (TIM) berdiri di Jakarta. Berbagai cabang kesenian mendapat doping. Kesempatan bernapas, tumbuh, berkembang, bertapa, bereksperimen, bergaya, berulah, berkoar, memberontak, membabi buta, dan juga kumpul kerbau. Seni tradisional- seni rakyat ataupun seni adiluhung- baik seni modern lokal maupun asli mancanegara, ada main. Main mata. Main-main. Main belakang. Tak terkecuali main kayu. Mereka saling pasang kuda-kuda. Aksi. Beberapa tahun hanya pandang-pandangan. Kemudian mulai salam-salaman. Saling mengenalkan diri dan menerima perkenalan. Bersenggolan, bersentuhan. Diikuti dengan raba-rabaan di mantan kebun binatang itu. Terjadi pergaulan bebas. Tawar-menawar. Saling mempengaruhi, berdialog, kadangkala bersaing, dan saling hendak mendesak-mengalahkan. Akhirnya, kawin buat yang tak dapat menahan nafsunya lagi. Ada rumah tangga, ada yang hanya hidup bersama. Ada juga hanya kumpul sebagai kongsi, teman hidup. Tetapi, tak urung, tak dapat dicegah, TIM berbadan dua lalu melahirkan anak. Melahirkan keturunan. Ada yang tetap asli, ada yang belasteran, yang bermata biru, merah, atau kuning. Ada yang bule. Tim kemudian bukan lagi hanya taman, tetapi asrama. Dalam prakteknya taman itu jadi museum hidup sekaligus laboratorium dan juga pasar. Di dalam bekas "kandang-kandang binatang" itu, terjadi hubungan rahasia. Seni rupa, seni sastra, seni teater, seni musik, seni tari, bahkan juga film, hidup dalam satu kurungan tanpa sekat-sekat. Kehidupan anak kolong, yang dihuni seni pribumi (tradisional, seni rakyat, dan seni kontemporer) dan seni dari mancanegara (baik Barat maupun Timur) merupakan peristiwa kontak badan dan kontak rohani. Semacam pertapaan. Dampaknya banyak. Pertemuan itu menimbulkan arus interaksi yang deras. Mula-mula tak jelas arahnya. Kabur dan sekaligus juga ngawur. Tetapi, kemudian muncul hasil-hasil karya yang aneh dalam berbagai cabang kesenian. Mengejutkan karena tradisional tetapi juga modern, atau modern tetapi juga tradisional. Hasil-hasil kesenian yang lahir akibat pergaulan bebas itu, baik yang baru gres maupun yang lama tapi dibarukan, baik yang mapan maupun yang eksperimental, menciptakan satu era baru. Sebuah spektrum warna. Sebuah fenomena. Sebuah penegasan munculnya perilaku, perlakuan, sikap, dan nilai-nilai yang baru. Sebuah tradisi baru. Semangat untuk menerima keberadaan semua hasil karya seni di Indonesia, tanpa membeda-bedakannya. Memberikannya hak hidup yang sama menurut jenis, tempat, ladang, kubu perjuangan dan tata nilai masing-masing. Ada karya-karya baru di bidang teater. Karya-karya yang memantulkan identitas Bali, Jawa, Sunda, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan sebagainya, tapi dalam satu format lain. Karya-karya yang bukan lagi hanya lahir dari ide-ide tentang sebuah Indonesia, tetapi ekspresi kongkret Indonesia. Kalau pencipta tari Bagong Kussudiardjo, misalnya, sudah lama mencoba menggabungkan berbagai unsur-unsur tari dari seluruh pelosok Nusantara, seni tradisi baru ini sudah sampai pada tahap bukan hanya kolase tetapi peluluhan. Banyak orang mencoba menempatkan kelahiran karya-karya teater itu sebagai hasil pengaruh dari Barat karena mereka berpendapat bahwa kiblat "seni pergaulan bebas" itu adalah Barat. Akibatnya, mereka menolak untuk memberikan pada hasil karya itu label Indonesia- sebagaimana sudah mereka berikan pada seni tradisi, teater Bali dan Jawa, misalnya. Di dalam teater, karya-karya Rendra, Arifin, Sardono, Danarto- sekadar menyebut contoh- tak pernah dipropagandakan atau dibanggakan secara resmi sebagai buatan Indonesia. Walhasil, teater kontemporer Indonesia menjadi anak tiri kalau tidak bisa dikatakan anak haram jadah. Bahkan ada kesan bukan bagian dari Indonesia tetapi kuman-kuman dari seberang lautan yang membawa wabah. Sudah sering terjadi kekeliruan telaah terhadap karya teater dan seni Indonesia karena selalu hendak "diabdikan" atau "dipetakan" pada tuannya di Barat. Hubungan gelap mereka dengan Barat pastilah ada. Tetapi, hubungan darah ke akar tradisi pun kongkret. Keteleran para kritikus menyebabkan teater dan atau kesenian Indonesia hanya gema kentut-kentut yang meledak di bagian barat dunia. Seni pertunjukan, naskah drama, sastra, seni rupa, tari, musik Indonesia, kalau diusut, ditata, atau dipetakan dengan Barat sebagai moyangnya apalagi nabinya bisa berbeda sekali seandainya dipreteli dengan nenek-kakeknya di Indonesia. Memang ada hasil seni Indonesia yang tidak bisa tidak harus direlakan sebagai keponakan Barat, karena memang bule. Pastilah bapak atau ibunya dari "sono". Tetapi memukul rata "bule dan belasteran" itu sebagai satu-satunya tampang minimal mayoritas kesenian Indonesia adalah kejam. Kata orang Jawa tuman, alias mau gampangnya saja. Teater Indonesia bukan-lagi-hanya puncak-puncak teater daerah atau tradisional di masa lalu. Tapi seluruh keramaian yang ada. Seluruh pasar yang ada. Seluruh lalu lintas yang hidup. Termasuk hasil peluluhan, tradisi baru itu. Dalam tahun Kesenian Indonesia di Amerika, KIAS- tahun lalu dan tahun ini -- kesempatan untuk membuat "KTP baru" terbuka. Wajah kita yang macam mana akan muncul? Wajah seorang penjual pisang goreng yang tersenyum supaya pembeli mau singgah. Atau wajah memelas seorang anak aleman yang minta dimanjakan. Atau wajah primitif yang ingin menjaring perasaan haru karena keterbelakangan memang bisa mempesona orang gedongan. Pameran akbar KIAS bisa benar-benar menjadi "diplomasi budaya", sebuah "peristiwa budaya". Memperkenalkan Indonesia seutuhnya, atau hanya kepingan-kepingan masa lalu yang diawetkan. KIAS bisa menjadi peristiwa menempelkan wajah: yang orang lain inginkan menempel di wajah kita, ataupun wajah yang kita mimpikan layak sebagai wajah kita. Atau wajah kita di wajah kita sekarang saja. Semoga pikiran sesat tidak ikut ambil bagian. KIAS sebuah kesempatan langka untuk membuat tradisi baru. Sudah saatnya menampilkan wajah kita yang sebenarnya. Menurut keadaan kita. Bukan wajah menurut pesanan para turis yang haus tontonan "asli", ataupun kerinduan para "ahli" yang lapar obyek penyelidikan yang masih "murni". Sudah saatnya untuk mengenalkan diri dalam format yang sebenarnya. Ke-"aslian" yang semata-mata hanya untuk memburu puji-puji sudah kedaluwarsa, tidak representatif lagi. Kolom ini disajikan dengan kerja sama Mobil Oil Co. untuk menyambut KIAS.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini