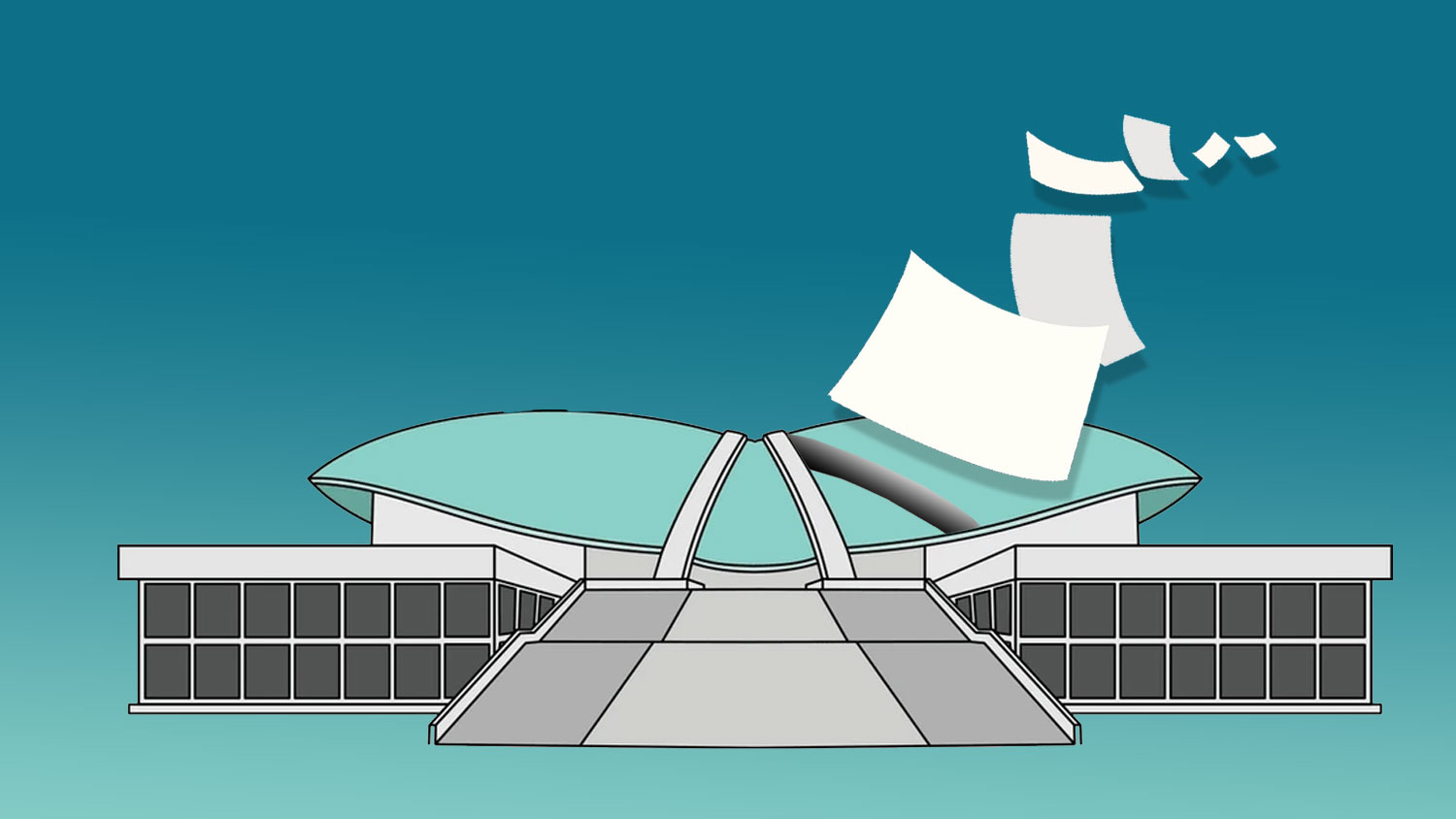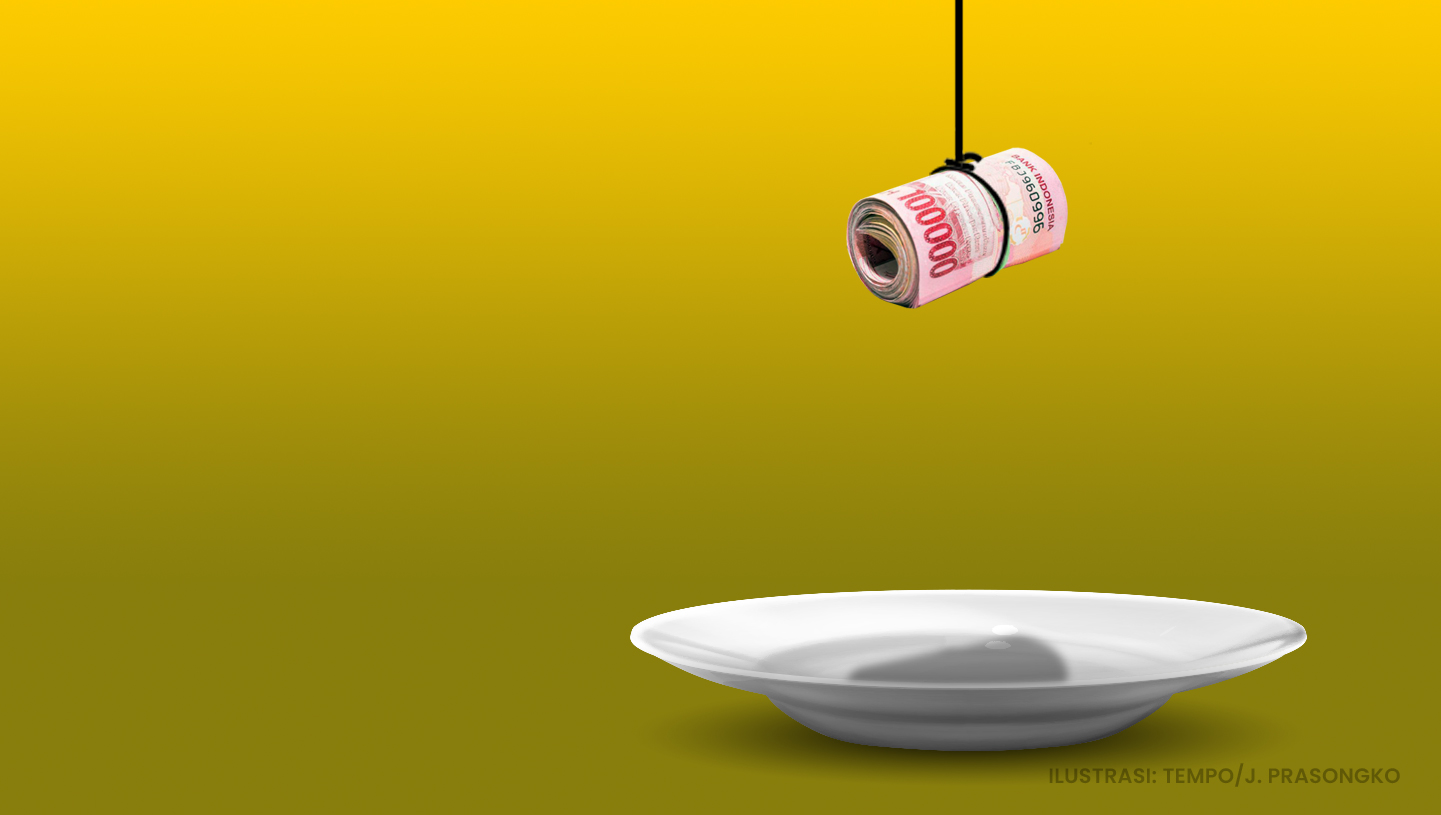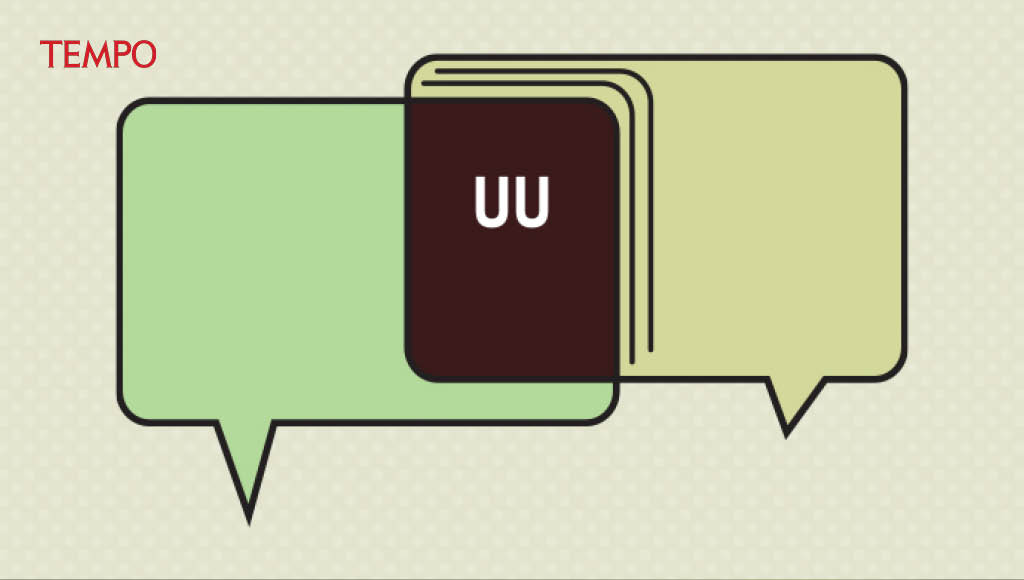KINI semakin jelas, bila ekonomi rusak, ia tidak rusak sendirian. Bersamaan dengan itu juga hukum. Sebaliknya, jika hukum rusak, ia juga tidak rusak tanpa dampak. Pemerintahan Soeharto boleh bangga bahwa di bawah kemudinya, ekonomi Indonesia maju. Namun ia tak bisa menutup mata bahwa di bawah kekuasaannya hukum hancur. Akibatnya: kehancuran itu merembet ke ekonomi. Maka, siapa yang tak melihat bahwa ekonomi yang baik memerlukan hukum yang baik akan tersesat dalam mencari jalan ke luar perbaikan keadaan sekarang.
Ada dua tema dalam cerita hubungan hukum dan ekonomi itu. Yang pertama adalah mereka yang mengutang—dan tak membayar kembali—dana-dana dari bank pemerintah. Yang paling mencolok ialah dua anak bekas presiden Soeharto, Bambang Trihatmodjo dan Tommy Soeharto. Jumlah utang mereka mencapai Rp 28 triliun (jumlah yang seandainya dibebankan kepada setiap penduduk Indonesia, sampai ke bayi-bayinya, masing-masing akan menanggung Rp 140.000).
Kedua "pengusaha" itu tidak akan mendapatkan kredit dari bank pemerintah sebesar itu seandainya aturan—dan itu akhirnya berarti hukum—berjalan tanpa pilih kasih. Namun aturan telah pilih kasih, hukum bisa dipermak untuk kepentingan Keluarga Cendana, dan kini akibatnya terasa benar bagi ekonomi Indonesia: dana sebesar itu, ditambah dengan yang diutang oleh 50 debitur lainnya (daftarnya ada di halaman 68), kini macet total. Yang tinggal adalah langkah hukum. Bagaimana mereka dibawa ke Pengadilan Niaga, dan bagaimana Pengadilan Niaga yang baru itu—yang prestasinya masih belum terpuji—bisa memaklumkan status mereka yang bangkrut.
Di sini pula terletak soal kepercayaan dari masyarakat pengusaha, terutama para investor asing. Bagi mereka, menyogok atau memberi fasilitas khusus kepada para pejabat tinggi bisa mereka lakukan. Namun lama-kelamaan ini bukan jaminan yang baik, dan bukan pula sesuatu yang efisien. Terlampau banyak yang tak terduga-duga di sini—misalnya terjadinya pergantian pejabat. Akan lebih bagus seandainya ada perangkat hukum yang bisa jadi pegangan yang pasti. Banyak hal bisa direncanakan jauh hari. Kompetisi akan jauh lebih terbuka, dan belum lagi dana ekstra untuk suap sana suap sini akan lenyap.
Itu sebabnya ada pengadilan niaga. Kini tinggal bagaimana ia berbuat.
Tema yang kedua adalah tema bankir yang menguras bank yang mereka miliki sendiri. Setelah likuidasi 38 bank diumumkan, masalah penegakan hukum terhadap para pemilik dan pengurus bank kini apa? Tentang ini, seorang direktur Bank Indonesia mengatakan bahwa daftar para bankir itu telah diserahkan kepada polisi. Soalnya ialah bahwa sampai sekarang polisi tak cukup melakukan tugasnya.
Mengingat likuidasi 13 Maret itu adalah yang ketiga kali semenjak likuidasi November 1997, polisi tentu sudah dilibatkan sejak dua tahun silam. Kasus kejahatan bank bukan hal baru bagi mereka. Sejumlah berkas kabarnya pun telah diserahkan ke pihak kejaksaan, sehingga pada pertengahan 1998, banyak bankir papan atas yang mondar-mandir ke kejaksaan untuk penyidikan. Beberapa di antaranya bahkan sempat ditahan.
Waktu itu, penyidikan terhadap bankir papan atas menjadi tontonan gratis yang mengipas-ngipas rasa ingin tahu dan harapan banyak orang. Namun, anehnya, tanpa petir dan angin yang menyambar, tontonan itu usai begitu saja semata-mata karena dalih "mereka harus bekerja agar bisa mengembalikan BLBI".
Bagi yang mengerti hukum, keputusan ini barangkali bisa dianggap sebagai pelecehan. Sejak saat itu pula, masalah bankir tercela menjadi isu remang-remang dan penegakan hukum di sektor perbankan seakan lepas—sengaja atau tidak—dari tangan polisi dan kejaksaan. Padahal untuk menuntaskan kasus-kasus kejahatan bankir, ada SKB (surat keputusan bersama) yang merupakan dasar hukum bagi penyidikan polisi dan kejaksaan.
Ketidakjelasan dalam penegakan hukum terhadap para bankir tercela—termasuk kasus pelanggaran batas maksimum pemberian kredit (BMPK)—kini memperpanjang daftar masalah (lihat halaman 72). Akibatnya, kekhawatiran bahwa restrukturisasi tidak mencapai sasaran kian menjadi-jadi.
Kekhawatiran itu dipicu oleh pemahaman bahwa restrukturisasi akan sukses hanya kalau dilakukan secara transparan, lugas, tegas, cepat, dan tepat. Yang sekarang terjadi ialah, Bank Indonesia mengucurkan dana talangan untuk nasabah sekitar Rp 50 triliun—sebelumnya mencapai sekitar Rp 140 triliun—plus dana pesangon untuk karyawan bank terlikuidasi, sedangkan pemilik dan pengurusnya lepas dari jangkauan polisi.
Hal yang tidak elok itu lagi-lagi membuktikan bahwa ada cacat dalam restrukturisasi karena kurang transparansi dan minus law enforcement.
Padahal, selain dua faktor itu, restrukturisasi baru akan berhasil kalau didukung oleh komitmen dan konsensus yang dipegang teguh antara pemerintah, DPR, polisi, kejaksaan, Bank Indonesia, dan IMF tentu saja. Dalam konsensus itu, tercakup koordinasi untuk kerja sama yang terjadwal dengan rapi.
Tetapi apakah polisi dan kejaksaan dan para hakim sudah rapi? Sekali lagi, masalahnya bukan hanya masalah keadilan, tapi juga kepercayaan dan kepastian. Tanpa itu, jangan harap perekonomian bisa kembali bangun.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini