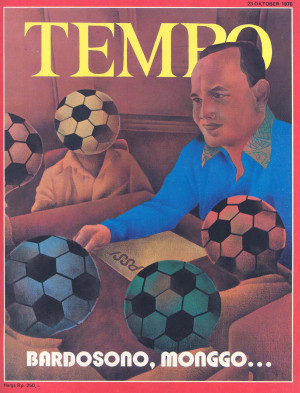GAGASAN Ibnu Sutowo membangun armada tanker Pertamina --
mula-mula untuk dalam negeri, kemudian melanglang samudera --
dimulai tahun 1969. Waktu itu ada tawaran dari Inter Maritime
Bank, Geneva, untuk menjamin pembelian 21 kapal tanki secara
angsuran selama 10 tahun. Tapi untuk jaminan itu, bank kepunyaan
Bruce Rappaport itu minta 6 tanker Pertamina dijadikan jaminan.
Dengan syarat: registrasi keenam tanker itu -- MT Permina 1001
s/d MT Permina 1006 -- harus dipindahkan dari bendera Indonesia
ke bendera Liberia.
Berbekal jaminan dan syarat Rappaport itu, Ibnu Sutowo sebagai
Dirut Pertamina melayangkan sepucuk surat permohonan pada
Menteri Perhubungan waktu itu, drs Frans Seda. Isinya minta izin
pengalihan bendera ke-6 tanker milik Pertamina tersebut. Adapun
maksud pembelian 21 tanker carteran secara berangsur itu, adalah
untuk melayani penyaluran bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri.
Sebelumnya, tugas itu masih dilaksanakan sebagian oleh
tanker-tanker Stanvac dan Caltex, karena tanker milik Pertamina
sendiri jauh dari memadai. Setelah konsultasi dengan Menteri
Pertambangan Prof. Sumantri Brodjonegoro (kini sudah almarhum),
Frans Seda kontan setuju.
"Saya memang merasa sudah saatnya kita membangun armada tanker,
tapi khusus untuk angkutan minyak dalam negeri", tutur Frans
Seda, pensiunan Menteri & Duta Besar MEE itu. Alasannya: "Tidak
cukup kita hanya kuasai produksi, tapi kita juga harus menguasai
distribusinya". Tapi kalau begitu, mengapa bukan pemerintah yang
memberikan jaminan buat sewabeli 21 tanker itu?
Hasyim Ning
"Soalnya, pemerintah tak gampang lagi memberikan garansi pada
unit-unit ekonominya. Ini berdasarkan pengalaman pahit kita di
masa yang lampau. Setelah dipotong hutang-hutang senjata, hampir
separo hutang Orde Lama dulu disebabkan karena pemerintah
menyediakan diri sebagai garansi bagi pinjaman-pinjaman luar
negeri. Sampai-sampai pinjamall Hasyim Ning sebanyak AS$ 15 juta
dari Bank Dunia, juga dijamin oleh pemerintah. Makanya semenjak
saya jadi Menteri Keuangan, saya mengambil langkah
debirokratisasi di bidang ekonomi. Artinya, unit ekonomi
pemerintah pun harus mampu mengembangkan dirinya sendiri secara
otonom, mencari pinjaman sendiri dan menyediakan borg-nya
sendiri. Itu sebabnya Pertamina harus menyediakan keenam
tankernya itu sebagai borg, untuk mendapat jaminan bank asing
itu bagi pembelian armada 21 tanker itu", tutur Seda di kantor
Yayasan Unika Atma Jaya, Semanggi.
Tapi mengapa ke-6 tanker Pertamina itu harus ditukar benderanya?
Jawab ekonom lulusan Tilburg, Belanda itu: "Itu soal biasa dalam
bisnis kapal internasional. Djakarta Lloyd dengan seizin saya
sebagai Menteri Perhubungan waktu itu, juga ada berbuat
demikian. Kapal-kapal itu diperlukan sebagai borg. Kalau tetap
berbendera Indonesia, fihak kreditor tidak bisa dengan bebas
menahan kapal itu bila Pertamina tidak melunasi kewajibannya
pada kreditor. Makanya registrasinya perlu dilihkan ke luar
negeri, tetapi tetap milik Indonesia".
Selain itu, permohonan Ibnu Sutowo tertanggal 2 April 1969 itu,
sekaligus mengandung maksud minta izin agar keenam tanker itu
tetap diperkenankan berlayar di perairan Indonesia, setelah
berganti bendera. "Inilah yang disebut izin flag convenence",
kata Seda. Sebab untuk menegakkan Wawasan Nusantara, ada
ketentuan Departemen Perhubungan bahwa hanya kapal yang
berbendera Indonesia boleh berlayar di perairan Indonesia.
Sedang kapal berbendera asing harus minta izin dulu.
Tapi dalam surat Ibnu Sutowo No. 285/DR/DU/69 itu tidak
tercantum bobot mati, harga dan besarnya sewa cicil 21 tanker
itu. Mengapa itu tidak ditanyakan lebih dahulu oleh Seda,
sebelum izin angkutan khusus minyak diberikan?
"Soal tonnage, itu kompetensi Menteri Pertambangan yang langsung
membina Pertamina. Sedang soal harga dan cicilannya, itu
wewenang Menteri Keuangan dan Bank Sentral. Kalau ada yang tidak
beres, mestinya merekalah yang pertama mencegatnya". Dalam soal
jumlah dan jenis pesawat terbang Pelita, yang kini dinyatakan
jauh melampaui kebutuhan, Seda berpendapat bahwa itu pun
wewenang Dewan Komisaris untuk mencegahnya sejak semula.
Pokoknya, begitu Seda menegaskan lagi, "tugas saya sebagai
Menteri Perhubungan waktu itu, hanyalah membina angkutan umum
yang langsung berada di bawah Departemen saya. Seperti Garuda,
Djakarta Lloyd dan Pelni. Sedang izin yang diminta Pertamina
dari Perhubungan, termasuk untuk pelabuhan minyaknya, angkutan
udara Pelita Air Service dan jaringan telkomnya, adalah izin
khusus. Jadi semuanya ditetapkan dengan SK Menteri Perhubungan.
Sehingga kami berhak menentukan tarifnya supaya tidak merusak
pola perhubungan secara menyeluruh. Misalnya tarif penerbangan
Pelita, yang juga khusus diperuntukkan bagi
kontraktor-kontraktor minyak yang butuh gerak cepat".
Menurut Frans Seda, "dia (Ibnu) selalu lebih dahulu minta izin
pada Departemen Perhubungan. Sedang Departemen-Departemen lain
selalain dia bypass saja".
Diakuinya bahwa kasus tanker ini merupakan "satu blunder
(kesalahan besar) dalam soal manajemen, penggunaan dana dan
wewenang dalam pembinaan Pertamina. Tapi bukan kesalahan policy
Perhubungan". Begitu pendapat Seda, yang kini jadi anggota DPA.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini