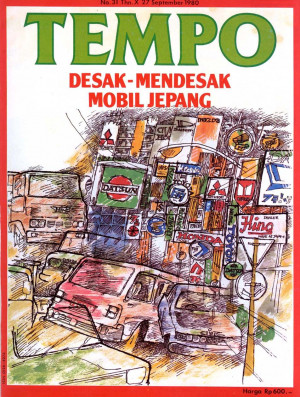TIDAK pernah terdengar ada upacara membakar mayat di Jawa. Tidak
seperti di Bali, yang terkenal dengan ngaben-nya yang khas.
Karena itulah barangkali, orang hampir tidak pernah mengingat
Jawa bila bicara tentang agama Hindu. Padahal, sebuah acara
besar yang disebut Maha Sabha Parisada Hindu Dharma, yang dibuka
24 September ini di Denpasar, dihadiri oleh utusan 22 provinsi
-- termasuk sudah tentu Jawa (Tengah maupun Timur). Dan jangan
disangka mereka yang dari Jawa misalnya hanya mewakili orang
Bali yang merantau.
Maha Sabha, kali ini yang ke-4, adalah acara dewan agama
tertinggi yang disebut Parisada Hindu Dharma (PHD) Pusat setiap
empat tahun. 400-an orang hadir mewakili provinsi, kabupaten
(100 buah) atau Kantor Departemen Agama bagian Hindu. Ditambah
sekitar 2,5 ribu pemuka adat, kelihan desa dan kelihan subak di
Bali -- khusus untuk acara pembukaan. Dalam sidang empat hari,
mereka juga mendengarkan ceramah dari Menteri-menteri Agama,
Dalam Negeri, Sosial, Menko Kesra dan Pangkopkamtib.
Tidak, sudah tentu tujuan penting bukan membahas masalah bakar
mayat. Maha Sabha adalah pertemuan nasional yang lebih banyak
membicarakan hal-hal organisatoris. Tapi memang juga disinggung
masalah kesatuan tafsir ajaran agama -- yang selama ini sudah
diseminarkan enam kali dan terdiri dari 18 materi.
Kalangan Kejawen
Bahkan, seperti dituturkan drh. Willy Pradnyasurya, direktur
pada Ditjen Bimas Hindu & Budha Departemen Agama, hal-hal ritual
seperti soal bakar mayat pun bisa muncul. Dicontohkannya upacara
bakar mayat bagi anggota ABRI -- yang biasanya dimakamkan di
pekuburan yang disebut Taman Makam Pahlawan. Ini tentu merupakan
tambahan bagi masalah bakar mayat di Jawa Hindu seperti sudah
disebut.
Dan masyarakat Hindu di Jawa memang ada -- dan konon cukup
besar. Dibia Asmara, Sekretaris Umum PHD Daerah Istimewa
Yogyakarta, bahkan memperkirakan umat yang diurusnya sekitar 28
ribu -- sudah termasuk orang Bali yang tinggal di sini lebih
lima tahun. Setidak-tidaknya di provinsi berpenduduk sekitar 2,5
juta ini sekarang terdapat enam pura: tiga di Bantul, dua di
Sleman dan satu di Gunung Kidul.
Belum lagi di luar Yogya dan Jawa Timur. Di Klaten ada sebuah
PGAH, Pendidikan Guru Agama Hindu. Juga di Blitar. Di luar Jawa
dan Bali, di samping Institut Hindu Dharma di Denpasar dan
Akademi Pendidikan Guru Agama Hindu di Singaraja. Tapi berapa
jumlah seluruh umat Hindu?
Kalangan PHD memperkirakan sekitar 7 - 8 juta. Willy
Pradnyasurya, pejabat Departemen Agama tadi, menyebut jumlah 4,6
juta -- dan sekitar 2,1 juta di antaranya bermukim di Bali.
Memang, mayoritas orang Hindu di luar Bali diperkirakan orang
Bali juga. Misalnya para transmigran -- di Sulawesi Selatan,
Lampung atau Kalimantan Tengah. Tetapi di Jawa, potensi Hindu
pada penduduk asli sebenarnya cukup besar -- khususnya pada
mereka yang kejawen. Apalagi bila tak ada kekhawatiran akan
"di-Bali-kan". Sebab, bagai perbedaan tarian Jawa yang diam,
dengan tari Bali yang dinamik, Hindu di Jawa memang pernah punya
tradisi sendiri -- sebelum tertutup oleh Islam yang merambat
lewat pesisir. Dan K.S. Kadi, Ketua I PHD DIY, bisa menuturkan
contoh-contoh perbedaan selain soal pembakaran mayat tadi.
Orang Jawa misalnya tidak mengenal sesajen yang dibuat begitu
njelimet seperti di Bali. Juga upacara potong gigi yang
besar-besaran. Struktur desa di Bali, yang tak lepas dari pura
tri kanyangan yang menjadi keharusan tiap desa (pura desa, pura
puseh dan pura dalem), juga tidak dikenal.
Belum lagi soal sembahyangan dan bahasa. (Murdiono, Ketua PHD
Bantul, DIY, juga mengisi mimbar agama di TVRI dengan bahasa dan
"versi" Jawa). Atau, bisa ditambahkan, soal perhitungan tahun
yang di Bali terdiri dari tujuh bulan (210 hari) dan di Jawa 12
bulan. Maka, kata K.S. Kadi: "Kalau hal-ha yang ada di Bali
'dipaksakan' di luar Bali, bisa timbul kesalahpahaman.
Memang, orang Hindu mengenal pengertian desa-kala-patra (tempat,
waktu dan adat). "Dengan falsafah ini, penyelenggaraan upacara
tidak harus seragam," kata Murdiono. Tapi yang jadi masalah:
tidak selalu mudah membedakan mana adat dan mana agama dalam
Hinduisme -- di samping perbedaan kadang memang bukan hanya
karena adar. Kasus Hardjantha Pradjapangarsa, misalnya, tokoh
kebatinan yang beberapa tahun lalu memproklamasikan agama Sanata
Dharma Majapahit-PancasiIa (Sadhar-Mapan), dan pernah jadi
pimpinan PHD Sala, boleh menjadi contoh.
Setelah terbentuk PHD, nama Sadhar-Mapan tetap mau dia
pertahankan. Ia berkata: agama Hindu janganlah di-Bali-kan.
Bahkan, menurut kalangan PHD DIY, Hardjantha dan para pengikut
menyatakan nama Sadhar-Mapan baru bisa hilang kalau PHD Pusat
dipindahkan dari Bali ke Sala --sebab begitulah menurut
penyelidikan Hardjantha terhadap peninggalan masa kejayaan Hindu
dahulu. Tak terlaksana, tentu saja, 1972 mereka mengundurkan
diri dari PHD.
Akan hal umat Hindu selebihnya di Jawa, sudah tentu tak sejauh
itu. Mereka, misalnya, tetap memakai buku pedoman PHD Pusat
untuk upacara. Murdiono sendiri tetap yakin bahwa PHI) Pusat
memang mestinya di Bali -- "benteng terakhir agama Hindu,"
katanya. Hanya saja ia mengharap di dalamnya diperbanyak unsur
non-Bali -- dan "ini bukan karena sukuisme" -- meskipun di PHD
DIY orang Jawa mendominir kepengurusan. Harapan itu siapa tahu
malah sejalan dengan ucapan Wayan Surpha, Sekjen PHD Pusat di
Bali: "Kami tidak mau agama Hindu dijadikan sekte-sekte."
Maha Sabha, yang sekarang ini sedang berjalan, memang tidak
secara langsung memberi prioritas pada masalah ini -- kecuali
bila terbawa oleh pembicaraan tentang hal-hal ritual. Pemillihan
pengurus PHD Pusat sendiri sudah diperkirakan akan sedikit
"panas". Bukan soal aliran. Wayan Surpha, misalnya, yang juga
salah seorang pendiri PHD, masih menganggap perlunya dewan itu
"ditegakkan wibawanya". Orang memang melihat, bahwa soal seperti
Golkar dan non-Golkar saja, antara lain, pernah ramai di disini.
Biasa.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini