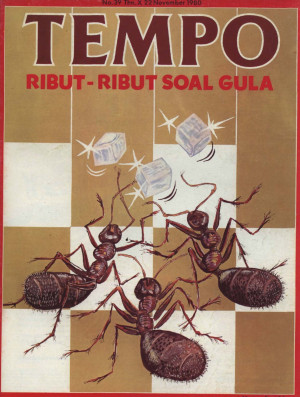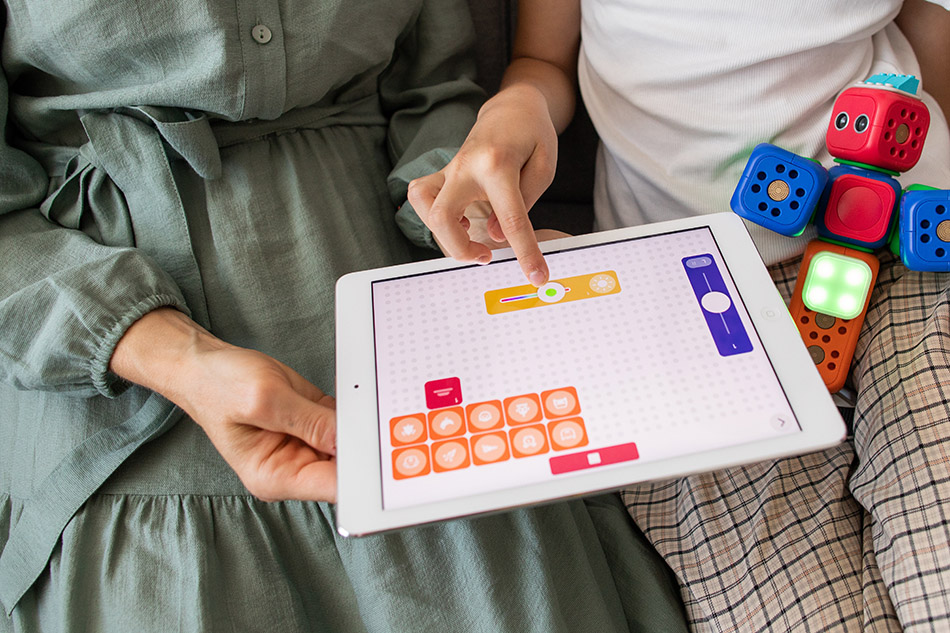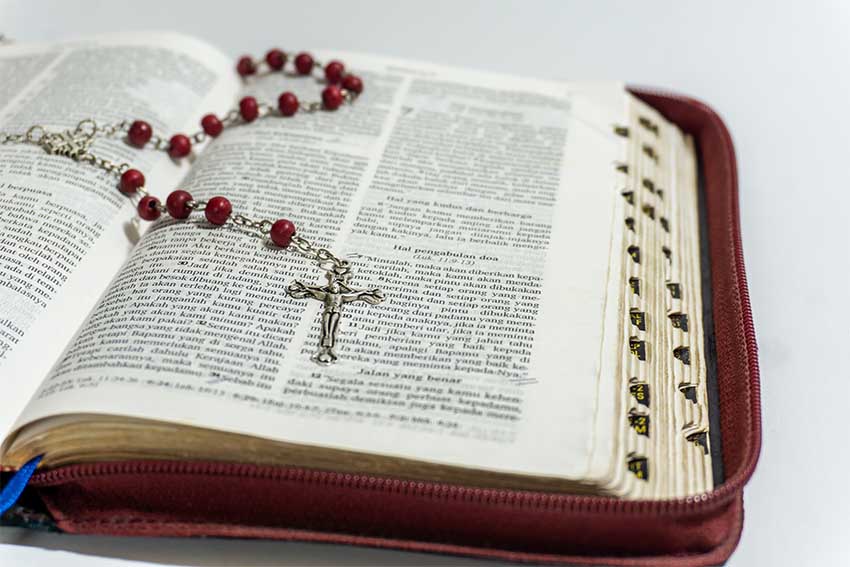NASIB buruh kecil Pabrik Gula Jatiroto di Kabupaten Lumajang
(Ja-Tim) selama puluhan tahun tak banyak berubah. Turun-temurun7
jumlah mereka kini sekitar 29.000 jiwa, ratarata keluarga
tinggal di gubuk sempit di Kampung Rojopolo. Mereka tak punya
keahlian lain kecuali menanam, menebang dan membersihkan kebun
tebu.
Mereka merupakan generasi ketiga buruh-buruh yang
berdatangan dari berbagai kawasan di Jawa Tengah dan Jawa Timur
di awal abad ke-19. Nenek moyang mereka datang menebas hutan
bukan atas kemauan sendiri. Tapi dikerahkan Pemerintah Hindia
Belanda.
"Kami dikumpulkan dalam satu rumah besar beratap kajang,
yaitu atap dari anyaman daun kelapa," tutur H. Djamaluddin
Malik, 54 tahun, mengenang cerita embahnya, H. Hasan Ali. Hasan
Ali pada 1901 diseret Belanda dari Bojonegoro, 350 km sebelah
utara Jatiroto. Selama beberapa tahun, sebelum pabrik
berproduksi, Hasan Ali dkk. diizinkan bertanam padi, jagung dan
palawija di tanah hutan yang barusan dibabat.
Setelah roda pabrik mulai berputar, sekitar 1908, para buruh
mendapat perumahan kecil dan resmilah mereka menjadi buruh
pabrik. Yang sedikit punya kemampuan diangkat jadi juru tulis
atau mandor Selebihnya buruh kasar.
Sebagai imbalan, selain menerima upah, mereka boleh
menggarap tanah selain (yang tidak ditanami tebu), ditambah
pinjaman 2 ekor sapi untuk membajak. Mandor dan juru tulis
mendapat 3 ha (untuk ditanami padi) sedang buruh biasa 0,1 ha
(untuk jagung).
Bila panen, mereka harus menyetor 1/3 hasilnya ke pabrik.
Romusha
Meskipun hanya penggarap mereka, boleh dikata merupakan
golongan elite di Jatiroto. "Soalnya mereka lebih mampu
dibandingkan penduduk di luar desa," kata H. Basyuni, 50 tahun,
bekas penghuni rumah kajang Seperti halnya Basyuni, kini
sebagian besar penduduk yang mampu di sekitar Jatiroto memang
keturunan para mandor atau juru tulis. Mereka keluar dari
perkampungan, lantas membeli sawah di sekitar perkebunan, dan
menetap di situ.
Yang masih tinggal di Rojopolo hingga sekarang adalah para
buruh kecilyang tetap saja bekerja sebagai kuli pabrik. Nasib
mereka merosot dari tahun ke tahun. Di zaman penjajahan Belanda,
mereka masih mendapat imbalan atas tanaman tebu mereka. Kini
mereka tak lagi terikat oleh pabrik. Artinya, mereka boleh
bekerja untuk pabrik, boleh juga tidak.
Pihak pabrik pun tidak lagi menyediakan tanah sela (1973)
meskipun mereka masih tinggal di perkampungan.
Maka mulailah tingkat kehidupan mereka memudar. Apalagi setelah
Pabrik Gula Jatiroto dinasionalisasi pada tahun 60-an.
"Sekarang penduduk Rojopolo termasuk yang miskin di desa
ini," kata H. Djamaluddin Malik, eks penghuni persil yang kini
jadi Kepala Desa Rojopolo. Penghasilan mereka rata-rata berkisar
antara Rp 250-Rp 400 sehari. Kalau pabrik lagi tidak giling,
pada Februari dan Maret, buruh-buruh itu pun mulai melilitkan
pinggangnya dengan utang. Begitu seperti dialami Munadji alias
Ramelan, 56 tahun, ayah dari 9 anak.
Untunglah Munadji masih bisa bertukang. Dari penghasilannya
sebagai tukang itulah ia menyekolahkan anakanaknya. Ada anaknya,
tamatan SD, yang kini sudah bekerja di luar desa. Tapi pondoknya
yang masih saja berukuran 3 x 9 meter itu kini penuh sesak
dihuni anak dan cucunya.
Nasib Dirah alias Kenek, 60 tahun, setali tiga uang. Orang
tua ini sudah 37 tahun tinggal di Rojopolo la melarikan diri
dari Sampang (Madura), karena diuber Jepang untuk dijadikan
tenaga kerja paksa atau romusha. Ketika itu sudah ada saudaranya
yang tinggal di Rojopolo.
Dulu, ketika pabrik masih memberi kesempatan pada Dirah
bertanam jagung di tanah sela seluas 0,1 ha, lumayanlah. "Kalau
badan sakit ya masih bisa makan dari jagung simpanan," katanya.
Tapi sekarang? "Kalau tidak ada yang kasih utang ya tidak makan,"
tambahnya memelas Keempat anaknya meneruskan nasib sebagai
buruh pabrik.
Satu-satunya harapan sisa-sisa keturunan para kuli itu
ialah: tidak digusur dari kampung persil. Sebab memang tinggal
itulah sandaran hidup mereka. Tak seorang pun tahu sampai kapan
bisa tinggal di sana. Kelak, kalau pabrik memperluas areal
tanaman tebu, ya . . .
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini