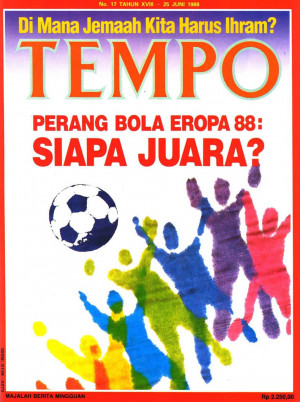KOTA Salatiga di Jawa Tengah mendadak hangat. Gairah itu ditebarkan oleh puluhan wanita muda, yang Kamis pagi 1 Juni lalu memenuhi halaman Pengadilan Negeri di kota yang sejuk itu. Simbol jantung merah jingga bertuliskan Ida menempel di dada mereka. Di bagian bawah emblem dari karton tipis itu tertulis Gerakan Kesadaran Perempuan. Ada "gerakan"? Demonstrasi? Bukan.Gadis-gadis menor dan harum itu mau bersimpati kepada Nyonya Ida, yang hari itu perkaranya hendak divonis. Beberapa di antara anggota Gerakan Kesadaran Perempuan (GKP) - begitulah mereka menamakan diri - membagi-bagikan emblem itu sambil berkata, "Anda cinta Ida?" Begitu Ida turun dari mobil tahanan, dua GKP-wati menyongsong lantas memapahnya, sementara yang lain mengerumuninya. Damairia Pakpahan, mewakili rekan-rekannya, menyerahkan pernyataan simpati terhadap kasus Ida. "Terimalah ini, sebagai rasa simpati kami kepada Mbak Ida," kata Damairia sembari menyematkan emblem merah hati itu. Siapa Ida? Ia adalah Nyonya Rumini Ida, 32 tahun, karyawati PT Damatex Salatiga. Dialah terdakwa yang dituduh membakar suaminya hingga meninggal (TEMPO, 26 Maret 1988, Kriminalitas). Selama 10 tahun ia menikah dengan Djunaedi Bandi Saputro, 35 tahun, dan dikaruniai tiga anak, rumah tangganya kacau. Perempuan berhidung lancip, berbibir tipis, dan pendiam itu menderita batin. Suaminya, meski sehari-hari sebagai pendidik, sering menghajarnya. Bahkan tak jarang memukul anak-anaknya dengan gagang sapu. Selain tak pernah memberi nafkah cukup, ia juga mengabaikan "nafkah batin". Usaha menggugat cerai lewat Pengadilan Agama pada 1982, sia-sia. Pengadilan Agama tak pernah memanggil dan menyidangkan perkaranya. Melalui BP4 (Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian) juga gagal. Mengapa Pengadilan Agama tidak menyidangkannya, tidak jelas. Padahal, bila jelas suami melakukan penganiayaan, apalagi sampai dua tahun tidak memberi nafkah keluarga, gugatan cerai seorang istri (rafak) mestinya bisa dikabulkan. Derita batin itu seperti bom waktu yang siap meledak. Tiba-tiba Ida menemukan penyulutnya Minggu pagi 18 Oktober tahun lalu, ia menerima sepucuk surat yang ditujukan kepada suaminya. Pengirimnya: Tulus Bakti, Asrama Brimob, Manahan, Solo. Surat itu disimpannya, karena suami dan anak-anaknya lagi piknik. Mendadak kecurigaannya muncul. Dibukanya surat itu. Matanya membelalak. Ternyata, surat itu ditulis seorang wanita bernama Sri Sulastri, yang juga sudah berkeluarga. Kahmat-kalimat mesra dalam surat itu - antara lain menyebutkan sudah saatnya menjalin ikatan perkawinan setelah lima tahun berkasih sayang - menyulut kemarahannya. Ia tak bisa tidur, dan pada pukul 01.00 terjaga. Mula-mula ia bimbang. Tapi lantaran kamarahannya memuncak, disiramkannya seember bensin campur minyak tanah ke kemaluan Djunaidi. Suaminya itu terbangun. Ida bukan mengurungkan niatnya, malah menyulut suaminya. Bret. Api menjilat sekujur tubuh Djunaidi. Ida dan korban sempat berteriak minta tolong.- Orang sekampung datang menolong, lalu Djunaidi dilarikan ke RSU Salatiga. Tapi beberapa saat kemudian meninggal di RSU Dr. Kariadi, Semarang. Kasus inilah yang menarik sejumlah wanita muda untuk membentuk GKP di Yogyakarta, April lalu. Tak kurang dari 200 orang dari Salatiga, Yogyakarta, Jakarta - sebagian besar wanita - menandatangani pernyataan itu. Di antaranya Emha Ainun Nadjib (Yogya), penyair, dan Marianne Katoppo, novelis dan teolog dari Jakarta. Menurut pernyataan itu, perbuatan Ida salah. Tapi kepada majelis hakim diharap kannya agar dalam menjatuhkan vonis jugamempertimbangkan struktur masyarakat Indonesia yang memperlakukan kaum perempuan secara tidak adil. Pernyataan itu didukung Kelompok Studi Gereja dan Masyarakat Yogyakarta, yang bernada sama. Majelis hakim akhirnya menghukum 6 tahun penjara potong masa tahanan, lima tahun lebih ringan dari tuntutan jaksa. Begitu vonis jatuh, keplok tangan-tangan halus bergema. Dan Ida, yang didampingi lima pembela Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) dan Kosgoro, menunduk menitikkan air mata. Maria Bithia Juita Dinata, 22 tahun, koordinator GKP, puas. "Saya yakin 50% vonis itu dipengaruhi pernyataan kami," ujar mahasiswi Fakultas Pertanian UKSW itu. Tapi Nyonya Ary Haruni Diono, S.H. membantah. "Kalau vonis itu memenuhi rasa keadilan mereka, itu kebetulan saja. Pendapat dari luar 'kan tidak bisa jadi pertimbangan," katanya. Lagi pula, kata hakim anggota itu, amar putusan sudah disusun seminggu sebelum pernyataan GKP diterima. "Dan sidang 16 Juni itu hanya membacakan hasil musyawarah majelis sebelumnya," tambahnya. Tapi ia mengakui, kesaksian psikolog Nyonya Leila Ch. Budiman banyak dipakai sebagai pertimbangan. Menurut saksi ahli itu, ketika melakukan perbuatannya kondisi kejiwaan terdakwa sangat terganggu, seperti "gili sesaat". Namun, Leila sendiri menganggap vonis itu terlalu berat. "Penderitaan Ida selama 10 tahun yang penuh penganiayaan sudah merupakan hukuman tersendiri. Kok sekarang ditambah enam tahun lagi?" katanya. Kasus ini jadi menarik lantaran munculnya GKP. "Sudah saatnya kami bicara membela kaum yang tidak terwakili," kata Maria Bithia. "Tapi ini bukan semacam gerakan kaum feminis di Barat, hanya semacam mediator bagi kaum perempuan golongan bawah," ujarnya. Kenapa "perempuan" dan bukan "wanita"? "Karena wanita itu artinya yang diminati, sedang perempuan berasal dari kata empu," tambahnya. "Pendeknya, gerakan ini mandiri, tidak ndompleng profesi suami," ujar Maria. Para pendukung umumnya aktivis lembaga sosial masyarakat. Maria dkk. misalnya, sering membimbing tukang becak di Salatiga, sementara Damairia suka menyantuni gelandangan Kali Code dan anak-anak penyemir sepatu di Yogya. Bagaimana menyantuni Ida dan anakanaknya? Menurut Marianne Katoppo, hal itu harus dipikirkan organisasi wanita seperti Dharma Wanita. Lalu perempuan macam Sri Sulastri yang merebut suami orang? Katanya, "Peranan dia juga mesti dipersoalkan, apakah ia menyadari tanggung jawabnya. Dan berapa banyak Sulastri-Sulastri di antara kita?" B.S.H., Diah Purnomowati, Aries Margono
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini