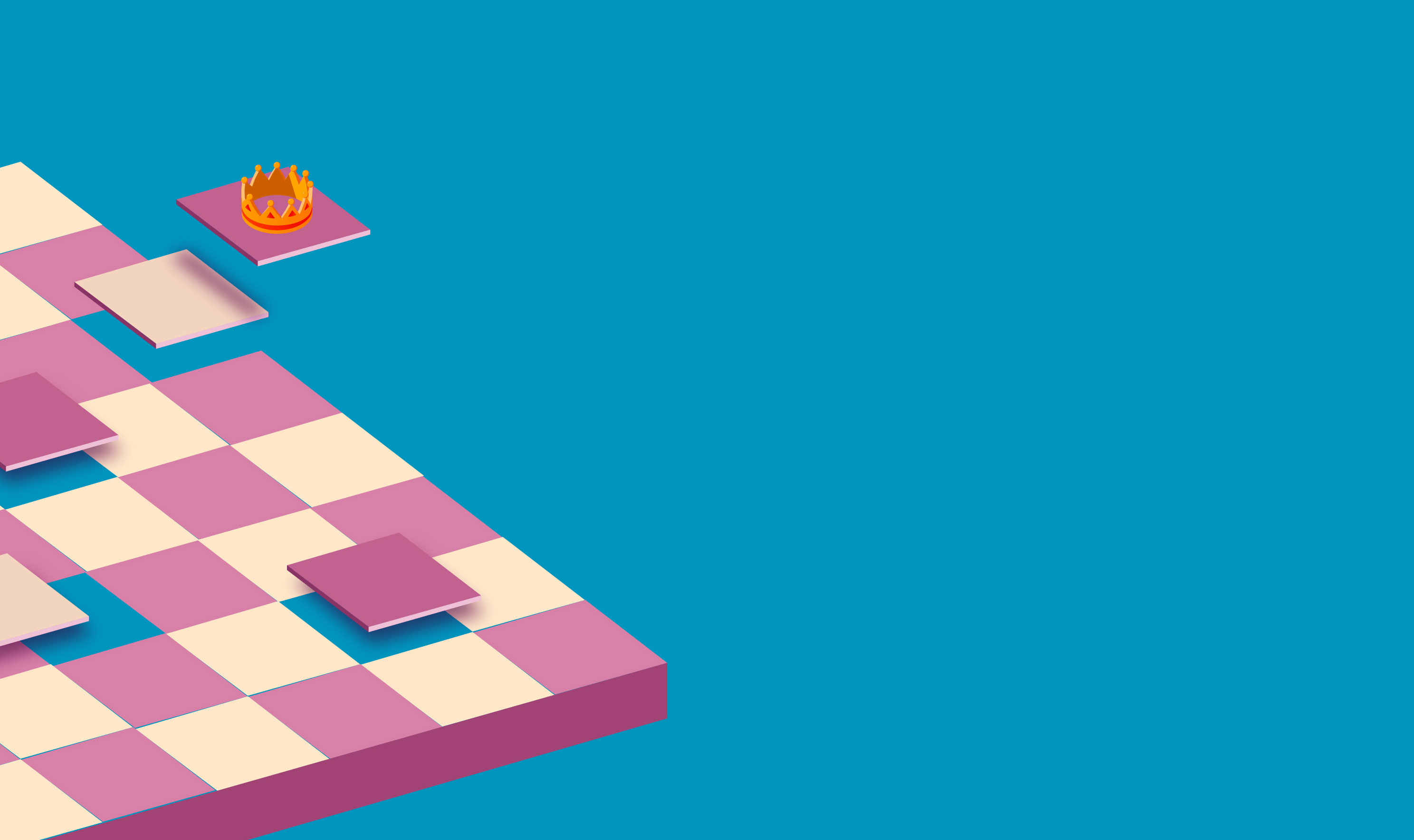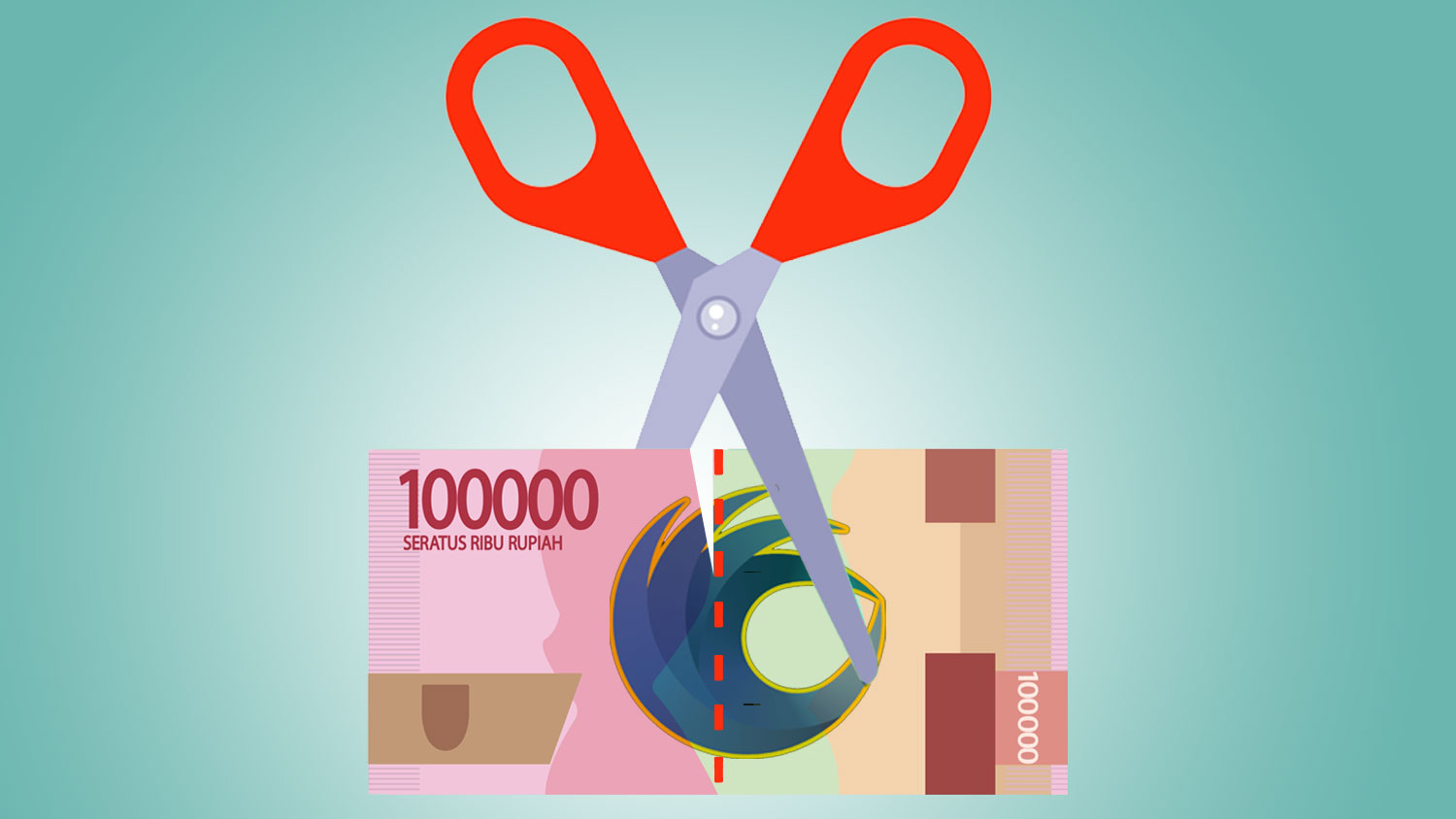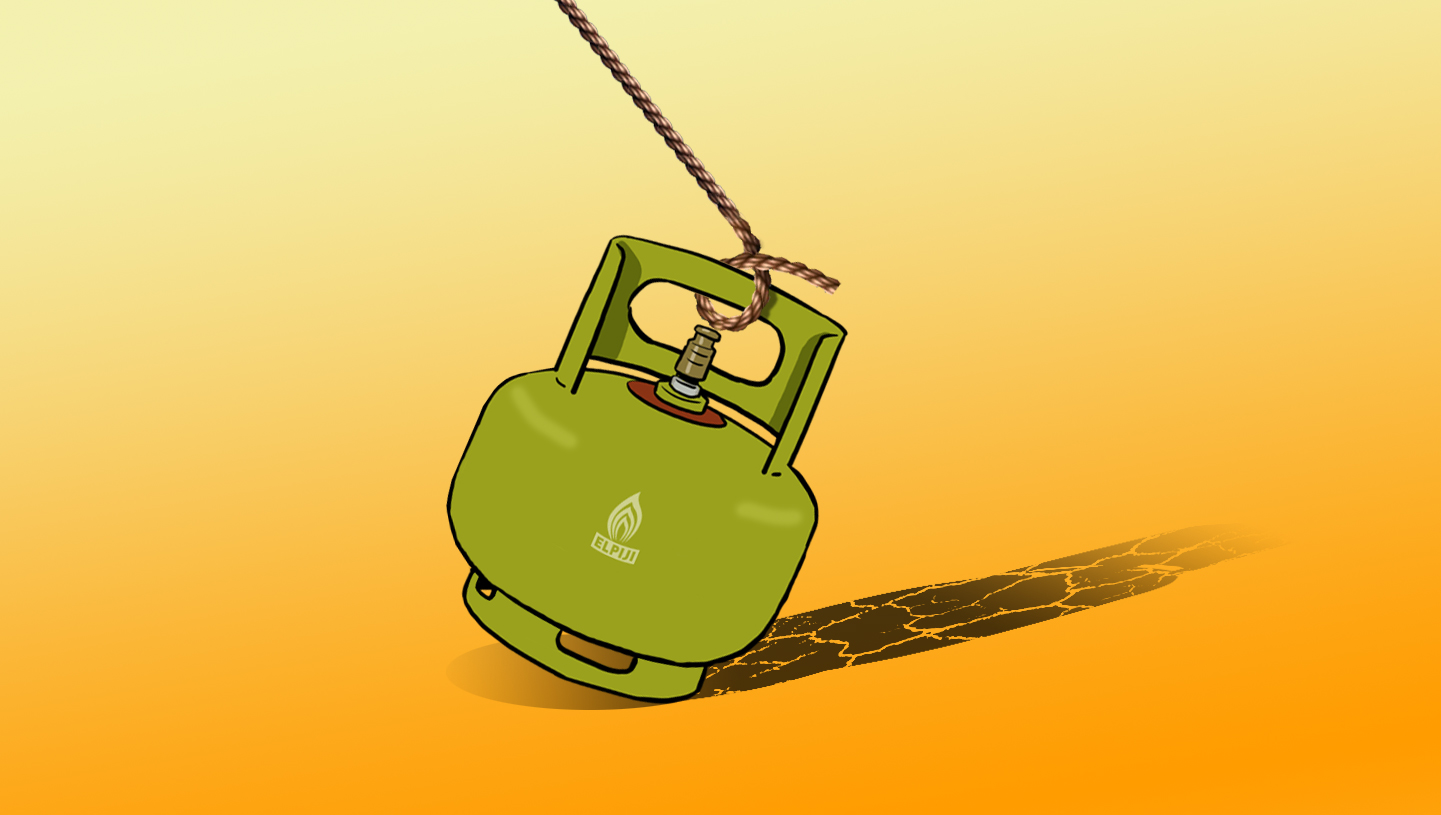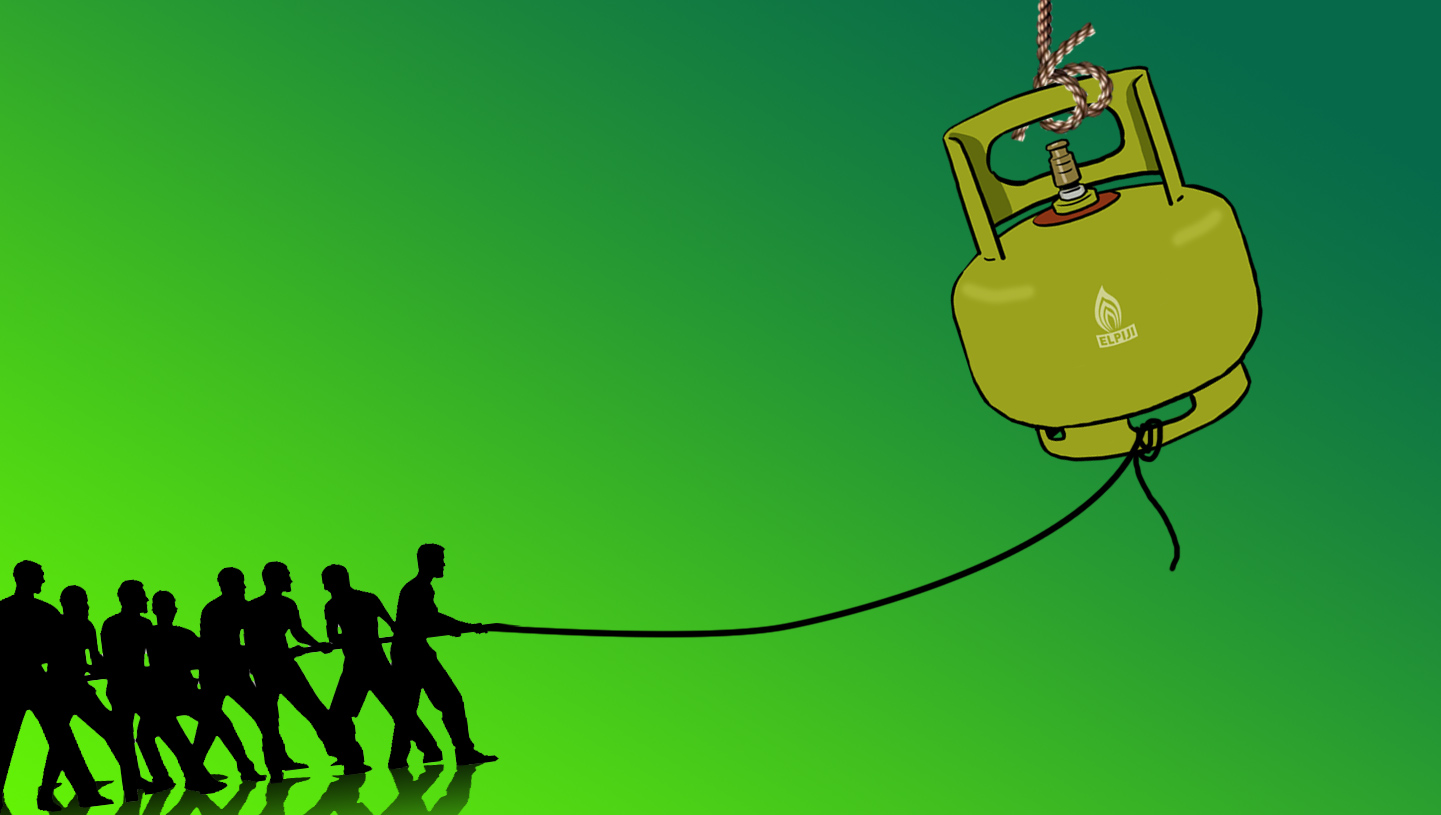Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ringkasan Berita
Presiden Joko Widodo sebenarnya sedang mempraktikkan konsep kekuasaan dalam budaya Jawa.
Kekuasaan dalam budaya Jawa itu terpusat dan tidak mempersoalkan keabsahannya.
Konsep itu berlawanan dengan konsep negara demokrasi seperti Indonesia.
Satrio Wahono
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sosiolog dan Magister Filsafat UI
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Selama hampir satu dasawarsa pemerintahannya, persepsi media dan sebagian masyarakat tentang Presiden Joko Widodo telah berubah dari political darling menjadi political strawman, dari sosok yang dipuja menjadi sosok yang segala masalah sering dinisbatkan kepadanya. Hal ini terjadi terutama setelah Mahkamah Konstitusi (MK) melonggarkan batas minimal usia pencalonan presiden dan wakil presiden. Sebab, putusan ini berujung pada majunya putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden yang mendampingi calon presiden dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Padahal sudah menjadi rahasia umum bahwa Prabowo adalah sosok yang telah mendapatkan endorsement secara implisit dari Presiden Joko Widodo, terlepas dari pernyataan resmi Presiden untuk tidak cawe-cawe dalam pencalonan presiden.
Melayanglah tuduhan bahwa Jokowi dalam praktik kepresidenannya sudah kian melenceng dari rel demokrasi karena seakan-akan mendukung suburnya dinasti politik. Belum lagi fakta yang memprihatinkan bahwa supremasi hukum (rule of law), sebagai salah satu pilar demokrasi terpenting, justru makin lemah di era Jokowi. Kredibilitas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan MK, dua institusi yang sebelumnya selalu menjadi andalan penegakan hukum, semakin tergerus. Terakhir, setelah terungkapnya fakta bahwa Presiden Jokowi-lah yang dulu sempat memiliki keinginan memperpanjang masa kekuasaan presiden menjadi tiga periode, lengkaplah tuduhan bahwa Jokowi saat ini terlalu dahaga akan kekuasaan dan tidak lagi menghiraukan demokrasi.
Sebetulnya tidak perlu heran akan praktik politik Jokowi ini. Dari sudut pandang antropologi politik, konsep kekuasaan budaya Jawa, sebagai budaya yang dianut presiden asal Surakarta, Jawa Tengah, tersebut, memang bisa mempengaruhi seorang penguasa untuk tidak sejalan dengan kultur demokrasi ala Barat, yang dalam derajat tertentu sedang ditempuh Indonesia.
Menurut Ben Anderson dalam “Gagasan tentang Kekuasaan dalam Budaya Jawa” (1984), kekuasaan dalam budaya Jawa memiliki sejumlah kekhasan vis a vis kekuasaan versi Barat. Pertama, kekuasaan itu konkret, penuh misteri, dan bersifat ketuhanan. Hal ini berbeda dengan kekuasaan versi Barat yang abstraksi-teoretis. Kedua, kekuasaan itu homogen, yaitu sama jenis ataupun sumbernya. Adapun Barat memandang kekuasaan itu heterogen karena ada kekuasaan yang bersumber dari kekayaan, senjata, dan lain sebagainya.
Ketiga, kekuasaan dalam budaya Jawa selalu tetap sehingga terpusatnya kekuasaan di satu tempat atau sosok mengharuskan pengurangan kekuasaan di tempat lain dalam jumlah sebanding. Di sisi lain, Barat menganggap akumulasi kekuasaan tidak ada batasnya. Keempat, kekuasaan tidak mempersoalkan keabsahan karena bersifat homogen. Hal ini berbeda dengan cara pandang Barat yang lebih rumit karena harus mempersoalkan keabsahan kekuasaan berdasarkan sumbernya, apakah ekonomi, karisma, senjata, ataupun yang lain.
Kelima, Jan Christie dalam “Raja dan Rama: Negara Klasik di Jawa” (1989) menambahkan bahwa konsepsi kekuasaan raja di Jawa sangat spiritual, dalam makna seorang raja Jawa memiliki teja alias sinar kekuasaan dan dianggap tidak mementingkan diri sendiri (pamrih).
Dari konsepsi kekuasaan budaya Jawa seperti itu, kita sebenarnya bisa memahami praktik kepresidenan yang sedang terjadi. Menjelang berakhirnya periode kedua masa kepresidenan Jokowi, jelas kekuasaannya akan berkurang atau bahkan lenyap. Karena itu, dia harus mengkompensasikannya dengan mengurangi prospek kekuasaan orang lain. Inilah yang termanifestasi dari naiknya sang putra sebagai calon wakil presiden. Kemudian, mengingat dimensi keabsahan kekuasaan bukan soal utama dalam budaya Jawa, maka saluran-saluran untuk melanggengkan kekuasaan bisa didapatkan dari mana saja, entah dari hukum, karisma keluarga, ataupun pengaruh politik.
Perlu dipahami pula bahwa pelanggengan kekuasaan tidak mesti karena ambisi pribadi. Hal itu bisa saja dari motif tanpa pamrih sang presiden untuk melanjutkan segala kerja yang ia yakini akan menguntungkan rakyat atau kawula, seperti saat ini dalam bentuk pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara dan proyek infrastruktur. Isu keberlanjutan menjadi penting baginya jika kita lihat dalam tradisi politik Jawa.
Dengan kata lain, praktik kepresidenan yang banyak dikritik masyarakat saat ini sebenarnya bisa dipahami dalam konteks budaya Jawa. Namun sesuatu yang bisa dipahami tidak berarti bisa dibenarkan. Apalagi jika dipandang dari budaya lain, dalam hal ini budaya demokrasi. Itulah yang kini menjadi persoalan karena konsep kekuasaan Jawa ini berlaku dulu di zaman kerajaan Jawa kuno, sedangkan Indonesia bukanlah kerajaan, melainkan negara yang menaungi beragam kebudayaan dan memutuskan menjadi negara modern dengan sistem demokrasi.
PENGUMUMAN
Redaksi menerima tulisan opini dari luar dengan syarat: panjang sekitar 5.000 karakter (termasuk spasi) atau 600 kata dan tidak sedang dikirim ke media lain. Sumber rujukan disebut lengkap pada tubuh tulisan. Kirim tulisan ke e-mail: [email protected] disertai dengan nomor kontak dan CV ringkas.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo