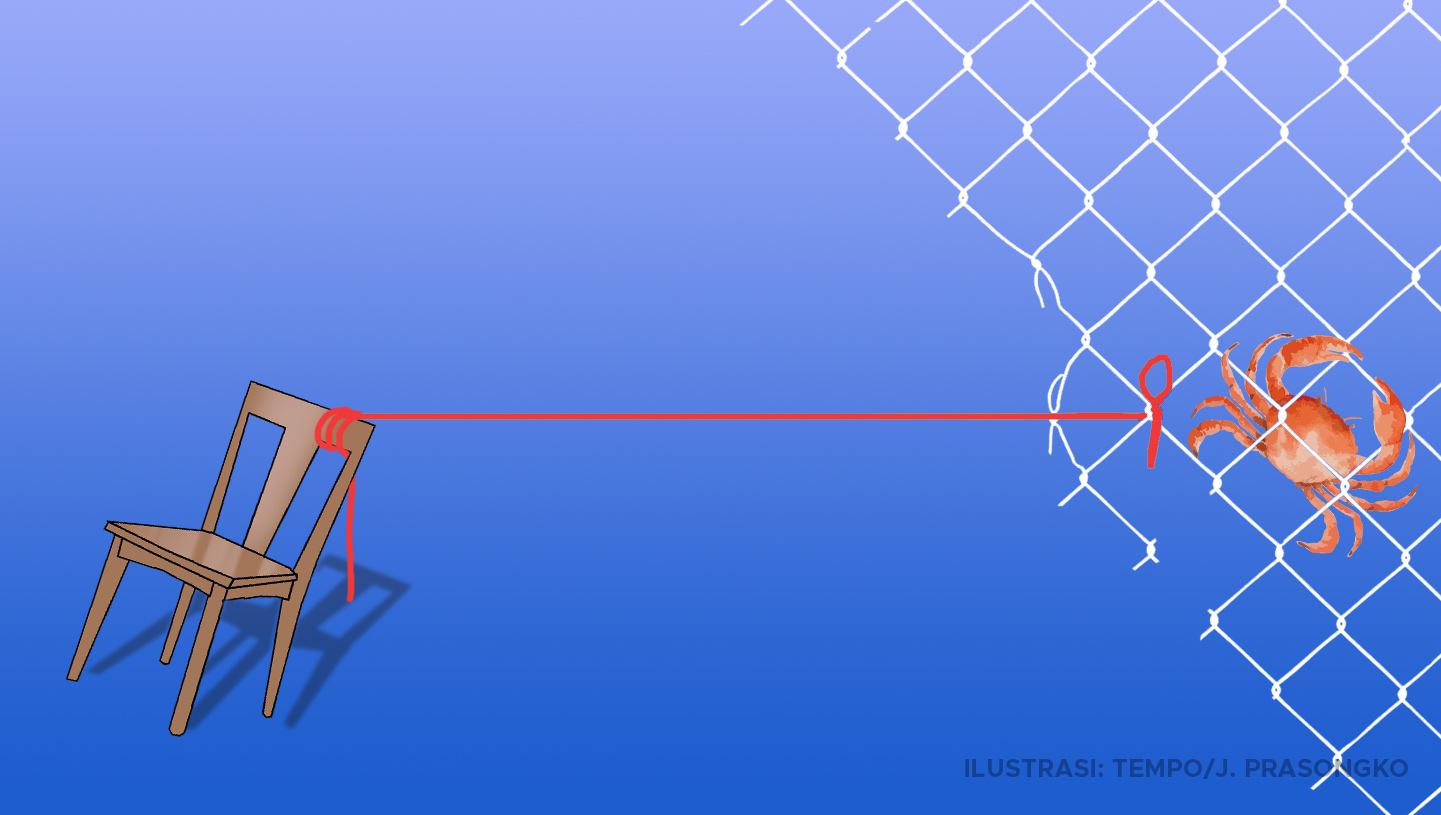Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
![]() H.S. Dillon *)
H.S. Dillon *)
*)Executive Director of The Centre for Agricultural Policy Studies (CAPS)
AKHIR-AKHIR ini eskalasi protes petani dalam menuntut keadilan kian menggelinding. Fenomena ini tecermin dari pendudukan tanah-tanah milik Keluarga Cendana, pemaculan tanah lapangan golf di Cimacan, perlawanan petani Lampung, tragedi penembakan petani Sosa di Sumatra Utara, dan lain-lain. Umumnya protes petani itu sendiri dilatari masalah sengketa tanah yang berurat berakar selama puluhan tahun dan belum memberikan asa akan terselesaikan dalam waktu dekat. Berdasarkan laporan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), saat ini diperkirakan ada sekitar 1.742 kasus sengketa tanah yang masih diikuti dengan penangkapan (259 jiwa), penculikan (12 jiwa), penganiayaan (41 jiwa), penembakan (31 jiwa), dan pembunuhan (26 jiwa). Seiring dengan tergelarnya realitas tersebut, kita pun semakin khawatir menyaksikan perkembangan sosial saat ini. Keadaan seakan sedang berada dalam situasi "semi-chaos". Pemerintah pusat mulai digugat oleh rakyatnya. Para politisi digugat oleh konstituennya. Kewibawaan pemerintah mulai melemah dan memudar. Simbol-simbol kekuasaan pemerintah dan pemilik modal dianggap oleh rakyat seakan "berhala" yang selayaknya dihancurkan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai peristiwa perusakan kantor DPRD dan pembakaran kantor pengusaha nasional/lokal di berbagai daerah. Semua tu merefleksikan betapa rasa ketidakpuasan rakyat telah elampaui ambang batas toleransinya. Bagaimana tidak? Di luar masalah ketidakadilan agraria, pemerintah rela mengeluarkan biaya ratusan triliun rupiah untuk menyelamatkan kepentingan para konglomerat, sedangkan pengalokasian anggaran untuk menumbuhkan produktivitas Kaum Tani Indonesia (mayoritas usaha kecil) masih jauh dari memadai. Lihat saja laporan berbagai lembaga studi selama ini mengenai ketimpangan perolehan kredit antara pengusaha besar dan pengusaha kecil, yang berbanding 75:25 (persen), serta tingginya tingkat kesulitan akses yang dialami pengusaha kecil dalam memperoleh kredit. Gerakan petani mendesak kita untuk mulai mempertanyakan ketidakjelasan arah reformasi pembangunan ini. Mungkinkah supremasi hukum ditegakkan di atas rambu-rambu hukum positif produk Orde Baru yang melegitimasi perampasan hak-hak asasi Manusia Petani Indonesia dan masyarakat adat? Mungkin saja ada kearifan, jika kita mau becermin pada kesadaran intelektual generasi Sukarno-Hatta ketika mulai membangun republik ini. Founding fathers itu memiliki kesadaran "menjebol-membangun" sebagai koreksi total terhadap tatanan warisan kolonialisme dan feodalisme. Karena itu, membangun tatanan baru yang bersendikan keadilan, kemanusiaan, dan kemakmuran dipandang sebagai kemutlakan. Kesadaran itulah kemudian yang melatari lahirnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, dan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, sebagai pengejawantahan Pasal 33 UUD 1945. Bila visi ini kita perbandingkan dengan apa yang telah dan sedang dilakukan oleh elite generasi reformasi ini, kita melihat adanya ketimpangan khazanah intelektual yang amat kontras. Sesungguhnya, apakah makna kedua kebijakan itu (UUPA 1960 dan UUPBH 1960) bagi rakyat Indonesia? Kedua kebijakan itu bermakna dimulainya suatu era baru, yaitu era reformasi pertanahan dan tata hubungan produksi di sektor pertanian sebagai landasan dapat terselenggaranya suatu proses pembangunan yang berkeadilan, merata, dan bertanggung jawab. Sebab, sejak zaman feodal dan kolonial, kaum tani selalu diperlakukan tidak adil. Ketidakadilan itu senantiasa mengintai dan menghantui kehidupan mereka, dari mekanisme penguasaan aset ekonomi produktif (tanah), pertukaran komoditi, pembayaran upah, pungutan pajak, sampai sistem produksi (intensifikasi modal), dan lain-lain. Seluruh mekanisme ketidakadilan struktural inilah yang menyebabkan lestarinya kemiskinan dan keterbelakangan Manusia Petani Indonesia selama ini. Jadi, selama seluruh mekanisme ketidakadilan struktural ini tidak dikoreksi secara total, pembangunan yang berkeadilan, merata, dan bertanggung jawab hanyalah fatamorgana belaka, yang tidak pernah tergapai rakyat kecil. Proses reformasi dan demokratisasi sejauh ini belum mengetengahkan upaya yang sungguh-sungguh ingin memecahkan problem-problem struktural yang mengungkung petani. Bahkan, yang lebih terlihat adalah upaya menutup mata atas segenap persoalan struktural tersebut. Lihat saja kebijakan pemerintah baru-baru ini dalam menaikkan harga BBM, yang dipastikan bisa membuat petani memikul beban berat karena biaya transportasi merupakan komponen terbesar dalam menentukan harga komoditi pertanian. Barangkali pernyataan seorang Amartya Sen pantas kita renungkan, dalam mengoreksi asumsi-asumsi dasar yang diyakini selama ini: "Tatkala kebutuhan untuk reformasi ekonomi memberikan peluang lebih besar bagi pasar bebas, justru saat itu sebenarnya pengembangan peluang-peluang sosial yang fundamental (seperti sekolah, pelayanan kesehatan, land reform, dan lain-lain) membutuhkan kebijakan publik yang sangat teliti dan sungguh-sungguh, yang jauh melintasi cakupan pasar semata". Lebih mendasar lagi, Sen mengatakan: "Pembangunan itu pada hakikatnya merupakan suatu proses peningkatan kebebasan manusia dalam berbagai bentuk, yang bukan saja penting secara sendiri-sendiri, tetapi juga saling mendukung. Hal ini memerlukan kemajemukan kelembagaan efektif, di mana pasar memainkan peran yang cukup penting, tetapi juga membutuhkan suplementasi yang sangat kuat dari pelbagai sisi". (Amartya Sen, 1999) Menyimak perkembangan yang sedemikian rupa, saya berkesimpulan bahwa sesungguhnya yang dibutuhkan bukanlah sekadar retorika reformasi, melainkan sebuah revolusi dalam perubahan paradigma dari generasi elite reformasi ini. Sebenarnya soal ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Para petani yang tingkat produktivitas dan kesejahteraannya sudah tinggi pun memberikan perlawanan terhadap globalisasi dan liberalisasi perdagangan. Gagalnya perundingan WTO di Seattle dan perusakan rumah makan McDonald di Prancis sebagai pelambang globalisasi beberapa waktu lalu adalah, terutama, karena penolakan para petani negara maju terhadap globalisasi dan liberalisasi perdagangan. Perlawanan petani ini memaksa kita untuk menilai semua proses yang sedang berlangsung secara jernih. Apakah ada reformasi bila kedaulatan petani tidak ditegakkan? Apakah ada reformasi bila keadilan tidak diwujudkan? Jawabannya jelas tidak. Sebab, kaum tani dan nasibnya adalah representasi kepedihan mayoritas rakyat Indonesia. Sebagaimana jiwa Zapata's "Plan de Ayala" (1911), yang menginginkan socialisation of land: "The lands, forests, and water that have been usurped... will be immediately restored to the villages or citizens who have title to them... because the great majority of Mexicans own nothing more than the land they walk on... One-third of these properties will be expropriated... so that the villages and citizens of Mexico may obtain ejidos, sites for towns, and fields". (Tanah, hutan, dan air yang telah dirampas secara langsung akan diberikan kepada rakyat dan desa-desa sesuai dengan kepemilikannya. Sebab, mayoritas bangsa Mexico tidak memiliki apa-apa selain tanah tempat kakinya berpijak. Sepertiga dari lahan ini akan disita, sehingga desa-desa dan penduduk Mexico akan memiliki "ejidos", lahan untuk tempat tinggal dan ladang.) Reformasi seyogianya bermakna penguatan otonomi rakyat sepenuhnya, yang meliputi masalah penghapusan kepincangan struktural dan pemberdayaan kelembagaan. Hal ini sangat terkait dengan masalah keadilan, pemerataan, dan kemanusiaan. Situasi ini hanya bisa diperbaiki bila kita mau mengubah kerangka kerja dasar pembangunan (produksi dan konsumsi) selama ini, dan menggantinya dengan sebuah kerangka kerja dasar yang dapat menjamin keadilan bagi rakyat dan memberikan perlindungan lingkungan hidup secara sistematis. Kinilah saat yang tepat untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia Indonesia, dan mengakhiri segala bentuk diskriminasi. Pembaruan agraria mutlak harus dilakukan, mengingat rata-rata luas usaha Manusia Petani Indonesia hanya sekitar 0,74 ha. Seiring dengan itu, kita pun harus berani menjebol seluruh kelembagaan ekstraktif untuk membangun sistem kelembagaan yang representatif. Sebab, sejarah pembangunan ekonomi bangsa-bangsa maju membuktikan bahwa pembaruan agraria dan pembaruan kelembagaan ternyata lebih berpengaruh bagi perkembangan ekonomi daripada sekadar kepentingan perubahan teknologi dan kebutuhan investasi asing. Karena itu, pertanian tidak dapat lagi dipandang dalam perspektif sektoral yang sempit, tetapi harus dilihat sebagai peluang untuk membangun fundamental ekonomi bangsa yang kokoh menuju kemandirian. Dengan kata lain, peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani merupakan landasan pembangunan bangsa. Selagi kita masih merupakan masyarakat agraris dengan jumlah penduduk yang sangat besar, proses peningkatan produktivitas pertanian tidak boleh terlepas dari proses peningkatan penghasilan petani dan upah buruh tani. Artinya, kita harus mampu merakit kebijakan sedemikian rupa sehingga pola pembentukan modal senantiasa terarah pada peningkatan produktivitas mayoritas warga bangsa. Dalam era keterbukaan dan keseketikaan yang dibawa oleh globalisasi dan liberalisasi perdagangan/investasi, tidak mungkin kita menuntut petani dan masyarakat untuk tetap bersabar. Melalui tindakan nyata, elite bangsa harus mampu tetap menyalakan bara pengharapan bagi rakyat kecil, terutama para petani dan buruh tani. Ini baru akan dapat dicapai kalau segenap elite penguasa negeri ini mau menoleh kembali visi para pendiri Republik, dan meletakkan nasib Manusia Petani Indonesia sebagai "apinya" reformasi saat ini. Selama hal ini belum terwujud, kita akan terus melihat Manusia Petani Indonesia mengadakan perlawanan menuntut keadilan, betapapun lemahnya kekuatan mereka. Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini  Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
 Edisi 1 Januari 2001  PODCAST REKOMENDASI TEMPO cari-angin marginalia bahasa  Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini Jaringan Media © 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum |