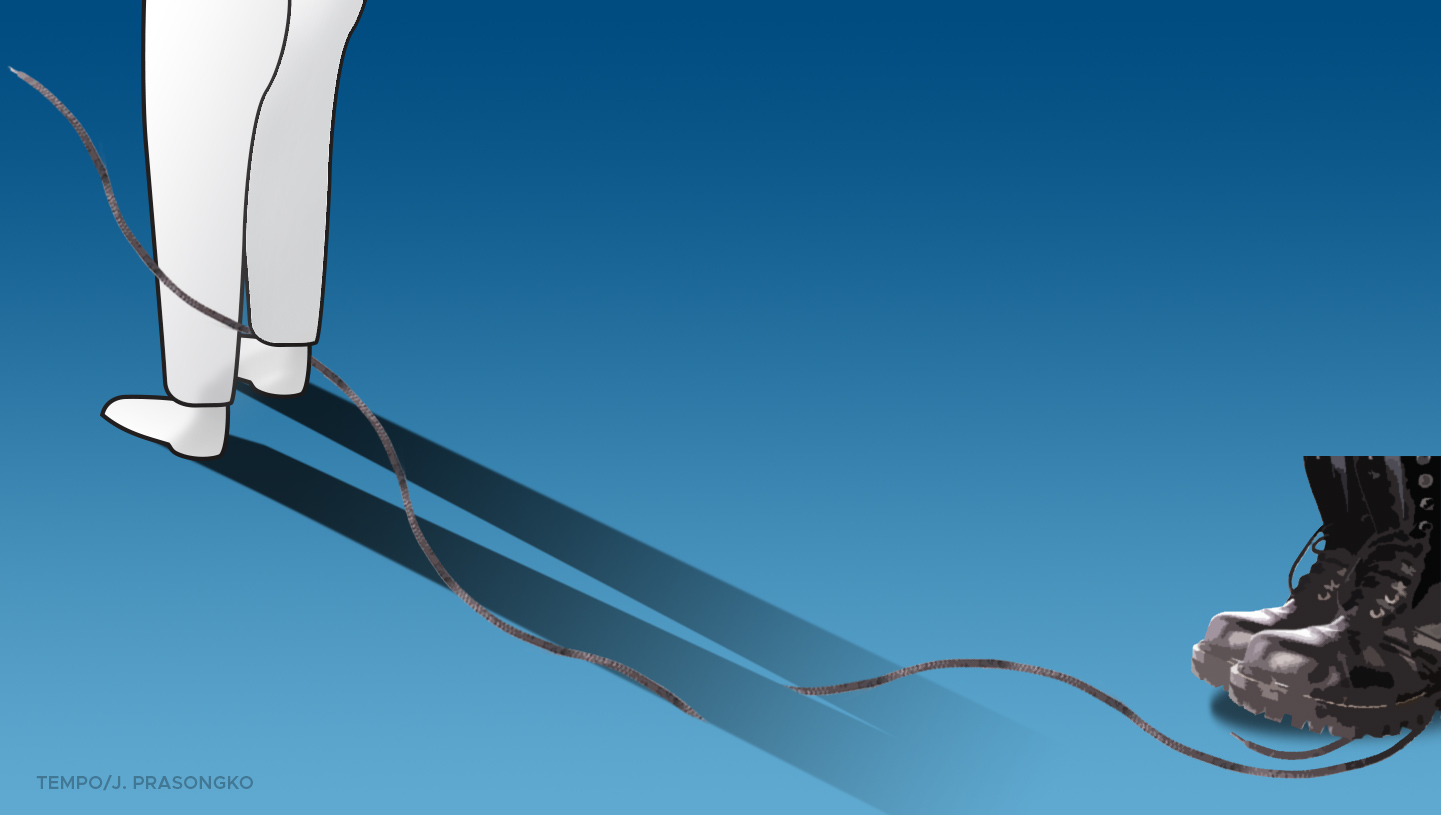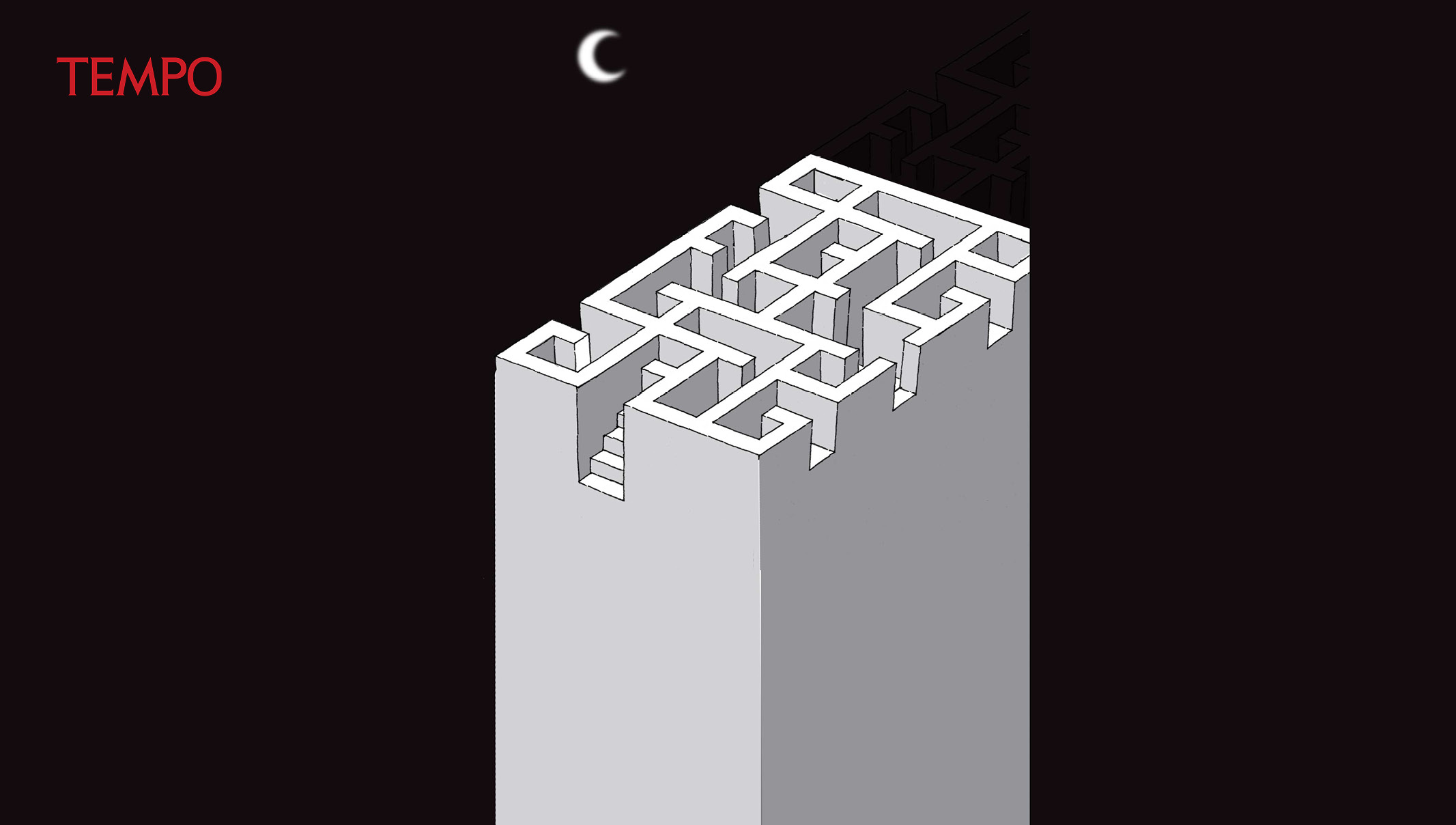Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ramdan Malik
Wartawan
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kabar bohong (hoaks) atau berita rekayasa (fake news) dengan memainkan sentimen agama bukan monopoli "serdadu papan ketik" lewat media sosial dalam pertarungan politik mutakhir. Setelah Gerakan 30 September (G30S) 1965 yang mengawali transisi Orde Lama ke Orde Baru, hoaks telah memicu emosi kolektif yang melahirkan kekerasan, diskriminasi, dan ketidakadilan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Setelah mayat tujuh perwira tentara Nasional Indonesia (TNI)dahulu Angkatan Bersenjata Republik Indonesiayang dibunuh oleh G30S pimpinan Letnan Kolonel Untung ditemukan di Lubang Buaya, Jakarta Timur, pada 4 Oktober 1965, pada hari itu juga koran TNI, Berita Yudha, menuding Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai dalang G30S. Hal ini diikuti unjuk rasa pertama yang menuntut pembubaran PKI.
Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) dan Pemuda Rakyat, dua onderbouw PKI, dituduh sebagai pelaku utamanya. Foto-foto penemuan jasad para perwira di Lubang Buaya terpampang di halaman muka dua koran yang disponsori Angkatan Darat, Berita Yudha dan Angkatan Bersenjata, pada 5 Oktober. Ini dilengkapi dengan pernyataan Soeharto: "Pembunuhan para jenderal yang paling menyedihkan terletak pada dugaan penyiksaan dan pemotongan alat kelamin oleh pemuda dan wanita komunis." (Anderson & McVey, 2001).
Kemarahan masyarakat pun tersulut. Tapi Soe Hok Gie tidak. Kendati menjadi salah seorang arsitek unjuk rasa mahasiswa yang menumbangkan Sukarno, Gie adalah orang Indonesia pertama yang mengkritik pembantaian anggota dan simpatisan PKI.
Di koran Mahasiswa Indonesia yang terbit pada Desember 1967, Gie menulis tentang pembunuhan massal di Bali, provinsi dengan korban terbesar setelah Jawa Tengah dan Jawa Timur. "Di akhir tahun 1965 dan sekitar permulaan tahun 1966, di pulau yang indah ini telah terjadi suatu malapetaka yang mengerikan, suatu penyembelihan besar-besaran yang mungkin tiada taranya dalam zaman modern ini, baik dari waktu yang begitu singkat maupun dari jumlah mereka yang disembelih," demikian ia menulis.
Pembunuhan itu, kata Gie, telah menelan korban sekurang-kurangnya 80 ribu jiwa. Rumah-rumah dibakar dan pemerkosaan terhadap mereka yang dituduh Gerwani menjalar ke mana-mana, "dan dicontohi oleh pemuka partai setempat." (Gie, 1995).
Padahal Presiden Sukarno sudah membantah soal mutilasi jenazah para perwira tersebut. "Dalam pidato-pidato pada 12 dan 22 Desember, Presiden menyatakan bahwa para dokter yang meneliti mayat-mayat itu melaporkan tidak terjadi pencungkilan mata dan pemotongan alat kelamin seperti yang disebutkan dalam berita Angkatan Darat." (Anderson & McVey, 2001).
Banalitas massa yang dipicu sentimen agama tersebut berujung pembubaran PKI setelah Sukarno mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) kepada Panglima Angkatan Darat Soeharto pada 1966. Bandul segitiga pertarungan kekuasaan elite politik pun berayun dari PKI ke TNI, hingga akhirnya Soeharto diangkat menjadi presiden oleh parlemen setahun kemudian. Ini sebuah suksesi berkat hoaks yang mungkin terbesar dalam sejarah Indonesia.
Hoaks atau berita rekayasa oleh media massa yang dimiliki militer berbalut masalah moral yang peka bagi pemeluk agama bagaikan bensin yang menyulut api kemarahan massal setelah September 1965. Sebagai intelektual bebas, Soe Hok Gie melawannya dengan risiko teror karena memprotes pembunuhan massal di Bali, penahanan anggota dan simpatisan PKI, serta diskriminasi terhadap keluarga mereka. Dia hampir ditabrak mobil yang pengemudinya melempar gulungan kertas bertulisan "Tjina + PKI = Mati".
Dalam Catatan Seorang Demonstran, pada 7 dan 16 Agustus 1968, Gie menegaskan sikapnya: "Menghadapi kekejaman-kekejaman ini, orang hanya punya dua pilihan: menjadi apatis atau ikut arus. Tapi syukur ada pilihan ketiga: menjadi manusia bebas… Seseorang dinilai oleh keterusterangan dari keberanian moralnya." (Gie, 1983).
Cendekiawan merdeka semacam Gie inilah yang dibutuhkan pada era media sosial kini agar masyarakat tak terbelah oleh kabar bohong berkedok isu suku, agama, ras, dan antar-golongan. Kendati telah wafat hampir setengah abad silam, ia seakan-akan menjadi cermin zaman. Ketika banyak orang pintar tenggelam dalam fanatisme buta menjelang pemilihan presiden, tsunami hoaks menantang siapa pun untuk melawannya dengan argumentasi yang cendekia serta bernurani.