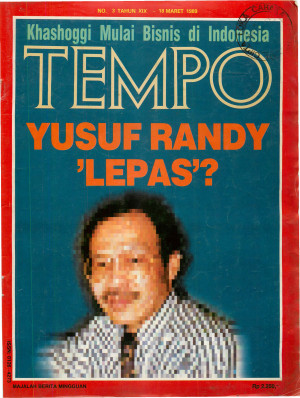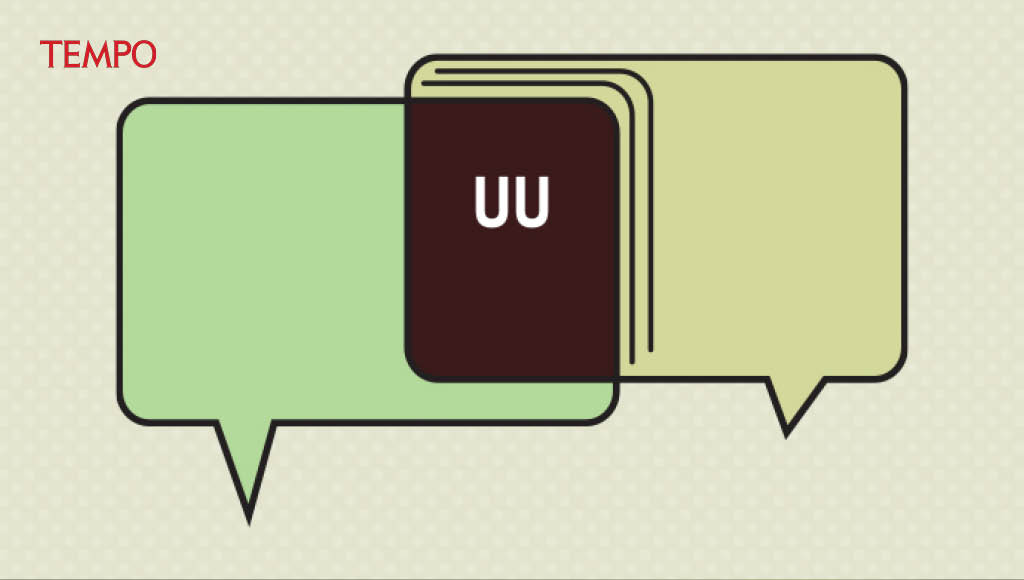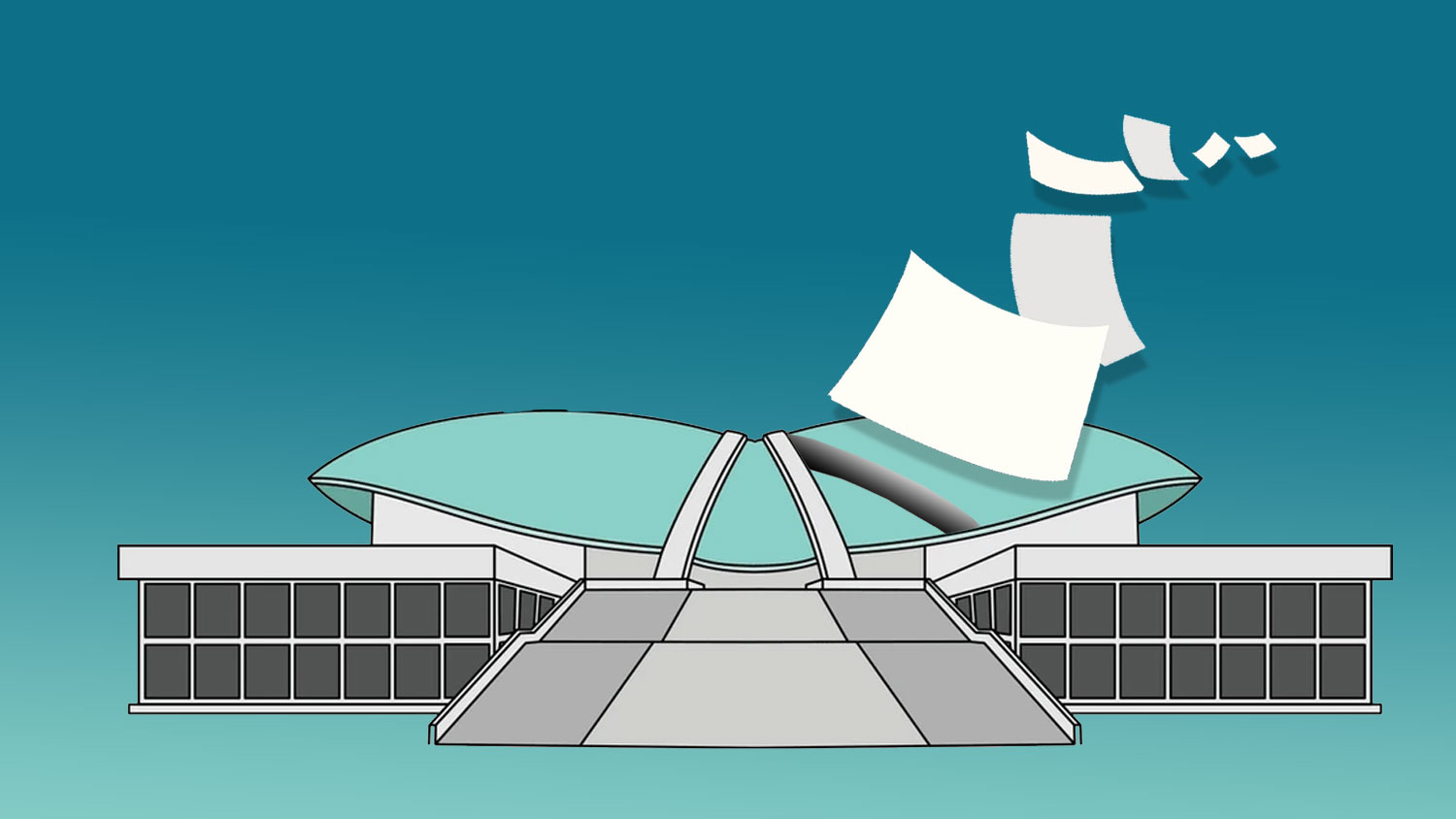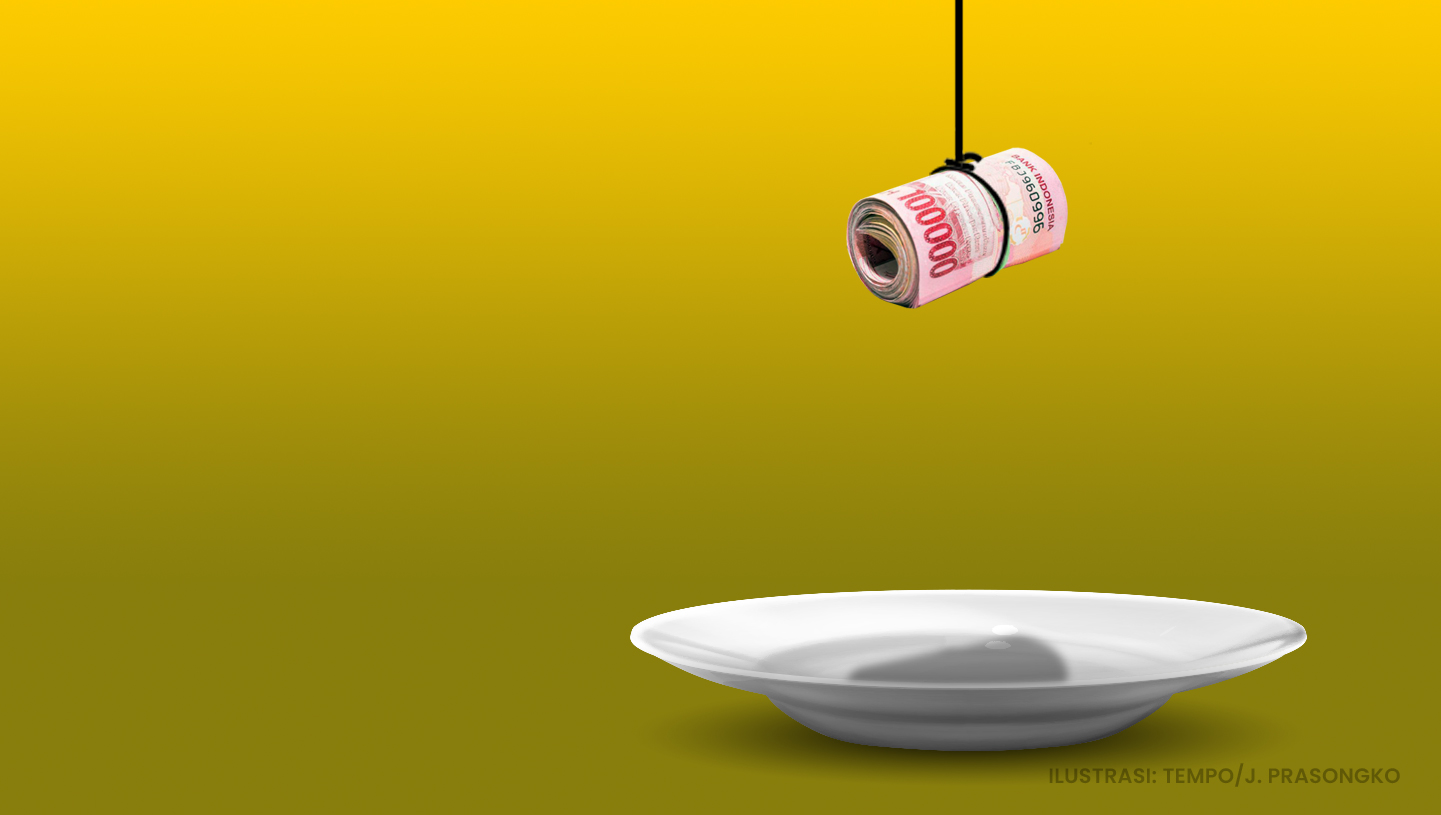UPACARA jumenengan Sultan Hamengku Buwono X punya akar yang panjang. Ia memiliki dasar tradisional dari konsep politik -- konsep mengenai kedudukan raja dan kerajaan -- yang terdapat di banyak daerah di Asia Tenggara. Upacara, simbolisme kekuasaan, dan struktur politik yang ada berasal dari pengaruh kebudayaan Hindu, atau lebih baik Sanskerta, sejak kira-kira abad pertama Masehi. Pengaruh itu berkisar pada konsep "deva-raja". Akar Sanskerta ini bertahan di Jawa biarpun melalui perubahan agama, datangnya kolonialisme, modernisasi, dan lain-lain. Upacara jumenengan HB X mungkin, seperti halnya upacara penobatan raja Muangthai, adalah contohnya. Dalam detail, upacara penobatan raja Muangthai dan HB X banyak berbeda. Namun, dasar konsepnya banyak bermiripan. Kata Siti-Inggil, misalnya. Inilah tempat keramat dari kerajaan tradisional yang mengingatkan kita pada mitologi Hindu: bahwa para dewa tinggal di puncak gunung. Siti-Inggil berarti "tanah yang tinggi", atau gunung. Artinya, raja -- seperti juga para pangeran dan abdi dalem keraton -- tinggal secara simbolis di atas gunung. Angka Keramat Yang juga merupakan petunjuk adalah soal angka yang dianggap keramat. Perubahan lambang keraton Yogyakarta dari sembilan sayap jadi sepuluh sayap, kita tahu, telah menyebabkan sedikit heboh dari para pangeran tua. Hal ini tak mengherankan. Angka 9 dalam konsepsi kerajaan tradisional adalah keramat. Dalam pemerintahan kerajaan juga terdapat empat bupati luar dan empat bupati dalam. Dengan adanya seorang patih, jumlahnya jadi sembilan. Demikian pula bintang pusaka yang ada di dada Sultan HB X: pucuknya 8, dan pribadi Sultan sendiri merupakan pucuk ke-9. Tarian bedoyo -- yang melambangkan pernikahan antara raja Mataram dan Nyai Roro Kidul -- juga punya sembilan penari. Angka 9 adalah salah satu di antara angka yang dianggap keramat dalam konsepsi Asia Tenggara tradisional. Yang lain adalah 7, 5 atau 3, dan 1. Tak mengherankan kalau Bung Karno memformulasikan Pancasila, yang kemudian dikatakan "dapat diperas" jadi Tiga Sila, bahkan jadi Satu Sila. Di samping angka keramat, peta perbintangan di alam semesta merupakan pola lain yang mempengaruhi susunan tradisional. Susunan kompleks keraton, seperti juga formasi tentara tradisional, mengambil peta langit. Demikian juga tarian bedoyo, letak posisi pusaka-pusaka keramat, yang dalam upacara jumenengan ada di belakang dan depan takhta Siti-Inggil. Angka keramat dan pengaruh peta alam semesta, konsep yang di Indonesia sumbernya terpokok adalah India, sebenarnya punya sejarah yang kuno, yakni dari Mesir dan Timur Tengah lama yang juga menyebar ke Cina. Dari Cina ini datang pengaruh budaya lain ke Asia Tenggara. Karena dua pengaruh inilah, menurut Heine-Geldern, sarjana klasik mengenai konsep politik tradisional Asia Tenggara, makna keramat dari angka dan dari peta langit membudaya sampai kini. Istilah keramat mengandung aspek magi yang sangat kuat, yakni untuk memperbesar wibawa, karisma, dan kekuasaan raja, yang disamakan dengan dewa di dunia. Upacara Kirab Pada jumenengan HB X diadakan upacara kirab, yakni prosesi mengelilingi dinding-dinding seputar kompleks keraton. Upacara mana sebenarnya yang lebih penting, upacara penobatan, atau kirab? Ini bersangkutan juga dengan persoalan: mana yang lebih magis, pribadi raja atau keratonnya? Di zaman dahulu, jawabnya tergantung situasi politik di sekitar kerajaan. Konsep "deva-raja" yang penuh magi memang secara teoretis memberikan kekuasaan mutlak pada raja. Tapi, dalam prakteknya, justru itu melemahkan kedudukannya: menjadikannya sasaran yang diperebutkan. Bila magi terletak para pribadi raja, maka, bila raja dibunuh, magi kerajaan jatuh pada sang pembunuh, seperti ketika Ken Arok membunuh Tunggul Ametung dan menggantikannya. Bila magi kerajaan dianggap terletak pada keraton, atau pada pusaka-pusaka keraton, maka cukuplah orang merebutnya. Para pemberontak pada akhir abad ke-19 di Mangkunegaran misalnya menduduki vila Mangkunegara di Temanggung karena tempat itu dianggap posisi magis. Ketika kerajaan Burma dalam abad ke-19 menghadapi Inggris dan istana Burma berada dalam keadaan terpecah-belah, raja terakhir Mindon Minh tak berani mengadakan upacara kirab mengelilingi keraton karena khawatir bahwa, ketika ia tak di sana, keraton akan diduduki oleh salah seorang perebut. Dengan singkat upacara kirab mengandung banyak bahaya bagi seorang raja yang baru diangkat. Sudah lama di Jawa tak ada lagi ancaman terhadap raja baru, tetapi pada upacara kirab HB X kita tetap diingatkan pada masa lampau. Ketika HB X melakukan upacara kirab dengan menaiki kereta Kyai Garuda Yekso, announcer memperingatkan pada para penjaga untuk melindungi Permaisuri dan para kerabat keraton -- seakan-akan suatu bahaya masih mengancam mereka ini. Tiba kembalinya HB X dari kirab ke keraton disambut dengan syukur pada Tuhan yang Mahakuasa. Kecemasan yang tercermin dari masa lampau itu dikatakan masih mempengaruhi elite politik kini. Bila benar, itu artinya setiap proses pergantian dianggap mengandung bahaya. Negara-Teater Aspek upacara dalam kehidupan negara di Asia Tenggara sangat penting. Kadang terkesan bahwa justru yang penting itu adalah upacaranya. Upacara memberi makna magis pada negara, sedangkan, menurut konsep tradisional, aspek magis itu adalah inti kekuasaan. Aspek ini malah jauh lebih penting dibanding dengan akar-akar pelembagaannya, misalnya hukum. Sarjana antropologi Clifford Geertz menyebut negara tradisional sebagai "negara-teater", karena aspek teater atau panggung dari negara merupakan inti eksistensinya. Masyarakat pun hidup seakan-akan bagi upacara, seperti yang nampak di Bali dan Toraja: di akhir hidup, ada upacara kematian yang besar-besaran. Dalam pidato jumenengannya, HB X menekankan fungsi keraton sebagai lembaga pelestarian budaya. Dengan sendirinya, ini akan menonjolkan aspek teater dari kesultanan Yogyakarta. Seperti kerajaan-kerajaan lain di wilayah bekas Hindia Belanda yang kini Republik Indonesia, sebenarnya sudah lama fungsi itu berlangsung demikian. Di Yogya, masyarakat ternyata menyambut dengan hangat upacara jumenengan yang baru lalu itu meskipun tak lagi dengan ndodok (berjongkok) dan sembah. Mungkin ini petunjuk masih berakar dan membudayanya lembaga keraton Yogyakarta di masyarakat. Dengan sendirinya, selama lembaga keraton berdiri upacara-upacara harus tetap dilakukan untuk tetap bermakna.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini