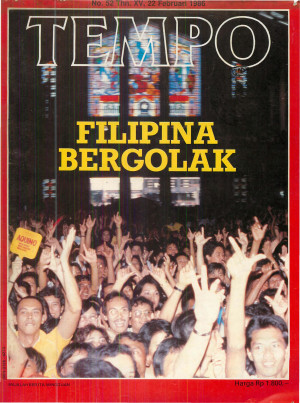APA yang kita pikirkan tentang kampung halaman? Seorang perempuan tua tegak di depan pintu rumahnya, di Jakarta. Ia menatap jalan. Dan kendaraan hilir-mudik. Ia kenal Empok Inah yang punya anak Saleha dan Taris. Suaminya seharian bekerja sebagai kuli bangunan. Ia kenal Sawah Besar, Pasar Minggu, juga Tangerang. Dan selama lebih dari dua dasawarsa perempuan itu mengajar di Jakarta. Seperti dia, anak-anaknya yang banyak telah lekat dengan Jakarta. Bersama suami dan anak-anaknya, ia sudah terbiasa menghirup udara yang hiruk. Tapi, tiga puluh atau tiga puluh dua tahun yang lalu dia masih tinggal di Susoh, di pelosok ujung Sumatera. Alangkah jauhnya. Dari dusunnya, setiap hari ia berangkat ke Lam Kuta. Di sana ada Sekolah Rakyat Islam (SRI), tempat ia belajar di masa kanak-kanak dan kemudian mengajar. Ustad Sayed Saleh, gurunya dan kepala sekolah, mendendangkan lagu: Sekarang telah tiba waktu 'ku rayu dan susah Hati bertambah iba karena akan berpisah Di pantai telah berlabuh kapal api yang besar Menunggu waktu subuh Aku akan berlayar Lagu itu mungkin tidak untuk mengantarkannya pergi. Tapi lagu itu begitu tersosialisasikan hingga kini. Dan dia memang pergi dengan seuntai sajak yang ditempelkan di lemari tua: Tinggallah ranah tinggallah tepian tempat mandi .... Sajak itu kini telah hilang. Apakah yang kita pikirkan tentang kampung halaman? Di sebuah flat di Tampines, Singapura, saya mengunjungi sebuah keluarga Melayu. Hampir separuh anak-anaknya tidak di kampung. Seorang sedang belajar di Mesir. Seorang di Saudi, seorang lainnya di Indonesia. Dengan tetap, keluarga itu mengirimkan biaya untuk anak-anaknya belajar. Bertahun-tahun -- lima tahun atau tujuh tahun. Dan anak-anak itu mungkin tak akan pernah kembali. Akan bercinta dengan gadis atau pemuda setempat, lalu mungkin menikah dan menetap di sana. Apa arti kampung bagi mereka? Singapura bisa jadi bukan tempat yang layak untuk membangun ikatan emosional: negara kota yang kapitalis itu telah mengubah hubungan-hubungan manusia menjadi impersonal. Dan kampung-kampung Melayu yang ditutupi pepohonan rimbun sirna oleh derap efisiensi dan perhitungan ekonomis rasional. Mereka terlempar ke dalam flat-flat. Tidak ada lagi perkauman di sana. Tidak ada kenduri. Tidak ada yang memelihara ayam atau kambing. Dan kokok ayam di subuh hari telah dikonsentrasikan ke dalam industri ternak massal. Oo, Haslinda. Apa yang kita pikirkan tentang kampung halaman ? Tentang ngarai dan lereng? Tentang Danau Maninjau yang hening tenang, tempat Hamka di masa kecil menatap hari depannya? Di Honolulu saya sempat menghadiri pengajian mahasiswa Indonesia. Ada acara perpisahan. Sebagian dari mereka akan berangkat ke main land -- demikian mereka menyebut dataran Amerika. Ada yang berpidato: "Kita adalah musafir. Banyak hal yang akan kita lihat. Banyak cobaan. Maka perkuatlah khittah, perkuatlah iman. Jaga kepribadian kita sebagai umat Islam, sebagai bangsa Indonesia". Dan setelah itu, atau beberapa hari setelah itu, mereka berangkat. Mereka mungkin akan disergap gedung-gedung pencakar langit, di New York atau Chicago. Disergap oleh kesunyian emosional. Atau malah sebaliknya. Tapi, apa yang dimaksud dengan musafir? Mungkin itu hanya konsep untuk menggambarkan suasana kesementaraan. Juga suatu petunjuk teknik peribadatan yang tertera dalam fiqh: seseorang yang sedang menjadi musafir mendapat dispensasi untuk mengurangi ritual tertentu peribadatannya. Agaknya, pengertian yang pertamalah yang dimaksud. Para mahasiswa itu akan hidup untuk sementara, di negeri orang. Namun, bukankah sebenarnya konsep musafir juga mengena pada perempuan tua itu, dan juga keluarga Melayu? Bahkan kita semua? Kampuang bagi perempuan itu menjadi tidak jelas. Ia pernah kembali ke dusunnya, dan di sana ia disambut mengharu biru -- bagai anak yang telah hilang, layaknya. Toh telah terjadinya transformasi dalam dirinya. Ia menghayati kehadiran dirinya di kampuang justru sementara -- untuk kemudian kembali lagi. Ia mungkin merasa terikat di kampuang -- secara emosional, tidak secara rasional. Dan orang-orang di kampung itu? Konsep musafir juga terkena kepada mereka. Sebelum mereka berpisah, mungkin sebagian masih gadis. Tapi tiga puluh tahun kemudian banyak di antara mereka telah menjadi nenek atau kakek. Kampuang ternyata juga berubah. Maka, musafir yang sebenarnya adalah hidup itu sendiri. Mungkin. Hidup yang penuh gerak dan perubahan. Perempuan tua itu menempelkan sajaknya di dinding lemari tua itu, untuk kemudian tidak kembali. Anak-anak keluarga Melayu hidup dalam transformasi kepribadian yang berbeda dengan orangtua mereka -- bahkan mungkin dari segi fisik dan geografi. Dan para mahasiswa Indonesia di Amerika -- tetapi juga di sini -- akan gagal mengembalikan asyik-masyuk masa lampau, sebagaimana yang dahulu ditemuinya. Apa yang kita pikirkan tentang kampung halaman? Di Susoh, Blang Pidie, kampuang begitu diidealisasikan: Bagai tampak negeriku walau hanya bayangan Kampungku di alam pergunungan Padahal desa itu desa pantai.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini