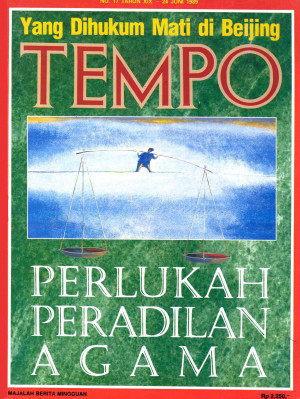GAJAH mati meninggalkan gading, Khomeini pergi meninggalkan milik yang tak sekemilau gading: sepetak tanah, sebuah rumah tanpa perabot, sepotong sajak. Apakah definisi seorang besar? Orang besar adalah orang yang mampu mengatasi ruangan jiwanya sendiri yang hendak diimpit benda-benda, karena ia menghendaki suatu kebebasan yang lebih punya arti. Orang besar adalah orang yang bekerja untuk akhirat seperti ia akan mati besok, dan bekerja untuk dunia seperti ia akan hidup selama-lamanya -- tapi bukan dengan keserakahan untuk dirinya sendiri. Bagaimanapun berbeda pandangan Khomeini dengan Gandhi dan Mao, ketiga orang ini punya satu hal yang sama: bagi mereka, cita-cita perubahan dunia adalah sesuatu yang teramat penting, yang begitu memukau, hingga milik dan kekayaan hanya terasa menggangu. "Revolusi bukanlah sebuah jamuan makan," kita ingat kata-kata itu. Manusia biasa, yang tidak berukuran besar, tak mampu untuk puasa panjang sekeras itu. aaaaaamereka tak mampu menanggung beban sebuah ide. Mereka mungkin ingin mengubah dunia, tapi sejauh mana, sepanjang kapan? Bagi orang kebanyakan, ikhtiar perubahan dunia pada suatu saat perlu jeda. Bagi seorang seperti Khomeini, Mao, atau Gandhi, ikhtiaritu tak pernah selesai kita hanya mengabaikannya beberapa kali. Sebab itulah orang kebanyakan kagum, gentar, ngungun, rebah, di bawah bayang-bayang orang besar. Mereka kalah stamina mental, mereka bertanya-tanya dari mana datangnya kekuatan dahsyat itu, lalu mereka tahu bahwa mereka memerlukan sosok luar biasa itu untuk mereka ikuti. Sering mereka menyerah dan taklid. Sering mereka mendapatkan ketenteraman yang tulus di tempat yang terlindung itu. Lalu pada suatu hari yang penih ilham, akan datang sebuah ide: "Kita harus mengikuti tauladannya." Dan ajaran-ajaran pun disusun, lalu disebarluaskan. Dari suatu krisis yang gawat, memang biasa lahir seorang pemimpin yang dituntut untuk jadi komplet: bukan hanya seorang pemimpin politik, bukan hanya seorang manajer kebersamaan, tapi juga sebuah mercu suar moral. Di dunia kini ada negeri-negeri yang terguncang, oleh revolusi ataupun oleh kelahiran diri yang mendadak. Di sana masa lalu dipatahkan, acapkali secara getas, dengan masa kini dan masa depan. Di negeri seperti itu ukuran-ukuran pun berseliweran, tabrak-menabrak. Dan orang gelisah, mengikuti ini mengikuti itu, dan mencari patokan perilaku. Tak mengherankan bila ide kepemimpinan komplet dengan cepat disambut. Gerakan "mengikuti jejak" dengan segera jadi gerakan pewejangan kebajikan, mobilisasi petuah dan penatran P-4. Disadari atau tidak, dengan itu semua kita menyusun sebuah dasar legitimasi tersendiri: para pemimpin, mereka yang berada di lapis atas kekuasaan, baru kita terima bila mereka mengekspresikan kemurnian moral. Di tahun 1950-an Bung Hatta menghendaki "pemimpin-pemimpin yang jujur dan disegani". Betapa bagusnya. Tapi dalam beberapa dawarsa ini, kita, di negeri-negeri yang terguncang ini, toh bertambah tua dengan rasa kecewa dan sedikit arif. Kita kemudian tahu bahwa legitimasi kekuasaan yang bersandar pada moralitas adalah sebuah legitimasi yang belum selesai. Ia tak memadai. Ia bahkan punya kekacauannya sendiri. Moralitas seorang pemimpin memang bisa punya kekuatan sebagai tauladan. Tapi mungkin cuma sampai di situ. Sebab, tak semua orang Iran adalah Khomeini, sebagaimana tak semua orang Cina adalah Mao dan tak semua orang India adalah Gandhi. Sebagian besar manusia, di mana pun, juga bukanlah orang-orang besar, yang jujur, mulia, berbudi. Maka, tatkala orang besar pergi, dan yang ditinggalkan adalah sebuah negeri yang kehilangan, kita pun insyaf betapa kita abai: kita tak menyiapkan suatu sistem yang sedapat mungkin bisa mengatur apa dan bagaimana sesuatu bisa disebut "jujur", "mulia", atau "berbudi". Pendek kata: kita tidak mengembangkan dasar legitimasi itu dari moralitas menjadi hukum. "Hukum" di sini, mau tak mau berarti hukum yang disepakati bersama secara sukarela. Tanpa itu, legitimasi yang ada hanya semu dan kacau. Tanpa itu, segala ketentuan bisa sangat tergantung hanya pada ketuntuan bisa sangat bergantung hanya pada ketentuan moral yang diputuskan dari satu sisi. Kita mungkin juga akan lupa, selagi sibuk berbicara tentang moralitas pemimpin, bahwa kekuasaan bukanlah hal yang "sepi ing pamrih". Kekuasaan juga bisa mengandung kepentingannya sendiri. Demokrasi dengan hukum yang pasti karena itu perlu. Hidup tak cukup dengan orang besar se-Khomeini.Goenawan Mohamad
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini