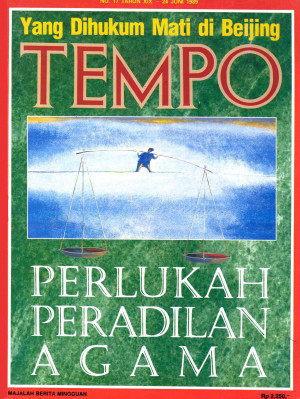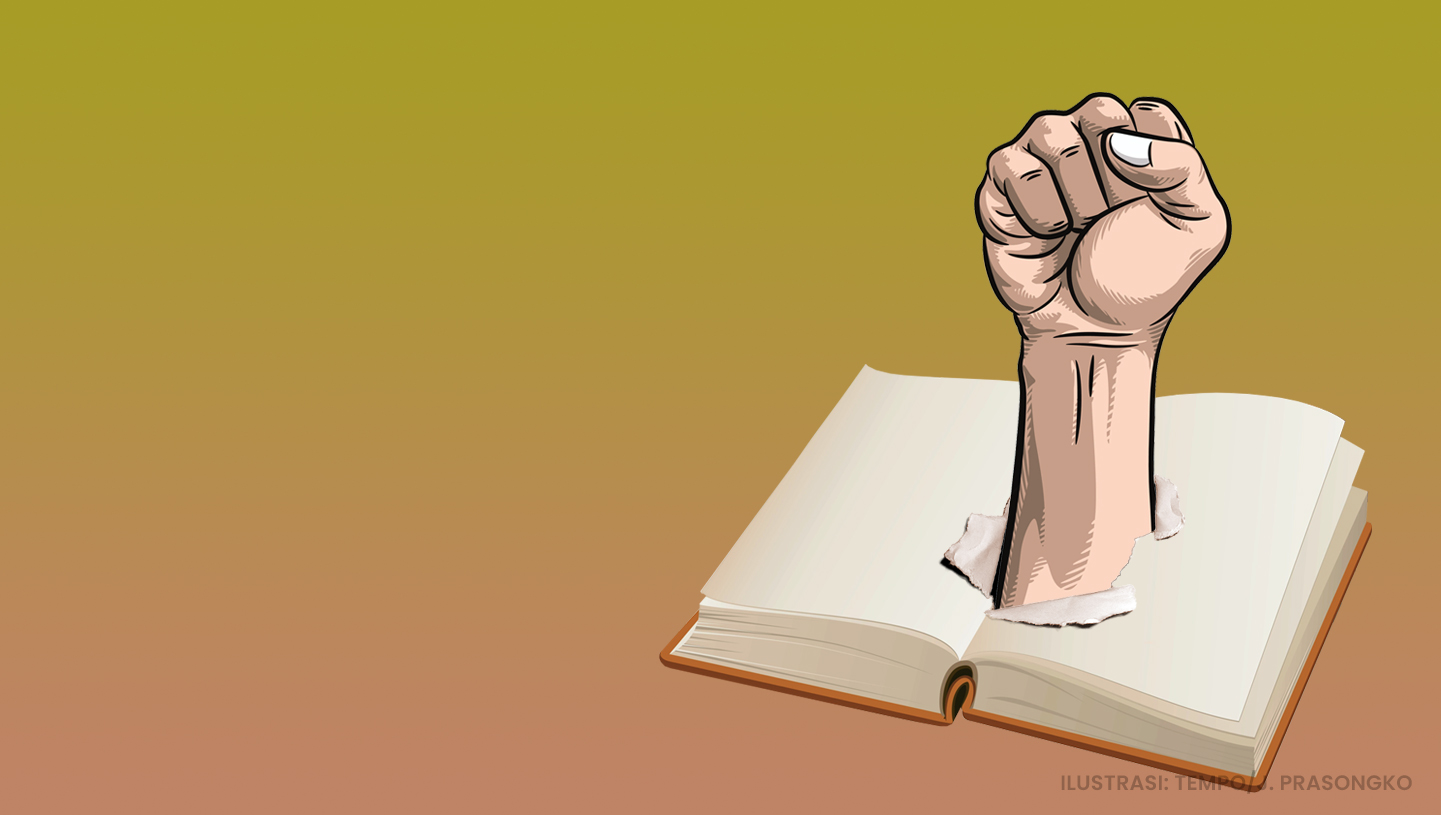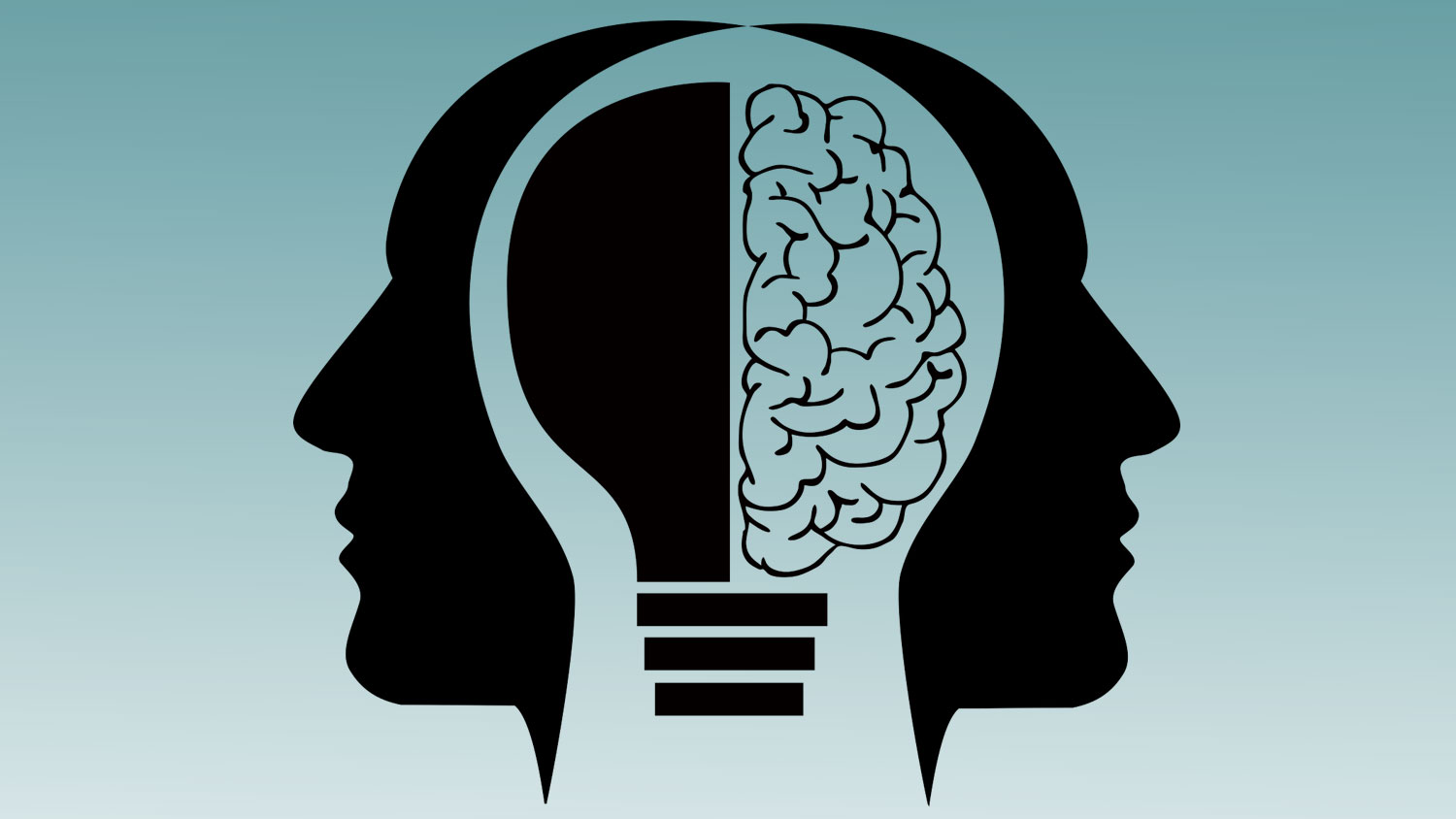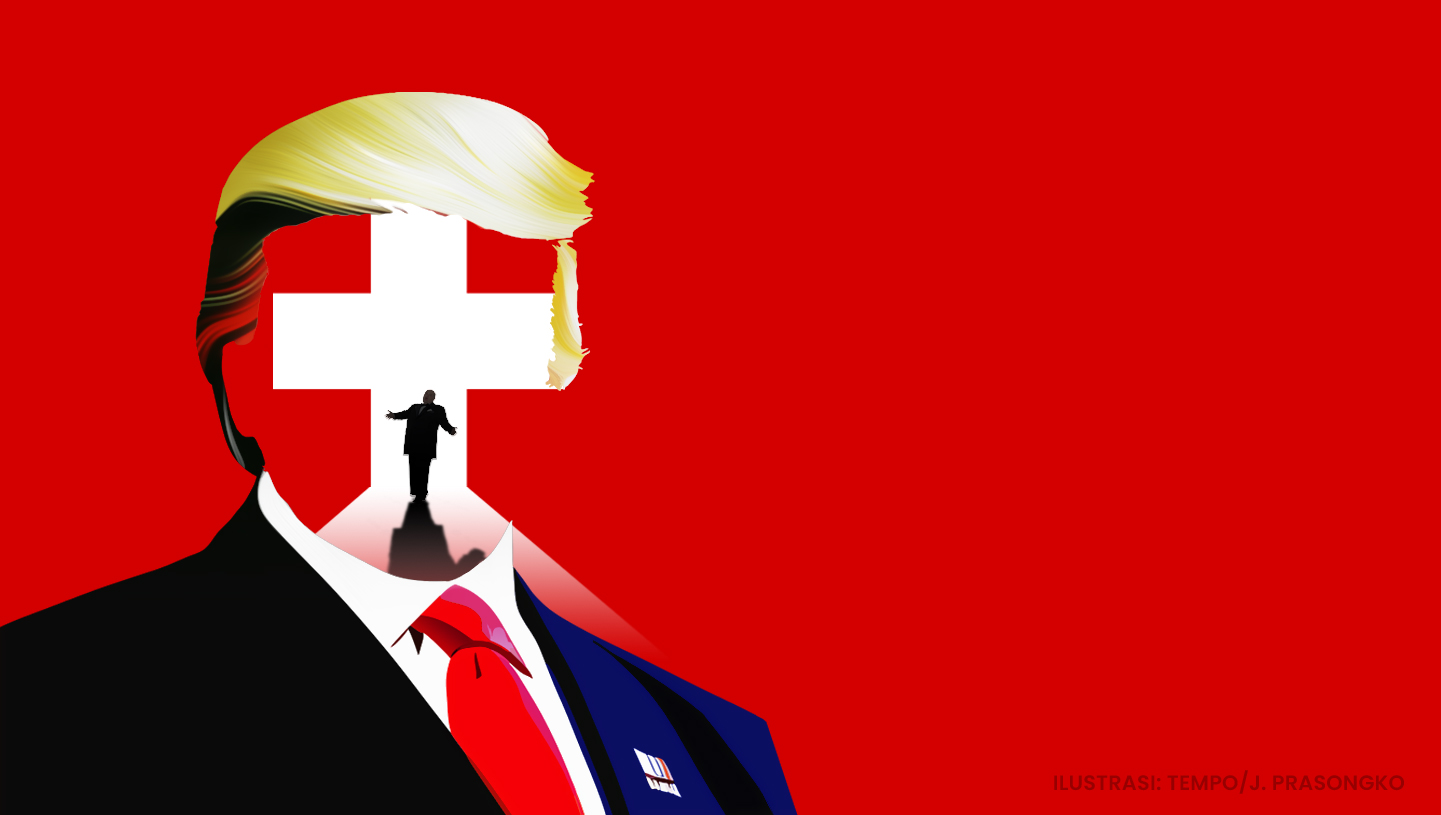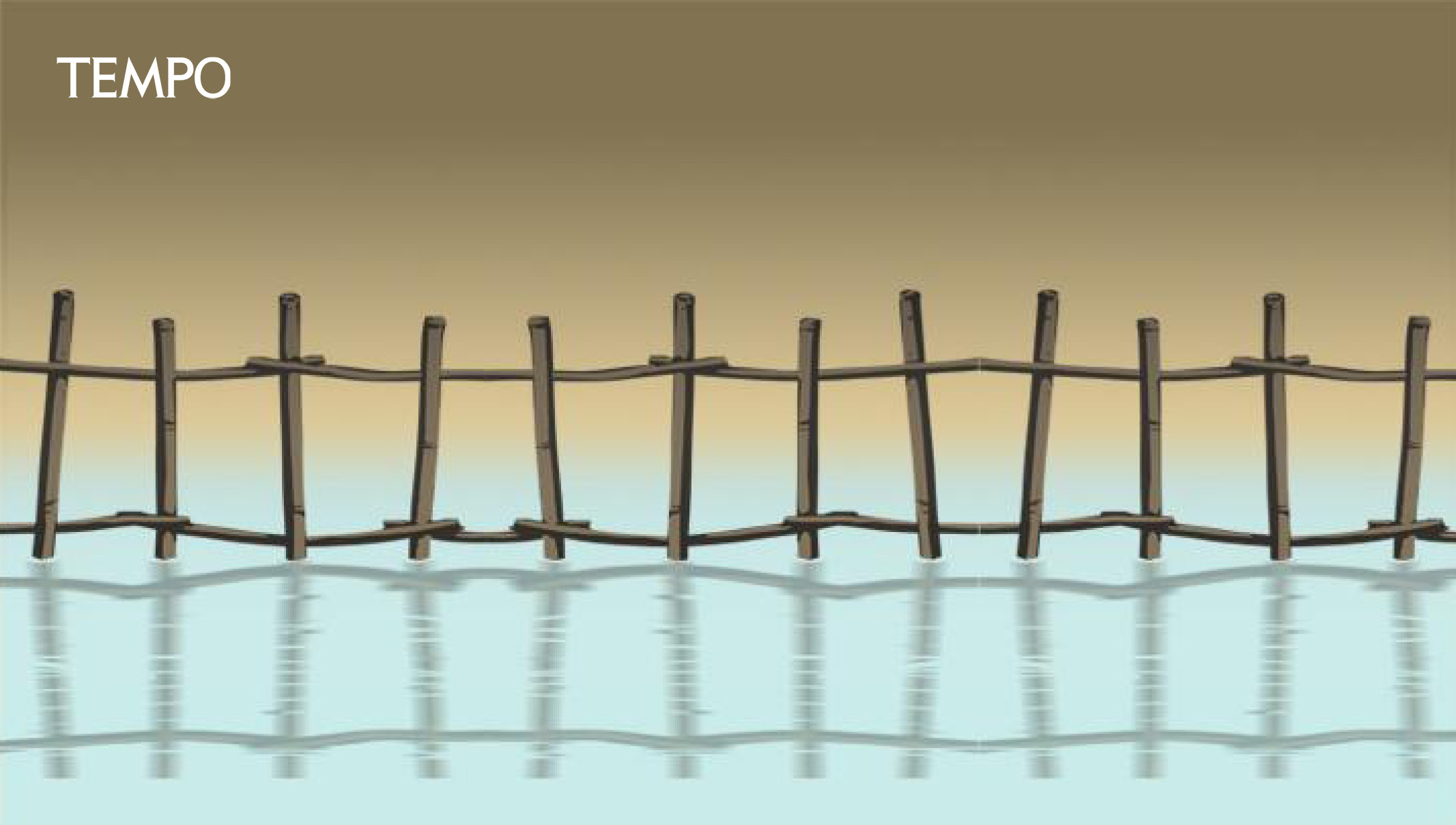DI kantor itu, segerombolan penduduk, laki-laki dan perempuan, tua dan muda, duduk bersila di atas lantai atau duduk di atas tembok rendah setengah badan. Caping yang biasanya mereka kenakan di sawah tampak berserakan di lantai. Hari itu, di kantor kelurahan Desa Sidomulyo, Kulonprogo, Yogyakarta, mereka sedang menunggu giliran menghadap pejabat desa untuk urusannya masing-masing. Suatu pemandangan yang mengingatkan kita pada situasi sistem perkebunan kolonial di masa lampau, ketika - seperti dilukiskan oleh Uemura Yasuo - "sandiwara" pembayaran sewa tanah berlangsung. Para petani menandatangani kontrak - tentu saja dengan cap jempol - dan kepala desa mengumpulkan uang sewa tersebut untuk diserahkan kepada dinas pajak. Dan para petani itu - dengan kepatuhan yang luar biasa - meninggalkan tempat tanpa membawa apa-apa. Juga tanpa protes. Tapi kesan "masa lampau" juga diimbangi oleh suatu bentuk "perubahan". Di balai pertemuan desa, pada waktu yang sama, sedang berlangsung sebuah penataran. Seorang dokter wanita (muda) sedang menatar aparat dukuh tentang bagaimana hidup yang sehat. Beberapa kepala dukuh, yang kemarin saya temui memakai celana kolor dan kaus oblong usang - yang menegaskan wajah "ke-petani-an"-nya--telah mengenakan safari dalam acara itu. Dan tidak seperti kemarin harinya, mereka mulai memperlihatkan sikap "kepejabatan"-nya berhadapan dengan setiap orang. Setidak-tidaknya, mereka inilah yang telah menjadi lapisan baru, yang menandai serentetan perubahan dalam masyarakat desa. Suatu lapisan masyarakat yang mempunyai akses terhadap aneka bentuk penataran yang diselenggarakan orang-orang kota. Merekalah yang kemudian menjadi pribadi-pribadi kunci (key persons), kepada siapa kita bisa memperoleh keterangan agak memadai tentang perkembangan desa. Bersatunya "masa lampau" dan "masa kini", yang memberikan dasar-dasar bagi perubahan yang terus-menerus, mungkin telah menjadi trade mark kehidupan dunia pedesaan. Yang "lampau" memfungsikan berlanjutnya keaslian "roh" kehidupannya. Sementara yang "kekinian" merefleksikan kondisi struktural pedesaan yang selalu harus berhubungan dengan kota. "Desa," ujar George Rosen, seorang antropolog, "tidak pernah bisa berdiri sendiri." Sambil mengutip Robert Redfield, Rosen menegaskan bahwa eksistensi desa harus selalu berkaitan dengan kota, baik secara politik, ekonomi, maupun moral. Di desa terdapat bahan makanan yang dikonsumsi orang kota. Di kota ada barang-barang manufaktur yang diperlukan orang-orang desa. Dan di atas itu, ada nilai yang dipancarkan kaum literati kota, dalam mana massa desa menggunakannya untuk menafsirkan pengalaman hidupnya. Bagaimana pentingnya nilai kekotaan setidaknya dapat dilihat pada gaya hidup yang dilakoni seorang pamong desa dalam pergulatannya "merebut" budaya kota untuk anak-anaknya suatu budaya yang tidak sempat dikecapnya. Di tempat petani yang bergerombol, di kelurahan itu, dia berkisah tentang hidup dan "perjuangan"-nya. Sak niki kulo sampun nedo sekul sedinten ping tigo malih (Kini saya telah makan nasi tiga kali sehari lagi), suatu kalimat akhir dari seluruh ceritanya. Dan ia tampak lega serta seakan-akan merasa menang - setidak-tidaknya untuk dirinya sendiri. Kalimatnya itu, bagi saya, merupakan hasil yang maksimal yang telah dicapainya untuk mendapatkan sekeping citra "kekotaan". Mungkin tidak lebih dari itu. "Hasrat saya," demikianlah kira-kira awal ceritanya, "untuk menjadikan anak-anak saya sarjana sangat kuat. Untuk itulah saya dan istri harus berani hidup prihatin." Gaya hidup prihatin itu dilakoninya selama hampir sepuluh tahun - sepanjang masa studi anak-anaknya di beberapa perguruan tinggi Yogyakarta. Meski dia mempunyai tanah pribadi yang relatif luas (lebih kurang 1,5 ha), ditambah dengan tanah bengkok dengan luas yang hampir sama - yang kini disewakan kepada pabrik tebu - toh mereka harus mengurangi jatah makan nasi secara teratur. Sejak anaknya yang pertama masuk ke perguruan tinggi, hingga anak perempuan terakhirnya lulus IKIP Yogyakarta, mereka hanya memakan tiwul (ubi kayu yang diolah menjadi makanan) sebanyak dua kali dalam sehari. Baru pada malam harinya mereka menikmati nasi. Padahal, sebelumnya mereka menikmati nasi setiap hari tanpa diselingi oleh tiwul. Di luar kebiasaan penduduk setempat, yang mengkonsumsi seluruh hasil panen padinya, ia menjual, baik hasil sawah maupun tegalan. "Hanya sedikit beras yang saya sisakan," ujarnya. Semua hasil penjualan panennya itulah yang diperuntukkan bagi biaya studi anak-anaknya. "Dua minggu atau paling lambat tiga minggu sekali, anak-anak saya kembali dari kota, meminta biaya. Dan saya selalu berusaha untuk siap," ujarnya lagi. Di samping bayar kuliah, anak-anaknya membutuhkan biaya untuk kos, uang saku, buku, dan rekreasi. Dan sebisa-bisanya, orangtua--yang terkadang saya panggil mbah itu--memenuhi semua permintaan anak-anaknya, demi mewujudkan impiannya. Dan impiannya itu memang terpenuhi. Ketiga anaknya kini telah menjadi sarjana semua. Dua orang laki-laki bekerja untuk pemerintah di Kulonprogo. Dan yang terakhir, perempuan, ikut suaminya sambil mengajar di Klaten. Dan sejak itulah lakon hidup prihatin diakhirinya. Suatu hasil akhir yang maksimal yang bisa diraih secara kongkret--dengan seluruh keprihatinannya "meraih" budaya kota--adalah apa yang telah dikemukakannya di atas: "Kini saya telah makan nasi tiga kali sehari lagi". Sementara itu, sang anak, yang kini telah menjadi sarjana, tertarik begitu jauh ke dalam budaya kota yang disorongkan orangtuanya. Dan tak pernah "kembali" lagi. Dan sang orangtua, yang kini tinggal berdua dengan rumah desanya yang besar, tetaplah bagian dari masa "lampau". Dan di balai desa itu, seusai dengan ceritanya, saya membayangkan kerutinan hidupnya. Sebentar lagi, pukul 1 atau 2 siang, dia akan meninggalkan kantor kelurahan tempatnya bekerja sehari-hari, turun sedikit ke jalan raya beraspal dan sepi--yang menghubungkan daerah itu dengan Wates atau, ke arah yang berlawanan, Purworejo, lalu melangkah beberapa ratus meter, membelok ke kanan melintasi sebuah kretek (jembatan) kecil. Melalui sawah-sawah yang sedikit berbukit-bukit, dan dengan sedikit disapa atau menyapa penduduk desa yang ditemuinya di jalan, ia akan sampai ke rumahnya yang besar dan sunyi (suasana yang juga dialaminya kemarin dan hari-hari esok). Dan istrinya, yang setia menunggu di rumah, pasti telah memasak "nasi" untuk santapan siangnya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini