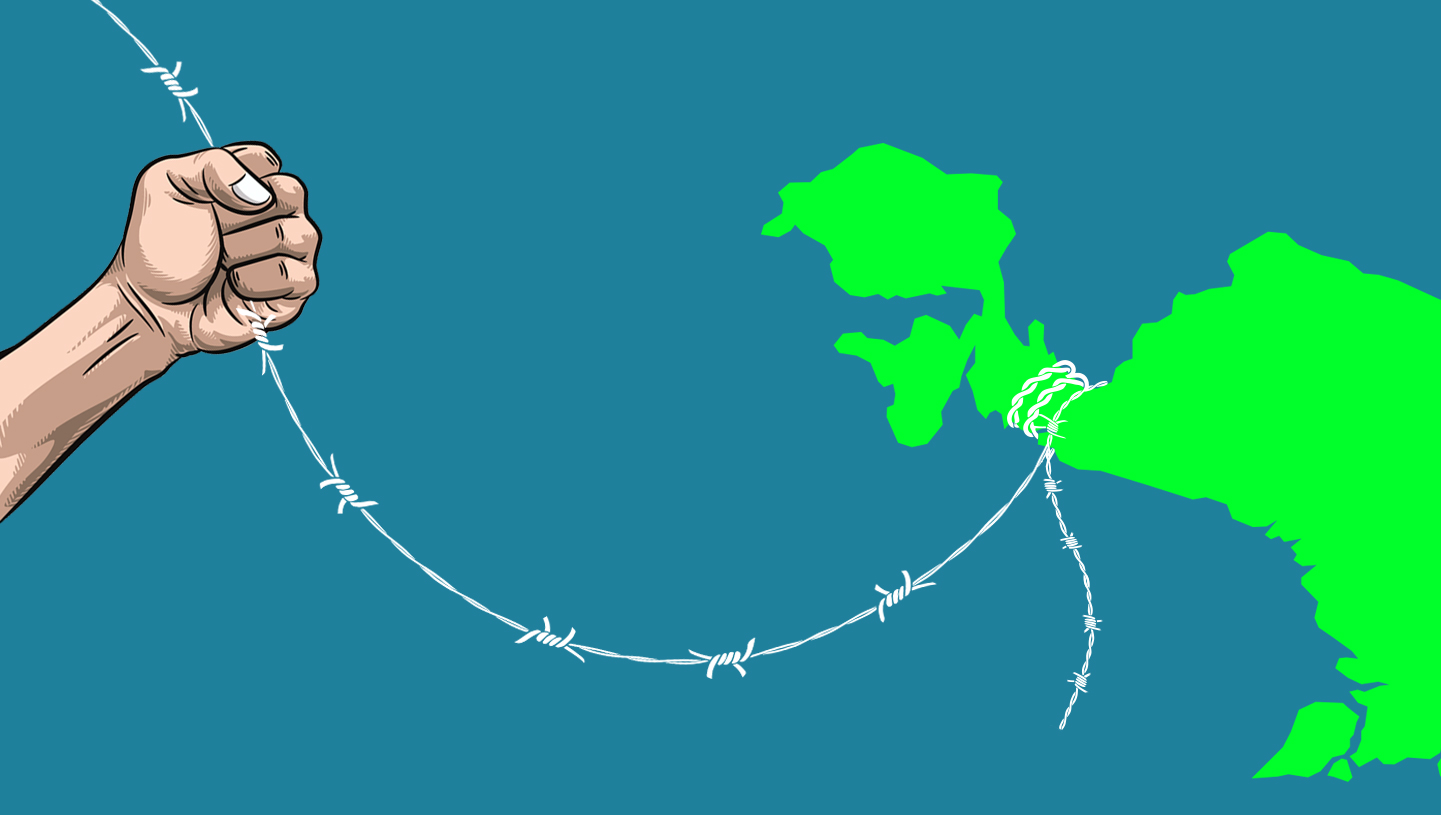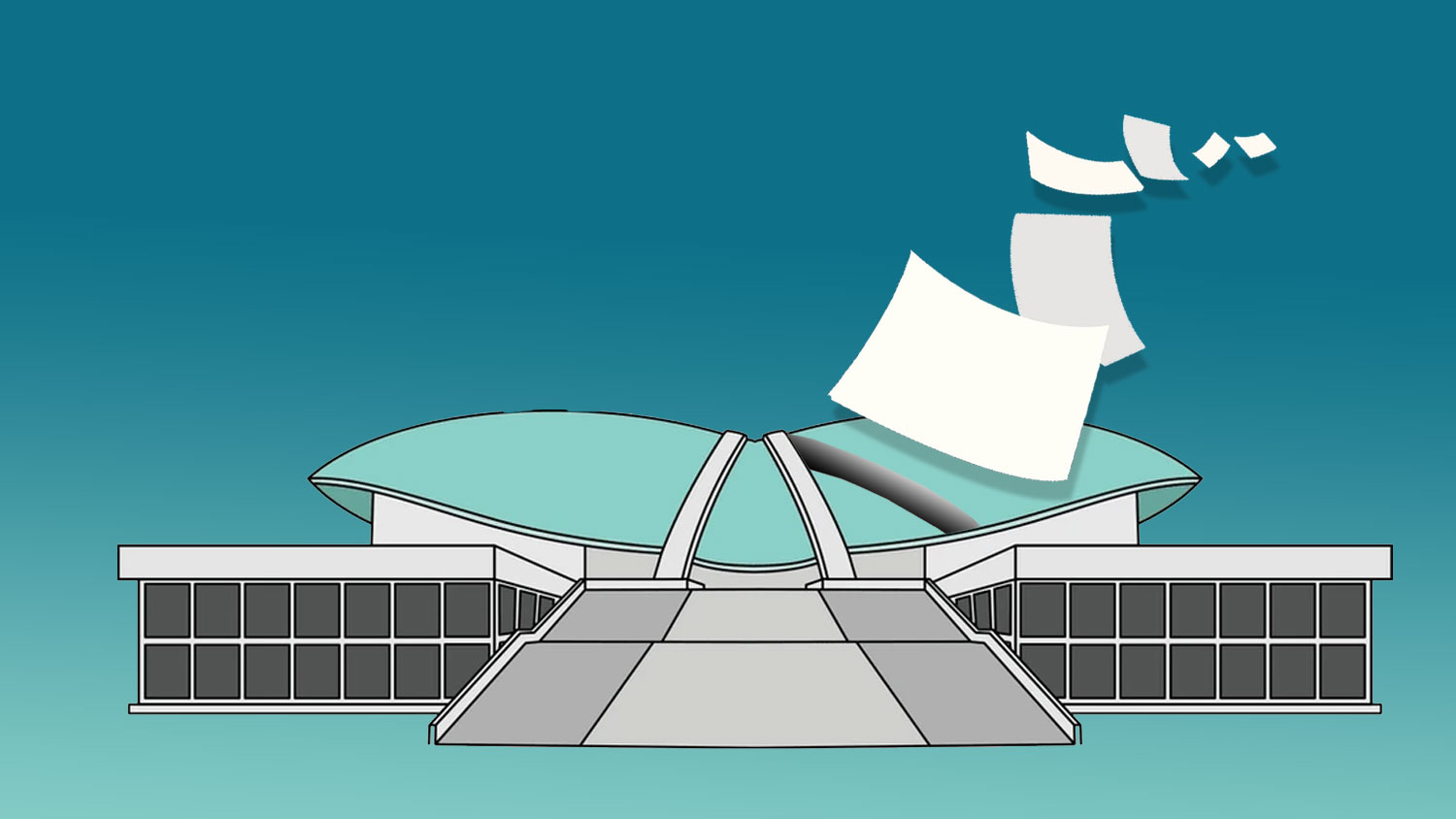"SAYA merasa seperti telah mendapatkan gelar Ph.D. dalam soal kematian," ia berkata. Namanya Maria Jimena Duzan. Umurnya baru 32 tahun, tapi ia memang tahu apa artinya kematian. Sebab, Maria adalah seorang wartawan yang bekerja di harian El Espectador. Koran ini koran tertua di Kolombia, dan tahu apa artinya harga diri. Tanggal 24 Agustus 1989, suatu kekuatan hitam di negeri itu -- para pengusaha obat bius telah memaklumkan perang yang "total" kepada media massa. Dan El Espectador adalah sebuah sasaran spesial. Soalnya, surat kabar itu memutuskan untuk terus mencari tahu, kemudian menuliskan, apa sebenarnya yang terjadi di dalam kehidupan di negeri itu. Pedalaman Kolombia dalam beberapa tahun terakhir memang jadi sarang obat bius, bisnis milyaran dolar yang pelan-pelan menghancurkan manusia itu. Para juragannya pun menguasai ekonomi, dan kemudian juga menguasai senjata. Bahkan mereka bisa membeli pengaruh di kalangan militer dan polisi. Syahdan, ketika ada yang mencoba menentang, anjing-anjing perang mereka pun menyalak. Sudah dua calon presiden mereka tembak. Dan ketika El Espectador dan media lain mencoba menyelidiki bagaimana jalinan hitam itu bekerja, dengan cepat sejumlah wartawan pun mati terbunuh. Hasilnya mengerikan: El Espectador kehilangan seluruh tim reporter investigasinya. Bahkan juga redakturnya, Guillermo Cano. Semua mati. Maria Jimena Duzan memang selamat -- tapi betapa tak mudahnya. Lima koleganya sudah gugur. Ia sendiri diancam, karena dialah yang membongkar hubungan antara pengusaha obat terlarang itu dan sejumlah perwira tentara. Sejak itu dia harus dikawal. Tapi adiknya, Sylvia, seorang wartawan di media lain, jadi korban ketika ia sedang mewawancarai sejumlah pemimpin tani di sebuah restoran, tiga orang masuk dan menyemprotkan senapan mesin. Sylvia roboh, untuk selama-lamanya. Kantor El Espectador juga dibom, dan Maria akhirnya lari ke Prancis, hidup sebagai orang di pengasingan, yang sedih, marah, dendam. Tapi koran-koran terus bertahan, juga El Espectador. Di tengah teror itu mereka terus bekerja, terus mengungkapkan apa yang harus diungkapkan, meskipun para pemasang iklan menarik diri ikut ketakutan dan tiap orang dari penerbitan itu tahu bahwa besok ia mungkin kena bedil atau ledakan. Untuk apa? Untuk apa terus jadi wartawan dalam keadaan seperti itu? Jawabnya, bagi para wartawan Kolombia karena suatu masyarakat akan hancur sendi-sendinya bila sebuah kekuasaan (yang tak mau sedikit pun diberi tahu ekses-eksesnya sendiri) bisa menggertak semua orang untuk ikut berbohong. Para wartawan Kolombia menunjukkan sejelas-jelasnya bahwa menulis berita tak berarti sekadar memperdagangkan informasi. Menulis berita yang benar adalah sebuah ikhtiar menjaga agar manusia tetap jadi manusia, bukan anjing. Pers memang sebuah perdagangan. Ia menjual jasanya kepada publik. Tapi bisnis pers bukanlah bisnis yang sama dengan bisnis garmen atau pun udang. Sebuah surat kabar memang harus tumbuh secara bisnis, tapi tujuan pertumbuhan itu adalah untuk meluaskan kemampuannya melayani informasi untuk khalayak ramai. Sebuah usaha pers memang harus dapat untung -- laba adalah satu kriteria kemampuan manajemen -- tapi untung itu adalah buat memperbesar dana, guna memperlancar lalu lintas informasi, dan dengan begitu mencerdaskan bangsa. Sebuah koran, sebuah majalah, pada dasarnya adalah sebuah misi demokrasi. Semua ini memang kabur kini. Bisnis media nampak menguntungkan, dan para wiraswasta pun terjun ke dalamnya baik untuk mendapatkan uang tambah atau, syukur-syukur, untuk prestise dan dagang sapi politik. Macam Murdoch, raja media dari Australia itu? Tidak. "Beda antara Rupert Murdoch dan para majikan pers sekarang," kata seorang wartawan kawakan Amerika dalam seminar di Harvard bulan lalu, "ialah Murdoch bagaimanapun orang koran, dan punya cinta kepada dunia koran. Sedang para majikan baru itu hanya melihat koran sebagai ia melihat produk industrinya yang lain seperti kecap dan ban mobil, misalnya." Itulah penjelasan, kata wartawan itu, mengeluh, kenapa mutu pers Amerika belakangan ini mundur. Tapi bukan cuma para pemilik modal yang jadi biang keladi. Kini pekerjaan wartawan sangat mudah tergoda untuk jadi empuk dan berlemak: si wartawan kian biasa hidup enak, hingga setiap ancaman atau gangguan kepada nikmat hidup itu akan langsung dihindari. Maka, ia pun akan rela untuk melakukan hampir apa saja -- untuk membagi dusta atau setengah dusta, untuk serba keder kepada kesulitan hidup dan ancaman pemberangusan atau pemecatan. Maka, jurnalisme pun, kata sebuah ejekan, telah membuktikan diri "jadi profesi tertua dalam sejarah -- seperti halnya pelacuran". Tentu saja berlebihan. Setidaknya masih ada Maria dan para wartawan Kolombia: mereka, yang di luar kemauan sendiri, telah mendapatkan gelar Ph.D. dalam hal kematian. Goenawan Mohamad
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini