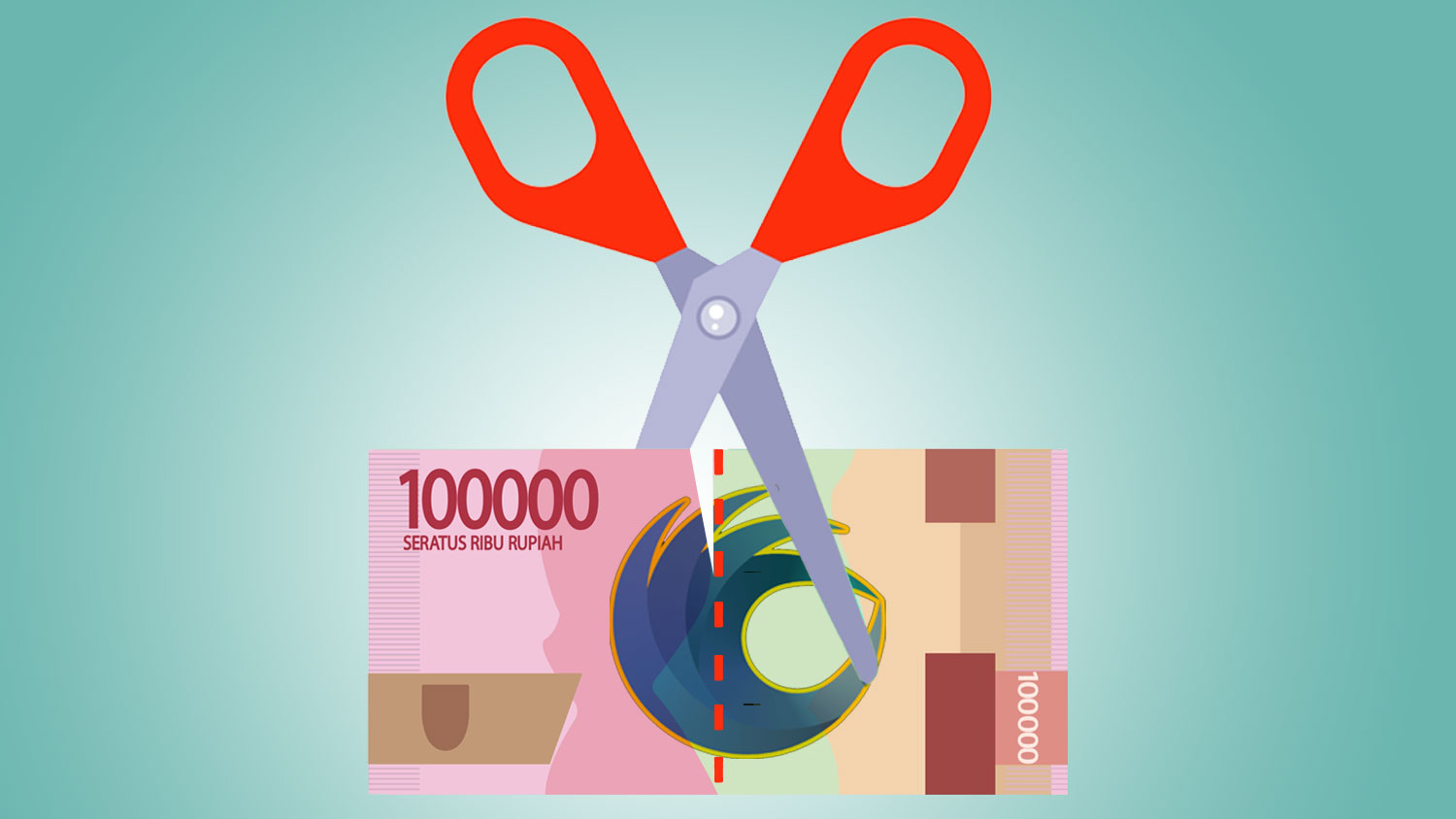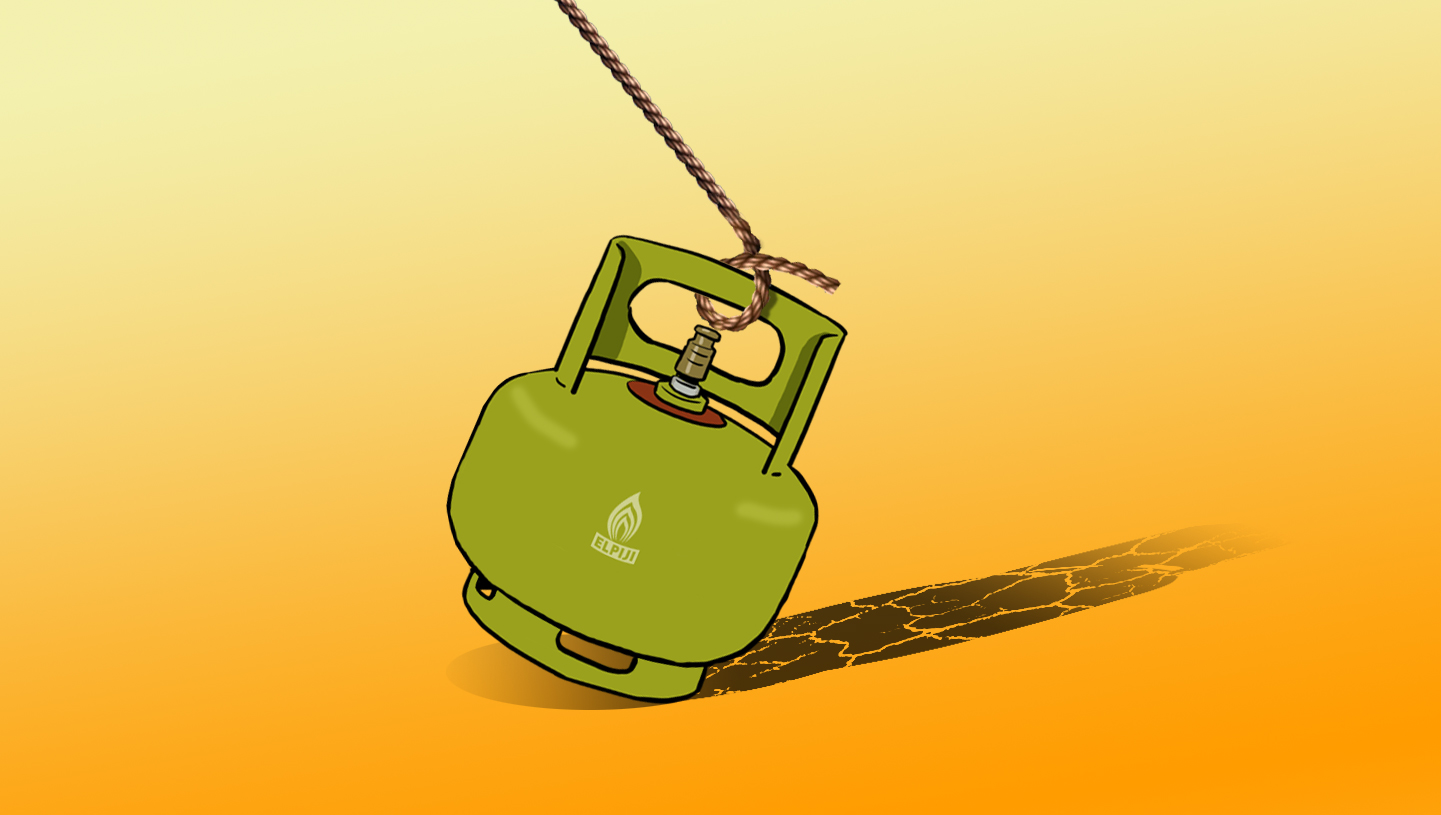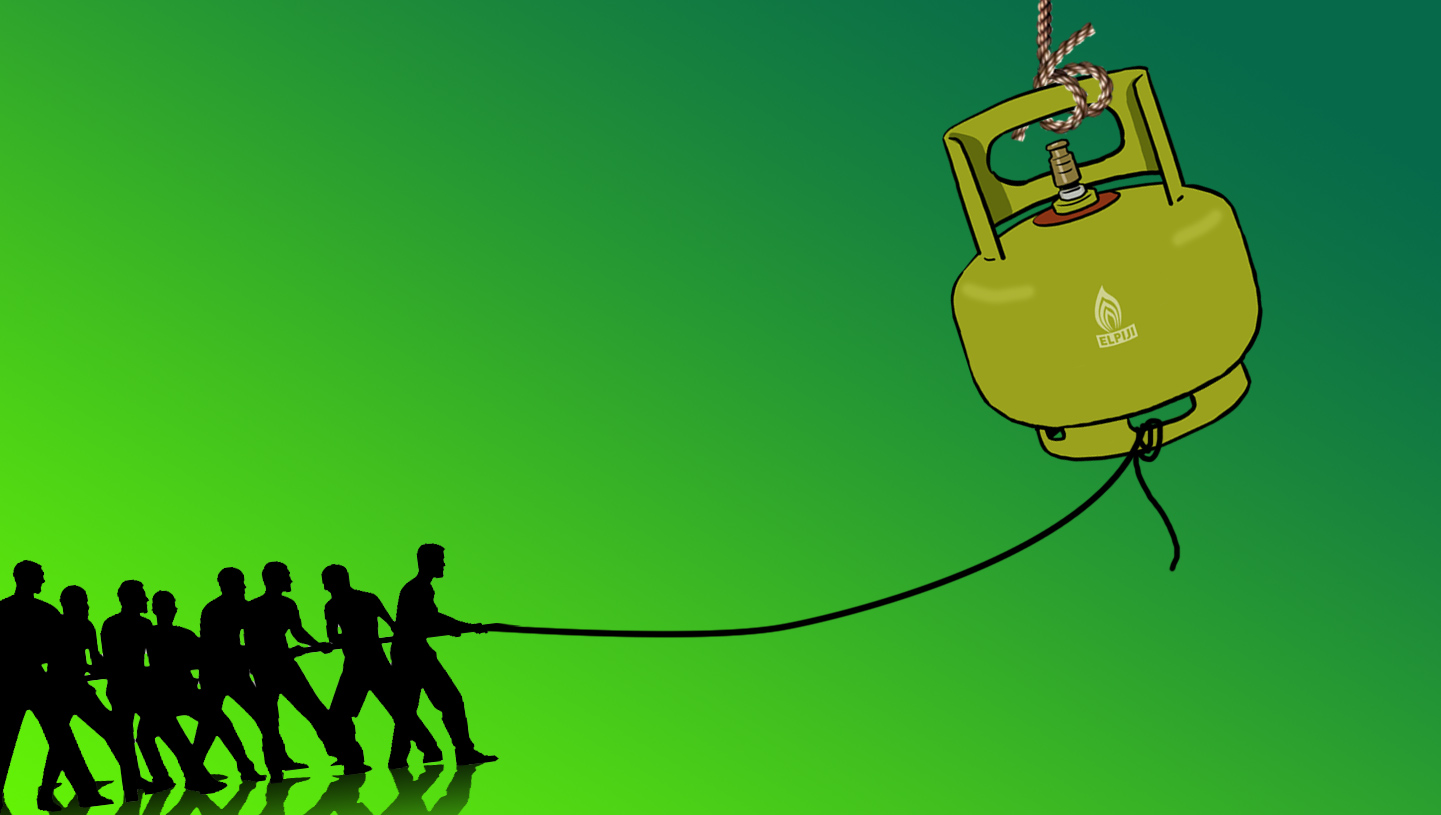"MARI kita kuburkan partai, kuburkan, kuburkan!" teriak
Soekarno, satu tahun setelah Pemilu yang pertama terlaksana.
Tidak hanya Soekarno yang jengkel dengan partai-partai.
Juga Hatta, sang demokrat. "Partai-partai," demikian Feith
mengutip, "sudah menjadi tujuan dalam dirinya sendiri, negara
menjadi alatnya. Kedudukan pemerintah sudah menjadi pesuruh
partai-partal politik."
Di samping A.H. Nasution menganjurkan Junta Pemuda untuk
menggantikan situasi oposan partai, Soekarno pada akhirnya
membuat klimaks: pembubaran partai-partai (oposan), setelah
Konstituante dibubarkan.
Politik 'nonoposisi' Orde Baru tampaknya merupakan kelanjutan
dari pemerintah sebelumnya. Perbedaannya terletak pada corak
kebijaksanaan Orde Baru yang bersifat lebih konseptual,
direfleksikan dari asumsi-asumsi kultural masyarakat Indonesia.
Kerangka yang dikemukakan adalah 'Demokrasi Pancasila', dan
bahasanya yang lebih teknis 'konsensus politik'.
Rosihan Anwar menyebutkan di tahun 1973 (The Indonesian
Quaterly, I:3), ketika untuk pertama kali Pak Harto terpilih
kembali bahwa tiadanya calon tandingan untuk presiden adalah
manifestasi konsensus politik, dan dengan sendirinya konsisten
dengan prinsip Demokrasi Pancasila. Dan bahwa sikap oposisi
adalah manifestasi steamroller politics, pemaksaan politik.
Corak konsensus semacam ini terus berlangsung sampai ke tingkat
lebih rendah. Contoh terakhir, terpilihnya Pak Sudharmono
sebagai ketua umum Golongan Karya.
Dengan melihat proses-proses itu, sebenarnya kita telah bisa
mencanangkan, dengan gembira, berakhirnya masa oposisi dalam
sistem politik Indonesia.
Tetapi corak oposisi yang berlangsung selama ini tidaklah unik.
Kalau tidak mengambil bentuk formal, maka dilaksanakan dengan
kekerasan. Pemberontakan yang pernah terjadi di beberapa tempat
memberikan corak kultural-ideologis - sejauh tesis Van Dijk bisa
dipegang - yang dimanifestasikan dalam bentuk kekerasan
bersenjata. Maka, amatlah menarik melihat suatu gaya oposisi
unik di Aceh, di sekitar 1963-1965.
Tahun-tahun itu adalah masa ketika Gerakan DI/TII Daud Beureu'eh
baru saja berakhir, dan proses Pemantapan Demokrasi Terpimpinnya
Soekarno baru digerakkan. Oposisi kultural ideologis telah
berakhir. Kritik Daud Beureu'eh yang menuduh pemerintah Soekarno
berhasrat mengembalikan zaman Kerajaan Majapahit dan Jawanisasi
tidak lagi terdengar. Keamanan sudah jalan.
Dalam situasi itulah muncul seseorang di tempat-tempat ramai
lebih sering di Peukan Aceh - berbicara dan berpidato. Orang
ramai menyebutnya gila - dan memang ia mengesankan diri sebagai
orang gila. Diawali kata-kata "Hancou klaha! Naa loum poudouk!"
ia berpidato, mengkritik kebijaksanaan Demokrasi Terpimpin.
Baginya demokrasi semacam itu hanya alat pengesahan pemupukan
kekuasaan di satu tangan. Tetapi yang terutama menjadi sasaran
kritiknya adalah proses komunikasi Indonesia di bawah
bayang-bayang kekuasaan Soekarno. "Tidak hanya Islam akan
terancam dengan gejala ini, tetapi juga agama-agama lain.
Termasuk Nasrani!" ujarnya.
Itulah yang penulis dengar setiap hari, ketika masih
kanak-kanak. Oposan ini selalu meminta-minta sebelum berpidato.
"Goloum jep kopi, pakiban meupidato" Belum minum kopi,
bagaimana bisa pidato? Demikian ujarnya setiap orang memintanya
bicara.
Meski demikian, kawasan 'gerakan'-nya ternyata tidak hanya di
Banda Aceh. Dengan gaya orang gila yang sama, ia berkelana ke
beberapa kota lainnya. Sampai ke Meulaboh, Manggeng, dan Labuhan
Haji. Hampir setiap orang di kota-kota itu mengenalnya, sampai
pun kanak-kanak.
Sikap kegilaannya dan materi pidato yang disampaikannya,
bagaimanapun punya fungsi tersendiri. Betapa pun ia dianggap
gila, ia telah menyebarkan kesadaran partisipasi politik,
pendidikan politik, dan sosialisasi politik di masyarakat Aceh.
Dan baru pada bulan Oktober yang lalu penulis ketahui,
sebenarnya ia tidak gila. Dengan sengaja ia mengesankan diri
sebagai orang gila agar pesan-pesan politiknya bisa sampai
kepada orang banyak tanpa gangguan.
Beberapa tahun kemudian, ia hilang. Kabarnya meninggal - entah
di mana. Dan yang mendorong tulisan ini lahir justru
kelenyapannya yang tidak wajar itu. Gaya oposisinya yang unik
pun dibungkam dengan cara yang unik pula. Dalam keadaan sakit,
dulu, ia berjalan maksudnya pulang ke Labuhan Haji, kota
kelahirannya. Tapi ia hanya mampu sampai ke Manggeng. Dan di
kota kecil yang sunyi inilah nyawanya lepas. Ia mati diracun
orang.
Ternyata, sikap gilaan pun tidak menjamin keamanan gerak
oposisi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini